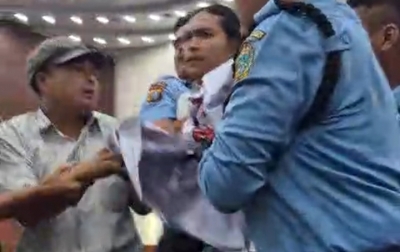Jones Gultom. SASTRA etnik bisa dibilang sudah punah dari kancah kesusasteraan nasional. Dalam teori sastra, sastra etnik diklasifikasikan sebagai jenis karya sastra lama. Salah satu jenisnya disebut mantra. Akibat pembabakan itu pula, sastra etnik semakin kehilangan eksistensinya. Di saat itulah, identitas bangsa ini mulai terkubur.
Sastra etnik tak berdaya berhadapan dengan sastra yang menggunakan Bahasa Indonesia-Melayu dengan serapan bahasa-bahasa asing. Begitu pula dengan bahasa penopang sastra etnik itu sendiri. Disebabkan masyarakat sudah tak lagi akrab dengan bahasa etnisnya, maka sejumlah karya sastra etnik itu pun lenyap begitu saja.
Di Batak, pemusnahkan sastra etnik sudah diawali sejak masa penjajahan Belanda. Seturut itu, misi zending juga ikut memunculkan konstelasi kebudayaan yang mendalam. Pertautan itu mencapai puncaknya, di masa Nommensen. Setelah itu, sastra dan bahasa Batak mulai hidup terpisah-pisah.
Meski bahasa Batak masih tetap dipakai, tapi tak demikian dengan sastra Batak. Ada opini yang dibentuk, seakan-akan sastra Batak bertentangan dengan paham agama (kekristenan). Mengingat sastra Batak secara umum, dipakai untuk peruntukan khusus. Termasuk dikuasai oleh kelompok orang tertentu. Raja, tabib atau tokoh-tokoh adat, kelompok marga atau huta. Eksklusivisme ini segera dimanfaatkan sebagai “kuda troya” oleh zending. Salah satunya dengan propaganda yang menyebut “Sastra Batak” sebagai produk budaya kafir.
Kondisinya berbeda yang dialami masyarakat Jawa. Kebudayaan Jawa, berikut sastranya justru dijadikan sebagai media syiar Islam. Di dalam Islam kita dapat menemukan Jawa dan sebaliknya.
Ironisnya, sejumlah pengetahuan menyangkut Batak tersimpan di dalam karya sastranya. Baik yang sudah dalam bentuk tertulis maupun sekedar oral. Dalam bentuk tertulis, sastra itu dituang dalam Pustaha Laklak, yang penulisannya menggunakan aksara Batak.
Pustaha Laklak, sering disebut sebagai kitab tabib (datu). Padahal Pustaha Laklak hanyalah media untuk menyebut buku (kitab) bagi orang Batak di masa lalu. Apa yang ditulis di Pustaha Laklak tergantung penulisnya sendiri. Jadi, keliru jika disebut Pustaha Laklak semata-mata berisikan ilmu nujum. Jika si penulisnya adalah raja huta, dia akan menulis aturan-aturan pemerintahan serta sanksi-sanksinya. Begitu juga bila si penulisnya adalah sastrawan, dia akan menulis sajak-sajak maupun turi-turian.
Begitupun, perpektif ilmu supranatural dan pengobatan yang ditulis tabib (datu) di dalam Pustaha Laklaknya, tak selamanya bersifat klenik. Justru pada saat sekarang ini beberapa di antaranya mulai dikembangkan secara modern. Misalnya penggunaan kencur pada orang sakit dan ibu hamil. Jika dulu fungsinya disebut-sebut untuk menjauhkan seseorang dari roh-roh jahat, sekarang dalam terminologi modern, roh-roh jahat itu kita kenal dengan bibit-bibit penyakit.
Mengutip tulisan Tokoh Supranatural, asal Sumut, Om Tatok, pada Pustaha Laklak yang ditulis oleh para tabib, dapat kita temui berbagai ilmu-ilmu supranatural, antara lain; Pangulubalang, Tunggal Panaluan, Pamunu Tanduk, Pamodilan/Tembak, Gadam, Pagar, Sarang Timah, Simbora, Songon, Piluk-piluk, Tamba Tua, Dorma, Paranggiron, Porsili, Ambangan, Pamapai Ulu-ulu. Ada juga berupa ramalan-ramalan, antara lain; Ramalan Perbintangan, seperti: Pormesa na Sampulu Duwa, Panggorda na Ualu, Pehu na Pitu, Pormamis na Lima, Tajom Burik, Panei na Bolon, Porhalaan, Ari Rojang, Ari na Pitu, Sitiga Bulan, Katika Johor, Pangarambui dan lain-lain.
Ramalan memakai Binatang, seperti: Aji Nangkapiring, Manuk Gantung, Aji Payung, Porbuhitan, Gorak-gorahan Sibarobat. Ramalan Rambu Siporhas, Panambuhi, Pormunian, Partimusan, Hariara masundung di langit, Parsopouan, Tondung, Rasiyan.
Terlepas dari fungsinya, semua yang tertulis di dalam Pustaha Laklak itu, merupakan karya sastra yang bernilai tinggi. Sayang, belum sempat digali pengetahuan atasnya, masyarakat sudah lebih dulu menganggapnya tabu. Dalam Pustaha Laklak Simalungun misalnya, Om Tatok pernah menemukan tabas (mantra) yang berkaitan dengan membangun rumah, yang kini kita kenal dengan sebutan Fengshui.
“Jaha sopo iholang-holang batang-batang sada, janah abing reben i desa otara Rohma naosuman bani oppungni sopou, matean oppung ni sopo ale amang datu. Jaha sopou ipajongjong bani suhi-suhi dalan nabolon topat bani topi dalan, rohma nasosuman bani oppunganni sopou inon. Buei marsilaosan begu monggop bani sopou inon, matean oppungni sopou inon”.
Artinya “Jika sebuah bangunan didirikan diapit balok besar, satu di antara balok terletak pada kemiringan di sebelah utara bangunan, pemiliknya tidak akan berhoki. Jika bangunan di tepi jalan raya pada posisi sudut jalan umum, maka pemilik akan ditimpa musibah karena banyak dilintasi energi negatif”.
Secara oral, sastra etnik dipakai dalam kasus-kasus tertentu. Pada Batak sastra itu dapat kita temui lewat, umpasa (pantun) umpama (perumpamaan), andung-andung (ratapan) turi-turian (cerita) huttica (teka-teki) tabas (mantra) tonggo-tonggo (doa-doa).
Membongkar Indonesia
Salah satu tokoh sentral sastra etnik nusantara adalah Herman Neubronner van der Tuuk. Van der Tuuk, peletak dasar linguistika modern beberapa bahasa, dituturkan di nusantara. Antara lain Melayu, Jawa, Sunda, Toba, Lampung, Kawi dan Bali.
Di tano Batak, van der Tuuk mempelajari bahasa dan sastra Toba secara guyub. Dia sengaja membuka warung kopi, untuk mempermudah berinteraksi dan mempelajari bahasa dan keseharian masyarakat Batak. Catatan-catatan van der Tuuk ini kemudian dipakai oleh Belanda, baik untuk kepentingan zending maupun tujuan kolonialisme.
Sejatinya, sastra etnik, mempunyai peran penting terhadap wacana keindonesiaan. Dari sisi antropologis, sastra etnik menjelaskan perspektif dan pola hidup suatu kelompok masyarakat tertentu. Sastra etnik merupakan kulminasi dari pengalaman-pengalaman empiris suatu masyarakat di satu fase tertentu yang cenderung transendental.
Di sisi ini, dapat kita lihat makna spiritual serta kekayaan bahasa yang dikandungnya. Tidak heran jika sastra etnik merupakan refrensi penting bagi para antropolog. Terutama ketika hendak menggambarkan identitas dan sistem kemasyarakatannya. Dapat kita lihat dari karya-karya Koentjaraningrat, seperti “Manusia dan Kebudayaan di Indonesia,” yang fenomenal itu.
Sastra etnik juga dipakai oleh peneliti psikologi komunal. Dari kandungan sastra etnik itu, akan terlihat kencenderungan kepribadian masyarakat secara kolektif. Di Indonesia, keduanya pernah dipakai sebagai pintu masuk bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia.
Pada saat ini, sastra etnik juga menjadi rujukan dalam pengembangan industri kesehatan dan kosmetik. Para pengobat alternatif maupun pakar kosmetik, menggali informasi yang ada dalam sastra etnik dari berbagai belahan nusantara. Pengetahuan itu kemudian diolah menjadi sebuah produk baru yang,dulunya pernah akrab bagi kita.
Sayangnya pada dunia sastra sendiri, sastra etnik tidak lagi mendapat tempat. Dia justru terusir karena dianggap bagian dari masa lalu. Usaha-usaha merevitalisasi sastra etnik, seperti yang pernah dilakukan Ajip Rosidi, terhadap Sastra Sunda, tidak terjadi secara massif di sejumlah daerah lain. Sebagai bangsa, kita pun kehilangan sesuatu yang sangat berharga; identitas!