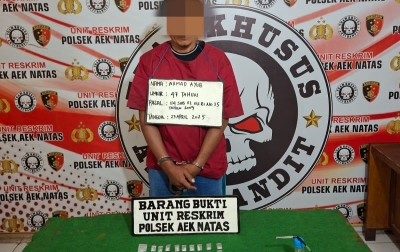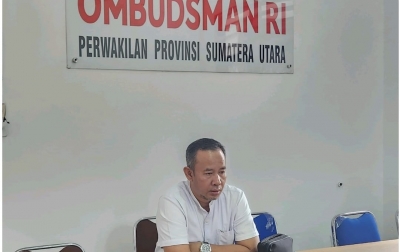Oleh: Hodland JT Hutapea. Apa yang Anda lakukan ketika barang elektronik Anda sudah tidak terpakai alias rusak? Mungkin Anda akan segera menyimpannya di dalam gudang. Mungkin pula menjualnya ke pedagang barang bekas. Atau bisa jadi malah membuangnya begitu saja ke tempat sampah.
Sebenarnya langkah terbaik yang perlu kita lakukan terhadap sampah elektronik adalah mengembalikannya kepada produsennya. Kenapa? Karena barang-barang elektronik seperti komputer, televisi, radio, microwave, vcd player, handphone, dan yang lainnya, adalah barang-barang yang umumnya mengandung bahan-bahan beracun yang sangat berbahaya bagi manusia dan lingkungannya. Jika tidak ditangani secara khusus maka sampah elektronik itu akan mencemari lingkungan dan secara tak langsung dapat mengancam kesehatan manusia.
Barang elektronik biasanya mengandung logam seperti timah, tembaga, kaleng, silikon, merkuri, cadmium, thallium, emas, dan sebagainya. Akan sangat berbahaya bila kita meletakkannya begitu saja di alam terbuka, terkena terpaan air hujan dan sengatan matahari. Kandungan logam-logam berat tersebut akan luntur terbawa air menjadi air lindi (polutan air), terserap ke tanah dan meracuni air.
Spesifikasi Sampah Elektronik
Ada dua jenis spesifikasi sampah elektronik yang kita kenal, yaitu barang elektronik seperti radio, televisi, pemutar MP3, ponsel, laptop, dan sebagainya, serta barang listrik rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, microwave, mixer, vacuum cleaner, dan sebagainya. Sampah elektronik dan sampah listrik rumah tangga ini biasa disebut electronic waste (e-waste).
Lalu bagaimana penanganan sampah elektronik di Indonesia? Ternyata masih sedikit masyarakat kita yang melihat barang elektronik bekas sebagai sampah. Bagi sebagian masyarakat, sampah elektronik biasanya tidak langsung dibuang begitu saja. Misalnya handphone, jika rusak umumnya dijual saja atau bisa juga tukar tambah dengan yang baru.
Beda halnya dengan di Eropa yang memiliki peraturan yang ketat soal penanganan sampah jenis ini agar tidak mencemari air, tanah dan udara. Di sana, sampah elektronik disebut sebagai waste electrical and electronic equipment (WEEE). Istilah WEEE tersebut merujuk pada limbah yang berupa barang elektronik dan barang listrik rumah tangga yang sudah rusak, tidak terpakai, dan dibuang.
Dulu, sebelum terbit peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) yang melarang adanya impor barang elektronik bekas (seperti AC, komputer, televisi), Indonesia sempat dibanjiri komputer bekas yang kemudian dirakit ulang dan dijual murah. Bagi negara pengekspornya, seperti Singapura dan Malaysia, tentu cekikikan karena mereka bisa membuang sampah elektroniknya dan sekaligus memperoleh keuntungan secara finansial pula.
Saat ini, meski telah ada aturan pelarangan impor sampah elektronik, tetap saja sampah ilegal ini dengan mudahnya “menginvasi” negara kita. Batam contohnya. Pulau terdekat dengan negara kota Singapura dan Malaysia ini telah lama dikenal dengan barang selundupan sampah elektronik. Di masyarakat kita, khususnya yang mendiami Pulau Sumatra, dikenal sebagai ‘barang Batam’. Tidak hanya sampah elektronik negara tersebut yang mengalir ke Indonesia, juga produk-produk elektronik bekas dari Malaysia, Thailand, China dan negara-negara Eropa dengan mudahnya mengalir ke Pulau Batam.
Aturan yang Jelas
Karena payung hukum yang jelas untuk menangani sampah elektronik belum ada di Indonesia membuat sebagian besar masyarakat menjadi bingung. Mereka tidak bisa mengkategorikan barang apa saja yang termasuk ke dalam sampah elektronik. Apakah semua barang elektronik bekas dapat dikategorikan sebagai sampah elektronik?
Di tingkat internasional, pengaturan tentang e-waste masuk ke dalam Konvensi Basel tentang Pengawasan Peredaran Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya, yang ditetapkan di Basel, Swiss, akhir tahun 1980. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini pada tahun 1993. Indonesia juga telah memiliki Peraturan Pemerintah yakni PP 18/1999 dan PP 85/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3. Hanya saja di dalam kedua peraturan pemerintah ini belum ada pencantuman tentang sampah elektronik. Dalam PP 18/1999 juncto PP 85/1999, limbah elektronik dikategorikan sebagai limbah B3 (barang beracun dan berbahaya), namun dengan catatan dari industri elektronik. Jadi, sampah elektronik rumah tangga yang potensinya lebih besar malah belum tercakup.
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan hidup (KLH), harus lebih peduli pada permasalahan ini. Harus dibuat suatu kebijakan yang menghasilkan pedoman spesifik tentang pengendalian dan penanganan limbah elektronik. Dalam membuat batasan, sebaiknya pemerintah membuat aturan yang jelas. Maka tidak ada salahnya jika pemerintah kita mengadopsi rumusan yang ada di negara lain. Batasan e-waste yang mencakup electrical/electronic equipment tadi bisa kita gunakan sebagai acuan.
Sebab dikuatirkan, ketiadaan payung hukum mengenai sampah elektronik ini hanya akan menyisakan persoalan yang besar bagi kita dalam hal mengantisipasi dampaknya bagi lingkungan. Dan bila tidak ditangani secara serius, masalah sampah elektronik akan dianggap sepele sehingga kita pun tidak menanganinya secara ramah lingkungan.
Penanganan yang Tepat
Penanganan sampah elektronik di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni: sampah elektronik yang berasal dari industri dan sampah elektronik yang berasal dari rumah tangga. Penanganan sampah elektronik yang berasal dari industri biasanya polanya lebih terkendali karena dibawa langsung ke perusahaan pengelola limbah B3. Sementara sampah elektronik yang berasal dari rumah tangga akan dibawa ke sektor informal, dikumpulkan oleh pengepul, kemudian dipreteli. Yang dapat dijual akan dijual, sementara yang tidak dapat dijual tidak jelas penanganannya.
Sebagian pengepul malah lebih senang mengambil jalan pintas. Sampah elektronik yang didapatnya biasanya dibakar begitu saja, misalnya bagian dalam kabel-kabel listriknya diambil untuk dijual lagi. Tindakan pembakaran ini menghasilkan asap hitam tebal yang beracun, mengotori udara bebas, dan sisa pembakarannya bercampur dengan tanah atau dibuang begitu saja ke aliran sungai.
Ada juga sebagian pengepul yang nekat mendaur ulang sendiri sampah elektronik yang dikumpulkannya berdasarkan bacaan dari internet atau karena telah melihat langsung orang lain melakukan hal yang serupa. Tindakan tidak terkendali seperti ini tentu saja akan menyebabkan pencemaran lingkungan menjadi lebih besar.
Penanganan sampah elektronik harusnya melalui sejumlah prosedur yang wajib dipatuhi oleh instansi pengolahan. Biasanya sampah elektronik disortir terlebih dahulu sesuai tujuan daur ulang, kemudian dihancurkan. Setelah dipotong-potong menjadi material kecil, kemudian dilakukan peleburan. Material yang telah dilebur sesuai dengan jenisnya akan dibentuk kembali menjadi material yang asli seperti tembaga, emas, timah, plastik, dan sebagainya. Selesai tahap tersebut, bahan-bahan yang ada akan diolah dan dibentuk kembali menjadi barang baru yang siap pakai.
Demikian pula penanganan sampah elektronik yang berasal dari rumah tangga, harus diambil alih oleh perusahaan pengelola limbah yang berkompeten. Dibutuhkan sebuah sistem di mana perusahaan penghasil produk elektronik bertanggungjawab mengumpulkan sendiri barang-barang elektronik produksinya yang sudah tak terpakai lagi dan mengolahnya kembali secara ramah lingkungan.
Undang-undang No.8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengitroduksi prinsip EPR (Estended Producer Responsibility) yakni tanggungjawab produsen yang diperluas. Artinya, produsen tersebut tidak hanya bertanggungjawab pada produk dan kualitasnya, tetapi juga setelah produk tersebut tidak terpakai lagi.
Pasal 15 UU tersebut mewajibkan produser mengelola kemasan dan/atau barang produksi mereka yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Sanksi pengabaian aturan ini adalah pidana. Prinsip EPR dapat diterapkan pada produsen elektronik agar mereka mengumpulkan sampah elektronik dari konsumen (Pramana Sukmajati, 2011).
Kita membutuhkan sebuah sistem yang bekerja dengan baik mengumpulkan sampah elektronik dari rumah tangga. Masyrakat pun perlu lebih aktif dan punya inisiatuf untuk mengantarkan sendiri sampah elektronik mereka ke pengepul dari produsen elektronik bersangkutan. Jadi produsen dan konsumen idealnya bekerjasama dalam penanganan sampah elektronik.
Dalam hal ini memang perlu dibuat aturan teknis dalam hal menggalang kerjasama kedua pihak agar penanganan sampah elektronik berjalan lebih efektif.