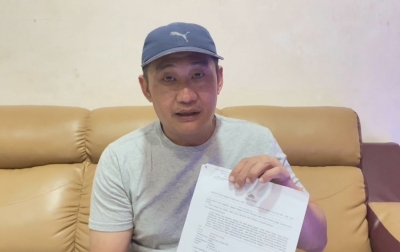Oleh: Meyarni
SAMPAI kini, kabut asap terus saja melanda berbagai daerah di negeri ini. Bahkan semakin hari kian parah. Di beberapa tempat, kabut asap malah telah melewati ambang batas bahaya. Di Jambi misalnya, indeks standar pencemaran udara mencapai 601. Batas bahaya hanya 300.
Puluhan ribu orang, khususnya anak-anak terserang penyakit ISPA. Puluhan di antaranya telah meninggal dunia. Angka ini pun terus bertambah. Mengingat sampai kini, titik-titik api semakin bertambah, wajar jika bencana kabut asap, dianggap paling parah sepanjang sejarah Indonesia.
Selain akibat musim kemarau, kabut asap juga ditimbulkan karena pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Entah sejak kapan cara-cara ini berlaku di Indonesia. Padahal nenek moyang kita tak pernah mengajarkan cara membuka lahan dengan pembakaran. Bahkan setiap suku di negeri ini punya ritus tertentu ketika akan membuka lahan. Baik untuk perladangan maupun sekedar pemukiman.
Termasuk dalam budaya masyarakat Batak Toba. Sebaliknya, bagi masyarakat Batak Toba, membuka lahan termasuk salah satu ritus yang paling dihormati. Tidak bisa seseorang dengan sembarangan membuka lahan. Misalnya menebangi pohon-pohon di hutan, baik untuk kepentingan pribadi maupun bersama. Apalagi dengan cara membakar.
Membuka lahan bagi masyarakat Batak Toba, harus melalui berbagai ritual tertentu. Itupun mesti memenuhi sejumlah syarat.
Pertama sekali, seseorang harus menyampaikan niatnya kepada orang kampung atau raja huta (kampung) di tempat dia tinggal. Jika disetujui barulah niat itu boleh dilanjutkan.
Orang Batak tidak boleh sembarang menebang kayu di hutan. Karena mereka yakin, setiap pohon memiliki kehidupan yang harus dihormati. Selain itu, mereka juga yakin, di setiap pohon ada kehidupan lain yang hidup di sana dan juga harus dihormati. Karena itu, biasanya mereka juga akan bertanya kepada orang pintar untuk menghindari bencana yang tak diinginkan.
Tidak heran, jika untuk sekedar menebang sebatang pohon saja, orang Batak harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, pohon yang akan ditebang harus berumur cukup. Kedua, tidak boleh menebang pohon dalam jumlah banyak hanya di satu titik atau areal saja. Ketiga, orang tersebut harus mengganti pohon yang ditebang dengan 3 tanaman baru.
Manakala pohon itu ditebang, segera dia harus menanam 3 bibit baru. Istilah ini kita kenal dengan tanam 3 tebang 1. Secara filosofis, 3 bibit pohon ini dimaksud sebagai pengganti, sekaligus menjadi cadangan untuk anak dan cucunya di masa mendatang.
Selain itu, seseorang tidak boleh menebang pohon yang berada di pinggir kampung. Atau yang termasuk pohon penyanggah.
Karena itu mereka harus masuk ke dalam hutan. Hal ini dimaksud agar tidak menganggu sistem sumber air di kampung tersebut. Tidak heran jika mereka akan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengambil beberapa batang kayu.
Menariknya, jika ada salah satu syarat yang dilanggar, orang tersebut tidak hanya akan mendapat sanksi adat maupun sosial. Lebih berat, justru sanksi secara spiritual. Biasanya, orang tersebut akan mereka bersalah. Merasa diteror. Batinnya tidak tenang.
Setiap kali ada hambatan dalam perjalanan selama proses menebang pohon itu, akan dikaitkan dengan roh penghuni hutan atau pohon yang marah. Rasa bersalah ini pun, terbukti sangat ampuh. Karena biasanya orang tersebut akan menghentikan proses penebangan pohon dan kembali ke kampung. Mereka akan meminta maaf dan menggenapkan syarat yang kurang.
Jika toh masih punya peluang, dia akan diberikan kesempatan. Tak jarang pula, akhirnya dilarang sama sekali.
Justru inilah nilai-nilai yang membuat setiap orang Batak begitu menghormati hutan yang mereka sebut dengan harangan. Di masa lalu, hutan-hutan yang ada di Tano Batak, selalu terjaga keberadaannya. Dalam perkembangan selanjutnya, apa yang diyakini nenek moyang orang Batak Toba itu, kita sebut dengan kearifan lokal. Di dalamnya dapat kita buktikan sebab akibat secara logis.
Budaya Go Green
Sebagai masyarakat komunal atau yang hidup secara berkoloni, semua masyarakat suku di Indonesia terikat oleh nilai-nilai kebersamaan. Tidak hanya dengan sesama manusia, tetapi juga terhadap alam. Jika dikaji, justru ritus-ritus yang biasanya bermakna spirtual itu selalu bersinggungan dengan visi alam. Pada akhirnya berkaitan dengan tujuan pelestarian alam.
Contoh paling sederhana adalah makna sesaji. Dalam istilah orang Batak Toba disebut pelean.
Sesaji biasanya dihaturkan di alam terbuka, baik di gunung, laut, sungai, hutan maupun lahan pertanian. Doa-doa yang dipanjatkan biasanya ditujukan kepada “penghuni” di lokasi tersebut. Sepintas ritus-ritus tersebut terkesan atheis.
Jika dikaji dari sisi psikologi agama, dapat kita pahami. Apa yang dilakukan nenek moyang kita itu, justru wujud penghormatan mereka terhadap alam sekitar.
Mengutip tulisan Jones Gultom,yang pernah dimuat di harian ini, prinsip nenek moyang itu merupakan pengejewantahan keyakinan mereka tentang adanya kekuatan yang berkuasa atas alam tersebut. Pengakuan akan sumber power itu, menujukkan rasa hormat mereka terhadap alam. Selain itu juga merupakan bentuk etika dan tatakrama serta menjauhkan diri dari sikap tamak. Sekaligus juga penegasan terhadap keyakinan akan adanya kehidupan di luar pemahaman an sich manusia.
Pada masyarakat Batak Toba, praktik yang paling jelas dapat kita lihat saat mereka akan membuka hunian atau perkampungan baru. Tidak jarang proses ini membutuhkan waktu sampai berminggu-minggu, sebelum penebangan pohon mulai dilakukan.
Biasanya, setiap hari selalu dilakukan ritus-ritus tertentu. Doa-doa dipanjatkan. Termasuk kepada penghuni tanah dan batu. Arah rumah yang akan dibangun pun ditentukan melalui berbagai pertimbangan. Semua ini dilakukan agar hunian yang akan dibangun kelak memperoleh tuah.
Pohon yang akan ditebang merupakan pilihan serta hasil diskusi bersama dengan “orang pintar”. Orang yang ditugaskan menebang pohon itu terlebih dulu harus menyucikan dirinya dengan mandi di pemandian tertentu. Mereka juga diharuskan berpantang. Prinsip ini sebagai bagian dari penghormatan terhadap semua roh makhluk hidup yang ada di bumi.
Memang budaya Batak, khususnya Toba dikenal masih sangat kuat memelihara keyakinan itu. Mereka hidup dalam bayang-bayang kausalitas. Mereka meyakini adanya karma untuk setiap perilaku dan tindakan yang menyakiti sesama makhluk hidup.
Keyakinan ini merupakan manifestasi dari kosmologi yang dianutnya. Adanya relasi antara mikro dengan makrokosmos. Bagi mereka kehidupan yang harmonis adalah yang berelasi antara masing-masing individu dengan alam sekitar mereka. Prinsip inilah merupakan substansi dari konsep go green.
Dengan kata lain, jauh sebelum konsep go green ada, nenek moyang orang Indonesia, khususnya Batak Toba, sudah lebih dulu melakoninya dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Karena itulah kita heran, mengapa kini dengan gampang masyarakat Indonesia, baik secara perorangan maupun perusahaan membakar lahan dan hutan dengan seenak hatinya. Sungguhkah keyakinan mereka akan kehidupan di luar diri mereka, seperti yang diajarkan para pendahulunya, telah hilang sama sekali?