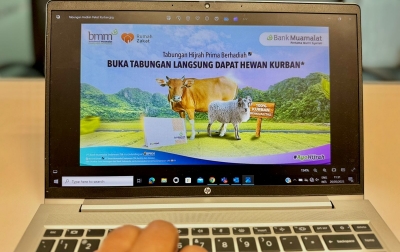Oleh: Muhammad Husein Heikal
PUISI merupakan produk buatan penyair. Sebagai produsen, tentu penyair “bebas” meracik puisinya sedemikian rupa. Bisa saja puisi yang dihasilkan dalam bentuk in/konvensional, ir/rasional, kongkret, kontemporer, bahkan kacau-balau.
Afrizal Malna, memanfaatkan “hak”-nya sebagai penyair, yaitu memproduksi puisi dengan cara “sebebas-bebasnya”. Seseorang menulis untuk keluar dari aku/ dan ia berjalan/ menuju sebuah pagar tinggi. tebal. tebal menjadi seekor binatang dalam kata berlalu.
Jelaslah, penyair memiliki “kebebasan” menggunakan kata-kata dalam berkarya. Penyair secara proses juga mempunyai tugas sebagai seorang defamiliarisasi. Konsep ini awalnya dikemukakan Victor Borisovich Shklovsky (1893-1984), menyatakan: “Defamiliarization is found almost everywhere form is found.”
Kutipan tersebut berarti “Hal-hal yang sudah biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari diubah fungsi ataupun pemahamannya menjadi asing dan ganjil atau aneh.” Tujuannya agar pembaca lebih tertarik, dan lebih menyadari hal-hal yang luput disekitarnya.
Dalam penelitiannya terhadap sastra, Shlovsky memandang karya sastra berdasarkan kesastraannya. Bukan sekedar isi kulitnya saja. Sifat kesastraan ini muncul dengan cara menyusun dan mengolah bahan cerita yang bersifat netral atau biasa (fabula).
Cara pengolahan atau penyulapan ini akan menghasilkan karya sastra yang indah (suzjet). Dimaksud dengan fabula adalah bahan dasar berupa jalan cerita menurut logika dan kronologi peristiwa. Sedangkan suzjet, sarana untuk menjadikan jalan cerita menjadi ganjil atau aneh. (Dick Hartoko, 1989: 33).
Mengaitkan puisi dengan teori suzjet, memang begitulah seharusnya. Puisi harus bisa menjadi karya sastra yang unik, menarik dan aneh. Penyair dalam meracik ramuan puisi harus menjadi “pawang” bagi kata-kata dalam puisinya.
Memilih kata-kata (diksi), sehingga dapat menyadarkan, menggemaskan, menjengkelkan, memabukkan, bahkan meracuni pembacanya. Dengan demikian, barulah penyair tersebut dianggap cerdas dan “berhasil” meramu puisinya. Gaya, teknik, bahasa yang menonjol atau menyimpang dari yang biasa, menggunakan cara yang baru. Membuat sesuatu yang umum menjadi asing, akan membuat puisi itu menjadi “agresif” dan berpengaruh (setidaknya pada jiwa) pembacanya.
Licentia Poetica
Puisi terbentuk dari bahasa. Tanpa adanya bahasa, tidak akan terbentuk puisi. Bagi penyair, ada semacam istilah kewenangan istimewa dalam memperlakukan bahasa. Istilah ini dikenal sebagai licentia poetica. Terangnya, licentia poetica ialah “kebebasan” seorang sastrawan untuk menyimpang dari kenyataan. Dari bentuk atau aturan konvensional, untuk menghasilkan efek yang dikehendaki (Shaw, 1972:291).
Pada sisi lain (Sudjiman, 1993: 18) menyatakan, licentia poetica kurang tepat jika diterjemahkan sebagai “kebebasan”. Mungkin lebih tepat “kewenangan”. “Kebebasan” memiliki konotasi semau-maunya, sedangkan “kewenangan” bermakna ada keabsahan.
Mendasari dua pendapat di atas, istilah licentia poetica menyiratkan adanya semacam dispensasi bagi penyair untuk tidak mematuhi tata/norma kebahasaan. Dispensasi yang diberikan pada penyair, agar penyampaian gagasannya dalam usaha menghasilkan efek diinginkan dalam puisi yang dihasilkan. Dengan kelonggaran dari norma tata bahasa ini, apakah penyair bisa menjalankan tugas sebagai defamiliarisasi? Belum tentu!
Kebebasan (saya lebih sependapat versi Shaw) dari aturan bahasa konvensional, tidak dapat dijadikan tonggak. Apakah puisi tersebut berhasil “mengungkap apa yang tidak terungkap.”
Penyair William Worthworth pernah mengatakan, puisi sebagai the best words in the best order (kata-kata terindah dalam bentuk terindah). Tidak harus begitu sebenarnya. Indah dalam pandangan Worthworth terlalu terpokok pada segi struktural atau tipografi puisi. Padahal, puisi haruslah memiliki pesan dan “efek samping” bagi pembacanya.
Tentunya untuk menimbulkan dampak ini harus diolah dalam kata-kata indah sedemikian rupa oleh penyair. Puisi itu layaknya permainan kata, menjadi medium antara penulis dengan pembacanya. Disinilah tugas penyair sebagai defamiliarisasi.
“Membuat sesuatu yang familiar/mudah dicerna menjadi tak begitu saja ditangkap maknanya dengan sekali baca.” (Yusri Fajar, Horison XLIX/2/2015).
Dengan tugas defamiliarisasi, terungkap kompleksitas penyair sesungguhnya. Sebagai produsen puisi, penyair juga harus mempertimbangkan fungsi/manfaat bagi pembaca. Contoh dalam puisi “Salju” karya Wing Kardjo (1937-2002).
Ke manakah pergi/ mencari matahari/ ketika salju turun/ pohon kehilangan daun.// Ke manakah jalan/ mencari lindungan ketika tubuh kuyup/ dan pintu tertutup.// Ke manakah/ lagi mencari/ api, ketika bara hati// Padam, tak/ berarti./ Ke manakah/ lari selain mencuci diri.
Perasaan yang terkandung dalam puisi diatas, (tafsir pribadi saya) cenderung pada nilai religiusitas (ketuhanan). Kehidupan penyair yang lama mukim di Jepang, terpresentasikan dalam puisinya. Nilai kepercayaan pada yang suci, (ke manakah/ lari selain mencuci diri). Menunjukkan eksistensi manusia selalu akan kembali kepada yang suci. Inilah yang disebut “bermanfaat bagi pembaca”. Memberi penerangan bahwa saat telah pergi, kehilangan, mencari, kuyup, tertutup, dan tak berarti, hanya mencuci diri-lah sebagai solusi atas segala cobaan yang dihadapi.
Identitas Penyair
Seni (dalam hal ini puisi) adalah ruh manifestasi keindahan manusia yang dituangkan dalam proses penciptaan. Dia lahir bersamaan dengan kelahiran manusia itu sendiri. Art is a old as mankind (seni berumur setua manusia).
Dengan seni, manusia berimajinasi. Dapat melahirkan karya sesuai keinginannya, berupa lukisan, patung, puisi dan lainnya. Melalui karya lukisan dia disebut pelukis, dengan patung dia disebut pematung, dengan puisi dia disebut sebagai penyair.
Identitas penyair selama ini menjadi absurditas. Seorang penyair tidak perlu orang mengakui bahwa ia adalah penyair. Dia juga tidak perlu mengukuhkan diri sebagai seorang penyair. Tidak ada istilah pelantikan penyair. Penyair itu manusia bebas, begitulah pandangan masyarakat.
Tak jarang, persepsi publik terhadap penyair berorientasi negatif. Seseorang memilih jalan hidup menjadi penyair, tersebab dia tak memiliki keahlian dan kemampuan apapun! Benarkah demikian? Saya kira tidak!
Taraf imajinasi setiap orang tentu berbeda. Seorang penyair haruslah mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Imajinasi yang dihasilkan bisa aneh, asing, eksentrik atau bohong. Imajinasi tetap berpijak pada realitas.
“Mana mungkin ilham menyambarmu dan imajinasi mengurai dalam bait-bait sajakmu, kalau engkau tidak berdiri di suatu realitas” tulis Sutardji dalam sebuah esainya. Dengan didasari realitas pula seseorang memantapkan diri menjadi penyair. Bukan hanya dengan angan-angan belaka, seseorang berangkat menjadi penyair.
Identitas pada diri penyair yang tidak bersungguh-sungguh menjadi penyair bisa memunculkan kegelisahan. Seringkali penyair “jadi-jadian” ini mempertanyakan jati diri kepenyairannya.
Benarkah aku memilih jalan penyair? Bagi yang mengukuhkan niatnya menjadi penyair akan tetap tegar bagi karang. Chairil Anwar sejak di Medan pada usia 15 tahun dengan sepenuh hati memantapkan dirinya masuk dunia kepenyairan. Baru pada tahun 1941 dia pergi ke Jakarta sebagai penyair yang matang, sekaligus dengan sikap dan kepribadian yang terarah.
Sekitar dua-tiga tahu di Jakarta dia meledakkan “bom” yang dibawanya dari Medan. Chairil menjadi seorang penyair besar, ternama dan buah bibir dimana-mana. (Damiri, 2014:101).
Demikianlah, ke-revolusioner-an penyair yang memliki kepiawaian mengolah kata-kata menjadi luar biasa. Semua berawal dari sikap dan kesungguhan memantapkan diri menjadi seorang penyair. Jadi sekarang tentukan, apakah anda memilih menjadi penyair atau tidak!? Jika tidak, yang bukan penyair tidak ambil bagian!