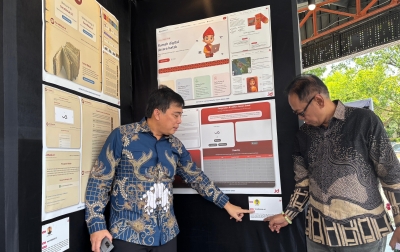Oleh: Sartika Sari
PENCERITAAN kembali kisah yang telah menjadi milik masyarakat budaya ke dalam bentuk yang lebih modern. Menjadikannya tantangan yang lebih bagi seorang pengarang. Dia memikul tanggung jawab untuk menyampaikan segala sesuatu yang telah dipahami masyarakat luas. Tentu dengan kadar yang tepat, mendekati realita yang ada. Pengurangan dan penambahan “bumbu” dituntut sesuai dengan yang seharusnya. Jika tidak, yang tercipta adalah bentuk-bentuk baru. Cenderung mengundang kekeliruan tafsir atau justru berujung pada perubahan esensi cerita.
Pada umumnya, pengarang dalam kerja kreatif seperti ini, cenderung lebih serius memantapkan pengetahuan mengenai latar. Tak lupa suasana lingkungan, kondisi sosial masyarakat budaya dan karakter tokoh. Konsep telah dimiliki dalam kisah sebelumnya menjadi pemantik. Kemudian diolah menjadi sebuah bangunan ilustrasi baru. Aktivitas ini, menurut Baudrillard, sebagai simulasi. Penciptaan kenyataan melalui model konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan mitos yang tidak dapat dilihat kebenarannya dalam kenyataan (Azwar, 2014).
Lebih lanjut, Baudrillad menyublim aktivitas tersebut dalam istilah hiperealitas untuk menjelaskan perekayasaan (dalam pengertian distorsi) makna di dalam media. Hiperealitas komunikasi, media dan makna menciptakan satu kondisi, kesemuannya dianggap lebih nyata daripada kenyataan.
Dalam konteks yang sama, Wisanggeni, dalam perwayangan Jawa bertindak sebagai hypogram. Menurut Riffaterre, seorang kritikus sastra dan pakar semiotika, merupakan sumber interteks. Landasan untuk menciptakan karya-karya yang baru, baik dengan cara menerima maupun menolaknya.
Dalam proses pengamatan dan analisis Wisanggeni yang ditulis Seno Gumira Ajidarma (selanjutnya disebut SGA) dengan yang ada dalam perwayangan Jawa. Sudut pandang untuk menemukan bentuk-bentuk baru yang dimunculkan SGA sebagai penulis, beragam.
Dalam analisis ini penulis akan merujuk pada sudut pandang Baudrillard. Dikarenakan banyaknya kemunculan simulasi yang mendampingi dan membangun ilustrasi tokoh Wisanggeni SGA. Baudrillard menampilkannya sebagai proses penciptaan bentuk nyata yang tidak ada asal-usul atau referensi realitasnya, penanda sebagai duplikat dari dirinya sendiri, sebagai simulacrum.
Berdasarkan beberapa sumber ditemukan, Wisanggeni adalah nama tokoh pewayangan yang tidak terdapat dalam wiracarita Mahabharata. Dia adalah tokoh asli ciptaan pujangga Jawa. Wisanggeni merupakan anak Arjuna dari Dewi Dresanala. Dia lahir karena Dresanala bersikukuh tidak menggugurkan kandungannya seperti tujuh bidadari yang juga hamil. Hamil sebagai anugerah Dewa kepada Arjuna yang membebaskan kahyangan dari raksasa Niwatakawaca karena menginginkan Dewi Supraba.
Dalam hubungan Arjuna dan Dewi Dresanala, para Dewa melarang lahirnya seorang anak. Karena Arjuna merupakan keturunan manusia, dianggap tidak pantas memberi keturunan untuk para Dewa. Ternyata Dewi Dresanala mengandung. Kelahiran Wisanggeni membuat ontran-ontran di Kahyangan karena hendak dibunuh oleh kakeknya Batara Brama. Pembunuhan atas perintah Sang Hyang Giri Nata atau Batara Guru. Dianggap menyalahi kodrat. Wisanggeni adalah titisan Sang Hyang Wenang, dia luput dari bala tersebut.
Ketika itu, Wisanggeni, dalam SGA dituliskan telah diculik dari hutan, beberapa saat setelah dia dilahirkan dan digigit oleh kakeknya sendiri. Dikenai bisa, namun Wisanggeni tidak juga terbunuh. Dengan amarah yang meluap-luap, kakeknya melontarkan ke laut. Wisanggeni kemudian ditemukan oleh Batara Baruna (Dewa Penguasa Lautan) dan Hyang Antaboga (Rajanya Ular yang tinggal di dasar bumi), yang menjadikan Wisanggeni punya kemampuan yang luar biasa.
Kehidupan Wisanggeni dalam perwayangan Jawa secara tulisan memang belum penulis temukan. Dari beberapa sumber diduga merupakan pihak kedua (pengamat) kisah dalam perwayangan Jawa. Secara lisan Wisanggeni dicitrakan sebagai tokoh angkuh, namun baik hatinya dan suka menolong. Ini berkaitan dengan namanya yang berasal dari wisa = bisa dan geni = api.
Tak peduli siapapun pasti dibakarnya. Musuh atau saudara, teman atau tetangga. Kriterianya hanya satu, yang dibicarakan adalah kebenaran, dan kebatilan adalah musuhnya. Dalam hal berbicara, Wisanggeni tidak pernah menggunakan basa krama (bahasa Jawa halus) kepada siapa pun, kecuali kepada Sanghyang Wenang.
Alur dan konflik Wisanggeni dalam kancah perwayangan Jawa cenderung mirip dengan apa yang dituliskan SGA ke dalam teks. Jika pada umumnya secara lisan yang dituturkan para dalang berfokus pada dialog yang menghubungkan antartokoh, dalam Wisanggeni ditulis SGA. Deskripsi suasana menjadi berperan penting untuk mendukung pembentukan imajinasi dan interpretasi pembaca mengenai suasana pada masa itu.
Selayaknya tulisan-tulisan cerita modern, SGA membangun deskripsi yang padu. Bentuk deskripsi-deskripsi tersebutlah yang kemudian, menurut penulis, menarik untuk ditelusuri sebagai bentuk simulacra. Beberapa deskripsi yang dianggap kuat di antaranya adalah sebagai berikut.
Padang pasir panas dan sunyi dan debu mengepul dan berterbangan dihembus angin kering. Dari balik muncul seorang laki-laki berpakaian compang-camping. Berjalan tersaruk-saruk memasuki kota yang mengakhiri lautan padang pasir itu. Ketika matahari menyemprot dengan ganas dan wajah lelaki itu terlindung oleh sebuah caping lebar. Telapak kakinya dialasi terompah yang terbuat dari kulit kerbau.
(Wisanggeni, hlm. 1)
Secara fisik, Wisanggeni dalam perwayangan Jawa disebutkan, adalah pemuda yang tampan dan sakti. Dalam SGA, ilustrasi fisik seorang Wisanggeni menjadi lebih utuh. Jika dikaitkan dengan kemunculan kembali Wisanggeni yang sebelumnya hidup di laut dan lapisan dasar bumi, tentu deskripsi SGA ihwal tampilan Wisanggeni masih masuk akal. Terutama pada pakaiannya yang seperti pengemis. Hanya menggunakan semacam cawet dan caping serta penampilan fisiknya yang berewokan, tak terurus. Da tidak berpakaian seperti manusia lain. Dengan adanya bangunan ilustrasi ini, pembaca lebih “duduk” dalam memahami Wisanggeni.
Sadar atau tidak, deksripsi yang ditulis Seno berhasil mendekatkan pembaca dengan Wisanggeni. Meski berasal dari berpuluh-puluh tahun yang lalu, melalui keterangan yang diberikan Seno, jarak tersebut tersublim. Simulacra yang dibangun SGA sangat kuat.
Seyogianya sebuah cerita baru, SGA juga menjawab pertanyaan banyak pembaca mengenai letak dan rupa “kahyangan” yang umumnya merebak. Dalam petikan; Suralaya selalu sejuk dan gemerlapan dan udaranya selalu cerah berkat kesaktian para dewa. Pembaca dengan mudah dapat menginterpretasikan bagaimana keadaan kahyangan. Kemudian, dimanakah letaknya?
“Kahyangan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, Kahyangan bukan sekedar nama suatu tempat. Hanya kesaktian dan kebatinan tinggi, akan mampu menjajakinya. Kemudian dilanjutkan dalam dialog, ‘Biarpun kau putari bumi sampai tujuh kali, kita tak akan sampai Wisanggeni,’ ujar Hanoman yang lahir dan dibesarkan di Surlaya.”
(Wisanggeni, hlm. 58)
Dalam deksripsi tersebut, secara implisit, SGA menerangkan dimana sebenarnya Kahyangan itu. Sebuah tempat yang selama ini dipertanyakan ternyata diperjelas oleh Seno. Selain deskripsi-deskripsi, SGA turut membangun ilustrasi tentang dewa pengatur kehidupan jagad raya, tersembunyi jauh dari manusia awam. Dalam tulisannya, SGA menyebutkan:
“Sanghyang Pramesti yang selalu bertaburkan cahaya gemilang sehingga membuat silau yang melihatnya itu kini meninggalkan ekor cahaya yang panjang bagaikan sebuah komet. Bau dupa dan taburan bunga yang selalu mengirinya buyar di ruang angkasa yang sunyi tak berpenghuni.”
(Wisanggeni, hlm. 63)
Simulacra diciptakan SGA melalui narasi. Dialog dan deskripsi terhadap tokoh-tokoh dalam cerita Wisanggeni berikut suasana yang terjadi pada masa itu membangun. Bangunan utuh tentang Wisanggeni dengan lebih nyata daripada jika secara lisan yang kita dengar dari para dalang. Seno Gumira Ajidarma “mendudukkan” segala perseteruan, tindakan dan kondisi kisah Wisanggeni. Terkesan lebih “baru” dan rill. Sebagai penulis (kedua) setelah kisah perwayangan asli, SGA berhasil melakukan naturalization. Pembaca tidak merasa asing dengan tokoh dan suasana yang diceritakan.
Selain bentukan simulacra pada penggambaran tokoh dan suasana, menarik dilakukan SGA yaitu pada teknik penceritaan. Salah satunya ketika mempertemukan Batara Guru dengan Pak Semar. Diceritakan sebagai kakaknya yang merupakan seorang petani. Kelihaian SGA dalam menulis cerita memang sudah tidak diragukan lagi. Cerpen dan novel yang dia tulis membawa karakteristik khas. SGA tidak hanya lihai menghadirkan tokoh-tokoh yang kuat dalam cerpennya. Juga lihai meliuk-liukkan alur, sehingga terkesan lebih menarik dan menantang.
Keberanian SGA dalam menegaskan karakter tokoh-tokoh dalam novel Wisanggeni Sang Buronan menjadi salah satu kekuatannya. Seno, secara sadar juga menyebutkan, ada pengaruh dari babonnya, R. A Kosasih dan Lahirnja Bangbang Wisanggeni (Bandung: PT Melodi, 1970, 4 jilid a 82 halaman). Tentu saja, kemudian hal tersebut berperan besar dalam proses kreatif penulisan kisah ini.
Wisanggeni, dalam perwayangan Jawa dikisahkan memiliki akhir hidup yang mengharukan. Dia merelakan diri menjadi tumbal demi kemenangan para Pandawa menjelang meletusnya perang Baratayuda. Beberapa waktu kemudian bersama Antasena, mencapai moksa. Musnah dari jasad mereka. SGA tidak melakukan hal yang serupa.
Fenomena seperti ini, menurut Damono (dalam Sastra Bandingan, 2009 : 21) merupakan kecenderungan dimiliki sastrawan untuk meminjam langsung atau tak langsung. Sumber pinjaman itu bermacam-macam. Mulai dari karya sastra sampai berbagai jenis teks kronik dan sejarah. Kenyataannya, hingga saat ini kemunculan berbagai jenis karya sastra terinspirasi atau terpengaruh karya sastra klasik semakin banyak. Salah satunya adalah novel Wisanggeni yang ditulis SGA.
Sastrawan yang juga merupakan seorang jurnalis, secara gamblang menyebutkan. Kisah Wisanggeni merupakan hasil penelusurannya terhadap tokoh-tokoh perwayangan Jawa. Ketertarikan Seno pada tokoh Wisanggeni bukan berarti tanpa alasan. Jika pada umumnya kisah wayang terkenal sebagai kisah cenderung membosankan. Seno hendak melakukan perubahan pada stereotip tersebut. Seno menghadirkan kembali tokoh Wisanggeni dengan senyata-nyatanya. Berikut dukungan penggambaran suasana yang jelas. Alur menarik dan teknik bercerita yang jauh lebih modern.
Alhasil, membaca Wisanggeni yang ditulis SGA sangat mengurangi beban membaca dan memahami teks aslinya. Tidak sebatas itu, SGA turut melakukan sejumlah inovasi-inovasi lain yang menarik.
Puncaknya terjadi pada ujung cerita. Barangkali jenuh dengan kesamaan akhir cerita dengan tokoh-tokoh wayang yang lain, termasuk Wisanggeni dalam cerita aslinya, SGA melakukan perombakan total. Wisanggeni dalam SGA tidak mengakhiri hidupnya dengan moksa. SGA membangunkan kembali Wisanggeni dari ‘tekanan batin’ yang ia rasakan. Keberadaannya ang mengundang banyak huru-hara. Keterasingan dia rasakan kemudian membawanya pada satu-satunya pilihan. Dia tidak bisa merasakan kebahagiaan hidup bersama ayah dan ibunya. Satu-satunya dia lakukan, hidup seperti manusia biasa. Menganggap hidup di bumi adalah kodratnya.
Melalui perenungan cukup panjang, dia memutuskan untuk hidup di suatu kota yang dilihatnya. Tulisan SGA, cukup bagus dengan sebuah istana terletak di antara alun-alun. Kota terletak di antara dua alun-alun. Kota terletak di antara gunung dan laut. Ketika Wisanggeni sampai pada kota itu, dia mendapati kerumunan warga masih menonton wayang.
Seno, dengan lihai kemudian menempatkan tokoh Wisanggeni sebagai tokoh yang menonton penceritaan dirinya sendiri dalam perwayangan Jawa yang sedang dimainkan oleh dalang. Dia menelusup di antara orang-orang yang beberapa di antaranya itu sudah tertidur.
Pada ujung cerita, ketika wayang Wisanggeni dikatakan telah moksa oleh dalang, Wisanggeni justru terbahak-bahak melihat kisahnya sendiri. Dari barisan penonton, suaranya terdengar sangat keras. Orang-orang merasa terganggu dengan suaranya. Beramai-ramai menyeret lelaki gondrong yang pakaiannya seperti pengemis itu, menjauh dari arena pertunjukan.
Rupanya Wisanggeni tak berhenti tertawa. Suaranya makin keras. Orang-orang pun semakin geram. Mereka beramai-ramai menyeret dan menendangi Wisanggeni. Wisanggeni tetap terbahak-bahak. Dari jauh suara Ki Dalang masih terdengar diiringi gamelan dengan suara rebab yang menyayat-nyayat. Wisanggeni tertawa terus. Entah karena telah berada pada puncak kesedihan atau dia sedang belajar melupakan pesakitan.
Wisanggeni dalam dua penulis berbeda berakhir pada cerita yang berbeda pula. Perbedaan ini sekaligus menjadi bukti, kemunculan karya sastra tak bisa lepas dari pengaruh peristiwa atau kisah yang sudah ada.
Penulis; Mahasiswa Pascasarjana Universitas Padjadjaran