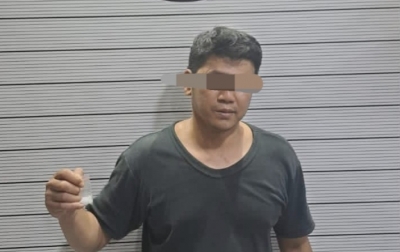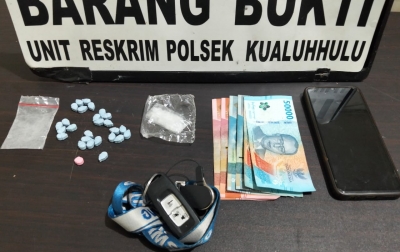Oleh: Dr. Sadieli Telaumbanua, M.Pd., M.A
Setiap memperingati Hari Guru Nasional/HUT PGRI di negeri ini, kata-kata pada judul tulisan ini senantiasa bergemuruh. Sejak dimulainya upacara hingga selesai, biasanya yel-yel itu bergema dan kadang membahana. Maklum, para guru terbiasa berbicara “lantang” di depan kelas.
Pada tahun ini, tepatnya 25 November 2015, seluruh guru di tanah air ini memperingati hari jadi mereka. Adalah hal yang sangat membanggakan para pendidik bahwa hari lahir PGRI ditetapkan sebagai HGN (periksa Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 dan UU Nomor 14 tahun 2005). Tema perayaan HGN/HUT PGRI tahun ini adalah, “MEMANTAPKAN SOLIDITAS DAN SOLIDARITAS PGRI SEBAGAI ORGANISASI PROFESI YANG KUAT DAN BERMA MARTABAT”. Sungguh sebuah tema yang memberi spirit kependidikan dan keguruan bagi seluruh guru di negeri ini. Akan tetapi, tunggu dulu! Salah satu pertanyaan yang urgen dijawab adalah, “Apakah sebutan profesional telah terpatri dalam diri guru di negeri? Sembari merayakan HGN dan HUT PGRI, ada baiknya kita para guru (baca: pendidik) tafakur sejenak sambil berefleksi akan hakikat profesionalisme guru.
Sertifikat Pendidik, Profesionalkah?
Pemberian sertifikat pendidikan sebagai pengakuan atas keprofesionalan guru telah berlangsung sejak tahun 2007. Para guru yang memiliki sertifikat pendidik ini mendapatkan penghasilan satu kali gaji pokok yang dibayar (kadang per triwulan, sering per semester, hampir tidak pernah per bulan). Hidup guru pun semakin membaik, jika tidak mau disebut sejahtera. Kendaraan roda empat pun mulai terlihat berjejer di sejumlah halaman sekolah. Sungguh sebuah pemandangan baru di lingkungan pendidikan (baca:sekolah) pada era reformasi ini. Para pendidik tidak mau ketinggalan dengan rekan-rekannya pegawai negeri sipil lainnya. Guru yang selama ini identik dengan sepeda dayung (baca: guru Umar Bakri) terkikis pelan dan pasti. Lagi-lagi, sertifikat pendidik membawa nikmat. Hidup Guru!
Sertifikat pendidik diberikan oleh pemerintah (baca: Kemdikbud melalui LPTK) setelah para guru memiliki empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) melalui PLPG dan/atau portofolio (ke depan melalui PPG). Para guru tahu persis indikator setiap kompetensi termasuk standar kompetensi guru setiap satuan pendidikan. Dengan kepemilikan kompetensi ini, kualitas lulusan satuan pendidikan (baca: siswa) semakin membaik sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Bagaimana realitasnya? Hasil uji kompetensi guru tahun 2012 (baik yang telah mendapatkan sertifikat pendidik maupun yang belum) masih jauh di bawah standar. Hal ini membuktikan bahwa sertifikat yang telah dimiliki oleh guru tidak berpengaruh pada kepemilikan kompetensi. Lebih memprihatinkan lagi jika dikaitkan dengan kualitas peserta didik yang diluluskan.
Pengalaman saya (tidak dapat digeneralisasi) sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli (2012 – 2015) menunjukkan bahwa dari kurang lebih 3000 guru (PNS dan non-PNS untuk semua satuan pendidikan) sekitar setengahnya telah mendapatkan sertifikat pendidik (baca: profesional). Guru yang benar-benar melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi dapat dihitung dengan jari. Pembelajaran berlangsung apa adanya. Penggalan syair lagu, “aku masih seperti yang dulu” relevan dilekatkan kepada teman-teman guru ini. Dalam kunjungan ke sekolah-sekolah saya sering bergumam,”Apalah arti sebutan pendidik profesional yang disandang oleh guru-guruku ini? Apa yang keliru dalam penyelenggaraan sertifikasi guru ini? Semakin banyak pelatihan guru, semakin tidak terlihat hasilnya”. Setelah menjadi akademisi pun, hingga kini, saya belum menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tidak mungkin juga diikuti ajakan Ebiet G.Ade untuk bertanya pada rumput yang bergoyang. Tampaknya, sebutan pendidik profesional bagi sebagian besar guru di negeri ini perlu dikaji ulang. Sekedar diketahui bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (pasal 1, ayat 4, UU Nomor 14 Tahun 2005). Jika ini yang diacu, fenomena saat ini ibarat, “jauh panggang dari api”.
Kompetensi Altruisme
Selama menjadi guru/dosen, kepala sekolah/rektor, dan birokrasi pendidikan di daerah yang tergolong “tertinggal”, saya mengamati bahwa sebagian besar guru sedang minus sifat altruistik. Para guru telah luntur sifat edukasi/pedagogik atau tarbiyah (usaha membawa keluar dan membimbing atau mengembangkan potensi anak didik sehingga berpengaruh pada didaktiknya (pembelajaran). Tidak sedikit guru yang berstatus pendidik profesional masih menggunakan desain atau model pembelajaran yang “kadaluarsa” (baca: transaksional). Model pembelajaran mutakhir yang diperoleh dalam diklat atau workshop tersimpan rapi dalam almari dan meja kerja. Sungguh sangat kontras dengan kinerja guru era 50-an hingga 80-an yang selalu membaharui pola pembelajaran. Patut diakui bahwa terdapat juga guru-guru yang selalu berinovasi dalam membelajarkan anak-anak.
Kepemilikan kompetensi guru (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional), kualifikasi akademik (S-1/D-4), sehat jasmani dan rohani serta kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 2, PP No 74 Tahun 2008) perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Namun, jika tidak disertai dengan kepemilikan kompetensi altruistik (ketulusan/keikhlasan) hanya akan berhenti pada formalitas belaka. Profesi guru sebatas memenuhi kebutuhan hidup belum menjadi bagian dari hidup dan kehidupan. Memang diakui bahwa kompetensi altruistik ini telah terakomodasi dalam kompetensi kepribadian. Tetapi justru kompetensi ini jarang menjadi mata diklat. Uji Kompetensi Guru (UKG) yang saat ini berlangsung lebih menekankan pada kompetensi pedagogik dan profesional. Kompetensi kepribadian dan sosial dipandang sebelah mata.
Menurut saya, pada dimensi inilah kelemahan penyelenggaraan diklat profesi guru. Oleh karena itu, memasuki 70 tahun RI (termasuk PGRI), api kompetensi altruistik perlu dikobarkan. Agama apa pun senantiasa mengajarkan untuk selalu melakukan yang terbaik kepada siapa pun. Nilai-nilai budaya kita di nusantara ini sarat akan sifat altruisme. Ungkapan Jawa,misalnya, “sepi ing pamrih rame ing gawe” menunjukkan sifat ketulusan dan keikhlasan menolong sesama.
Borrong (2006) mengartikan altruisme sebagai kewajiban yang ditujukan pada kebaikan orang lain. Suatu tindakan altruistik adalah tindakan kasih yang dalam bahasa Yunani disebut agape (tindakan mengasihi atau memperlakukan sesama dengan baik semata-mata untuk tujuan kebaikan orang itu dan tanpa dirasuki oleh kepentingan orang yang mengasihi) Maka, tindakan altruistik pastilah selalu bersifat konstruktif, membangun, memperkembangkan dan menumbuhkan kehidupan sesama. Dari hal tersebut seseorang yang altruistik dituntut memiliki tanggung jawab dan pengorbanan yang tinggi. Guru sebagai pendidik profesional sejatinya memiliki kompetensi altruistik ini. Caranya? Perlu membebaskan diri dari sifat hedonisme dan konsumerisme. Menjalani hidup seturut rahmat dan anugerah Ilahi. Orang bijak pernah berujar, “cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu”. Gaji dan tunjangan profesi jika dikelola dengan bijak, insya Allah, cukup. Mendidiklah dengan kasih dan mengajarlah dengan hati. Solidaritas!
Bersamaan dengan itu, pemerintah (Kemdikbud dan Pemerintah Daerah) perlu menyederhanakan (baiknya meniadakan) semua beban administrasi yang mesti dipenuhi oleh guru terutama dalam sistem kenaikan pangkat/jabatan termasuk syarat mendapatkan tunjangan profesi. Mari kita memberi ketenangan dan ketentraman kepada semua guru agar mereka fokus pada kegiatan membelajarkan anak-cucu kita. Semoga.***
(Penulis Dosen Kopertis Wilayah I dpk pada Universitas Prima Indonesia, mantan Rektor IKIP Gunungsitoli dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli).