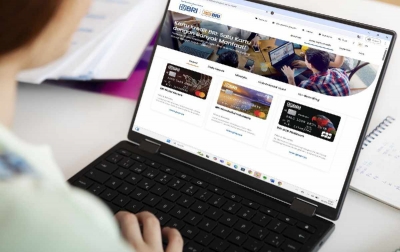Oleh: Sartika Sari
Sejak Ayat-Ayat Cinta berhasil menarik perhatian publik, fenomena ekranisasi semakin menjamur di Indonesia. Dunia perfilman semakin ramai. Dengan film-film diadaptasi dari novel, yang pada umumnya adalah novel best seller. Alhasil, khalayak dihadapkan pada dua teks naratif. Menurut Chatman (dalam Aderia, 2013) dijabarkan menjadi dua. Pertama, cerita atau isi. Kedua wacana atau ekspresi.
Cerita dapat terbentuk dari peristiwa dan eksistensi. Bentuk dari wacana atau ekspresi adalah struktur dari transmisi naratif. Substansi dari wacana atau ekspresi berupa manifestasi yang dapat berbentuk verbal, sinematik (film), balet, pantomime, dan lain-lain.
Perubahan media ini, disebut Sapardi (2012:96) sebagai proses alih wahana. Perubahan dari satu jenis kesenian ke dalam jenis kesenian lain. Alih wahana dimaksudkan di sini tentu berbeda dengan terjemahan. Alih wahana adalah pengubahan karya sastra atau kesenian menjadi jenis kesenian lain. Proses ‘pentransferan’ kisah dari novel ke film, didasari oleh adanya kesamaan susbtansi yang dikandung.
Novel adalah karya yang memuat kisah fiksi. Menurut Nurgiyantoro (dalam Aderia, 2013) novel bersifat imajinatif. Mengemas persoalan kehidupan manusia secara kompleks dengan berbagai konflik, sehingga pembaca memperoleh pengalaman-pengalaman baru tentang kehidupan.
Pada tahun 2003, Ronggeng Dukuh Paruk ditulis oleh Ahmad Tohari. Mengisahkan tentang kehidupan masyarakat di sebuah desa terpencil. Memiliki kepercayaan adat tentang keberadaan tanah leluhur dan seorang ronggeng yang dipuja-puja, diterbitkan. Dalam novel, penulis mendeskripsikan dengan sangat detil. Bagaimana kehidupan masyarakat yang masih terbilang primitif ke dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan yang khas.
Pada tahun 2011, Salto Film, meluncurkan Sang Penari, terinspirasi dari novel Ronggeng Dukuh Paruk. Ekranisasi dilakukan atas novel Ahmad Tohari benar-benar menghasilkan tafsir baru. Mengacu pada cara pandang Eneste, maka beberapa perubahan yang terjadi yaitu:
1. Pengurangan
Eneste (1991:61) menyatakan dalam ekranisasi, pengurangan dilakukan terhadap unsur karya sastra seperti cerita, alur, tokoh, latar, maupun susasana. Berdasarkan pertimbangan pengemasan dan penayangan film, melalui proses pengurangan atau pemotongan, tidak semua hal diungkapkan dalam novel, dijumpai pula dalam film.
Membaca Ronggeng Dukuh Paruk, pembaca akan digiring mulai dari suasana Dukuh Paruk dengan Srintil dan Rasus yang masih kecil.
Srintil kecil, harapan baru bagi Dukuh Paruk. Pedukuhan miskin, terpencil memegang kuat amanah leluhurnya, Ki Secamenggala untuk menjaga jati diri Dukuh Paruk melalui perlambang seorang Ronggeng. Sejak Ki Sakarya mendapati cucunya, Srintil, yang orang tuanya meninggal akibat peristiwa tempe bongkrek, tengah menari dan terlihat kenes laiknya seorang Ronggeng.
Dukuh Paruk bergairah kembali. Sebelas tahun sudah Dukuh Paruk kehilangan ronggengnya. Ki Sakarya langsung menemui Kartareja, seorang dukun ronggeng, untuk memberitahu tentang Srintil. Tidak ada perdebatan pelik, dengan sangat bergembira juga Ki Kartareja langsung memungut Srintil dan mendandaninya seperti seorang ronggeng.
Tak lama kemudian, Srintil menjalani ritual bukak kelambu, sehingga dia resmi diangkat sebagai seorang ronggeng. Srintil menjadi ronggeng, Rasus bekerja menjadi tobang, melayani para tentara dalam pekerjaannya kemudian diangkat menjadi tentara.
Pertemuan Rasus dan Srintil diwarnai haru dan kesedihan. Rasus mesti melanjutnya pengabdian sebagai seorang tentara. Srintil menetap di Dukuh Paruk sebagai seorang ronggeng. Keadaan ini rupanya menyebabkan Srintil patah hati. Karena itu sejak kepergian Rasus, dia tidak meronggeng dalam waktu yang cukup lama.
Barulah ketika diundang ke acara agustusan oleh pihak kecamatan, berkat dorongan Sakum, Srintil mau menari kembali. Selain menari, Srintil juga menerima tawaran menjadi gowok di Alaswangkal.
Tawaran menari datang semakin banyak. Srintil dan grup ronggeng Dukuh Paruk bertemu dengan Pak Bakar, kemudian memberi banyak pembaharuan pada Dukuh Paruk. Tidak seorang pun mengetahui siapa sebenarnya Pak Bakar. Lambat laun, semuanya terungkap.
Dukuh paruk menjadi buronan karena dianggap terlibat dalam komunis. Sebagian besar warga ditangkap. Mendengar kabar itu, Rasus datang ke Dukuh paruk, menjenguk neneknya yang sudah dua tahun lebih da tinggal. Di pangkuan Rasus, sang nenek menghembuskan napas terakhir.
Beberapa tahun setelah kejadian itu, Srintil berhasil keluar dari tahanan dan kembali ke Dukuh Paruk. Dia ingin memulai hidup baru, meninggalkan masa lalunya sebagai seorang ronggeng. Dia bertemu dengan Bajus, seorang pemborong dari Jakarta. Perlahan-lahan, perasaannya terhadap Rasus memudar dan tertutupi oleh cinta kasih kepada Bajus.
Srintil sangat berharap Bajus menikahinya. Namun harapan itu sirna. Bajus ternyata hanya memanfaatkan Srinti untuk menjadi ‘pelayan’ bosnya. Srintil dihantam depresi hebat. Hingga akhirnya ia tak bisa mengontrol dirinya lagi.
Dalam Sang Penari, penayangan dimulai dengan situasi penahanan warga di sebuah ruangan kecil. Kemudian dilanjutkan dengan kedatangan Rasus ke Dukuh Paruk, pasca penangkapan seluruh warga Dukuh Paruk, kecuali Sakum.
Pemilihan adegan dalam novel, justru terletak hampir pada akhir cerita. Menunjukkan yang ingin dilakukan film adalah pengulangan alur (sorot balik). Setelah scene itu, barulah muncul flashback masa kecil Rasus dan Srintil. Langsung pada ketika Rasus dan Srintil dewasa. Kehidupan masa kecil yang detil dipaparkan dalam novel disublim dalam bentuk beberapa montase saja. Hal ini tentu menyebabkan banyak cerita Srintil dan Rasus serta masyarakat Dukuh Paruk yang berkurang.
Setelah pengurangan pada kehidupan masa kecil Rasus dan Srintil, masa-masa awal kemunculan Srintil, dalam film juga terjadi pengurangan pada cerita Srintil yang menjadi gowok. Srintil berada dalam konflik cerita dengan Marsisus (bagaimana dia berusaha lari dari kejaran Marsisus) serta hubungannya dengan Bojes.
Sejumlah bagian menunjukkan, bagaimana kehidupan seksual Srintil. Juga Rasus dan warga Dukuh Paruk, dikemas dengan sangat rapi dan jauh dari kesan vulgar. Selain pengurangan pada bagian ini, dalam film juga tidak dimunculkan beberapa tokoh, termasuk dua anak Sakum dan Bajus.
2. Penambahan
Seperti halnya pengurangan yang terjadi pada ranah cerita, penambahan juga berada pada konteks yang sama. Eneste (1991:64) menyatakan, penambahan merupakan tindakan seorang sutradara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penting dari sudut filmis.
Mengenai indang di diri Srintil, dalam Rongeng Dukuh Paruk, Ki Sakaryalah yang mengetahui dan kemudian segera mengabarkan hal itu pada Kartajaya. Dalam film, sutradara menambahkan bagian Sakum yang berdialog dengan Srintil (menit ke 11.48). Dalam dialog, Sakum berkata, “Jenganten, aku ini sudah puluhan tahun kenal ronggeng. Suara jenganten itu sudah seperti ronggeng, bau badan jenganten itu bau badan ronggeng. Kalau nanti indangnya itu pergi, saya juga tahu.” Perkataan Sakum ini dilontarkan ketika Srintil sedang duduk di depan makan Ki Secamenggala. Kata-kata itu juga yang menguatkan keyakinan Srintil atas keronggengannya.
Pada film, ditunjukkan bagaimana Srintil melakukan pementasan pertama. Digelar Ki Sakarya di belakang rumah untuk menunjukkan pada dukun ronggeng, Srintil benar-benar ronggeng. Ki Kartareja belum mau mengakui keronggengan Srintil. Ada penambahan ketegangan pula antara Ki Sakarya dengan Kartareja karena perbedaan pendapat tentang ronggeng. Dalam novel, dituturkan, Sakarya dan Kertareja hanya mengintip Srintil ketika menari di bawah pohon nangka.
Pada scene lain juga terdapat penambahan cerita tentang bagaimana Rasus belajar membaca. Penayangan bagaimana suasana tahanan serta bagaimana warga diinterogasi petugas mengenai PKI.
3. Perubahan Bervariasi
Menurut Eneste (1991:65) ekranisasi memungkinkan terjadinya variasi-variasi tertentu antara novel dan film. Variasi ini bisa terjadi dalam ranah ide cerita, gaya penceritaan dan sebagaiya. Dalam mengekranisasi pembuat film merasa perlu membuat variasi-variasi dalam film. Agar terkesan, film didasarkan atas novel itu tidak seasli novelnya. Dalam Sang Penari, beberapa perubahan yang dilakukan di antaranya:
Pertama, Bakar muncul sejak pertama kali Srintil akan menjadi ronggeng. Dia muncul di sebuah warung dan langsung bertemu Rasus yang ketika itu masih menjadi pekerja biasa. Kebetulan sedang bertemu warga lain di warung itu. Dalam novel, Bakar muncul sejak Srintil menerima pentas agustusan dan ketika itu Rasus tengah menempuh pendidikan tentara.
Kedua, cara Rasus memberi keris dalam novel adalah diam-diam dan meletakkannya di samping Srintil. Rasus membungkusnya dengan bajunya agar Srintil mengetahui siapa yang memberikan keris itu. Dalam film, Rasus justru mengetuk jendela kamar Srintil, membangunkannya untuk memberi keris. Tanpa percakapan apa-apa (menit ke 27:45).
Dalam film ditunjukkan keris diperoleh dari jenganten, ketika peristiwa tempe bongkrek. Kemudian menjadi penanda, Srintil resmi menjadi ronggeng dan dipercaya Ki Kartajaya. Dalam novel hanya disebutkan, itu peninggalan ayah Rasus dan diberikan hanya sebagai hadiah kepada Srintil, karena kerisnya kebesaran.
Ketiga, hal yang dilakukan Rasus setelah malam bukak kelambu terjadi. Rasus bisa menghadang Dower dan memukulinya, sedangkan dalam novel adegan itu tidak ada.
Keempat, dalam novel Rasus bertemu dengan Sersan Slamet di pasar Dawuan. Ketika Sersan mencari bantuan untuk membantu menurunkan peti-peti serta barang-barang lainnya. Sersan menawari rasus untuk menjadi tobang. Itulah awal mula Rasus bergabung dengan tentara. Dalam film, dinyatakan, Rasuslah yang mendatangi markas para tentara dan meminta pekerjaan (menit 42:38)
Kelima, dalam film, nenek Rasus meninggal sebelum kasus penangkapan PKI. Dalam novel, itu terjadi ketika sudah benar-benar masa tegang PKI. Selain itu, pencarian Srintil oleh Rasus menjadi lebih tegang karena Rasus berusaha menembus barisan tentara penjaga para tahanan dan berteriak memanggil Srintil. Dalam novel, mereka bertemu lebih tenang, dan tidak bicara apa pun.
Keenam, dalam novel, dinarasikan, Srintil ditangkap ketika dia bersama Kartajaya. Melapor dan meminta pengayoman atas kericuhan yang terjadi di Dukuh Paruk. Berbeda dengan yang ditunjukkan dalam film, Srintil ditangkap ketika dia sedang di Dukuh Paruk, sama seperti warga yang lain.
4. Perempuan dalam Dua Persfektif
Selain pengurangan, penambahan dan perubahan variasi yang dilakukan. Dalam proses ekranisasi, secara keseluruhan menurut penulis, karakter yang dibentuk oleh novel dan film pun cenderung berbeda.
Ronggeng Dukuh Paruk menghidupkan Srintil dengan karakter yang lebih demokratis pada keadaan. Srintil anak Dukuh Paruk yang senang menari, menjadi ronggeng. Hal itu tidak dapat bertahan kuat ketika hatinya berada dalam dilema. Terutama ketika perasaannya terhadap Rasus demikian besar. Dia rela meninggalkan kehidupannya sebagai ronggeng. Hal ini tersurat dalam petikan dialog:
“Eh, Rasus. Mengapa kau menyebut hal-hal yang sudah lalu? Aku mengajukan permintaanku itu sekarang. Dengar, Rasus, aku akan berhenti menjadi Ronggeng karena aku ingin menjadi istri seorang tentara; engkaulah orangnya” (hlm. 105).
Dalam film (menit 01:00:26) Srintil bersikeras menjadi ronggeng:
“Maksud riko opo si? We jadi tentara, ora pantes maning jadi wong kampung? Sus, ronggeng ini duniaku. Wujud dharma baktiku pada duku Paruk. Ya kalau kamu memang begitu, ya lungo bae lah.” Srintil teguh dengan pilihannya sebagai seorang Ronggeng. Meskipun Rasus menawarkan pilihan untuk hidup bersama asalkan Srintil berhenti menjadi Ronggeng, tetapi Srintil menolak.
Pada novel dipaparkan, peranakan Srintil telah rusak karena telah ‘dimatikan’ oleh Nyai Kartajaya agar Srintil tidak bisa hamil. Dalam film, ketika Nyai Kartaraja ingin melakukan tindakan itu, Srintil menolak. Cerita ini terdapat pada adegan menit ke 47:12. Srintil memaksa menghentikan pijitan Nyai Kartajaya.
Dalam novel, kesan yang dimunculkan adalah sikap Srintil. Menurut saja pada ketentuan Kartaraja dan istrinya. Termasuk ketika Nyai Kertareja berniat untuk memasang sesaji untuk memutuskan perasaan Srintil dan Rasus. Dalam narasi tersebut, dikatakan Srintil tidak sengaja mengencingi sesaji yang dipendam dalam tanah gembur itu. Berbeda dengan yang ada dalam film, kesan yang dimunculkan adalah Srintil lebih cerdas yang mampu membaca gerak-gerik kedua dukun ronggeng itu.
Kesan ini diperkuat dengan ‘pembelokan’ akhir cerita. Dalam novel, Srintil pada akhirnya mengalami depresi karena mengalami kekecewaan luar biasa atas hubungannya dengan Bajus, seorang pemborong dari Jakarta. Srintil sudah sangat berharap Bajus akan menikahinya, pasca dia keluar dari tahanan dan dalam proses perbaikan diri. Srintil telah melakukan perubahan besar untuk memulai hidup baru sebagai seorang istri dan seorang ibu bukan seorang ronggeng.
Rupanya Bajus justru hanya memanfaatkan perasaan Srintil untuk menjadikannya ‘pelayan’ bos Bajus. Srintil yang mengalami penkhianatan ini tentu saja dirundung kekecewaan yang dalam. Terhempaslah ia dari segala kekuatan yang selama ini dia bangun. Srintil mengalami depresi.
Dalam film, pada ujung cerita Srintil tidak mengalami depresi. Justru mampu kembali tegar menjadi seorang ronggeng, didampingi oleh Sakum. Ketika Rasus menemukannya di sebuah pasar, Srintil menunjukkan ketegarannya mengampu beban sebagai mantan tahanan PKI, dan seorang ronggeng. Dia menari terus dan terlihat bahagia dengan pilihannya. Rasus tak mampu berbuat banyak. Hanya mengembalikan keris yang pernah menjadi milik Srintil.
Perbedaan pengemasan cerita dalam kedua wahana, pada akhirnya memberikan kesan berbeda-beda. Meski pada awalnya terasa, film belum mampu membawa seutuhnya cerita dalam novel, tapi film Sang Penari, cukup mewakili polemik Srintil sebagai ronggeng. Kendati demikian, tanggapan lain tetap berpeluang.
Penulis; Mahasiswa Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung