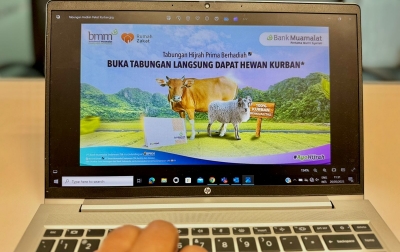Oleh: Diurnanta Qelanaputra.
Mulutmu harimaumu, sebuah kiasan yang menempatkan betapa berbahayanya ucapan seseorang. Pasca reformasi 1998, urusan mulut ini semakin menjadi-jadi. Atas nama demokrasi yang dimaknai sebagai kebebasan berbicara setelah dibungkam selama 32 tahun oleh rezim Soeharto, semua orang mudah bersuara menyampaikan pendapat dan mengeluarkan unek-uneknya. Apa yang tak cocok menurutnya, langsung diungkapkan kepada umum.
Dari buruh sampai anggota DPR yang terhormat, semua tiba-tiba menjadi nyinyir. Sedikit saja yang tak berkenan di hati, langsung diungkap. Media sosial, salah satu wadah tempat melepas pendapat. Tidak tanggung-tanggung setingkat presiden republik pun dihujat, lewat kata maupun gambar.
Sebenarnya tak ada yang salah jika kritik disampaikan secara konstruktif. Karena demokrasi tanpa kebebasan berpendapat sama saja demokrasi mandul. Persoalannya, mengapa harus mencaci, membully, bahkan memfitnah?
Itulah yang sering kita jumpai di media sosial saat ini, terutama setelah Joko Widodo terpilih menjadi presiden. Kasus terakhir yang kemudian dibantah adalah pertemuan antara Jokowi selaku presiden dengan masyarakat suku Anak Dalam dimana netizen menganggap pertemuan itu sudah direkayasa tapi kemudian dibantah dengan fakta-fakta foto dan kronologis oleh pihak yang ikut pertemuan tersebut.
Sebelum itu, kunjungan Jokowi ke AS juga dikomentari oleh seorang netizen yang menganggap kedatangan presiden dipandang remeh oleh Amerika karena tidak disambut Presiden Barack Obama, tanpa upacara penyambutan sambil membandingkan saat SBY presiden ke AS. Yang paling fatal, keremehan penyambutan Jokowi dan rombongan digambarkan dari adanya petugas cleaning service berdiri di depan pesawat kepresidenan RI. Belakangan apa yang diungkapkan netizen tersebut ternyata keliru 1.000 persen. Yang dikatakan petugas cleaning service ternyata petugas pemadam kebakaran dan alat yang dikira tong sampah adalah alat pemadam kebakaran modern untuk antisipasi jika terjadi hal yang tak diinginkan. Dan soal tidak adanya penyambutan oleh Presiden AS karena memang telah terjadi perubahan protokoler dimana presiden AS tidak menyambut langsung di bandara.
Fitnah dan hasutan untuk membenci, entah mengapa kini seolah menjadi “kewajiban” bagi sementara pihak. Dan itu bukan hanya ditujukan kepada Presiden Jokowi melainkan juga semua pihak di pemerintahan, lembaga legislatif, yudikatif mulai dari tataran tertinggi sampai terendah. Demikian juga pada elemen masyarakat dan profesi.
Ekspresi berpendapat bahkan terasa keluar dari koridor ketika menanggapi masalah masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti dalam kasus rumah ibadah, yang bertikai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sudah berdamai, tapi yang tidak menyaksikan langsung malah “kepanasan”, sibuk terus menghujat atas nama agama. Hujatan kebencian memprovokasi orang lain seperti laron lepas di media sosial. Sama halnya juga dalam konteks kesukuan dan ras. Ketika hukum akan ditegakkan, sebagian pihak kemudian mengaitkan dengan masalah rasis.
Apa yang terjadi pada hari-hari ini sesungguhnya sangat berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bangsa ini dulu dikenal bangsa yang menjunjung tinggi sopan santun, adat istiadat, tepo seliro, tenggang rasa, hormat menghormati. Kenapa sekarang berubah menjadi pemarah, nyinyir, penghasut? Kebablasan. Seenak perut mencaci orang lain dan menebarkannya lewat akun media sosial. Bahkan juga di media cetak. Apakah mereka yang kemaruk menghasut kebencian itu tidak pernah berfikir akibatnya akan sangat fatal bagi kelangsungan hidup bernegara?
Ada dugaan, hasutan kebencian itu berasal dari pihak-pihak yang kalah dalam Pilpres dan yang tersangkut oleh ketegasan hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena tak mau menerima perbaikan di negeri ini, tak mau menerima kekalahan dan mengakui kesalahan, maka kompensasinya adalah merecoki terus negeri ini dengan menebar rasa benci kepada pemerintah yang resmi, kepada pihak yang tidak disenangi, kepada semua yang dibencinya. Apa tujuannya? Mau membubarkan NKRIkah?
Salah Kaprah
Kita menilai pemaknaan demokrasi hari ini sudah salah kaprah. Kebebasan berpendapat diartikan bebas mencaci, membully, memfitnah bahkan dengan kata kata kamus kebun binatang. Demo demo hari ini pun seperti mengerdilkan hukum dan kebebasan orang lain. Jalan umum ditutup karena peserta demo mau berorasi. Ban dibakar di tengah jalan. Saat orasi memaki maki. Saat berpawai kebut kebutan di jalan raya tanpa helm. Bagaimana rakyat -yang selalu dibawa-bawa oleh pendemo sebagai representatif mereka- mau bersimpati? Mengapa mereka tidak berfikir karena tindakan mereka aktivitas orang lain terganggu? Bagaiaman jika ada yang harus cepat dibawa ke rumah sakit? Yang harus ke bandara? Yang harus melahirkan? Dimana hati nurani mereka?
Melihat luar biasanya harimau dalam mulut para penebar kebencian di jejaring sosial pun unjuk rasa di negeri ini memang perlu ada rem pakem. Orang boleh bebas berpendapat dan bebas mengkritik tetapi jangan blong. Jangan mencaci maki, memprovokasi dan yang lebih jahat lagi memfitnah.
Maka itu, keluarnya Surat Edaran Kapolri ujaran kebencian atau hate speech yang ditandatangani pada 8 Oktober lalu dengan nomor SE/06/X/2015 sudah tepat momennya. Surat Edaran itu untuk mengingatkan masyarakat bahwa apabila mengeluarkan pendapat dalam orasi pidato, maupun di dunia maya agar hati-hati dan jangan sembarangan. Surat Edaran itu akan mampu meredam dan mengantisipasi berbagai isu, juga hasutan dalam pernyataan kebencian di publik, terutama di jejaring media sosial oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini sangat banyak dan sering terjadi.
Kita sepakat dengan Kapolri, hidup berdemokrasi bukan berarti bebas tanpa aturan. Demokrasi juga memiliki batasan agar tidak melanggar hukum. Dalam berbicara dan berpendapat, kita harus menghargai hak orang lain.
Lagipula, Surat Edaran itu bukanlah larangan seperti gambaran pembungkaman di era Orde Baru melainkan alat bagi institusi Polri untuk mencegah dan bagi masyarakat mengingatkan agar jangan seenaknya menghasut dan mencaci maki terutama di media sosial. Bila ada pihak yang merasa dirugikan maka barulah polisi akan menindaklanjuti dengan KUHP maupun UU Informasi Transaksi Elektronik. Antara lain pasal 310, 311, 156 KUHP dan pasal 36 UU ITE.
Itulah yang membedakannya dengan era Orde Baru. Jangan pernah lupa bagaimana kita selama 32 tahun dilarang mengkritik pemerintah. Di zaman Soeharto, demokrasi benar-benar dibungkam. Tak boleh seorangpun mengkritisi Soeharto, keluarganya dan menterinya sekecil apapun, walaupun kritik itu konstruktif dan disertai data yang valid.
Orang-orang yang kritis seperti Kelompok Petisi 50 yang di dalamnya ada Ali Sadikin, langsung dibungkam dan hak hak asasinya dikebiri. Yang dianggap berseberangan dengan pemerintah jangan harap bisa tampil di TVRI, satu-satunya stasiun televisi di tanah air milik pemerintah seperti dialami oleh grup musik Hawaiian Senior pimpinan mantan Kapolri jujur, Hoegeng Imam Santoso. Demikian juga nasib Rhoma Irama karena bergabung di Patai Islam PPP tidak boleh tayang di acara TVRI yang notabene Golkar. Media cetak yang dianggap mempermalukan pemerintah pun langsung dibreidel seperti Harian Indonesia Raya dan Harian Prioritas. Bahkan dalam sejumlah kasus, aktivis yang vokal kepada penguasa “dibuang” ke luar negeri atau tewas seperti nasib Munir dan wartawan Udin. Tak ada kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Tak sedikit pula yang hilang tanpa jejak.
Kesimpulan
Mari kita mensyukuri kebebasan demokrasi yang sudah tertata hari ini dengan berkata-kata yang baik, mengeluarkan pendapat secara santun, mengkritisi pemerintah secara sehat maupun pihak lain yang kita anggap salah. Mari juga kita ikhlaskan mereka yang menabur kebencian menuai kesalahannya lewat penegakan hukum. ***
Penulis peminat masalah sosial dan budaya.