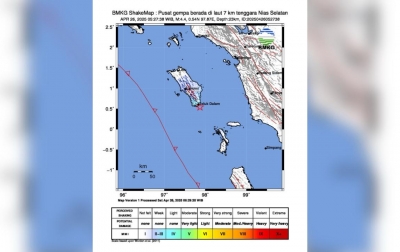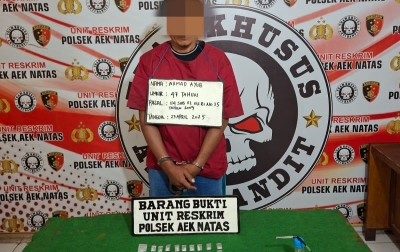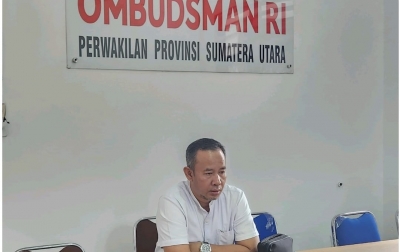Oleh: Jones Gultom.
TAK banyak refrensi maupun catatan budaya Batak Toba, menjelaskan arti maupun makna dari upacara mandudu (baca; maddudu). Beberapa tulisan menjelaskan, ritual masyarakat tradisi Batak (Toba) itu, sering lebih sekedar laporan yang bersifat reportase. Tidak heran jika banyak orang Batak Toba asing dengan istilah ini.
Berdasarkan pengamatan penulis beberapa kali mengikuti upacara ini, secara sederhana terbetik kesan. Mandudu merupakan upacara meminta berkat kepada Sang Khalik melalui perantara arwah leluhur. Dalam upacara itu, arwah leluhur diundang untuk hadir pada saat upacara berlangsung. Tidak heran, jika biasanya ritual mandudu digelar di tempat-tempat yang dianggap sakral atau keramat. Paling populer adalah di Gunung Pusuk Buhit, Samosir.
Pelaksanaan ritual ini wajib dilakukan pada malam hari. Pada saat ritual puncak berlangsung, tidak boleh ada setitik cahaya, termasuk api rokok dan handphone. Hanya ada bunyi-bunyian gondang sabangunan (dudang-dudang). Mengalun ritmis sekaligus mistis di tengah gelap gulita.
Catatan penulis, kala menghadiri kegiatan itu di Pusuk Buhit, tepatnya di kawasan Batu Cawan. Beberapa waktu lalu, ada beberapa rangkaian upacara digelar, sebelum acara puncak dilaksanakan. Terlebih dulu disediakan sejumlah pelean (persembahan) yang diletakkan di atas altar, berupa tikar pandan berlapis (7 lapis).
Jenis yang dipersembahkan antara lain; pangir (jeruk purut) yang digabung dengan telur ayam kampung. Air, beras, sirih, air putih, kain tiga warna (hitam-putih-merah).
Persembahan itu ditaruh di atas tikar pandan tujuh lapis. Bersama dengan kain tiga warna (berturut-turut; hitam-putih-merah) serta pendupaan. Pemimpin upacara memanggil 7 orang untuk diurapi. Mereka dipersenjatai dengan sebilah pedang. Di kepala mereka diikatkan pelepah kelapa yang masih muda. Mereka bertugas mamungka harbangan (membuka gerbang/pintu mata angin) sekaligus menjaga/mengamankan jalannya ritual dari bermacam gangguan eksternal. Mereka menyebar di tiap sudut harbangan.
Setelah persiapan sempurna, pargonci penabuh (gendang)yang mengenakan pakaian serba putih berikut ikat kepala, mulai bersiap di posisinya masing-masing. Setiap rangkaian ritus dilakukan, selalu dimulai dan diakhiri dengan gondang yang berpola 7 kali putaran. Lebih penting, selalu ada dialog antara pemimpin upacara, Raja Bius (raja adat di kampung setempat) dengan pargonci (pemain musik). Masing-masing dimintai pendapat dan kesepakatannya manakala rangkaian kegiatan dilakukan.
Tepat pukul 23. 30 WIB ritual puncak mandudu pun berlangsung. Semua lampu dimatikan, termasuk alat-alat elektronik yang dapat mengganggu jalannya ritual. Pemimpin ritual menyeru kepada semua yang hadir agar, siikat hoda na be ma hita yang berarti mengikat kudanya masing-masing.
Secara simbolik kalimat ini bermakna agar peserta maupun orang yang sekedar melihat kegiatan, menghormati jalannya upacara, tidak mengganggu ritus itu. Baik secara fisik maupun dengan kebatinan.
Selama beberapa jam pargonci memainkan musiknya tanpa henti. Selama itu para peserta khusuk berdoa secara pribadi-pribadi. Memanjatkan permohonannya masing-masing. Musik itulah yang diyakini akan menghantarkan doa-doa kepada Sang Pemilik Kuasa.
Suasana hening, nyaris tanpa suara. Hanya ada dentuman gondang dan rintih sarune bolon yang ritmis. Upacara berlangsung, selama kurang lebih 2 jam.
Tidak banyak yang bisa dicatatkan selama upacara puncak ini berlangsung. Sepanjang waktu, hanya tetabuhan taganing (perkusi Batak (Toba). Seperangkat ogung (gong) dan Sarune Bolon (alat tiup) yang berkumandang. Penulis hanya mencatat ada dua kali angin berhembus dengan karakter dan kecepatan yang nyaris sama. Pertama, di menit ke-15 saat dimulainya upacara serta sekitar 20 menit pada saat upacara akan usai.
Di akhir upacara, manakala lampu dinyalakan, pimpinan Pargonci langsung berseru; “bereng horbo ta bo!” (lihat kerbau kita). Ucapannya disambut dengan jawaban mengida tu purba (melihat ke sebelah timur).
Penulis segera menanyai maksud dari kalimat itu. Rupanya ada keyakinan, posisi kerbau menjadi salah satu indikator diterima tidaknya upacara itu. Diyakini, jika dia menghadap ke Timur, upacara itu berhasil. Sebaliknya, jika menghadap ke barat, berarti upacara gagal (tidak direstui). Upacara berlanjut keesokan harinya, tetapi lebih bersifat melengkapi adat. Di hari itu dilaksanakan ritual mangalahat horbo atau mengurbankan seekor kerbau.
Musik yang Berdialog
Meski masyarakat tradisi Batak (Toba) mengenal sejumlah ritus untuk berdoa, agaknya mandudu termasuk yang paling jarang dilakuka. Boleh jadi, selain karena bersifat ritual, upacara ini juga memerlukan biaya cukup besar.
Selain itu, bisa jadi juga karena pelaksanaannya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu. Tidak heran jika sebagian orang menilainya negatif dengan mengaitkannya kepada hal-hal yang bersifat supranatural.
Sebagaimana upacara dalam masyarakat tradisi Batak (Toba), Pargonci menjadi sentrum. Mereka tak boleh ditempatkan sekadar pemain musik. Pola tingkah dan ucapan mereka juga tak boleh sembarangan. Mereka orang-orang pilihan yang disebut pande. Perlakuan kepada mereka pun tak boleh serampangan. Bila pargonci kesal karena perlakuan suhut atau panitia yang dinilai tak patut, bunyi taganing, ogung, sarune bisa tak nyaring dan kegiatan dianggap gagal.
Dalam sistem kosmo-metalurgi Batak (Toba), pargonci, adalah manifestasi dari Batara Guru (salah satu dari Debata Natolu. Dilambangkan dengan warna hitam). Memiliki sifat kebajikan dan kebijaksanaan. Fungsi utama mereka sebagai pengantara sekaligus penghantar doa-doa manusia kepada Mulajadi Nabolon (Sang Khalik).
Tidak heran jika pargonci diperlukan secara istimewa. Termasuk menempatkan posisi mereka lebih tinggi dari peserta yang lain, ketika mereka harus melakukan tugas-tugasnya itu.
Diyakini musik merekalah doa-doa itu sendiri. Doa yang berdialog, antara manusia dengan penghuni alam semesta lainnya. Boleh dikatakan, kualitas suatu ritual pada masyarakat Batak Toba, ditentukan oleh pargoncinya.
Keheningan yang Bicara
Pada dasarnya mandudu sama dengan berdoa pada masyarakat tradisional. Meminta sesuatu kepada penguasa alam. Hanya saja, mandudu tidak sesederhana orang berdoa atau yang disebut martonggo. Agaknya mandudu seperti terikat berbagai syarat.
Apakah ini konsekuensi dari permintaan yang terlalu “spesial” atau akibat dari kepada siapa permohonan itu ditujukan. Karena itulah, ritus ini sering dianggap sebagai praktik yang menyimpang. Sarat dengan klenik.
Pandangan itupun tak dapat dipungkiri, apalagi jika dilihat dari sisi waktu, tempat dan tata pelaksanaannya. Ada sisi hal yang menarik.
Adanya prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara mikro dengan makrosmos. Antara batin seorang individu dengan alam sekitar. Bunyi-bunyian menjembatani harapan-harapan itu. Suatu keheningan yang kini jarang kita dapatkan.
Di lain hal, praktik ini tak jauh berbeda dari ritus-ritus berdoa di masyarakat nusantara lainnya. Seperti pada masyarakat Tengger yang kerap melakukan hal sama di Puncak Gunung Bromo.
Para abdi dalem keraton Yogya yang berkiblat kepada Gunung Merapi. Mereka menyampaikan doa-doanya di puncak-puncak gunung. Secara universal, gunung adalah simbol kesucian. Tidak heran bila gunung dianggap tempat paling dekat dengan sumber keillahian. Terlepas apakah sumber keilahian itu ada kaitannya dengan agama atau tidak.