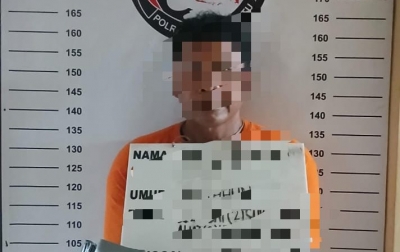Oleh: Dian Tiara
TAK pernah inginku, mimpi ini menjadi dusta. Suatu khyalan yang indah, walau hanya aku dan Dia yang tahu. Tentang bagaimana aku mendambanya–setiap aku merasa sepi di antara keramaian. Kaku. Seluruh pikiranku hanya teralih padanya. Dia yang kukenal belum lama telah membuatku merasakan cinta untuk pertama kalinya. Inilah bagaimana aku mencinta, di dalam kenangan yang telah kuiriskan setiap kami berjumpa. Meski itu hanya beberapa menit, tanpa mata saling menatap dan bibir saling mengucap dengan akrab. Aku kukuh, bahwa aku telah jauh tenggelam. Aku mencintanya dalam mimpi dusta.
Tidak. Cintaku bukan seperti pungguk merindukan bulan. Aku memang mengharapnya datang dalam nyataku, tapi hanya ingin menunggunya dengan caraku. Tidak ingin, aku merindunya seperti pungguk–seperti orang bodoh. Kutuliskan cintaku melalui kata-kata “bagaimana aku mencinta” agar dia tahu cintaku bukanlah dusta. Cintaku nyata untukmu, tapi hadirmu mimpi bagiku. Bisakah kau jadikan mimpi ini ada? Beritahu aku. Walau hanya sekali dalam rentang yang lama untuk melihatmu. Aku bahagia, maka itu jawab aku. Jawab aku dengan barisan kata-kata “bagaimana kau mencinta”. Wanita ini menunggumu. Bahkan setelah sekian lama keinginanku untuk bersamamu telah tercapai, kenapa aku masih menunggumu?
Anak kita hampir menginjak dewasa. Rardi akan tahu segalanya. Selama bertahum-tahun aku mendampingimu, kau tetap sama. Terlalu mencintainya.
“Kumohon genggamlah tanganku. Jadikan aku sandaran kesedihan dan kebahagiaanmu. Berpuluh tahun sudah aku selalu melengkapimu, tidak bisahkah kau mengizinkanku untuk berdiri di sampingmu untuk selamanya? Kenapa hanya punggungmu yang selalu kau tunjukkan padaku, abang? Sedang wajahmu kau hadapkan padanya.”
***
Dia bilang kami harus belajar bahasa Inggris, sedangkan kata mamak, “molo bahasa Batak do bahasa na onjago”. Ibu itu pernah bilang, gini katanya, “disini matahari pagi sangat indah membiaskan butiran embun menjadi udara yang menyapa seluruh dedaunan ubi.” Bah, mana ngerti aku ibu itu ngomong apa? Lalu aku tanya ibu ngomong apa? Katanya sayang kalo ubi sekarung hanya untuk satu orang. Eeh, amang, Ibu ini makin gak nyambung. Memang, aku sudah SMA, tapi kan belum dewasa. Terus tiba-tiba ibu itu bilang gini, “adik-adik pengen gak belajar bahasa Inggris?” yang lain langsung aja bilang pengen. Lalu kami pun belajar.
“Introduction, inilah awal kalian untuk mengenal bahasa internasional.” Benar kan, ibu itu memang aneh. Tiba-tiba semangat dan ngomong gak jelas. Tapi dia benar, kami memang harus belajar apalagi bahasa Inggris. Walau aku akui bahasa Batak yang terhebat dan bahasa Indonesia tentunya. Ibu itu sangat cantik, sesuai dengan namanya Nauli. Kekagumanku akan sosok wanita yang selalu memancarkan ketenangan, hanya dengan mendengar suaranya. Sesaat, sebelum takdir membuat catatannya.
Dia hadir sebagai pendidik di SMA tempatku menuntut ilmu. Wajahnya yang cantik dan suara yang merdu mampu menyihir siapapun yang melihatnya. Bukan hanya itu, kepribadiannya juga menyenangkan dibanding dengan guru-guru yang lain. Ia seperti oase di tengah padang gurun. Nauli Hutabarat, berasal dari kota besar dan sekarang pindah di desa ini–desa Nauli. Desa kami terkenal karena kesuburan tanahnya yang tiada habis. Secara turun temurun tanah ini menghidupi kami dengan menghasilkan berbagai macam tanaman dengan kualitas tingkat dewa dibandingkan daerah lain di sekitar Kabupaten Tobasa ini. Karena itulah desa ini bernama nauli yang berarti cantik. Tapi, tempat ini tidak lagi nyaman bagiku dan juga keluargaku, khususnya ibu. Orang yang telah melahirkanku kini telah terkoyak hatinya dengan kehadiran orang itu. Orang yang kukagumi, berubah menjadi orang yang paling kubenci. Secantik paras hanya untuk merayu.
Sore itu aku sedang menjaga beberapa kambing kami di ladang, dan tanpa sengaja aku melihat ibu duduk bersama ibu Nauli di sebuah gubuk di tengah ladang tak jauh dari tempatku menjaga kambing. Riang aku coba untuk menghampiri mereka. Tapi sesuatu yang busuk akhirnya tercium juga oleh hidungku. Kisah kelam antara bapak dan Bu Nauli serta kebodohan ibuku.
“Kenapa kau kembali lagi?”, mamak bertanya dengan mencoba mengendalikan amarahnya. Dihadapannya duduk seorang wanita yang sedang menatapnya sendu.
“Ini semua salah paham.”
“Kenapa kau kembali!”, membentaknya sambil menggebrak tempatnya duduk. Tak ayal membuat Bu Nauli terkejut. Wajahnya memerah.
“Sudah kukatakan ini semua salah paham! Aku kembali bukan mengharap dirinya. Apa salah aku kembali ke tanah kelahiranku?”
Keheningan tercipta di antara keduanya. Sesekali terdengar suara isakan dari mamak. Punggungnya bergetar. Oh, Tuhan ia menangis. Mamak yang selalu tersenyum kepada kami menangis.
“Tapi ia masih mengharapmu. Selama ini ia hanya mencintaimu.”
Air mata membasahi wajahnya yang lelah. Ibuku meraung di hadapan wanita itu. Suara tangisnya sangat memilukan bagiku. Diam-diam aku berlari sejauh mungkin dari tempat itu. Mamak menangis dan memohon kepada wanita itu. Kenapa kau rendahkan kepalamu dihadapannya, mak? Bu Nauli, selamat kau telah mengenalkan padaku kebencian.
***
Kau yang selalu dianggap sampah oleh mereka – kekasihku. Walaupun ia tahu, aku selalu mencintaimu bahkan ketika semua orang bergunjing tentangmu, maka semakin kuat pula hati ini untuk meminangmu menjadi pendamping bagiku. Itulah mimpiku sejak 23 tahun yang lalu. Kala itu kita masih remaja dan kau menolak cintaku karena Surat, anak kepala desa berparas tampan dengan tanah berhektar-hektar. Kau menikah dengannya tanpa mau mempertimbangkan bagaimana hatiku selalu menyayangmu, dan kini setelah ia pergi meninggalkanmu. Aku bahagia. Diriku kembali terjerat dalam pesonamu. Nauli, teman yang berubah menjadi cintaku. Biarpun kini ada seorang wanita yang menjadi ibu dari anakku, tapi tetap saja mata dan hati ini selalu memandang kearahmu. Tubuhku seperti menjerit kala melihat kau meratapi kepergian lelaki bodoh itu. Airmatamu menganak selama 40 hari kepergiannya dengan jarum yang bersarang dipergelangan tanganmu. Begitu besarkah kau mencintanya. Oh, sayangku. Lihatlah aku yang selalu mengharapmu. Ketika pagi menjelang hanya kau yang ingin kulihat pertama kali saat aku terbangun dari tidurku, membelai rambutmu yang menutupi sebagian wajahmu. Maka dari itu, izinkanlah aku menyimpan sebagian perasaan ini dalam hatiku sebagai jejak cintaku untukmu.
Kini aku ragu untuk mendepakmu, karena sendu wajahnya tanpa terasa membuat hatiku nyeri seketika. Ia yang selalu tersenyum kepadaku telah menunjukkan lukanya. Nauli, cintaku yang seperti matahari sore. Fajar ternyata lebih dulu datang kepadaku.
Aku seperti kucing hitam yang mengendap-endap untuk menangkap mangsanya, setelah berhasil mendapatkan makanan kubawa ia pergi ke tempat persembunyian. Kemudian ku makan sampai habis, tanpa kusadari sisa tulang meninggalkan bau hingga tercium oleh sang semut. Semut itu yang merupakan makhluk lemah mengabaikan bau busuk dari tulang tersebut dan membagikan tulang tadi sebagai makanan yang ia dapatkan untuk dimakan bersama dengan saudara-saudaranya. Bukankah aku sangat jahat? Nauli, cintaku yang kini menjanda. Tinggalah sendiri. Karena aku telah teduh.
Gelitar, 2015