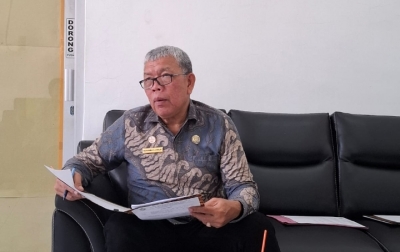Oleh: Jones Gultom.
Seperti bahasa etnis lainnya, bahasa Batak Toba memiliki kekayaan makna. Bahkan dikarenakan kedalamannya itu, banyak kosa kata dalam bahasa Batak Toba, tak memiliki padanannya dalam bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia didominasi dari bahasa Melayu. Hal lain disebabkan karena kata dalam bahasa etnik, khususnya Batak Toba, memiliki bermacam tingkatan. Tingkatan yang tergantung dengan kedalaman makna, rasa dan nilai yang dikandungnya.
Seiring waktu bahasa Batak Toba terus mengalami pergeseran dan perkembangan. Secara umum bahasa Batak Toba, kini digunakan dibagi atas dua kelompok. Yakni bahasa yang dipakai dalam keseharian serta yang digunakan dalam lingkungan adat.
Sebagai contoh, kata “kepala” jika dalam keseharian disebut ulu. Sedangkan dalam bahasa adat, yang dianggap lebih halus, disebut simanjunjung. Pembagian ini oleh sekelompok orang kerap disebut sebagai bahasa Batak Toba prokem dan bahasa raja.
Pada dasarnya, pemberian nama dalam bahasa Batak Toba, didasarkan atas fungsinya. Seperti kata “kepala” yang dalam bahasa Batak Toba “raja” disebut “simanjunjung” itu. Berarti yang menjunjung. Inilah ketegasan bahasa etnik, khususnya Batak Toba yang tidak kita temukan dalam bahasa Indonesia.
Konteks bahasa dalam Batak Toba, juga tidak terlepas dari pemaknaan atas benda itu sendiri. Dengan alasan-alasan itu pula, banyak kata dalam bahasa Batak Toba menjadi sulit terdefenisikan dalam kosa kata bahasa Indonesia. Termasuk tidak ditemukan padanan katanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Selain itu, kadangkala suatu kata mengandung banyak pengertian beragam, jika diartikan dalam bahasa Indonesia. Misalkan, kata roh. Dalam bahasa Batak Toba, kata ini diklasifikasikan atas begu, tondi, sahala dan sumangot. Begu berarti roh jahat. Tondi adalah roh yang bertendensi baik.
Sahala adalah roh seseorang yang masuk ke orang lain. Jenis roh ini biasanya diyakini memiliki power tertentu. Demikian sumangot, berarti roh nenek moyang, masuk ke dalam diri seseorang dan biasanya memiliki misi tertentu. Sumangot mengandung makna lebih mendalam, karena berkaitan dengan nilai-nilai yang melekat padanya.
Selain itupula, seringkali pemberian imbuhan atas suatu kata dalam bahasa Batak Toba, akan memberikan dampak lebih luas dan mendalam. Terkadang tampak jadi tak sesuai dengan pengertian kata dasarnya. Sebagai contoh, kata tondi yang berarti roh. Jika diberi awalan “ter” menjadi “tartondi”. Secara umum, orang yang terguncang batinnya.
Dari sisi lain, inilah kekayaan bahasa etnis. Bahasa yang tidak hanya menjadi media penyampai informasi, juga merupakan tempat bermacam narasi.
Karena mengandung narasi, bahasa juga menjadi tempat bagi simbol-simbol dan perlambang. Disesuaikan dengan kapasitas serta nilai yang terkandung di dalamnya. Itulah yang menjadikan satu kata dalam bahasa Batak Toba, kadangkala sulit kita temukan dalam kosa kata bahasa Indonesia. Apalagi narasi selalu mengikuti ruang pikiran, pencitraan, pengertian bahkan imajinasi manusia. Simbol maupun perlambang ketika masuk dalam wilayah narasi, selalu bersifat ambigu.
Nilai-nilai dalam bahasa etnik, biasanya juga terkait dengan sisi spiritualitas yang mereka yakini. Begitu pula dengan bahasa Batak Toba. Antara lain dapat dilihat dari karya sastranya. Karya sastra lisan berupa umpasa, umpama, tabas maupun mantra-mantra adalah karya sastra dalam bahasa Batak Toba. Dikenal sarat dengan nilai-nilai dan filosofis. Biasanya dia mengandung simbol dan narasi tertentu. Terkadang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Karenanya, sulit sekali mentransformasikan nilai-nilai termuat dalam karya sastra berbahasa Batak Toba ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh, bait puisi Suhunan Situmorang berjudul, “Senjakala di Huta Nauli” termuat dalam antologi puisi dua bahasa (Indonesia-Batak Toba) Situriak Nauli, berikut ini. Senja // saat yang paling intim denganku digubah menjadi bot ari // pertingkian na sai solhot di rohangku.
Kalimat “intim denganku” mendapat porsi yang pas dengan “solhot di rohangku” (yang artinya kira-kira; “paling mengena di perasaanku”). Jika saja diterjemahkan bebas, bisa saja kalimatnya menjadi “solhot tu ahu” (dekat denganku) yang maknanya terasa dangkal.
Karena itu tidak mudah mentranslate karya sastra berbahasa etnik ke dalam bahasa Indonesia. Ada pertimbangan di luar sekedar pengalihbahasaan. Seperti mencari padanan kata yang sesuai dengan makna, ungkapan serta rasa.
Tidak heran jika pada banyak kasus, pengalihbahasaan justru mencederai rasa karya sastra etnik itu sendiri. Saratnya makna dalam setiap teks narasi dalam karya sastra berbahasa etnik, merupakan kekayaan yang dimiliki masyarakatnya.
Berbeda dengan bahasa Indonesia yang begitu sederhana. Bahasa Indonesia, merupakan adopsi dari berbagai bahasa yang telah mengalami pemadatan makna. Akibat penyerapan bahasa, ruang bahasa nasional menjadi begitu terbatas.
Seringkali narasi-narasi yang ada pada bahasa nusantara, tidak dapat diakomodir dalam versi bahasa Indonesia. Inilah keterbatasan bahasa Indonesia. Barangkali akibat narasi-narasi yang tidak terakomodir itu, wilayah impresi spiritualitas masyarakatnya kini menjadi dangkal.
Psikoetnografi
Penjabaran lebih detail tentang ini pernah disampaikan etnografi, Victor Barnow. Dia berpendapat, bahasa etnik mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok penggunanya. Hal ini, konsekuensi kebudayaan yang terkait erat dengan kepribadian. Adanya pola kelakuan ideal biasanya terekam dalam bahasa yang digunakan.
Viktor menegaskan sangat tidak mungkin jika kelompok masyarakat berprilaku kasar, padahal makna dan nilai dalam bahasa yang digunakan mengandung sifat-sifat kehalusan dan budi pekerti.
Dia menyimpulkan suatu bahasa menggambarkan pola kelakuan (psikologis) masyarakatnya. Begitu juga dengan masyarakat nusantara. Keragaman bahasa yang dimiliki mencitrakan kelakuan ideal masyarakat pemiliknya. Mungkin itu sebabnya jika dalam bingkai budaya, masyarakat cenderung berkepribadian halus. Bila sudah dalam konteks umum, sifatnya seakan berubah. Jika dikaji dari psikoanalisa, Sigmund Freud, tampaknya hal itu menjadi logis. Manusia pada umumnya memiliki kepribadian ganda.
Kehancuran bahasa-bahasa nusantara dengan segala kekayaan yang dimilikinya itu kini terjadi secara massif. Salah satunya dilakukan oleh media massa. Tanpa sadar media massa ikut menyeragamkan masyarakat melalui kutipan maupun etimologis yang diambil dari bahasa kelompok masyarakat tertentu. Termasuk pula dengan menciptakan bahasanya sendiri.
Bahasa sengaja dibuat untuk menyederhanakan sesuatu hal. Ruang untuk bahasa termasuk sastra etnik itu sendiri, nyaris tidak ada dalam media massa kita. Mungkin akibat keseragaman inilah yang membuat karakter masyarakat Indonesia menjadi seragam. Baik pola pikir, pola laku dan terutama cara mengatasi masalah (problem solving). Kita memerlukan keragaman bahasa itu, bukan hanya sebagai ciri masyarakat pluralis, melainkan sebagai bagian penting demi terawatnya keragaman nusantara itu sendiri.