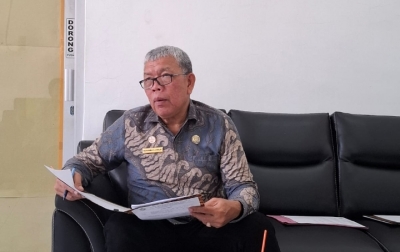Oleh: Eka Azwin Lubis
Era globalisasi membawa banyak dampak perubahan dalam segala sendi kehidupan masyarakat, termasuk transformasi bahasa yang dewasa ini menjadi hal urgen dalam pergaulan hidup manusia. Bahasa sejatinya merupakan alat penyambung komunikasi antar sesama manusia, sehingga penting kiranya kita memahami dan fasih dalam berbahasa asing khususnya bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional.
Persoalan muncul ketika generasi muda yang notabenenya adalah kaum penerus peradaban, justru lebih berbangga hati jika mereka mengerti bahasa asing diketimbang bahasa daerahnya. Berapa banyak saat ini pemuda Indonesia yang tidak mengerti bahasa daerah yang dahulu dipakai oleh leluhurnya.
Stigma berbahasa daerah hanya dilakukan oleh orang kampung yang kolot, tertanam kuat dalam pola pikir masyarakat Indonesia kebanyakan, yang pada akhirnya mengikis identitas budaya bangsa dimana kelestarian bahasa daerah tidak lagi menjadi fokus perhatian yang dianggap penting.
Lebih parah dari situ, ketika anak-anak muda bangsa ini disibukkan untuk mengikuti berbagai pelatihan guna mendorong daya tangkap mereka dalam berbahasa asing, disisi lain ternyata masih terlalu banyak generasi muda Indonesia yang tidak memahami dan mempraktikkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Komunikasi gaya alay yang kerap memelesetkan bahasa Indonesia menjadi trand paling laris dalam pergaulan hidup anak muda Indonesia kini. Rasa anggap enteng dengan bahasa ibu sudah mendera kerangka berpikir bangsa kita sehingga kebanggaan untuk menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan benar kerap kalah pamor diketimbang kebanggaan manakala mampu berkomunikasi dengan bahasa asing dengan teman sepergaulan.
Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia menyiratkan makna tanggung jawab kita sebagai warga negara. Tuntutan tanggung jawab itu pada setiap orang berbeda porsinya, perbedaan porsi ini terjadi mengingat banyak hal yang menjadi kendala dan harus dipertimbangkan, antara lain latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan atau profesi, serta minat dan perhatian yang bersangkutan terhadap bahasa Indonesia itu sendiri.
Dalam kenyataannya, sumpah pemuda yang di dalamnya mengandung pengikraran berbahasa satu, bahasa Indonesia, merupakan berkah yang luar biasa bagi negeri ini.
Kesepakatan para pendiri bangsa yang memilih bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa baru bernama bahasa Indonesia telah menghindarkan kita dari sebuah kesulitan serius untuk memilih dan menentukan bahasa nasional sebagaimana yang dialami India atau Filipina.
Di India, bahasa yang paling banyak pendukungnya adalah Bahasa Urdu. Sementara di Filipina yang terbanyak pendukungnya adalah Bahasa Tagalog. Kebijakan kedua negara yang mengambil bahasa yang paling banyak pendukungnya menjadi bahasa nasional ternyata menyimpan sebuah persoalan yang tidak sederhana.
Protes dan perlawanan serius terhadap kebijakan tersebut tak jarang membawa pada tindak kekerasan. Alhasil, tidaklah mengejutkan jika dengan mudah akan kita temukan di Filipina orang menolak Bahasa Tagalog sebagai bahasa nasional, karena para pengguna bahasa yang menggunakan Bahasa Ilokano jumlahnya juga meyakinkan.
Akhirnya, kaum muda Filipina lebih suka menyebut berbagai bahasa di Filipina sebagai Bahasa Filipinos. Lantas bagaimana dengan bahasa pengantar dan lingua franca mereka? Para pedagang rokok eceran dan ibu-ibu di pasar umumnya bisa berbahasa Inggris meski kemampuan bahasa Inggrisnya terbilang ala kadarnya. Begitulah kondisi yang dialami Negara Filipina.
Bagaimana dengan Indonesia? Tentu pada awalnya, kita akan bertanya apakah sebenarnya yang membuat para aktivis pergerakkan kita pada waktu dulu memilih Bahasa Melayu dibandingkan dengan Bahasa Jawa dan Sunda yang populasinya sangat besar waktu itu?
Ada beberapa kemungkinan yang bisa saja melatarbelakanginya. Pertama, Bahasa Melayu telah konkret terbukti sebagai bahasa penghubung (lingua franca) dalam berbagai kegiatan, khususnya perdagangan di wilayah Nusantara. Kedua, Bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan secara luas sebagai bahasa pers dan penerbitan. Ketiga, Bahasa Melayu merupakan bahasa yang demokratis, tidak mengenal strata dan kasta. Hal ini berbeda dengan Bahasa Jawa dan Sunda yang sarat dengan undak-usuk dan tata krama feodalistik dalam berbahasa.
Akan tetapi, dalam tumbuhkembangnya dikemudian, Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bukannya tidak mengalami berbagai hambatan dan persoalan. Dalam diskusi dengan teman-teman perkuliahan, menyeruak berbagai pertanyaan, di antaranya adalah bagaimana pengaruh bahasa daerah terhadap perkembangan bahasa Indonesia?
Boleh jadi pertanyaan ini hadir dengan melihat beberapa fenomena yang mulai menampakkan tanda-tanda akan kebangkitan bahasa daerah.
Bahkan jauh sebelumnya, seorang pakar bahasa dan budaya sebesar Prof Dr St Takdir Alisyahbana terbengong-bengong melihat adanya gejala di beberapa daerah pada waktu itu yang berusaha mengembangkan kembali bahasa daerahnya. Apalagi dalam perkembangan berikutnya bahasa daerah sempat mendapatkan porsi di bangku pendidikan yang diajarkan secara formal melalui sebuah istilah muatan lokal.
Dengan demikian, sudah pasti kita tidak ingin perkembangan bahasa daerah yang mulai digaungkan akan menjadi sebuah ancaman bagi keberlangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Demikian pula, jika kita terlalu fokus terhadap keberadaan bahasa Indonesia, kita harus berupaya pula semaksimal mungkin agar keberadaan bahasa daerah tetap terjaga kelestariannya. Pekerjaan seperti ini bukanlah pekerjaan yang ringan, mengingat bahasa sebagai sebuah subsistem yang hidup dalam perkembangannya, sudah tentu ada yang punah (hilang) karena tidak dipakai lagi dan ada kata baru yang menggantikannya.
Persoalan berikutnya yang cukup merisaukan adalah bagaimana terbukanya kran istilah atau kata-kata dari bahasa asing yang dengan amat deras masuk dan membanjiri kosakata Bahasa Indonesia. Maka tidak perlu heran jika pada tempat-tempat strategis terpampang tulisan, welcome, exit, in, push, open dan lain-lain. Padahal dalam Bahasa Indonesia kata-kata yang demikian sudah ada padanannya.
Dari dua persoalan yang dikemukan di atas jelaslah bahwa adanya saling pengaruh antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Dengan demikian, kita dituntut lebih bijak dalam memahami kenyataan demikian.
Salah satu sikap yang cukup bijak di antaranya adalah dengan meletakkan maupun memandang bahwa bahasa daerah maupun asing bukan sebagai dua bahasa yang menjadi pesaing bagi bahasa nasional kita. Justru dengan adanya kedua bahasa tersebut lebih menguntungkan kedudukan bahasa Indonesia. Dengan sifatnya yang lebih dekat pada kehidupan emosional rakyat maka bahasa daerah bisa memperkaya pengembangan bahasa Indonesia terutama dalam komponen “rasa” atau emosionalnya.
Demikian pula halnya dengan bahasa asing yang kiranya mampu menghubungkan kita dengan bangsa lain, sebagai alat bantu mengembangkan bahasa Indonesia menjadi lebih modern dan sebagai alat bantu guna pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Akan tetapi, masalah berikutnya adalah bagaimana dengan hadirnya bahasa gaul? Bahasa prokem? Bahasa SMS? Apakah istilah kontroversi hati yang terjadi di era globalisasi yang penuh muatan politisi dan mengandung janji imaji, akan kita hindari guna menemukan bahasa Indonesia yang sejati? ***
Penulis adalah Staf Pusham Unimed dan Aktivis HMI