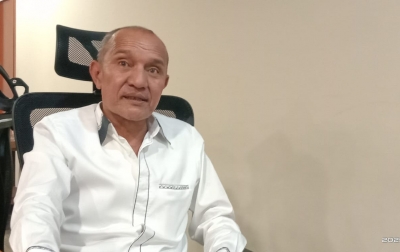Oleh: Wing Irawan. Dalam tradisi sastra dan musik di Indonesia, sepertinya musikalitas bagian yang cukup eksotik. Banyak larik dan lirik syair lagu atau puisi indah. Keindahan bunyi itu menjadi unsur spontanitas dan nature.
“Menurut abang, bagaimana standart musikalisasi yang baik dan benar itu?”
Sejak SMP, aku mengenal puisi sebagai ‘catatan kecil, berbaid dan berima, dengan sebentuk aturan tertentu. Musikalisasi, boleh jadi sebentuk apresiasi penguat. Semacam mengentalkan diksi pada realitas pasar.
Puisi, jika dibacakan sebagai puisi kurang populer dibanding, jika diiringi musik. Selebihnya, musikalisasi ini semacam brending para penggiat sastra dalam meraup audiens, di tengah geliat seni populer lain.
Menurutku, Musikalisasi Puisi, ketika pasar mengenal bentuk karya sastra puisi pada khalayak. Kemudian dikemas dan di garap dengan iringan musik. Artinya, masyarakat lebih mengenalnya sebagai karya sastra. Seperti puisi karya Taufik Ismail yang dinyanyikan Bimbo. Puisi karya Sapardi Joko Damono, dimana orang kebanyakan mengenal sebagai puisi kemudian di populerkan lagi dengan garapan musik. Tentu masih banyak polemik yang akan muncul, selaras dengan perkembangan musikalisasi puisi itu sendiri.
Di Padang dalam lawatanku, keliling Indonesia tahun 2015 ini. Taman Budaya Padang mengajak kelompok musikalisasi 7 Keliling-Medan dan saya. Untuk memeriahkan parade dan kolaborasi musikalisasi dengan kelompok musikalisasi Nan Tumpah Padang. Penonton malam itu cukup apresiatif. Itu dibuktikan dengan banyaknya penonton yang malam itu hadir. Termasuk salah satunya, Kepala Taman Budaya Padang.
Beberapa hari sebelumnya, berita kematian pencipta lagu Rinto Harahap. Seolah mengingatkan saya akan pentingnya kesadaran pasar, bagi para penggiat musikalisasi di Indonesia. Akan banyak pilihan diksi dan dibutuhkan kerelaan untuk soal apresian sastra kita.
Anak ketiga dari enam bersaudara ini pernah bercita-cita menjadi dokter. Ayahnya, malah menginginkan dia jadi pendeta. Rinto berketetapan untuk hidup dari musik. Rinto sempat bekerja pada sebuah perusahaan besi beton, sedangkan malamnya ngamen di klub malam, sebelum dirinya terjun ke bisnis rekaman.
Membaca sejarah perkembangan dunia sastra di Indonesia, dan bagaimana ghiroh penggiatnya, menemukan dan mengupayakan pasarnya. Adalah seperti cita-cita “tersesat’ sejumlah seniman yang kemudian disebut sastrawan dalam memilih medium apresiasinya sampai hari ini.
Musikalisasi, semacam obat herbal dunia sastra yang masih dipertanyakan keabsahannya. Musikalisasi, semacam perasaan malu-malu seorang calon pendeta di tengah jemaat fanatiknya. Sebab sastrawan adalah pekerja-pekerja pabrik beton kata-kata, dimana kontruksi moral di tengah realitas sosial membentur tembok baja.
Sastrawan hanya sebagai pengamen-pengamen di trotoar dan rumah makan di pinggir jalan. Di bulan-bulan awal gajian dan keinginan bersedekah masyarakatnya.
Tentu menjadi terkenal adalah semacam bonus dari realitas pasar buat sastrawan. Akan tampak berbeda dengan profesi seni lainnya. Memilih sastrawan di tengah carut-marut dan begitu banyaknya pilihan profesi di tengah modernitas seperti sekarang dibutuhkan stamina tersendiri.
Apa saja yang ada dihatimu
Akupun tahu
Apa saja yang ada di hatiku
Engkaupun tahu
Kau duduk di sana
Bicara soal motivasi, boleh jadi syair almarhum Rinto Harahap di atas, sedikit melankolis. Mempertegas garis demargasi bagi perkembangan sastra. Upaya seniman dalam mempopulerkan karya sastra sebagaimana musikalisasi puisi itu. Semisal begitu.
Terpenting adalah memperkuat motivasi sang seniman dan penggiat sastra. Sebab proses kreatif adalah ‘realitas yatim’. Di tengah kepedulian logika modernitas yang juga piatu. Kehadiran musikalisasi Puisi adalah seperti Gereja Tua, di antara Gereja-Gereja baru yang lebih profit mengeja popularitas sebagaimana lagu-lagu pop, menjadi wartawan atau menjadi presenter. Atau menjadi Menteri Pendidikan, semisal begitu.
Kau duduk di sana
Ku duduk di sini, menyepi
Dari dunia ini
Yang takkan peduli
Adalah keliru, pembiaran pada logika sejumlah sastrawan dalam membangun idealism dan memilih sendiri. Duduk di atas ketinggian apresiasinya pada realitas sosial dengan karya-karya sastranya. Adalah keliru, pembiaran pada kesadaran pasar, sastrawan tak akan peduli pada perkembangan dunia. Adalah keliru, pembiaran ‘hanya sastrawan sajalah yang boleh menyepi dan duduk sendiri dan membangun etika sepinya dalam karya sastra berupa puisi, semisal begitu. Adalah keliru, pembiaran pada etika pasar, nilai jual sastra kemudian di konversikan sebagaimana dunia ilmu pengetahuan dan menimbulkan alergi itu. Adalah keliru, pembiaran pada keangkeran dunia teks utamanya karya satra.
Ketika beberapa mahasiswanya membantu program Pusat Bahasa membuat musikalisasi puisi, karya beberapa penyair Indonesia, dalam upaya mengapresiasikan sastra kepada siswa SLTA. Saat itulah tercipta musikalisasi Aku Ingin oleh Ags. Arya Dipayana dan Hujan Bulan Juni oleh H. Umar Muslim. Kelak, Aku Ingin diaransemen ulang oleh Dwiki Dharmawan Dwiki dan menjadi bagian dari “Soundtrack Cinta Dalam Sepotong Roti” (1991), dibawakan oleh Ratna Octaviani.
Beberapa tahun kemudian lahirlah album “Hujan Bulan Juni” (1990) yang seluruhnya merupakan musikalisasi dari sajak-sajak Sapardi Djoko Damono. Duet Reda Gaudiamo dan Ari Malibu merupakan salah satu dari sejumlah penyanyi lain, mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Album “Hujan Dalam Komposisi” menyusul dirilis pada tahun 1996 dari komunitas yang sama.
Sebab puisi sebagai keindahan kata-kata adalah musikalitas. Ritme, diksi dan rima dari esensi ‘ketuhanan’ dan fitrah kemanusiaan dalam menemukan muara. Dimana kerelaan bersepakat atas keseimbangan nan nature sebagaimana keniscayaan pada perbedaan itu sendiri. Musikalisasi puisi bukanlah nyanyian gereja tua, hanya orang-orang tertentu saja boleh mendengar dan mengapresiasinya. Artinya, popularitas toh bukan kata yang haram untuk kontruksi masyarakat yang selama ini berstigma terlalu horor. Sastrawan dan karya-karyanya. Adalah ‘Dunia Lain’.
Nyanyikan saja lagu tentang gereja tua
Bukannya lagu tentang engkau dan aku
(lirik lagu ‘Bila Kau seorang diri Karya; Rinto Harahap).
Sastra bukan semacam aliran atau sekte. Keindahan yang selama ini abai dan diyatimkan etika pasarnya. Di sinilah seniman dan penggiat sastra mestinya mencari titik tumpu yang lebih. Keterasingan sastra bukan menjadi kerak bagi perkembangan sastra itu sendiri. Musikalisasi puisi boleh jadi menjadi semacam alternatif baru untuk memperkenalkan sosok sastra kembali menjadi bagian lebih lunak dan renyah untuk dikenali kontruksinya.
Bimbo, Leo Kristi, Ebiet G. Ade, Harry Rusli, Gombloh, Iwan Fals dan musisi-musisi lain. Syah-syah saja untuk mendapat predikat ‘musikalisasi puisi’. Pasar pun memiliki etika komunikasinya sendiri. Begitu banyak genre musik yang dapat saja di kelola sedemikian rupa untuk mempertegas atau memperkuat unsur-unsur puitisnya. Sekaligus mengungkap lebih detail perspektif keindahan dan proses kretaif sastrawan dalam membidik realitas masyarakatnya.
Penulis; Seniman dan pemerhati budaya NTB