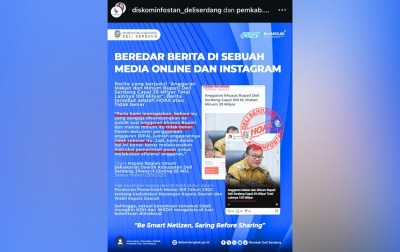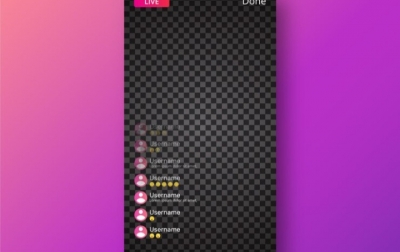Binjai, (Analisa). Sejarawan Sumatera Utara, yang juga Ketua Program Studi Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara (USU), Dr Suprayitno M Hum menilai, penetapan tanggal 17 Mei 1872 sebagai pedoman peringatan hari jadi Kota Binjai, sangat tidak relevan.
Pernyataan itu diungkapkannya ketika menjadi salah satu dari empat narasumber Seminar Sejarah dan Budaya Kota Binjai, dengan makalah berjudul “Sejarah Kota Binjai,” di Pendopo Umar Baki Kota Binjai, Selasa (26/5) pagi.
Menurut Suprayitno, penetapan hari jadi Kota Binjai masih harus dibuktikan kembali melalui pengumpulan sumber dan fakta-fakta sejarah yang lebih valid dan rasional. Sebab, menurutnya, peristiwa Perang Sunggal pada 17 Mei 1872 itu, dianggap tidak bersinggungan langsung dengan perjalanan sejarah Kota Binjai.
Apalagi berdasarkan catatan sejarah, diakui Suprayitno, Kota Binjai sebenarnya telah lama memerankan fungsinya sebagai kota tradisional yang strategis di bidang ekonomi dan politik, jauh sebelum meletusnya peristiwa Perang Sunggal.
“Dari kaca mata sejarah, peristiwa Perang Sunggap di tanggal 17 Mei 1872 itu tidak relevan. Terutama jika dihubung-hubungkan dengan hari jadi Kota Binjai. Apa urusannya Datuk Mahini perang, sehingga bisa lahir Kota Binjai,” ujarnya.
Dia menganggap peristiwa Perang Sunggal hanya sebatas motode penguasa menumbuhkan kesan heroik dan semangat perjuangan masyarakat melawan penjajahan. Sayangnya, menurut Suprayitno, hal itu justru akan menimbulkan kekeliruan sejarah yang selamanya akan sulit dipahami masyarakat.
“Boleh-boleh saja kesan heroik Datuk Sunggal itu ditampilkan ke publik, dalam upaya membangkitkan semangat perjuangan melawan kolonial. Namun, jika hal itu dilihat dari kaca mata sejarah, jelas sangat tidak relevan dan cenderung menyesatkan,” ungkapnya.
Tanpa Jati Diri
Di sisi lain, Suprayitno menilai Binjai sebagai kota tanpa jati diri, karena telah banyak kehilangan ciri khas dan ikon sejarahnya. Ini mengingat telah banyak produk khas maupun simbol sejarah berupa bangunan dan benda cagar budaya, yang justru telah menghilang.
“Hampir tidak ada ikon ataupun landmark, yang bisa menampilkan jati diri Kota Binjai. Lihat saja sekarang. Menara air hilang. Rambutan juga susah dicari. Bahkan Tugu Pahlawan pun tidak mampu menampilkan Binjai sebagai kota pejuang,” tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan narasumber lain, yakni Dr Phil Ichwan Azhari, selaku Ketua Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan (Unimed), saat memaparkan makalah berjudul “Menemukan dan Mengelola Nilai-Nilai Sejarah dan Kekuatan Budaya Lokal, dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Kota Binjai Maju, sejahtera dan Bermartabat”.
Menurutnya, Kota Binjai masuk dalam kategori kota galau tanpa ikon, tanpa identitas, dan tanpa budaya andalan. Bahkan nyaris semua bentuk arsitektur bangunan baru, termasuk Gedung Balai Kota Binjai, tidak mampu menggambarkan simbol kultural yang unik dan khas.
Padahal, berdasarkan catatan sejarah, Binjai adalah kota yang dibangun dalam bingkai ekonomi plural, yang cenderung kental dengan nuansa keanekaragaman etnis dan kebudayaan.
“Sekalipun Binjai pernah masuk kategori kota cerdas oleh salah satu surat kabar nasional, namun hal itu justru tidak terlihat bagi saya. Sebab, hingga saat ini, Kota Binjai belum mampu memelihara dan mengelola warisan sejarah dan budayanya sendiri dengan baik,” ungkap Ichwan.
Guna mengantisipasi tergerusnya nilai sejarah dan budaya lokal, menurutnya, Pemerintah Kota Binjai harus segera menentuikan kebijakan komprehensif dan sistematis.
Langkah itu meliputi upaya revisi hari jadi Kota Binjai, revitalisasi simbol sejarah, dan budaya, melalui pemanfaatan museum daerah, serta menciptakan kurikulum berbasisi pengetahuan sejarah dan kearifan lokal di sekolah-sekolah.
Pusat Pembauran
Sebelumnya, Prof Dr M Dien Madjid, dalam makalahnya berjudul “Membentuk Integrasi Kebangsaan berdasarkan Kebudayaan Multikurltural,” menyatakan Kota Binjai sebagai salah satu pusat pembauran sosiokultural, dan sangat identik sebagai Indonesia mini.
Hal itu, karena Kota Binjai telah lama tumbuh dan berkembang sebagai pusat interaksi sosial dan budaya. Bahkan masyarakat Binjai, seperti halnya penduduk kota-kota lain di Sumatera Utara, cenderung bersikap terbuka terhadap pengaruh baru, dan perubahan kebudayaan.
Meskipun demikian, menurut Madjid, sudah sepatutnya pemerintah maupun masyarakat Kota Binjai tetap waspada. Sebab, sifat multikulturalisme yang ada di wilayah ini, bukan hanya dilihat sebagai sebuah aset pembangunan, tetapi juga harus dilihat sebagai tantangan menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.
“Ancaman perpecahan dalam sebuah komunitas multietnis itu jelas sangat besar. Tetapi ukurannya bukan pada perbedaan budaya masing-masing etnis, melainkan perseteruan akibat sikap kefanatikan budaya yang berlebih,” tegasnya.
Penjelasan itu, diperkuat dalam isi makalah berjudul “Sejarah dan Transformasi Budaya,” oleh Dr Budi Agustono MA, yang turut membahas secara mendalam tentang perubahan sikap dan karateristik masyarakat Kota Binjai, mulai dari masa kerajaan tradisional, masa kolonialisme barat, hingga masa kemerdekaan.
Sebab dalam makalahnya itu, sejarawan yang juga Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara itu, menilai ciri multikulturalistik Kota Binjai sebenarnya bukan bentukan alami, melainkan tercipta atas dasar perkembangan kapitalisme global melalui pengaruh ekonomi perkebunan. (wa)