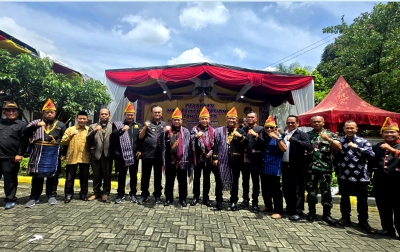Oleh: Jones Gultom. Jauh sebelum Indonesia mengenal demokrasi, bahkan sebelum negeri ini terbentuk, nenek moyang kita telah mengenal sistem pemerintahan. Kurang lebih sama nilainya dengan demokrasi. Malah jika dikaji lebih dalam, pemahaman demokrasi oleh masyarakat tradisi di masa lalu itu, sering lebih kontekstual dibanding nilai-nilai yang ada pada demokrasi modern ala John Locke.
Demokrasi John Locke, dikembangkan kemudian oleh Montesquieu, hanya mengacu pada distribusi kekuasaan. Kekuasaan dibagi-bagi kepada tiga lembaga, disebut trias politika. Itulah yang kini dianut banyak negara di penjuru dunia, termasuk Indonesia.
Sebelum negara menganut mahzab itu, masyarakat nusantara, khususnya orang Batak Toba di masa lalu, telah memiliki konsep yang lebih matang. Kita mengenal sistem demokrasi Suhi ni Ampang na Opat. Suhi ni Ampang na Opat, menekankan aturan, seorang Batak Toba harus somba marhula-hula, elek marboru, manat mordangan tubu dan mardebata-maraja.
Hanya saja setelah Belanda berhasil menguasai beberapa daerah-daerah penting di Negeri Batak, sistem ini dipangkas. Pakem mardebata-maraja, dihapuskan. Istilah Suhi ni Ampang na Opat, diganti menjadi Dalihan na Tolu. Diduga penghapusan mardebata-maraja selain bertujuan mengurangi pengaruh raja, juga memudahkan syiar Kristen bagi orang Batak.
Yang menarik dari nilai mardebata-maraja, bahwa raja yang dimaksud bukan seperti dalam konsep monarki. Raja memiliki makna ganda. Raja sebagai pemimpin politis dan juga raja sebagai pemimpin spiritual.
Dalam tataran politis, fungsi inilah yang dibelenggu oleh Belanda. Raja sebagai pemimpin spiritual secara radikal mengalami transformasi ke dalam pemahaman kekristenan. Agaknya konsep mardebata-maraja ini, mirip-mirip dengan prinsip pemerintahan monarki parlementer. Seperti yang dipraktikkan negara-negara maju di Eropa, seperti Inggris maupun Belanda sendiri.
Raja tidak berdiri sendiri. Fungsi kontrol tetap ada pada masyarakat yang diwakili oleh bermacam lembaga. Jika terkait mengenai praktik spiritual maupun ritus, raja akan dibantu oleh kelompok Parbaringin.
Kelompok Parbaringin, adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan khusus. Mereka peka membaca fenomena alam serta “cakap” memformulasikannya ke ranah spiritualitas. Biasanya fenomena-fenomena itu berkaitan dengan sifat-sifat astrologi alam. Parbaringin juga dimintai perannya, pada situasi-situasi tertentu.
Pada konteks adat, raja dibantu oleh tokoh-tokoh adat, berasal dari kelompok-kelompok marga maupun huta (kampung). Mereka tidak hanya berperan dalam melaksanakan jalannya adat, juga menjadi tempat bertanya mengenai masalah hak dan kewajiban yang terkandung dalam adat tersebut. Mereka juga berfungsi sebagai hakim atas persoalan yang tengah terjadi. Karenanya sudah menjadi keharusan, tokoh-tokoh adat harus memiliki segudang pengetahuan dan bijaksana dalam mengambil keputusan.
Jika kelompok Parbaringin adalah pure mengurus hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa khusus, maka tokoh adat lebih berperan dalam keseharian hidup masyarakat. Meski pada moment-moment tertentu keduanya akan saling bersinerji, namun mereka tetap memiliki batas dan koridornya masing-masing.
Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, seorang raja juga dibantu oleh raja bius. Raja ini mewakili kelompok masyarakat dalam satu wilayah tertentu.
Seperti kita tahu, konsep pemerintahan masyarakat Batak Toba di masa lalu juga bersifat federatif. Hal ini memudahkan penyebaran informasi dan distribusi kekuasaaan.
Seiring tidak diakuinya fungsi politis raja, maka kelompok-kelompok yang dalam terminologi modern sebagai perwakilan masyarakat di atas, tidak lagi berafiliasi kepada sosok tertentu.
Tidak hanya menyangkut relasi pemerintahan, khususnya pembuat undang-undang (legislatif) dengan pelaksana (eksekutif) dan peradilan (judikatif).
Lebih dari itu, sistem demokrasi pada masyarakat Batak Toba itu, juga mengatur sendi-sendi kehidupan yang lebih luas. Seperti ekonomi, teritorial, pemanfaatan sumber daya alam, hubungan dengan sesama makhluk hidup, bahkan sistem kepercayaan.
Memang, pola pemerintahan itu, tidak berlangsung mulus. Secara de jure dia ada, namun tidak sepenuhnya dipraktikkan. Luasnya Negeri Batak Toba, serta sulitnya menentukan legitimasi, membuat konsep ini layu sebelum berkembang. Sampai hengkangnya Belanda dari Negeri Batak, konsep pemerintahan itu masih bersifat anasir.
Ada dugaan bahwa model pemerintahan itu merupakan formula yang sedang digagas oleh Sisingamangaraja XII untuk menghimpun kekuatan. Lagipula di masa penjajahan, tidak semua Negeri Batak diduduki, apalagi berhasil dikuasai oleh Belanda.
Luasnya Negeri Batak Toba menyulitkan untuk memunculkan satu sosok pemimpin. Agaknya masyarakat Batak Toba, mulai terbiasa dengan Dalihan na Tolu, sebagai panduan hidup mereka hingga saat ini.
Demokrasi Tak Tertulis
Meski tidak dituliskan, aturan-aturan yang termuat dalam Dalihan na Tolu, tetap harus dijalankan. Dalihan Natolu yang berazaskan keseimbangan ini, tidak hanya menjadi panduan dalam upacara-upacara adat, tetapi juga diamalkan dalam hidup keseharian orang Batak Toba.
Memang dia bersumber dari petuah yang bersifat oral. Tetapi nilai-nilai yang termuat di dalam konsep ini, dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Walau berdasarkan analogi, namun di dalamnya dapat kita temukan bermacam pengetahuan yang mengacu pada kebijaksanaan.
Seperti kita tahu, dalam Dalihan na Tolu, disebutkan; somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongan tubu. Somba marhula-hula. Berarti hormat terhadap keluarga dari pihak istri/maupun ibu. Sebaliknya seorang hula-hula harus elek marboru. Elek bisa kita terjemahkan sebagai sikap yang mengayom, lembut. Manat mardongan tubu, bermakna bijaksana di dalam keluarga. Keluarga di sini tidak hanya satu ayah-ibu, juga teman satu marga.
Relasi-relasi ini tentunya akan menimbulkan konsekuensi, yakni berupa ikatan hak dan tanggungjawab bagi masing-masing pihak. Dalam hak dan tanggungjawab itulah akan kita temukan kelogisan dan kausalitas.
Misalnya karena seorang boru harus menghormati hula-hulanya, maka seorang hula-hula harus menunjukkan sikap sebagai seorang yang memang pantas untuk dihormati. Demikian juga sebaliknya, hula-hula yang tidak elek marboru berarti tidak pantas untuk dihormati.
Relasi ketiganya dalam Dalihan na Tolu itu kemudian diterjemahkan dalam ritus-ritus. Salah satunya, dalam upacara adat, pihak hula-hula akan mengulosi pihak boru.
Konsep Dalihan na Tolu ini menarik bukan hanya disebabkan nilai-nilai di dalamnya, tetapi karena dia begitu universal. Semua orang Batak Toba akan terikat pada aturan itu. Di satu pihak dia akan menjadi boru.
Di lain pihak hula-hula atau dongan tubu. Termasuk akan mendapatkan predikat itu secara bersamaan, manakalah dia sudah menikah. Karena prinsip keseimbangan itulah, mestinya orang Batak Toba terbiasa hidup sesuai porsi untuk mengambil perannya masing-masing.
Atas dasar itulah, harusnya orang Batak Toba khususnya, tidak mengenal istilah korupsi. Bukankah nilai-nilai ini justru yang paling mendasar dibanding arti demokrasi modern yang kenyataannya hanya lebih mengurus masalah-masalah politik kekuasaan?