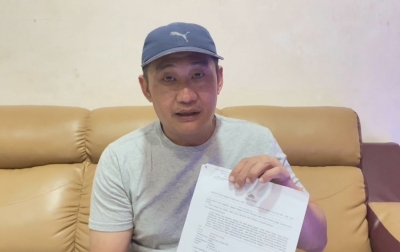Oleh: Miharf Harahap. Bukan soal bermutu atau tidak. Ketika membaca cerpen, terkadang kita tertegun, pangling. Ada pula yang biasa saja. Membaca cerpen Rebana harian Analisa, edisi Mei 2015 ini, kita temukan keduanya. Cerpen ”Memori Mei, Aku Amoi” karya Liven R, “Filosofi Ayah” karya Bamby Cahyadi dan“Oei, Commele Gloire” karya Alex R. Nainggolan. Cerpen “Yang Maha Pengasih” karya Karahayon Suminar dan “Sepasang Buah Kelapa” karya Rizki Siregar.
Umumnya cerpen mengesankan ketertegunan, meski jenis dan kedalamannya berbeda. Ada jenis berdasarkan cerita seperti cerpen Liven R dan Rizki Siregar. Ada pula jenis berdasarkan teknis cerita seperti cerpen Bamby Cahyadi, Karahayon Suminar, kecuali cerpen Alex R.Nainggolan.
Kedua kesan dengan tingkat kedalaman, mulai dari tahap sedang, hingga tahap rendah. Betapapaun tingkat atau tahap itu, tentu lebih baik yang tertegun ketimbangbiasa-biasa saja.
Cerpen “Memori Mei, Aku Amoi” karya Liven R ini, memang membuat kita tertegun. Betapa tidak, tragedi reformasi ternyata berdampak buruk bagi sebagian warga etnis Tionghoa. Ada aba-aba atau tidak,namun telah terjadi penjarahan toko, swalayan, rumah, penghancuran bangunan, fasilitas umum, bahkan pemukulan dan pemerkosaan. Padahal tak ada hubungan antara tuntutan reformasi dengan keberadaan warga etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia.
Cerpen ini berhasil melukiskan peristiwa Mei 1998 dari sudut apa yang dialami Amoi. Untung Amoi sempat diselamatkan Bi Asih ke rumahnya 3 hari, lalu diterbangkan ke Beijing. Sembilan tahun di sana, dia sekolah dan seandainya menetap, hidupnya bakal terjamin. Tetapi tidak! Dia kembali ke Indonesia bersama Mamanya. Kita tertegun atas pilihan ini. Dialah etnis Tionghoa yang sudah sangat meng-Indonesia. Beijing kota kelahiran namun Indonesia adalah negaranya.
Tujuh belas tahun kemudian, kita tertegun lagi. Ternyata tugasnya bidang pendidikan, siapkan tenaga guru bahasa Mandarin di SD. Hal ini menunjukkan, Amoi (sebetulnya tak suka dipanggil Amoi) tidak bersifat dendam. Malah aktif mengajarkan bahasa Mandarin kepada anak-anak dimana orangtuanya mungkin telah melempar rumah dan menjarah harta keluarga Amoi. Dengan bahasa dia ajarkan budi pekerti agar anak-anak sejak dini mampu menjadi lebih dewasa.
Disarankan, paragraf satu dan dua dari akhir cerita, supaya dipertimbangkan untuk dibuang. Alasannya, pertama, kedua paragraf seakan menjadi kesimpulan cerita. Biarkan pembaca membuat kesimpulannya sendiri. Kedua, kedua paragraf itu menerangkan secara eksplisit, sehingga cerpen kehilangan estetikanya secara implisit. Barangkali pecerpen khawatir kalau tujuan cerita tak sampai, hingga harus ada paragraf itu. Keraguan inilah yang sebenarnya perlu dihilangkan.
Cerpen “Sepasang Buah Kelapa” karya Rizki Siregar, juga membuat kita tertegun. Bayangkan, Mugi (anak usia 4 tahun) masih suka memegangsesuatu (disebut buah kelapa)ibunya atau orang lain. Sebab, biasanya anak bercerai netek usia 2-2,5 tahun. Mengingat ibu pergi-pulang kerja seharian, maka aku (gadis, kuliah) yang menjaga Mugi pun menjadi korban.
Aku berinisiatif, melarang Mugi memegang dan menghisap, dengan maksud supaya berhenti. Kita tertegun karena Mugi berani memegang sesuatu dari orang lain, seusianya. Tentu emak dan orang lain itu marah. Dikatai tak becus menjaga anak-anak. Untung tak mengadu ke kantor polisi. Lebih parah lagi, katakan sebagai puncak ketertegunan, ketika aku memergoki Mugi menghisap sesuatu dari ibunya.
Apa sebenarnya yang terjadi pada Mugi? Apakah kebiasaan itu sebagaimana kebiasaan anak yang terlambat bercerai netek pada ibunya? Atau kebiasaan ini merupakan suatu penyakit baru yang belum ditemukan jenis dan obatnya? Ataupun sebagai dampak buruk dari kerinduan ibu yang bercerai dengan suami?
Semua pertanyaan ini, sepatutnya terjawab di dalam cerpen. Ah, sayangnya, hal itu tak terjadi. Akibatnya, cerpen terkesan menjadi agak kering.
Barangkali pecerpen tidak berniat begitu. Tak menjawab pertanyaan yang dianggap sebagai persoalan. Pecerpen hanyalah menceritakan saja tentang kelakuan-kelakuan Mugi yang terasa aneh bagi seusianya dan merugikan orang lain.
Ujung-ujungnya, kurangnya perhatian orangtua, pengaruh media televisi serta lingkungannya. Kalau benar begitu, betapa ruginya. Sebab, cerpen ini masih bisa dikembangkan menjadi science fiction asal pecerpen mau serius mendalaminya.
Cerpen “Filosofi Ayah” karya Bamby Cahyadi, pun membuat kita tertegun. Bukan lantaran filosofi ayah, melainkan karena kejutan yang membuat aku (kelas 9 SMP) jatuh pingsan. Bayangkan, tiba-tiba aku ditelepon ibu, disuruh pulang oleh ayah. Tiba di depan gerbang komplek perumahan, terlihat bendera kematian, keranda dan orang ramai di depan rumah. Aku berlari kencang, sangat cemas, pandangan gelap dan sampai di depan pintu rumah langsung pingsan.
Ternyata, orang yang meninggal bukanlah ayah, tetapi Pak Fulan. Keluarganya, meminjam garasi mobil sebagai tempat persemayaman, agar para pelayat mudah menziarahi.
Filosofi ayah tak hanya hidup sederhana, tetapi juga suka membantu. Bahkan tidak sombong. Terbukti mau meminjamkan garasi, meski untuk orang mati. Padahal kehidupan ayah di atas lumayan. Bisa saja tak perduli dengan lingkungan, kalau ayah dan keluarga mau menyombongkan diri.
Persoalan muncul ketika cerpen disusupi kenanganku (waktu kelas 5 SD) bersama ayah pergi ke pantai. Di sana ditunjukkan kalau ayah memerhatikan kehidupan nelayan dan aku bergaul dengan anak nelayan. Akibat kenangan, sangat terasa, pertama, menguasai hampir separuh cerita.Kedua,tak ada kenangan khusus/istimewa terkait filosofi ayah. Kenangan telah memanipulasi cerita dalam arti filosofi ayah kurang berkembang. Karena itu , seharusnya perlu dihindari.
Cerpen “Yang Maha Pengasih” karya Karahayon Suminar ini masih memiliki kesan tertegun. Tatkala aku (Dinan) berhenti di pinggir jalan untuk menerima telepon Niken. Kawan Rizal dan Nando memasuki area parkir di depan apotik. Belum selesai teleponan, kawannya sudah kabur membawa sepeda motor orang/pembeli obat.Seorang ibu menangis keluar dari apotik. Sungguh tak diduga (kawan SMA yang baru ketemu, sepulang dari Bogor) ternyata maling.
Untung aku tak ikut komplotan pemaling. Maksudnya,terhindar dari layar CCTV karena tak masuk ke area parkir. Mendengar keributan di depan apotik, segera aku menjauh dan buru-buru pulang ke rumah.
Di dalam kamar di depan cermin, aku berusaha tenang. Bersyukur kepada Tuhan yang menyelamatkan dan berterimaksih kepada Niken yang menelepon. Kalau tidak, habislah aku. Polisi menangkapnya dengan tuduhan mencuri sepeda motor milik seorang ibu.
Cerpen yang dramatis dan melankolis ini, juga mengekspresikan ketiba-tibaan dalam cerita. Misalnya, rencana Rizal-Nando membawa Dinan memancing. Tiba-tiba berubah melakukan curanmor. Rencana ingin menjenguk Mama sakit dan si bungsu, Maysaroh, tunangan, tetapi tiba di kampung tak ada cerita sakit dan tunangan. Malah cerita Niken dan kawan yang nyaris menjebak. Karena itu, pengarang tidak konsisten dengan cerita yang dibuatnya sendiri.
Terhadap cerpen “Oui, Comme le Gloire” karya Alex R. Nainggolan, kesan kita biasa-biasa saja. Artinya, belum membuat kita tertegun, baik karena ceritanya maupun karena menyelipkan beberapa kalimat bahasa Asing. Ingat, cerpen tertegun bukan berarti terbaik, sebaliknya, cerpen biasa bukan berarti terburuk. Hanya, pembaca merasa tertarik bila membaca yang membuatnya tertegun, pangling. Karena itu, perlu penghayatan dan pendalaman cerpen.
Disatu sisi, pecerpen mengutip kalimat indah, cinta tidak mesti bersatu. Di sisi lain, menyunting kalimat oui comme le gloire.
Akhirnya, kita sepakat dengan kalimat pecerpen: “ cinta sering membawa seseorang, baik aku ataupun dia bimbang” (awal paragraf). Terbukti, setiap kali aku bertanya, apa kau mencintaiku atau apa ada orang mencintaimu selain aku, maka tak ada jawaban. Kecuali hanya menangis dan menangis, suatu sikap yang tak pasti.
Penulis; Kritikus Sastra, MPR-OOS, Ketua Fosad, Pengawas dan Dosen UISU