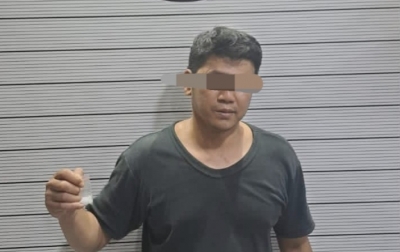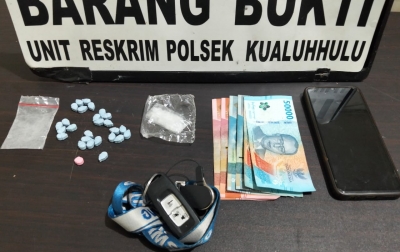PERJALANAN kehidupan sangatlah kompleks. Untuk mencapai tujuan sejati, aral rintangan selalu saja menghadang. Maka, eling lan waspada (ingat dan hati-hati) menjadi kunci utama bagi setiap orang agar mampu menjaga diri, tidak terkena dampak godaan menyesatkan. Dalam pada itulah, para leluhur Jawa telah mewariskan beragam sikap dan perilaku yang mencerminkan sikap eling lan waspada. Menariknya, meski falsafah ini berasal dari leluhur Jawa, namun dapat diterapkan pada setiap orang karena sifatnya yang universal.
Erat kaitanya dengan hal tersebut, buku Eling lan Waspada hadir dalam rangka menyebarluaskan falsafah Jawa sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh realita sosial yang terus berubah setiap saat. Salah satu bentuk eling lan waspada yang dibeberkan dalam buku ini antara lain adalah eling slirane dhewe (jangan sampai lupa daratan).
Manusia sering melakukan sesuatu di luar kendali. Ketika telah merasa memiliki segalanya, manusia sering melupakan asal-usul, kewajiban, hakikat, bahkan jati diri. Manusia yang merasa hebat biasanya lupa diri/daratan. Untuk mencegah atau mengendalikan sikap lupa diri, manusia harus selalu eling sesanggemane wong urip, yaitu ingat akan kewajibannya sebagai manusia yang hidup di dunia (halaman 45). Ada tiga bentuk eling sesanggeman. Pertama, eling sesanggeman tanpa melupakan kebutuhan pribadi. Kedua, eling lingkungan tanpa mematikan kepentingan pribadi. Ketiga, eling sejatining dhiri tanpa menjadi pengikut yang membabi buta.
Di samping eling, manusia juga mesti bersikap waspada. Manusia dituntut agar selalu waspada, baik lahir maupun batin. Sikap waspada harus dimiliki manusia setiap waktu seumur hidupnya. Jika sampai seseorang lengah sedikit saja maka hal itu dapat berakhir fatal. Jika dampaknya tidak dirasakan sekarang maka pasti berakibat buruk dalam jangka panjang. Waspada tan kena lena bermakna jangan sampai lengah dan lepas kontrol. Sikap waspada harus selalu dijaga untuk menghindari bahaya yang bisa menerpa tanpa diduga sebelumnya (halaman 79).
Hakikat dari berbagai falsafah Jawa ialah menunjukkan sikap mendhek atau merendah. Maksudnya, manusia diminta menyimpan dalam-dalam di benaknya terkait keunggulan yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk sikap tenggang rasa dan menjaga keharmonisan dalam pergaulan. Berpijak dari situ, muncul ajaran moral banter ora nglancangi, dhuwur ora ngungkuli, pinter ora ngguroni, landhep ora natoni.
Banter ialah melaju dengan cepat atau berkaitan dengan kecepatan. Namun demikian, jangan sampai kecepatan tersebut nglancangi liyane (mendahului orang lain). Dhuwur ora ngungkuli bermakna tetap rendah hati dalam segala situasi. Pinter ora ngguroni bermakna pandai, tetapi tidak menggurui. Sementara, landhep ora natoni bermakna berbicara tajam, tetapi tidak sampai menyakiti (halaman 236–240).
Saat ini, nilai-nilai falsafah Jawa semacam ini semakin meluntur. Padahal, untuk menggapai kesuksesan sejati, setiap manusia harus memiliki jati diri sebagaimana yang ada pada falsafah Jawa ini. Untuk itu, keberadaan buku ini sangatlah bermanfaat bagi pembaca dalam rangka mempelajari falsafah Jawa.
Setelah mempelajari dan memahami dengan seksama, pembaca akan dapat menjadikan materi-materi yang ada di dalamnya sehingga dapat dijadikan panduan hidup. Dengan begitu, seseorang akan mendapatkan pencerahan hidup. Kehidupannya akan benar-benar bermakna, bukan saja bermakna untuk kehidupan belaka, namun hingga akhir kelak. Dengan eling lan waspada, seseorang akan selalu bertindak penuh dengan pertimbangan.
Peresensi: Anton Prasetyo, Alumnus UIN Yogyakarta.