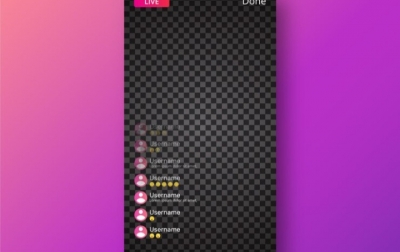Oleh : Isnaini Kharisma.
Indonesia memiliki sejarah yang cukup beragam, di antaranya keberadaan sebuah istana atau kesultanan di setiap daerah. Sejumlah kerajaan tersebut tersebar di beberapa lokasi. Itu sebabnya, di Sumatera Utara, maupun beberapa daerah lain, ada sejumlah peninggalan dari kerajaan/kesultanan yang ditinggalkan oleh pendahulu kepada generasi masa kini. Bentuknya, bisa hanya buku, tugu, alat perang, bahkan istana.
Untuk peninggalan berupa istana, sejumlah daerah malah menjadikannya aset pariwisata unggulan. Contohnya, Istana Maimum, peninggalan Kesultanan Deli. Istana ini, berdiri megah di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan Jalan Brigjen Katamso. Malah, beberapa tahun belakangan, ada beberapa turis mengaku tidak sah pelancongannya di Medan bila tidak berkunjung ke Istana Maimun.
Istana Maimun didirikan ketika jayanya Kesultanan Deli berada pada kepemimimpinan Sultan Makmun Al Rashid Perkasa Alam yang memerintah pada periode waktu 1873-1924. Pada masa itu, perdagangan tembakau sudah semakin maju dan kemakmuran Kesultanan Deli mencapai puncaknya.
Kemakmuran Kesultanan Deli pada masa itulah yang menyebabkan Sultan Makmun Al Rasyid Perkasa Alamsyah mampu membangun berbagai sarana pemerintahan, salah satunya adalah Istana Maimun sebagai ‘Singgasana’ untuk Kesultanan Deli.
Bangunan istana sejumlah 2.772 meter persegi, terdiri atas 2 lantai berketinggian 14,4 meter dan berada di area seluas empat hektare. Theo Van Erp, arsitek istana ini merupakan seorang tentara KNIL. Namun, dia mampu merancang bangunan ini dengan perpaduan multikultur, dengan gaya arsitektur tradisional Melayu, Timur Tengah, India Islam (Moghul) dan beberapa bagian mengadopsi gaya arsitektur Eropa. Gaya arsitektur tradisional Melayu terlihat dari penggunaan warna kuning yang mendominasi, warna yang melambangkan etnis Melayu.
Dosen Arsitek Institut Teknologi Medan (ITM), Saufa Yardha ST MT mengatakan, ukiran-ukiran khas Melayu terlihat dalam corak pucuk rebung dan awan boyan, yang digunakan pada pinggiran atas lesplank dan dinding atasnya. Ukiran bunga tembakau, awan boyan dan bulatan bunga matahari diaplikasikan pada tahta singgasana raja.
"Untuk bagian depan, bentuk atap kubah dan ground plan Istana Maimun merupakan bagian istana yang rancangannya dipengaruhi gaya arsitektur Islam di Timur Tengah dan India pada masa lampau. Lengkungan-lengkungan pada arcade yang berbentuk lunas perahu terbalik, lengkung runcing maupun yang berbentuk ladam kuda mencirikan seni arsitektur Islam Timur Tengah dan India," katanya.
Sedangkan pengaruh arsitektur Eropa pada istana ini adalah penggunaan material bangunan yang sebagian besar didatangkan dari Eropa, dan perabot seperti kursi, meja dan bufet seluruhnya adalah buatan Eropa. Gaya arsitektur India Islam diaplikasikan pada langit-langit istana dengan pola kubisme.
Menurut data sejarah, bangunan Istana Maimun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Masjid Raya Al-Mashun dan Taman Sri Deli. Tata letak ketiga bangunan ini saling bertaut, tanpa ada batas-batas fisik berupa pagar pembatas di antara ketiganya. Tidak adanya batas fisik (pagar) inilah yang merupakan ciri khas Kesultanan Deli, yang membedakannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa.
" Pada kerajaan di Eropa umumnya mengelilingi kawasan istana mereka dengan batas fisik masif dari lingkungan sekitarnya. Ini bertentangan dengan ciri pemerintahan Kesultanan Deli yang terbuka dalam berhubungan langsung dengan rakyatnya," jelasnya.
Kerajaan Siak
Selain Istana Maimun, di Siak, Riau juga memiliki keindahan tersendiri pada bangunan Istana Siak Sri Indrapura. Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura disebut juga dengan nama Istana Aseeraiyah Hasyimiah dibangun tahun 1889 oleh Sultan Siak XI yang bergelar Assyaidin Syarif Hasyim Abdul Jalili Syafiudin Syah. Sama halnya dengan Kesultanan Deli, Kerajaan Siak Sri Indrapura merupakan sebuah kerajaan Melayu Islam.
Kerajaan Siak awalnya bernama Kerajaan Buatan yang terletak di tepi Sungai Jantan (Siak). Istana Siak Sri Indrapura memiliki denah persegi panjang dengan arsitektur perpaduan antara Melayu, Arab dan Eropa. Di sisi kiri dan kanan depan istana berdiri enam buah pilar, dua buah masing-masing terdapat patung seekor burung garuda yang mengembangkan sayapnya dan dihiasi mahkota, bertengger di puncak pilar.
"Pada pilar lainnya terdapat patung garuda tanpa mahkota. Pintu dan jendela berbentuk kubah dengan hiasan mozaik. Bangunan terdiri dari dua lantai, lantai dasar terdapat lima ruangan utama yang berfungsi untuk menerima tamu dan ruang sidang. Sedangkan pada lantai atas terdapat empat ruangan berbentuk kamar berfungsi untuk istirahat Sultan dan tamu, serta dua buah ruangan berbentuk aula," ujar Saufa.
Kedua lantai dihubungkan dengan dua buah anak tangga berbentuk spiral, di sebelah kanan istana untuk naik dan di sebelah kiri untuk turun. Selain bangunan istana, terdapat pula bangunan Istana Peraduan yang berfungsi sebagi tempat tinggal sultan beserta keluarganya. Saat ini bangunan tersebut dipergunakan sebagai Kantor Pusat Yayasan Amanat Sultan Syarif Qasim.
Bahkan, di samping Istana Peraduan terdapat bangunan penjagaan yang terbuat dari bata merah. Pada saat ini , istana berfungsi sebagai museum yang menyimpan koleksi benda-benda Kerajaan Siak, antara lain foto raja dan pembesar kerajaan, dua buah fotokopi surat wasiat raja, meja pertemuan dengan lampu kristalnya, 'komet' sejenis alat musik dari kayu dan kuningan bermerk "Komet Goldenberg Zeitlei" yang masih mengeluarkan suara lagu-lagu klasik, kursi keemasan kerajaan, replika Mahkota Kerajaan Siak, tombak pusaka, payung kerajaan, cermin mustika, dan lain-lain.
Keraton Yogyakarta
Lebih lanjut, di Yogyakarta juga memiliki sebuah Keraton. Saufa menuturkan, Keraton Yogyakarta adalah nama populer yang digunakan pada masyarakat untuk menyebutkan nama asli dari Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
Lingkungan Keraton Yogyakarta disusun secara konsetrik yang merupakan tata ruang keraton yang tediri dari:
a. Lapis terluar : Dalam lapisan ini terdapat alun-alun Selatan dengan segala perlengkapannya yang terdiri dari Alun-alun utara dengan Masjid Agung, Pekapalan, Pegelaran dan Pasar. Sedangkan Alun-alun Selatan terdiri dari Kandang Gajah Kepatihan yang merupakan sarana birokrasi dan benteng sebagai sarana pertahanan militer.
b. Lapis kedua yang terdiri dari : Siti Hinggil yang merupakan halaman yang disebut juga pelataran yang ditinggikan yang berada di sebelah utara dan selatan. Siti Hinggil Utara terdapat tempat yang bernama bangsal Witana dan bangsal Maguntur Tangkil. Tempat ini digunakan untuk upacara kenegaraan.
Siti Hinggil Selatan sering dipergunakan untuk kepentingan Sultan yang bersifat pribadi misalnya menyaksikan latyihan para prajurit hingga adu macan dengan manusia (rampogan) atau banteng. Bagian terakhir dari lapisan ini adalah Supit Urang / Pemengkang yang merupakan jalan yang mengitari Siti Hinggil.
c. Lapis ketiga Keraton Yogyakarta terdiri dari Pelataran Kemadhungan Utara dan Selatan. Pelataran Kemadhungan digunakan untuk ruang transit menuju ruang utama. Pada pelataran Kemadhungan Utara terdapat bangsal yang bernama Pancaniti dan pada pelataran Kemadhungan Selatan terdapat bangsal Kemadhungan.
d. Lapis ke empat berdiri Pelataran Sri Manganti dan bangsal Sri Manganti yang dipergunakan untuk ruang tunggu sebelum menghadap raja. Di bangsal ini terdapat bangsal Trajumas yang terletak di sisi utara Pelataran Kemagangan sedangkan bangsal kemagangan berada dio sebalah selatan. Bangsal ini diperunakan sebagai tempat transit terakiti sebelum ke pusat Istanan.
e. Lapis terakhir adalah pusat konsentrik yang terdapat pelataran Kedhaton. Tata ruang dari yang tersusun oleh bangunan yang terdiri dari tratag, pendhopo, pringgitan. Bangunan-bangunan Keraton Yogyakarta lebih terlihat bergaya arsitektur Jawa tradisional. Di beberapa bagian tertentu terlihat sentuhan dari budaya asing seperti Portugis, Belanda, bahkan Cina. Bangunan di tiap kompleks biasanya berbentuk/berkonstruksi Joglo atau derivasi/turunan konstruksinya.
Joglo terbuka tanpa dinding disebut dengan Bangsal sedangkan joglo tertutup dinding dinamakan Gedhong (gedung). Selain itu ada bangunan yang berupa kanopi beratap bambu dan bertiang bambu yang disebut Tratag. Pada perkembangannya bangunan ini beratap seng dan bertiang besi. Permukaan atap joglo berupa trapesium. Bahannya terbuat dari sirap, genting tanah, maupun seng dan biasanya berwarna merah atau kelabu. Atap tersebut ditopang oleh tiang utama yang di sebut dengan Soko Guru yang berada di tengah bangunan, serta tiang-tiang lainnya.
Tiang-tiang bangunan biasanya berwarna hijau gelap atau hitam dengan ornamen berwarna kuning, hijau muda, merah, dan emas maupun yang lain. Untuk bagian bangunan lainnya yang terbuat dari kayu memiliki warna senada dengan warna pada tiang. Pada bangunan tertentu (misal Manguntur Tangkil) memiliki ornamen Putri Mirong, stilasi dari kaligrafi Allah, Muhammad, dan Alif Lam Mim Ra, di tengah tiangnya.
Untuk batu alas tiang, Ompak, berwarna hitam dipadu dengan ornamen berwarna emas. Warna putih mendominasi dinding bangunan maupun dinding pemisah kompleks. Lantai biasanya terbuat dari batu pualam putih atau dari ubin bermotif. Lantai dibuat lebih tinggi dari halaman berpasir. Pada bangunan tertentu memiliki lantai utama yang lebih tinggi. Pada bangunan tertentu dilengkapi dengan batu persegi yang disebut Selo Gilang tempat menempatkan singgasana Sultan.
Tiap-tiap bangunan memiliki kelas tergantung pada fungsinya termasuk kedekatannya dengan jabatan penggunanya. Kelas utama misalnya, bangunan yang dipergunakan oleh Sultan dalam kapasitas jabatannya, memiliki detail ornamen yang lebih rumit dan indah dibandingkan dengan kelas dibawahnya.
Semakin rendah kelas bangunan maka ornamen semakin sederhana bahkan tidak memiliki ornamen sama sekali. Selain ornamen, kelas bangunan juga dapat dilihat dari bahan serta bentuk bagian atau keseluruhan dari bangunan itu sendiri.