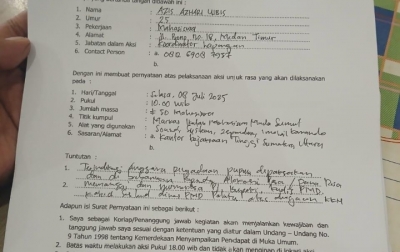Suara anak-anak perempuan kecil yang tengah belajar mengaji dan membaca ayat-ayat Alquran, mengiringi perbincangan Analisa dengan Damiri Mahmud (75), Kamis (17/11) siang itu. Bersarung kotak-kotak hijau dan baju koko putih yang terlihat melebihi ukuran tubuhnya yang kurus, penyair, cerpenis dan novelis senior Sumatera Utara ini, masih bersemangat saat diajak memutar ingatannya tentang “roman picisan” yang berjaya di Medan pada paruh 1930 sampai 1950-an.
Sesekali, bocah-bocah perempuan yang tengah belajar mengaji di teras samping rumahnya yang rindang oleh pepohonan dan tanaman bayam, di Desa Klambir, Kecamatan Hamparan Perak, mendatangi Damiri Mahmud.
“Assalamualaikum, Tuk, ” ujar mereka sembari mencium tangannya.
“Sebenarnya yang disebut roman picisan itu buku berbentuk majalah. Jadi tidak benar dikatakan buku. Tahun 1930-an terkenal sekali misalnya roman Elang Mas karya Joesoef Souyb, roman itu dimuat di majalah Dunia Pengalaman,” tuturnya.
Soebagijo I.N. dalam bukunya Jagat Wartawan Indonesia menyebut, majalah tengah bulanan yang memuat roman picisan itu berukuran saku, dijual sekitar delapan belas sen, tebal 62 sampai 86 halaman. Sekali terbit berisi satu cerita sampai tamat (Soebagijo I.N: 1981).
Roman picisan, menurut Damiri Mahmud, pada zamannya laris manis diminati masyarakat. Selain karena isi ceritanya bertutur masyarakat menengah ke bawah, ada juga bumbu roman atau percintaan. Selain itu ada juga kandungan misteri atau detektif yang membuat penasaran pembaca. Idiom-idiom khas Medan juga muncul dalam dialog-dialog tokohnya. Itu semua membuat masyarakat mudah mencerna isi roman picisan.
Elang Mas, menurutnya, terbit sampai 7 jilid pada 1942. Sebelumnya, Joesoef Souyb pada 1939 menerbitkan Bibir Mengandung Racun, lalu Gadis Komidi. Kemudian Pengorbanan di Medan Perang pada 1941, dan Ngaung Sirine tahun 1942 yang diterbitkan di Singapura.
Selain Joesoef Souyb, menurut Rizali Haris Nasution dan Koko Hendra Lubis yang tengah mendokumentasikan roman dan komik Medan, ada juga Joesoef Djajad yang menulis roman Mayat Bernyawa, Matu Mona atau Hasbullah Parinduri yang menulis Pacar Merah dan Muhammad saleh Oemar atau Surapati menulis Tanda Tangan Palsoe. Selain itu masih ada lagi Nurman Sati, Usman Siregar, SM Taufik, dan Dena Ardansyah.
Istilah roman picisan menurut Damiri Mahmud, penulis buku Menafsir Kembali Amir Hamzah, Rumah Sembunyi Chairil Anwar dan Kumpulan sajak Damai di Bumi, lahir dari polemik antara Matu Mona dengan Parada Harahap tahun 1939. Roman picisan dianggap rendah mutunya, tidak sesuai pakem roman Balai Pustaka dan karya para Pujangga Baru waktu itu. Sekalipun begitu, roman picisan mendapat sambutan luar biasa masyarakat, bahkan menembus pasar di Jakarta.
Kenyataan itu membuat orang-orang Jakarta cemburu. Parada Harahap mengejeknya sebagai roman picisan atau roman murahan. Sepicis itu sama dengan sepuluh sen, harga yang murah untuk sebuah buku saat itu. Walau digolongkan roman picisan, tahun 1980-an seorang sarjana dari Prancis pernah meneliti karya-karya tersebut.
Pujangga Surau
“Saya jumpakan langsung dengan Joesoef Souyb di rumahnya, sayang di lemari Joesoef pun sudah tak ada lagi. Punya saya dipinjam orang dan beli kembali sampai sekarang,” tutur Damiri Mahmud dengan tersenyum simpul.
Jika karyanya disebut roman picisan atau roman kodian, pengarangnya disebut ‘Pujangga Surau’, tambah Rizali Nasution. Rizali adalah anak dari Harris Muda Nasution (alm) pemilik Firma Harris yang terkenal sebagai penerbit buku komik dan cerita rakyat serta pidato-pidato Presiden Soekarno. Disebut pujangga surau karena mereka memiliki latar pendidikan agama.
Tahun 1950-an Firma Harris menerbitkan komik-komik Taguan Hardjo dan Zam Nuldyn yang legendaris dalam jagat perkomikkan Tanah Air. Juga komikus lain seperti Ali Darma, Basar SJ dan Lutfi Asmoro. Sedangkan buku fiksi yang diterbitkan, di antaranya Putri Kerbau Jalang, Sisebelah Mencari Tuhan, Hantu Laut Sikutumunu, Si Gale Gale, dan Senjakala.
Pidato Presiden Soekarno yang koleksinya masih ada di almari Rizali Nasution adalah Ambeg Parama Arta, Tahun Vivere Pericoloso TAVIP, Resopim, Repolusi, Pimpinan dan Deklarasi Ekonomi.
“Boleh dikata waktu itu Medan memang juara penerbitan untuk Indonesia. Buku-buku kami juga beredar sampai di Malaysia,” tutur Rizali Nasution. Bahkan Idris Pasaribu dalam Pengantar Antologi Cerpen 34 Tahun Analisa menengarai roman picisan juga beredar sampai ke Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Kamboja hingga ke Philipina Selatan.
Tapi sekali lagi, era kejayaan roman picisan dan komik Medan telah berlalu. Kini Medan, menurut Idris Pasaribu, seperti sedang tertidur pulas dari penerbitan buku-buku karya sastra. “Tidak ada lagi penerbit dari Medan yang berani berspekulasi menerbitkan karya-karya sastra orang Medan, apalagi yang bisa menembus pasar luar Medan seperti era 1950-an. Padahal Medan punya penerbit besar seperti Madju, Hasmar, Monora dsb.”
Minat Baca Rendah
Minat baca masyarakat yang rendah menjadi alasan penerbit di Medan enggan menerbitkan buku-buku sastra, termasuk buku-buku umum. Hal ini diakui Rizali Nasution dari Penerbit Harris dan Pustaka Widia Sarana serta Direktur Eksekutif Penerbit dan Percetakan Madju, Doni Irfan Alfian.
“Cetak buku itu tak seperti buat sepatu. Kalau nggak laku bisa dijual di emperan ruko, masih antri yang beli. Tapi kalau buku nggak laku, ya dikilokan,” ujar Rizali Nasution. Penerbit Widia Sarana sendiri lebih banyak menerbitkan buku-buku budaya Mandailing. Yang sudah terbit antara lain, Lebih Jauh tentang Willem Iskander dari Si Bulus Bulus, Si Rumbuk Rumbuk, Asal Usul Marga di Mandailing dan Mandailing Polit.
Rizali jujur mengakui, memang sebuah tragedi jika kini Penerbit Harris belum bisa ikut menerbitkan buku-buku sastra. Namun ia realistis, menerbitkan buku sastra juga harus memperhitungkan untung-rugi. Aceh, Padang dan Yogyakarta memang marak buku sastra. Tapi apakah buku-buku itu terserap pasar, habis dibeli masyarakat?
"Kalau nggak disubsidi, akhirnya ya seperti kita lihat, banyak penerbit akhirnya buat bursa buku murah," katanya.
Selain minat baca masyarakat yang rendah, Doni menyebut faktor harga kertas yang mahal. Harga kertas di Jawa menurutnya jauh lebih murah dibanding di daerah Sumut. “Itu aneh dan tak habis pikir karena pabrik kertas ada di Perawang, Riau, artinya secara geografis dekat Medan.”
Ia menyebut harga kertas di Solo Rp10.500/kg, di Bandung Rp11 ribu, sedangkan di Sumut antara Rp. 12 ribu – 13 ribu per kg. Padahal komponen kertas menyumbang 50-60 persen ongkos produksi buku. Itu sebabnya harga buku di Medan bisa lebih mahal dibanding di Jawa.
Kalau soal mutu cetakan, ia menjamin tak jauh beda dengan percetakkan di Jawa. Hanya soal layout dan cover diakui terkadang masih di bawah penerbit di Jawa.
Ihwal selama ini penerbit di Medan, termasuk Madju, belum melirik ke buku-buku sastra seperti novel, kumpulan cerpen atau puisi, menurut Doni, karena umumnya penerbit buku Medan tengah dalam masa transisi. Umumnya penerbit di Medan selama ini lebih banyak “bermain” ke buku-buku pelajaran. Namun sejak diberlakukannya kurikulum KTSP dan K-2013, mereka sudah mulai beralih ke buku-buku umum.
Penerbit Madju misalnya, kini juga membuka peluang penulis novel atau pengarang yang mau menawarkan naskah mereka. Ketua IKAPI Sumut 2016-2021 itu menambahkan, dalam waktu dekat IKAPI berencana membuat pertemuan dengan para pernulis dari berbagai bidang.
Ia memang berharap, setelah penerbitan swasta tak bisa terlibat bisnis buku-buku pelajaran, mereka bisa menerbitkan buku-buku bertema muatan lokal untuk sekolah-sekolah. “Saatnya generasi muda mengenal sejarah dan kekayaan budaya masyarakat Sumut lewat buku-buku muatan lokal.”
Jika gagasan tersebut terealisir, maka para penulis kebudayaan, cerita-cerita rakyat, novel, kesenian atau sejarah bisa menemukan kembali lahan mereka. Sebuah lahan yang telah “hilang” setengah abad lebih setelah berlalunya era roman picisan.