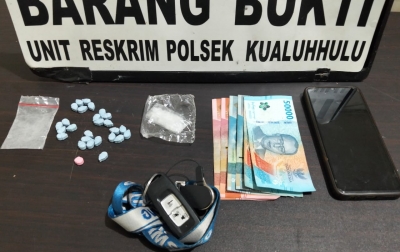Oleh: Muhammad Idris Nasution.
Seringkali terma-terma agama hilang dan tidak terdengar lagi dalam perbincangan sehari-hari orang beragama maupun dalam kajian-kajian keagamaan. Lalu sebuah peristiwa datang, terma yang sempat hilang itupun kembali terdengar, bahkan berserakan seperti jamur di musim hujan. Seperti itulah gambaran terma “ghairah”. Sebuah terma yang belakangan ini acap kali diperbincangkan dan diperdengarkan. Terma ini kembali dikaji dan ditelaah setelah terbentur dengan peristiwa tertentu, seperti kasus dugaan penistaan agama yang tengah ramai diperbincangkan.
Kata “ghairah” berasal dari bahasa Arab. Cara bacanya adalah dengan membaris-fatah-kan huruf “gh”. Bukan dengan meng-kasrah-kannya, “ghirah”, sebagaimana banyak beredar. Kata “ghairah” dan “ghirah” dalam bahasa Arab memiliki makna yang sangat berbeda. Dalam kitab Taj Al-‘Arus min Jawahir Al-Qamus (jilid 5 h. 248), Muhammad Murtadha Al-Husaini Az-Zabidi mengatakan kata “ghirah” berarti “mirah”. Kata “mirah”, dalam kamus Arab-Indonesia (h. 434), karya Mahmud Yunus, berarti “makanan beras dsb”. Kata “ghara”, bentuk kata kerjanya, dapat diartikan dengan “memberi makan dan memberi manfaat”. Ibnu Manzhur, dalam kitabnya, Lisan Al-‘Arab (jilid 6 h. 346), juga memaknai kata “ghirah” dengan “hujan dan kesuburan”.
Kata yang bermakna kecemburuan bukan “ghirah” tetapi “ghairah”. (Bisa diperiksa di kedua kitab tersebut, bahkan di Kamus Mahmud Yunus sendiri) Tetapi, kata ghairah dikaprahucapkan –meminjam istilah K.H. Mustofa Bisri—menjadi ghirah.
Di dalam bahasa Indonesia, kita menemukan kata, yang barangkali diambil dari bahasa Arab, “gairah”. Dalam kamus kata ini berarti keinginan (hasrat, keberanian) yang kuat. Dalam terminologi Islam, makna ghairah lebih dari sekadar itu, karena ghairah mengandung arti semangat, cemburu, kejantanan dan bela. Rasa ghairah-lah yang membuat kita, misalnya, berusaha terus menjaga apa atau siapa yang kita cintai agar tetap baik atau agar menjadi semakin baik. Menutupi aibnya bila ada, melindunginya, membuat kita marah bila sedikit saja dia diganggu orang, bahkan bersedia mati untuk itu. (Gus Mus, Saleh Ritual, Saleh Sosial, h. 105-106)
Seorang lelaki yang mencintai istrinya, dia akan menjaga istrinya dari gangguan orang lain, dia akan marah apabila ada orang lain yang hendak menodai istrinya. Apabila dia mencintai negaranya, dia akan membela dan mempertahankannya dari kekuatan apapun yang hendak merongrong kedaulatan negaranya. Jika dia mencintai agamanya, dia akan menjaganya dengan melaksanakan tuntunannnya dan menjauhi larangannya, dia akan marah apabila agamanya dinistakan, baik dengan ucapan maupun perbuatan, bahkan rela mati apabila kesucian agamanya diinjak-injak. Demikianlah sekelumit gambaran sifat ghairah ini.
Pada dasarnya, sifat ini adalah sifat terpuji. Imam Nawawi menyebutnya sebagai sifat kamal, ‘sifat kesempurnaan’. (Syarh Shahih Muslim, jilid 4 h. 125) Bahkan sebagian ulama menegaskan: la karama fi man la yaghar, ‘tidak ada kemuliaan pada orang yang tidak memiliki ghairah’. (Kitab Muhadarat Al-Adibba’, jilid 2 h. 255) Ulama asal Indonesia, Hamka, juga menekankan bahwa ghairah adalah nyawa seseorang. Beliau mengatakan, dalam buku kecilnya, Ghirah dan Tantangan terhadap Islam, jika sifat ini sudah tidak ada lagi, “Ucapkanlah takbir empat kali ke dalam tubuh ummat Islam itu. Kocongkan kain kafannya lalu masukkan ke dalam keranda dan hantarkan ke kuburan”.
Tetapi, sifat ini dapat berubah menjadi perilaku buruk dan merusak citra dari apa yang dighairahinya tersebut. Ghairah bersumber dari rasa cinta yang kuat. Karena itu, ia bisa lebih dekat kepada nafsu atau bahkan dikuasainya, dan bisa jauh dari akal sehat atau bahkan melawannya. Dengan demikian, sifat ini perlu disikapi dengan kearifan, tidak dibiarkan menjadi tingkah liar, keluar dari rel-rel pedoman agama itu sendiri. Teladan itu dapat kita lihat dari kisah kecemburuan Sa’ad bin Ubadah.
Sa’ad adalah pemimpin Kaum Anshar. Ketika Allah SWT menurunkan firman-Nya yang menegaskan bahwa hadd zina baru dapat dipenuhi apabila dapat menghadirkan empat orang saksi (QS AN-Nur: 4), beliau berkomentar: “Seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama isteriku, niscaya aku akan penggal dia dengan pedang tanpa ampun.” Lalu hal tersebut disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau pun berkata: “Apakah kalian heran terhadap ghairah (kecemburuan) Sa’ad? Sesungguhnya aku lebih cemburu daripada dia, sedang Allah lebih cemburu lagi daripadaku.” (HR Bukhari dan Muslim)
Paparan hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah mengakui ghairah Sa’ad bin Ubadah, tetapi beliau mengingkari keinginannnya untuk membunuh pelakunya. Karena had zina, sebagaimana firman Allah baru dapat dilaksanakan bila memenuhi empat orang saksi. Apakah ghairah Rasulullah lebih sedikit dibanding Sa’ad? Tentu tidak. Rasulullah sendiri mengakui beliau lebih ber-ghairah daripada Sa’ad, bahkan Allah yang menurunkan ketentuan itu jauh lebih ber-ghairah daripada mereka semua. Tetapi ghairah yang ditunjukkan oleh Rasulullah masih terkontrol sehingga tidak mencederai dan mendahului hukum yang ditetapkan oleh Allah.
Oleh karena itu, meskipun darah kita sedang memanas atau semangat kita sedang menggebu-gebu untuk membela dan menjaga harga diri sendiri dan keluarga, kedaulatan bangsa dan negara, atau kesucian agama dan kehormatan ulama, dan sebagainya, di samping itu kita harus tetap terkontrol dan menguasai diri. Alquran memerintahkan kita untuk tetap berlaku adil meski benci. (QS Al-Maidah: 8) Imam Al-Ghazali menegaskan, kita harus tetap menjaga ketawadhu’an meski sedang marah: marah dengan tawadhu’.
Jangan sampai amarah kita membuat kita berlaku semena-mena. Jangan sampai kebencian kita menyeret kita untuk berlaku anarkis. Jangan sampai dengan alasan ghairah membela kita malah terjebak pada perilaku tercela, seperti mencaci-maki dan merendahkan orang lain. Agama kita tidak mengizinkan kita untuk mencaci-maki dan merendahkan orang lain, apalagi orang tersebut belum tentu bersalah atau hanya sekadar berbeda pendapat dengan kita. Tetaplah arif dan adil dalam menyikapi perbedaan dan kesalahan orang lain, meskipun ghairah kita sedang menyala-nyala. Sebagaimana dituntunkan dan ditunjukkan oleh Rasulullah dan oleh Allah sendiri.
Demikianlah, semoga uraian ini ada manfaatnya. ***
Penulis adalah Imam Masjid Nurul Huda Asrama Brimob Medan.