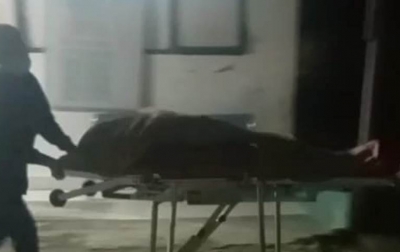Oleh : Hasan Sitorus.
Ikan Batak dengan nama lokal Ihan merupakan jenis ikan air tawar endemik yang hanya terdapat di sekitar Dataran Tinggi Toba (Datito). Ikan Batak yang memiliki nama ilmiah Neolissochilus thienemanni, Ahl 1933, memiliki nilai ekonomis dan sosial budaya yang tinggi khususnya bagi masyarakat Batak, karena dari dulu ikan ini sudah digunakan dalam upacara adat istiadat suku Batak, sehingga nama ikan inipun lebih dikenal sebagai ikan Batak.
Akibat pemanfaatan sumberdaya, Ihan ini telah mengalami tangkap lebih (over fishing), sehingga populasi ikan ini dihabitat aslinya di daerah Toba sudah hampir punah. Oleh sebab itu sejak tahun 1996, IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) telah menyatakan ikan Batak termasuk jenis ikan terancam punah (Red List of Threatened Species) dengan Kode Ref.57073.
Dengan kondisi demikian, maka ikan Batak sangat sulit didapatkan, dan kalaupun ada harganya sangat mahal dan bahkan tidak bisa ditawar. Implikasinya, penggunaan ikan Batak dalam upacara adat Batak sekarang ini tidak lagi menjadi keharusan dan posisinya sudah bisa digantikan dengan ikan mas dari famili yang sama yakni Cyprinidae.
Ada beberapa jenis ikan yang sangat mirip dengan ikan Batak dari genus yang sama, antara lain Neolissochilus sumatranus yang terdapat di daerah Aceh Tengah, dan jenis Neolissochilus longipinis yang terdapat di Danau Kawar, Propinsi Aceh dan Sungai Pangus, Ungaran, Jawa Timur.
Selain itu, ada juga ikan yang bentuk tubuhnya mirip ikan Batak, yaitu ikan Jurung, penyebarannya cukup luas di wilayah Indonesia, yang dalam taksonomi merupakan genus Tor dan satu family dengan ikan Batak. Oleh sebab itu harus dicermati bila ada orang mengaku memiliki stok ikan Batak, pada hal ikan itu adalah Jurung.
Untuk membedakan ikan Batak dengan jenis Jurung, ciri utama ikan Batak adalah ukuran sisik lebih lebar dan warna sisik lebih cerah berkilat dibanding jenis ikan Jurung pada umur muda, dan warna menjadi perak kuning kehijauan setelah ikan dewasa.
Dengan mengetahui bahwa populasi ikan Batak sudah mengalami deplesi di daerah Toba, maka sudah saatnya pemerintah daerah bersama masyarakat lokal untuk melakukan upaya konservasi baik secara in situ (di habitat asli) maupun ex situ (habitat buatan) agar ikan ini tidak mengalami kepunahan (extinction) alias tinggal nama.
Upaya konservasi hanya akan bisa dilakukan bila kita sudah mengetahui aspek ekobiologi dari ikan Batak, yang menyangkut karakteristik habitat asli, makan dan kebiasaan makan, dan pola reproduksi.
Bila infomasi ini dapat diketahui secara akurat, maka upaya peningkatan populasi ikan di alam melalui pemijahan buatan dan budidaya ikan dapat dilakukan dengan relatif mudah. Hal seperti ini sudah dilakukan Balai Riset Perikanan Air Tawar Cijeruk, Bogor, yang telah berhasil melakukan pemijahan buatan dan budidaya jenis ikan Jurung yang mirip dengan ikan Batak.
Aspek Ekobiologi
Ikan Batak umumnya menyukai perairan jernih, bersuhu dingin (21 – 24 oC) dan beraliran deras (lotik). Oleh sebab itu jenis ikan ini banyak mendiami sungai-sungai yang bermuara di sekitar Danau Toba.
Dalam mencari makan, ikan Batak bersifat aktif pada malam hari (Nocturnal). Sedangkan pada siang hari bersembunyi atau berlindung di balik batu-batuan. Termasuk jenis omnivora (pemakan fitoplankton, zooplanton dan detritus di dasar perairan).
Berdasarkan aspek reproduksi, pada gonad ikan Batak dengan Tingkat Kematangan Gonad IV (TKG IV), terdapat ukuran telur yang bervariasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikan Batak dapat memijah sepanjang tahun terutama di musim hujan. Fekunditas ikan dengan ukuran 212 mm, berat 88,50 gram mencapai 765 butir dengan diameter telur berkisar antara 1cm - 2,5 cm. Ukuran ikan dewasa kelamin (TKG IV) adalah berkisar antara 28 – 34 cm dengan bobot betina berkisar antara 1.400 – 2.250 gram, sedangkan jantan berkisar antara 1.350 – 3.500 gram.
Proses Konservasi
Dengan mengetahui karakteristik ekobiologi ikan Batak, maka sesungguhnya pemerintah daerah sudah melalukan kegiatan konservasi ikan Batak secara in situ melalui penetapan sungai tertentu menjadi daerah habitat ikan Batak yang dilindungi, apakah melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Desa (Perdes).
Dalam peraturan tersebut juga dapat ditetapkan ukuran ikan Batak yang tidak boleh ditangkap masyarakat karena berada dalam kondisi dewasa kelamin (TKG IV) dengan tujuan memberikan kesempatan ikan melakukan regenerasi secara alamiah.
Menurut penulis, pembentukan Kelompok Masyarakat Konservasi (Pokmasi) adalah salah satu cara yang efektif dalam melaksanakan proses konservasi atau pelestarian ikan Batak. Dengan model seperti ini, maka masyarakat lokal menjadi ujung tombak pelaksanaka konservasi di lapangan, sedangkan pemerintah lebih berfungsi sebagai fasilitator, yang memberikan penyuluhan, koordinasi dan dukungan dana terhadap kegiatan konservasi.
Selain itu, upaya pemijahan buatan dan budidaya ikan Batak secara ex situ juga perlu dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas Balai Benih Ikan (BBI) yang telah dibangun pemerintah di berbagai daerah. Kolam-kolam ikan beraliran air deras dengan dasar berbatu atau pasir sebagai tiruan habitat asli tidaklah sulit untuk pembuatannya. Demikian halnya teknologi pembenihan ikan sudah dapat dilakukan dengan bantuan hormon HCG dan Ovaprim, disertai pemberian pakan komersial dipastikan akan terjadi pemijahan buatan dengan derajat penetasan (hatching rate) yang tinggi. Dengan cara seperti ini maka kita dapat memperoleh benih ikan Batak yang kualitas dan kuantitasnya memadai, yang di satu pihak dapat digunakan untuk restoking di perairan habitat aslinya sehingga ikan Batak tidak punah di tanah Batak, dan di pihak lain dapat diproduksi ikan Batak ukuran komersial untuk memenuhi permintaan masyarakat dengan harga yang relatif lebih murah.***
(Penulis adalah Staf Pengajar di Universitas Nommensen Medan).