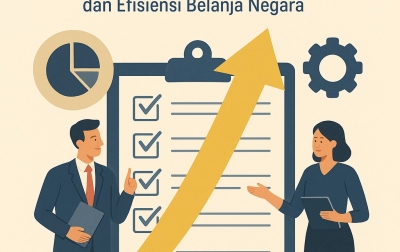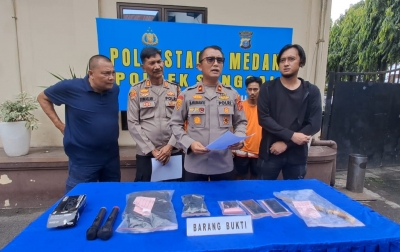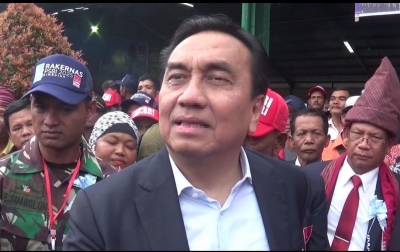'Pecinan' atau Kampung Cina (China Town/Tiongkok Town) merujuk kepada sebuah wilayah/kota yang mayoritas penghuninya beretnis Tionghoa. Saat ini, di dunia, kawasan 'Pecinan' yang biasanya kental dengan unsur budaya Tionghoa sering menjadi sorotan di bidang pariwisata. Beberapa 'China Town' yang kerap menjadi kunjungan utama, misalnya China Town Petaling Street Kuala Lumpur Malaysia, Sago Street Singapura atau Yaowarat Road Bangkok Thailand. Eksistensi 'China Town' juga ada di negara luar Asia Tenggara, misalnya Manhattan Amerika Serikat, Bengal Barat Kolkata India, atau Brisbane Australia.
Oleh: Syafitri Tambunan. Tidak hanya di luar negeri, kehadiran budaya dan arsitektur khas orang Tionghoa ternyata juga tersebar di Indonesia. Sebut saja Jakarta dengan Glodoknya, Waroeng Semawis Semarang, tidak terkecuali Kota Medan. Medan punya kawasan Kesawan (sekarang Jalan Ahmad Yani), Labuhan (Labuhan Deli) serta Komplek Asia Mega Mas dan seputaran Jalan Asia, Jalan Semarang, Jalan Surabaya, dan sekitarnya.
Khusus kawasan pecinan di kota ini, dulunya, terbentuk bersama dengan berkembangnya 'Kampung Medan Putri' menjadi sebuah kota (sekarang Medan). Artinya, adanya kawasan pecinan di Kota Medan tidak bisa dipisahkan dari sejarah berkembangnya 'Tanah Deli' di masa dulu.
Terbentuknya kawasan pecinan pada dasarnya terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor politik dan faktor sosial. Faktor politik berupa peraturan pemerintah lokal yang mengharuskan masyarakat Tionghoa dikonsentrasikan di wilayah-wilayah tertentu supaya lebih mudah diatur. Mengenai aturan ini, memang, Indonesia pada zaman Hindia Belanda dari pemerintah kolonial melakukan segregasi berdasarkan latar belakang rasial. Di waktu-waktu tertentu, malah diperlukan izin masuk atau keluar dari pecinan semisal di Pecinan Batavia. Juga bisa terjadi karena faktor sosial berupa keinginan sendiri masyarakat Tionghoa untuk hidup berkelompok karena adanya perasaan aman dan dapat saling bantu-membantu. Ini sering dikaitkan dengan sifat eksklusif orang Tionghoa. Namun sebenarnya sifat eksklusif ada pada etnis dan bangsa apapun, semisal adanya Kampung Madras/ India di Medan, Indonesia, kampung Arab di Fujian, Cina atau pemukiman Yahudi di Shanghai, Cina.
Kawasan pecinan di Medan dulunya berawal dari migran besar-besaran tenaga kerja (buruh/kuli) asal Daratan Cina/Tiongkok ke Labuhan Deli Medan Indonesia sekitar tahun 1863. Berdasarkan catatan, Ir. Soehardi Hartono, M.Sc, arsitek sekaligus konsultan konservasi, Kota Cina (Pecinan) hadir di Medan diawali dengan dimulainya penanaman tembakau. "Kota Cina, dulu adalah di 'Bulu Cina' Hamparan Perak. Jauh sebelum dimulainya penanaman tembakau, sudah ada orang-orang Tionghoa. Dulu, orang Tionghoa ada yang jadi petani dan pedagang. Bertumbuhnya (populasi) orang-orang Tionghoa di Tanah Deli puncaknya saat berkembangnya industri Perkebunan Tembakau Deli. Dulu, yang terkenal adalah perusahaan yang didirikan Jacobus Nienhuys, orang asing (Belanda) pertama yang mempelopori perkebunan Tembakau Deli," sebutnya.
Jacobus adalah orang asing pertama yang mendapatkan konsensus tanah dari Sultan Deli di masa itu. "Awal kedatangannya di tahun 1863 dan area Medan ini masih hutan belantara, yang dulu terpusat di Labuhan Deli sebab di sekitar daerah itu dia mendapatkan konsesi tanah. Waktu berusaha (buka perusahaan) itu, dia sudah memiliki beberapa pekerja yang merupakan orang Tionghoa setempat yang dulu masih bekerja sebagai petani ditambah beberapa orang India. Dulu, tidak banyak orang Cina yang menetap di Labuhan Deli dan Kota Medan bahkan (saat itu) masih kampung kecil (dulu Medan Putri)," paparnya.
Pada masa pesatnya perkebunan tembakau dan membuahkan hasil, Jacobus menjadi sangat terkenal dari Tembakau Deli. "Panen pertama mendapatkan sambutan terbaik dari pasar di Eropa dan mulailah terkenal Tembakau Deli. Maka, tahun 1870an, pemerintah kolonial membuka pintu investasi di Hindia Belanda dan makin banyak perusahaan-perusahaan asing mengusahakan perkebunan. Mereka mendapatkan konsesi tanah berkembang sehingga butuh kantor baru," sebutnya.
Namun, bukannya membangun kantor di Labuhan Deli, pengusaha ini justru berpindah ke 'Kampung Medan' (Kota Medan). "Begitu mereka mendirikannya, perusahaan-perusahaan lainpun ikut. Sementara itu Labuhan Deli ditinggalkan karena di sana sering terjadi banjir, rawa-rawa, banyak nyamuk dan tidak nyaman.
Deli Maskapai pindah, membuat perusahaan asing lain mengikuti jejak ke 'Kampung Medan' dan meletakkan Medan sebagai kota yang moderen. Mereka juga yang membuat perencanaan Esplanade (Lapangan Merdeka), perusahaan air minum, telepon, dan kereta api. Artinya, cikal bakal Medan menjadi moderen adalah dari maskapai ini. Dibangun oleh Jacobus, begitu melihat Kota Medan berkembang, maka ikutlah pedagang-pedagang pindah. Kuli-kuli asal daratan China/Tiongkok, setelah mereka bebas dari perbudakan kontrak, ada yang mengadu nasib ke kota," beber alumnus program International Visitors Leadership Program bidang Cultural Heritage Preservation di Amerika Serikat ini.
Karena itu, disebutnya, awal mula adanya kawasan pecinan di Medan dimulai dari Labuhan Deli. "Di Labuhan deli, Paya Bakung, Hamparan Perak, juga Langkat, Bulu Cina, di Semendah, Helvetia, dan Marelan. Labuhan Delilah yang terdekat dengan pusat kota. Makanya, setelah habis kontrak, mantan pekerja perkebunan beretnis Tionghoa itu memilih menjadi pedagang, petani misalnya di hamparan perak, yang selebihnya mengadu nasib ke Kota Medan," tuturnya.
Dulunya, Medan punya dua kawasan Pecinan, yakni pertama Kesawan dan sekitarnya, yang ke dua seputaran Jalan M.T. Haryono, Jalan Asia, Jalan Semarang, Jalan Surabaya dan sekitarnya. "Kesawan merupakan Pecinan pertama yang merupakan bentukan arsitektur bangunan hasil ekspresi diri mereka sebagai orang Tionghoa. Tapi, dulu belum bentuk ruko (rumah toko), masih rumah-rumah dari kayu. Namun, di tahun 1890an semua kios-kios pecinan yang dibuat dari kayu itu terbakar barulah akhirnya dibangun dari batu, termasuk yang ada di Jalan Perdana dengan arsitektur khas ruko-ruko lama Tiongkok. Sepanjang Jalan Kesawan itu sebagian besar bermodel arsitektur lama dan kolonial," ujar Direktur Eksekutif BWS periode tahun 2004-2006 tersebut.
Kemudian, akibat pesatnya pecinan yang di Kesawan itu, maka saat itu pemerintah membuat pecinan kedua. "Kemudian, mulai tahun 1920an, berlokasi di sebelah Timur areal Rel Kereta Api, dibangun lagi kawasan pecinan ke dua, yang letaknya melalui Jalan Irian Barat menuju Jalan M.T. Haryono, Jalan Pandu, Jalan Cirebon, Jalan Asia, dan sekitarnya. Tandanya, pecinan ke dua diidentikkan dengan nama jalan di negara Tiongkok aslinya, misalnya Jalan Kanton dan Jalan Makau. Kini, lokasi itu sudah diidentitaskan dengan nama kota-kota di Indonesia. Yang jelas, itulah pecinan ke dua, yang bentuk bangunannya pada waktu itu 1920-1980an sama semua. Setelah masa itu, barulah ada konsep bangunan baru," papar pria yang pernah aktif di Bandung Heritage Society itu.
Rumah-rumah di kawasan pecinan di masa lalu biasanya mengikuti iklim tropis yang ada di Asia Tenggara khususnya Indonesia. "Kenapa disebut tropis? Dilihat dari beberapa hal. Pertama, ada lorong (bagian depan), yang berguna untuk melindungi hujan dan panas. Dua cuaca ini umumnya tetap ada di daerah tropis seperti Indonesia. Lalu, ada jendela berbentuk sisir, yang bisa dibuka dan angin dibiarkan tetap masuk. Kemudian, bagian dalam ada semacam atrium taman atau bagian courtyard yang berguna untuk sirkulasi udara segar serta cahaya alami. bagian dalam untuk udara segar, untuk udara dan cahaya," rincinya.
Sebaliknya, ruko-ruko gaya baru kawasan pecinan tidak lagi sesuai konsep kesesuaian lingkungan. "Bagian yang terbuka (atrium) atau courtyard (taman) itu sudah tidak ada lagi. Cahaya juga dari lampu, sirkulasi udara tidak ada. Otomatis, sudah tidak sehat lagi rukonya, tidak seperti yang lama. Arsitektural Pecinan khas Asia Tenggara itu sudah berkurang drastis. Kawasan Pecinan pertama dan ke dua itu malah kini tidak lagi terjaga, bahkan hampir 100 persen hilang. Sebaliknya, yang di Labuhan masih bertahan," sebutnya.
Dia menilai, kini, arsitektural khas yang sarat sejarah dan kenangan itu hampir 100 persen tertinggal. "Sesuatu yang baik dari masa lalu sudah ditinggalkan. Makanya, kita berharap, yang masih ada, seperti Kesawan, harusnya dilestarikan. (Analogi) begini, kamu simpan foto-foto, hadiah dari sahabat dan buku favorit waktu kecil, untuk kenangan kan? Itu jawaban yang paling simpel. Memori masa lalu itu tersimpan di sini, di arsitektur tadi," ujarnya.
Anggota International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) sejak tahun 2006 ini menegaskan, melalui arsitektural, akan ada identitas budaya yang terwakili. "Sama seperti kawan-kawan Melayu yang masih punya Rumah Panggung atau kolonialnya. Semua ini mengingatkan asal - usul kita seperti ini 'loh. Jadi, kita tidak lagi amnesia sejarah. Bayangkan, jika 10 tahun lagi tidak ada seperti ini. Nah, habis itu, mau orang Tionghoa, mau dia orang Melayu, kalau saat ditanya dulu tinggal di lokasi seperti apa, bagaimana (jawabnya)? Kalau dia bilang seperti sekarang, ya pasti keliru. Asal usulnya menandakan seberapa tahukah dia nenek moyangnya seperti apa. Tahu tidak asal usul nenek moyang kamu dulu di tempat apa? bukan dokter bukan pengusaha, tapi kuli (buruh). Sama menderitanya dengan orang Jawa atau India ke Tanah Deli yang kerja sebagai kuli. Hanya segelintir yang datang sebagai pedagang. Ini yang harus dilestarikan," tambahnya.