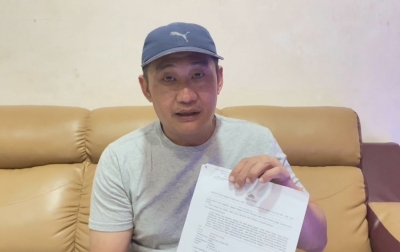Oleh: J Anto
Apa pentingnya menulis kisah pergumulan hidup orang-orang “kecil” di pedesaan? Orang-orang yang tengah bergulat dan berjuang keluar dari jerat kemiskinan serta tak memiliki lakon hidup spektakuler seperti kisah “Papa Minta Saham”-nya anggota dewan yang “terhormat”Setya Novanto?
Apa juga urgensinya menukilkan kisah perjuangan aktivis perempuan yang mengajari anak-anak desa agar terbiasa gosok gigi di pagi hari, membuang ingus yang berleleran di hidung atau mengajari orangtua agar membiasakan balita mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan? Adakah yang tertarik menulis tentang pohon pepaya yang banyak tumbuh di ladang warga, tapi saat berbuah justru pepaya tersebut dijadikan konsumsi ternak babi?
Intinya, adakah sesuatu yang bisa kita pelajari dari kisah orang-orang “kecil” itu?
Pada Oktober 2015 lalu, saya merasa beruntung dilibatkan PESADA (Perkumpulan Sada Ahmo), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang dikenal gigih berjuang membangun relasi kesetaraan gender di segala bidang kehidupan, sebagai salah satu tim penulis buku Pedoman Perilaku dari OMS yang berpusat di Sidikalang itu.
Semua cerita “biasa” di atas, saya peroleh saat merekonstruksi kegiatan diskusi yang dihadiri sejumlah aktivis OMS Sumut, warga desa dampingan, pejabat pemerintah dan para aktivis OMS Pesada sendiri. Hasil diskusi menjadi salah satu bagian dari buku Pedoman Perilaku PESADA yang ditulis Pdt Bonar Lumbantobing, salah seorang pendiri OMS tersebut.
Kisah tentang balita yang diajari cara“gosok gigi”, “buang ingus”, “makan sayur dan buah-buahan” sekilas terdengar remeh. Tapi mengubah budaya hidup sehat bagi anak-anak pedesaan selain bukan hal mudah, sejatinya juga menyelamatkan sebuah generasi. Dituntut sikap kesabaran, kecintaan dan ketulusan. Bayangkan balita yang tak ada sangkut paut hubungan keluarga apalagi pertalian darah, harus dibersihkan ingusnya.
Berapa honor yang diterima untuk pekerjaan mulia tersebut? Tak lebih dan tak kurang Rp 30.000 per bulan!
Terpepet kebutuhan atau pekerjaan? Ternyata tidak. Simak tuturan Dinta Solin. Sebelumnya sebagai guru honorer tahun 1993 setiap bulan ia sebenarnya sudah mendapat penghasilan Rp 50.000. Itu artinya saat memutuskan bergabung ke Pesada sebagai guru di Taman Bina Asuh Anak (TBAA), PAUD-nya PESADA, penghasilan Dinta berkurang hampir separuhnya. Orangtua Dinta tentu saja protes, tapi Dinta tetap pada pilihannya.
“Dimana pun saya berada, yang penting saya bisa melayani.” Memberikan pelayanan kepada orang-orang kecil, bukan sekadar bekerja, mungkin itu kata kuncinya.
Ada juga testimoni Rouli Manurung, aktivis PESADA yang juga bergabung sejak 1993. Ia memulai aktivismenya dengan mengorganisir kaum ibu pedesaan dengan membentuk lembaga ekonomi kerakyatan. Populer disebut Credit Union (CU). Lokasinya di beberapa desa di Pakpak Bharat, sebelum tahun 2003 daerah itu masih termasuk wilayah Kabupaten Dairi. Honor yang ia terima waktu itu Rp 45.000 per bulan. Menyiasati keterbatasan honor, saat turun ke lapangan, ia kerap membawa “bontot” dari rumah.
Pernah ia memasak nasi satu mug dalam periuk di rumah yang dijadikan penyelenggara TBAA. Saat tengah menanak nasi, Rouli juga harus menyapu halaman TBAA. Hanya ditinggal kurang lebih 5 menit, saat kembali ke dapur, ia menjumpai nasi sudah berubah jadi kerak. Namun ia tak kurang akal. Nasi kerak itu lalu disiram air dan ditambah sedikit garam. Jadilah bekal makan siang saat melakukan turba ke kelompok warga.
Transportasi umum antar desa di Kecamatan Tinada, juga kecamatan lain yang bertetangga, waktu itu juga sangat minim, bahkan tidak ada. PESADA sendiri belum mampu memberinya fasilitas sepeda motor. Alhasil Rouli memilih transportasi tradisional: berjalan kaki. Terkadang: “Agar bisa cepat jalan, saya buka sandal dan berlari-lari.” Jalan kaki alias nyeker dilakukan Rouli terutama saat harus menuju tempat pangkalan bus yang akan membawanya pulang ke Sidikalang.
Maklum, jika terlambat maka ia harus bermalam lagi di Tinada. Soalnya bus hanya melayani trayek Tinada -Sidikalang, jaraknya berkisar 40 KM, 2 kali per hari.
Merawat Idealisme
Mendengar kisah Dinta dan Rouli kita disadarkan bahwa ada sesuatu yang khas pada aktvisme OMS pada masa Orde Baru: perjuangan untuk mengubah tatanan sosial yang adil itu bersandar pada lakon hidup penuh kesederhanaan dan ketulusan. Ada juga nilai pelayanan atau berpihakan pada mereka yang termarjinalkan secara sosial, ekonomi, budaya dan politik. Orientasi terhadap materi tak menjadi prioritas utama. Istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan spirit seperti itu barangkali terangkum dalam istilah idealisme.
Persoalannya, waktu terus berjalan. Dewasa ini, kita tengah dikepung dengan arus materialisme dan hedonisme yang dibawa rezim kapitalisme. Menumbuhkan dan merawat kultur idealisme bukan hal mudah. Tak terkecuali di kalangan aktivis OMS seperti LSM.
Terlebih lagi paskareformasi, muncul fenomena “banjir dana” di kalangan LSM. Bahkan saat tsunami memporak-porandakan Aceh dan Nias, bekerja di LSM tiba-tiba jadi bahan rebutan para pencari kerja. LSM mendadak jadi primadona. Gaji jutaan rupiah, bahkan tak sedikit yang dibayar dengan dollar Amerika serta fasilitas kerja ala ekspatriat Amerika dan Eropa membuat kabur batas antara aktivisme versus kerja kantoran.
Dan dampaknya masih terasa hingga sekarang.
Era aktivisme berkarya di LSM yang saat orde baru dianggap sebagai pekerjaaan “subversif”, “merongrong kewibawaan negara”, “mbalelo” atau “tukang jual kemiskinan ke luar negri”, tampaknya makin memudar. Pandangan bahwa bergiat di LSM pasti “madesu” atau “kere materl” tampaknya tergerus oleh fenomena “banjir” pendanaan.
Tak salah menjadi sejahtera secara ekonomi dengan berkarya di LSM. Yang salah barangkali saat perjuangan untuk mengubah dunia agar lebih baik bersama masyarakat akar rumput, tak lagi dihayati sebagai elan perjuangan merebut hak rakyat yang termarginalisasi oleh berbagai sebab dan aktor.
Tetapi lebih dihayati sebagai pekerjaan mengelola proyek pembangunan seperti yang dilakukan actor negara. Idealisme seolah telah disimpan dalam laci meja kantor, kesederhanaan dan ketulusan seolah telah dikunci rapat-rapat dalam gudang.
Kisah-kisah perjumpaan para aktivis Pesada dengan “masyarakat akar rumput”, karena itu ibarat album lama yang telah berdebu menghuni gudang karena tak pernah dibuka lagi. Bagi aktivis LSM yang hidup di era Orde Baru, perkisahan tersebut tentu membangkitkan kembali ”romantisme” lama.
Tapi bagi generasi yang berkarya di LSM paska reformasi, tentu perkisahan tersebut dapat dijadikan cermin atau sumber inspirasi dan refleksi saat melakukan penguatan masyarakat akar rumput.
Terlebih lagi kisah-kisah perjumpaan aktivis PESADA dengan masyarakat akar rumput yang bersandar pada nilai kesederhanan dan ketulusan itu telah diinstitusionalisasi dan diwariskan kepada mereka yang lebih yunior di lembaga PESADA itu sendiri. Semacam estafet nilai.
Tentu hal itu dilakukan untuk memastikan agar nilai-nilai tersebut tetap hidup dan menghidupi seluruh aktivis PESADA sepanjang hayat. Pengurus boleh berganti seiring perjalanan waktu, namun nilai-nilai luhur yang menjadi roh lembaga tak punah digerus nilai-nilai lain yang lebih memuja hedonisme atau materialisme.
Barangkali itulah signifikansi dari kisah-kisah orang kecil yang nukilannya terdapat dalam buku “Pedoman Perilaku, 25 Tahun PESADA Menapak Perjuangan Kesetaraan Gender di Sumut”. Sebuah buku yang berisi kumpulan nilai yang lahir dari semangat pelayanan sosial terhadap mereka yang mengalami ketidakadilan structural dan personal.***
Penulis bekerja di Kajian Informasi, Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS)