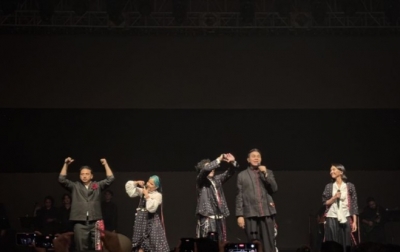Oleh: Prof. Dr. Ir. Hasan Sitorus, MS. Ribuan ton ikan mati mendadak di perairan Danau Toba, khususnya di zona Bandar Saribu dan Zona Rappa, Kelurahan Haranggaol, Kecamatan Haranggaol Horison, dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 41 miliar (Analisa, 7/5/2016). Kejadian kematian ikan secara massal di perairan Danau Toba sudah terjadi berulangkali, sebagaimana terjadi di beberapa danau atau waduk di berbagai wilayah di tanah air.
Tentu timbul pertanyaan, apa kemungkinan faktor penyebab terjadinya kematian ikan secara massal di suatu perairan ? Berdasarkan aspek ekobiologi ikan, terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya kematian populasi ikan di suatu perairan, yakni : 1) Kehabisan oksigen terlarut (Dissolved Oxygen/DO) dalam air, 2) Timbulnya senyawa beracun dalam air, dan 3) Serangan penyakit akibat bakteri dan virus.
Terjadinya deplesi kandungan oksigen terlarut dalam air disebabkan beberapa hal, yakni : a) oksigen terlarut habis digunakan mikroba air untuk menguraikan bahan organik sisa pakan yang terlarut dan tersuspensi dalam air, sehingga ikan tidak kebagian oksigen lagi dan bisa menimbulkan kematian mendadak akibat kadar DO sudah mencapai titik kritis untuk kehidupan ikan yakni < 3 mg/liter. b) senyawa hara hasil degradasi bahan organik sisa pakan tersebut menyebabkan penyuburan yang berlebihan (eutrofikasi) yang merangsang terjadinya ledakan populasi plankton/algae (blooming algae) dalam air.
Pada siang hari fitoplankton melakukan asimilasi (fotosintesis) dan menghasilkan oksigen ke dalam air sehingga kondisi aman, tetapi malam hari fitoplankton melakukan respirasi sehingga dengan kepadatan yang tinggi menyebabkan oksigen terlarut habis dalam air, dan ikan akan mati secara massal terutama setelah waktu dini hari.
Terbentuknya senyawa beracun dalam air adalah hasil dekomposisi atau penguraian senyawa organik sisa pakan atau bahan pencemar organik limbah domestik dalam air secara anaerobik (tanpa oksigen) terutama di bagian dasar perairan, yang menghasilkan senyawa-senyawa beracun seperti amonia (NH3), methan (CH4) dan asam sulfida (H2S).
Dari ketiga senyawa racun ini, gas amonia bebas yang paling mematikan biota air terutama dalam kondisi pH (tingkat keasaman) air tinggi. Gas-gas beracun ini bisa naik dari lapisan air bagian dasar ke lapisan air permukaan akibat terjadinya perubahan cuaca dari musim kemarau menjadi musim hujan.
Pada cuaca berhujan, suhu permukaan air lebih rendah daripada lapisan di bawah, sehingga massa air dari lapisan atas tenggelam (sinking water) ke bawah dan lapisan air dari bawah yang mengandung senyawa beracun naik ke lapisan permukaan air (upwelling), sehingga secara mendadak dapat mematikan ikan budidaya.
Di sisi lain, kematian ikan secara mendadak dan bersifat massal juga dapat disebabkan serangan mikroba patogen seperti bakteri dan virus. Banyak hasil riset memperlihatkan bahwa ada korelasi yang kuat antara kualitas air yang buruk dengan berkembangnya penyakit ikan budidaya. Bila ikan telah terserang virus maka tidak ada lagi obatnya, harus dipanen segera, yang bisa diobati bila ikan terserang bakteri patogen dengan menggunakan obat antibiotik. Oleh sebab itu, kualitas air perairan sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan budidaya ikan.
Pada kondisi padat tebar ikan yang tinggi dengan pemberian pakan buatan (pellet) yang intensif, maka dapat dipastikan akan menghasilkan limbah sisa pakan yang tinggi dan akan memasuki perairan. Dari hasil penelitian diketahui, sebanyak 20 % dari pakan yang diberikan dalam proses budidaya akan menjadi limbah, dan 55 % terlarut dalam air sebagai bahan organik dan 45 % mengendap di dasar perairan. Oleh sebab itu dapat kita bayangkan berapa banyak limbah budidaya yang memasuki suatu perairan danau bila pakan yang digunakan berupa pelet dengan jumlah ratusan ton per bulannya.
Lokasi perairan yang secara terus menerus dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya ikan dengan teknologi intensif, kondisi itu akan memberikan peluang terjadinya kematian ikan mendadak. Dengan perkataan lain, bila daya dukung perairan telah terlampaui oleh suatu aktivitas manusia, maka perairan itu tidak mampu lagi membersihkan dirinya sendiri secara cepat (self purification) dalam kondisi natural, terlebih-lebih bila arus perairan lambat dan waktu tinggal (residence time) bahan limbah relatif lama dalam perairan, maka ekosistem perairan akan menjadi rusak dan membutuhkan waktu lama dan biaya besar untuk memulihkannya. ***
Penulis Guru Besar Ilmu Perikanan dan Kelautan di Universitas Nommensen Medan