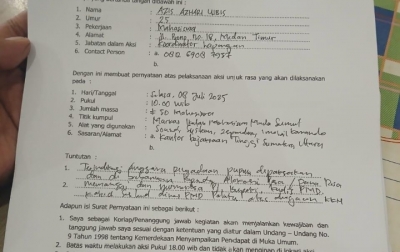Oleh: Riduan Situmorang
Plagiarisme bisa didekatkan artinya dengan meniru, menyontek, dan menduplikasi sebuah ide tanpa permisi dan tanpa mencantumkan darimana ide itu diperoleh. Memang, belum ada definisi final tentang bagaimana seseorang itu disebut sebagai pencuri karya. Akan tetapi, meskipun demikian, masyarakat sudah punya tolok ukur tersendiri tentang kapan seseorang dicap sebagai plagiat. Ukurannya adalah ketika sebuah artikel, misalnya, disadur ulang hampir secara utuh tanpa mengubah tendensi dan itu diatasnamakan oleh dirinya sendiri.
Tetapi catat, plagiarisme tidak sama dengan mengutip. Saya, jujur saja, termasuk orang yang sangat doyan mengutip pendapat para ahli. Sebab, bagi saya, kutipan itu penting untuk mendukung sekaligus menguatkan pesan yang ingin disampaikan. Bahkan, ada kesan tidak percaya diri ketika sebuah tulisan murni adalah kata-kata saya sendiri. Hanya memang, karena tidak bisa permisi secara langsung, saya selalu menyelipkan bahwa kutipan itu berasal dari si Anu atau si Pulan. Yang mau saya ungkapkan di sini adalah bahwa jikalau mengutip itu hanya untuk menguatkan pendapat, ini bukanlah palgiat. Maaf kalau saya salah!
Saya tidak akan menyinggung seseorang di sini. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya adalah agar budaya palagiarisme ini pelan-pelan dihilangkan. Sebab, sadar atau tidak, plagiarisme merupakan “warisan budaya” yang tak pernah lekang dari kehidupan kita. Siapa pun itu, apakah dia orang kecil ataupun orang besar, semua sama saja. Kalau tak percaya, sila Tuan dan Puan melacaknya dari internet! Di sana, mulai dari guru besar, dosen, pemerintah, bahkan masyarakat kecil pun ada yang suka mencomot karya orang lain.
Patut Dipuji
Memang, kita menaruh hormat pada mereka karena setelah diketahui menduplikasi karya orang lain, mereka langsung mengundurkan diri dari jabatannya. Tak jarang pula beberapa dari mereka langsung mengadakan konfrensi pers atau mengungkapkan rasa penyesalannya melalui media. Dapat dibayangkan bahwa untuk “mengakui” keculasan itu adalah hal yang memalukan sehingga bagaimanapun, kita harus tetap mengapresiasi mereka.
Semua orang suka dipuji, tetapi tak banyak orang yang mampu tetap “jantan” mengakui kesalahan. Maksud saya, keberanian dan kemauan mereka untuk meminta maaf, bahkan menjalani hukuman (sosial) adalah hal yang patut dipuji. Masalahnya adalah, minta maaf bukan menjadi silih atas dosa. Selalu ada yang dikorbankan. Sederhananya, maaf diterima, tetapi hukuman harus tetap dilanjutkan. Sampai di sini barangkali semuanya sudah jelas.
Tetapi, entah hanya saya yang merasakan, rasanya adalah sangat tidak adil jika hanya karena mencuri, maka kita mencoretnya dari “kehidupan”. Betul, dosa harus ditanggung dan yang menanggung adalah si pendosa sendiri. Baiklah, karena saya termasuk orang yang mengasyiki dunia literasi, izinkan saya mencontohkannya dalam bentuk artikel. Dan, kebetulan artikel sejauh ini lebih banyak diproduksi oleh media, seperti koran, izinkan pula saya menyuguhkan pendapat saya berkaitan tentang artikel koran.
Seperti kita tahu, adalah sangat sulit menembus rubrik pada sebuah koran. Standarnya tidak dapat diukur dengan akurat. Seperti yang pernah dituliskan pada sebuah kata pengantar di buku Cerpen Pilihan Kompas (lihat, saya mengutip bukan?) bahwa standar cerpen untuk masuk ke Kompas, misalnya, hampir tidak ada. Standar itu ada pada selera redaktur. Apakah itu maskdunya karena Kompas tak punya penilaian sehingga rendahan dan mengandalkan selera? Tunggu dulu!
Pada sebuah pertemuan yang diselenggarakan Kompas melalui Forum Pembaca Kompas, seseorang pernah menggumamkan bahwa redaktur Kompas itu adalah orang-orang hebat sehingga hanya orang hebat yang bisa berhasil nimbrung dan dimuat di sana. Tetapi, alangkah terkejutnya saya ketika orang Kompas sendiri mengatakan bahwa yang hebat itu bukan redakturnya, melainkan para penulisnya. Redaktur hanya menilai orang-orang hebat sehingga tangkapannya pun orang hebat.
Saya yakin sekali, redaktur harian apa pun itu merasakan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh orang Kompas. Bukan saya hendak mengatakan bahwa redaktur itu tak tahu apa-apa. Jujur saja, saya tak dapat membayangkan betapa pusingnya sebagai redaktur yang harus menerima ratusan artikel dari segala penjuru setiap harinya. Dan, mereka harus menilai mana yang dimuat, mana yang tidak. Mana yang aktual, mana yang buram. Mana yang membangun, mana yang merusak.
Belum lagi kalau kita berspekulasi kotor bahwa mereka harus menerima serapah dari orang-orang tertentu lantaran karyanya tak kunjung dinaikkan. Atau yang lebih emosional, harus menyediakan hati yang lapang untuk menerima curhatan dari setiap penulis. Maksud saya, menjadi redaktur bukan pekerjaan mudah. Apalagi konon, redaktur hampir selalu menjadi orang pertama yang harus disalahkan ketika di kemudian hari diketahui bahwa karya yang diloloskan itu adalah hasil plagiasi. Rakyat pasti geram.
Plagiator dan Kedelai
Rakyat dan pembaca hampir tak mau tahu. Rakyat dan pembaca adalah raja. Bagi mereka, redaktur mestinya harus mahatahu. Redaktur harus pula melacak apakah tulisan tersebut sudah pernah dimuat atau tidak. Padahal, kalau kita jujur, itu bukanlah tujuan dan pekerjaan redaktur. Dan, tentu saja sangat tak adil menempatkan redaktur sebagai orang yang mahatahu dan menanggungkan keserakahan para penulis—baik itu senior maupun junior—pada redaktur.
Itulah kiranya alasan mengapa hampir semua redaktur di dunia ini mengambil langkah aman. Redaktur tak mau rakyat geram yang lalu meninggalkan harian yang dibesuknya sehingga cara yang acap dipilih adalah menyerahkan tanggung jawab itu pada si penulis. Jika terbukti penulis artikel itu melakukan plagiasi, maka dia harus didaftarhitamkan. Di-black list istilah kerennya. Nah, isu pendaftarhitaman inilah sebenarnya yang mau saya beberkan di kolom ini.
Ini bukan soal apakah saya setuju atau tidak tentang black list. Ini soal mewarisi dan mempertanggung jawabkan keilmuan. Benar, adalah bijaksana jika kita memaafkan sembari menghukum para plagiator. Tetapi, apakah kita harus menghukumnya seumur hidup? Lagipula, bukankah yang kita benci adalah plagiarismenya dan bukan orangnya? Bukankah pula tujuan kita salah satunya adalah “menyelamatkan” agar plagiator itu tidak melakukan hal yang sama lagi? Jika demikian halnya, bukankah jika kita mem-black list-nya, itu artinya kita telah menghentikan dia?
Sekali lagi, ini bukan perihal saya tidak setuju pem-blacklist-an. Hanya, dalam hati saya yakin, seseorang pasti bertobat. Maka itu, (ini hanya pandangan) mari menghukum plagiator pada masa waktu tertentu. Setelah dirasa hukuman itu selesai, mari biarkan dia berkembang lagi. Orang hebat biasanya lahir setelah dihukum. Orang baik pun sering lahir dari pertobatan. Lagipula, jika plagiator dapat disamakan dengan koruptor yang suka mencuri yang bukan haknya, bukankah koruptor juga setelah selesai masa hukumannya, maka dia akan bebas?
Ya, plagiarisme harus dimusnahkan sehingga plagiatornya harus dihukum. Tetapi, memusnahkannya bulat-bulat boleh disamakan dengan menghentikan bakatnya. Maaf, kalau saya kejauhan. Maksud saya adalah, bagaimana kalau kita coba untuk tidak menghukum plagiator seumur hidup dengan semangat bahwa di ujung kebohongan pasti ada kejujuran sebagaimana di ujung mencintai tidak selalu membenci?
Sekali lagi, saya sangat benci palgiarisme, tetapi saya harus mengakui bahwa plagiator layak diberi kesempatan kedua. Kecuali plagiatornya tak jera-jera, maka hukum “pembantaian” harus dijatuhkan karena nyata bagi kita bahwa dia rupanya lebih “dungu” daripada kedelai. Kedelai saja tak mau jatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya. Masa plagiator iya? ***
Penulis adalah, Pegiat Literasi di PLOt (Pusat Latihan Opera Batak)