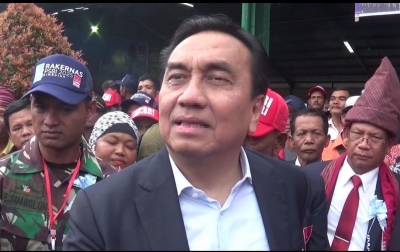Oleh: M. Arif Suhada
Sedari kecil kita diajarkan untuk tidak menganggap sepele terhadap apapun. Sikap sepele bisa diartikan sebagai memandang remeh, enteng, sebelah mata, dalam menyikapi segala sesuatu. Sepele adalah sikap negatif yang harus dihindari melekat dalam pribadi kita. Sebab kesepelean itu bisa berakibat buruk dan menimbulkan penyesalan pada diri kita.
Contoh sederhana, sewaktu sekolah misalnya, kita pasti pernah memandang sepele pada mata pelajaran yang kita anggap mudah, dan kita malas belajar karena merasa sudah menguasai materi pelajaran tersebut. Sialnya, ketika ujian, soal-soal yang tersaji malah tidak bisa kita jawab. Padahal soal yang diberikan pernah dipelajari sebelumnya. Hanya saja ketika itu kita lupa cara pengerjaannya sebab tidak ada persiapan. Alhasil, nilai ujian kita pun anjlok. Timbulah penyesalan mengapa kita tidak belajar pada hari-hari sebelumnya. Rasa sepele yang kita tanam itupun akhirnya menyesakkan dada.
Memang rasa sepele itu berbuntut pada sebuah penyesalan. Apa yang kita pikirkan ternyata tidak sesuai dengan realita di lapangan. Kita cenderung malas untuk memikirkan kemungkinan terburuk dari setiap tindakan yang kita lakukan. Praktis, itu membuat segala sesuatunya seakan tidak ada masalah. Kita pun menjadi lebih senang memandang remeh menyikapi berbagai persoalan. Barangkali sampai kita sendiri yang merasakan akibatnya, barulah kemungkinan kesadaran itu akan muncul.
Sikap itulah yang saat ini benar-benar meracuni paradigma berpikir masyaraka kita, utamanya dalam konteks lingkungan. Sehingga setiap bencana berawal dari sikap sepele itu. Berbagai peringatan tentang lingkungan selalu ditanggapi sepele dan diabaikan. Maka tidak heran, jika masalah lingkungan sulit sekali diatasi. Meski berulangkali diberi perintah, anjuran, dan larangan, tapi hanya sedikit di antara kita yang menjalankannya secara serius. Selebihnya masih mengedepankan rasa sepele dalam dirinya.
Lihatlah misalnya, mesti larangan membuang sampah sembarangan itu sudah terpatri dalam ingatan, bahkan sejak kita masih SD. Namun, masih banyak di antara kita yang suka sepele untuk membuang sampah sembarangan. Apalagi jika dirasa jumlahnya sampah cuma sedikit. Padahal, tumpukkan sampah itu mulanya juga diawali dari jumlah yang sedikit, lalu lama-lama menjadi bukit. Maka, menyepelekan sampah yang sedikit, berarti mendukung timbulnya keberadaan sampah yang lebih banyak lagi.
Anggaplah yang dibuang itu berupa sampah-sampah kecil atau yang jumlahnya sedikit. Seperti bungkus permen, plastik nasi bungkus, bekas minuman gelas, atau sampah lain yang sering kita hasilkan dalam aktifitas keseharian. Tapi jika kenyataan itu juga diamini dan dilakukan oleh ribuan orang, maka dalam waktu bersamaan ada ribuan sampah yang mencemari lingkungan. Inilah yang barangkali tidak terpikirkan sampai kesana, atau sebenarnya sudah dimengerti hanya saja disepelekan. Tampaklah memang jika kesepelean itu menutupi nalar berpikir yang sehat. Maka menjadi beralasan, jika berawal dari kesepelean itu bisa menyebabkan datangnya berbagai bencana yang merusak lingkungan kita.
Boros Karena Sepele
Pada akibat yang lain, rasa sepele yang kita pupuk dalam diri juga menumbuhkan sikap boros dalam hidup. Pemakaian barang secara berlebihan (boros) tidak dipahami sebagai suatu permasalahan yang berarti. Berangkat dari kesepelean itu misalnya, sangat jarang kemudian yang menyadari penggunaan tisue tanpa dihemat memiliki andil dalam pengurangan pohon di hutan. Pun dalam pemakaian plastik yang mengutamakan kebiasaan sekali pakai buang, tidak dilihat bahwa sampah plastik bisa mencemari lingkungan sampai ratusan tahun.
Bahkan, ketika pemerintah mengambil kebijakan tentang penerapan kantong plastik berbayar, sikap boros yang bermula dari kesepelean itu masih belum berubah. Padahal diambilnya kebijakan itu tidak terlepas karena kesepelean kita dalam menggunakan kantong plastik secara boros. Maka pemerintah pun mengenakan biaya sebesar Rp 200 perkantong plastik yang kita gunakan. Alih-alih supaya banyak yang melakukan penghematan, yang terjadi lagi-lagi sikap penyepelean lebih mendominasi. Ya, biaya Rp 200 itu dianggap tidak ada artinya, dan begitu mudah dikeluarkan sehingga kebiasaan boros dalam pemakaian kantong plastik masih terus berlanjut.
Padahal dengan adanya kebijakan itu harusnya bisa dipahami bahwa keberadaan sampah plastik di lingkungan kita sudah sangat mengkhawatirkan. Maka itu, kita diminta untuk bisa melakukan penghematan dan menggalakkanan pemakaian kantong belanja yang lebih ramah lingkungan. Jadi substansinya bukan pada jumlah biaya Rp 200 itu, tetapi mengapa kemudian kebijakan itu menjadi penting untuk diambil.
Kalaulah dengan biaya Rp 200 yang diterapkan pemerintah tidak lantas membuat kita segera tersadar, itu berarti kesadaran kita benar-benar hanya bersandar pada hukuman. Tanpa sadar kita telah meminta kepada pemerintah untuk dinaikkan lagi pengenaan biayanya secara berkali-kali lipat, hanya dengan begitu kesadaran itu baru muncul. Benarkah itu yang kita mau? Padahal baiknya, kita bisa menghemat atau melakukan sesuatu yang positif itu, tanpa terlebih dahulu harus terbebani unsur keterpaksaan.
Namun apalah mau dikata, kesepelean itu telah membawa kita pada kondisi yang sekarang ini, hukuman. Selain dihukum oleh lingkungan itu sendiri lewat berbagai bencananya, kita juga kerap dihukum dengan kebijakan-kebijakan yang membebani diri kita. Pun demikian, masih belum terlambat bagi kita untuk memperbaikinya. Maka, kegemaran kita dalam menyepelekan setiap tindakan yang bisa berdampak buruk bagi hajat hidup orang banyak haruslah segera dihentikan. Terlebih sikap semacam ini harus dipadamkan dalam diri kita agar peranan buruknya tidak semakin meluas dan bertambah parah.
Jika dengan keadaan ini ternyata juga tidak lantas membuat kita merasa terbebani dan lalu berubah, berarti kita sedang menanti hukuman yang lebih berat itu datang. Apabila kita terus-terusan kena hukuman karena sebuah kebiasaan dan kesalahan yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak lebih baik dari keledai. Sebab keledai pun tidak akan terjatuh di pada lubang yang sama.
(Penulis adalah mahasiswa UIN Sumatera Utara)