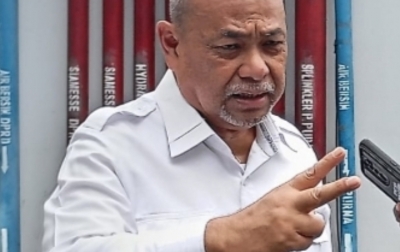Oleh: Sartika Sari
Sejarah sastra Indonesia telah menjadi ruang dikotomisasi yang menempatkan sastra berdasarkan gejala tertentu. Tidak hanya berdasarkan kurun waktu dan peristiwa yang mendampingi kemunculan teks sastra tersebut saja. Juga berdasarkan karakteristik yang sebenarnya tidak berdiri sendiri. Salah satunya adalah posisi sastra serius dan sastra populer. Kedua label ini lahir dan berkembang sebagai sebuah azimat. Lahirnya untuk mengkategorisasi kemunculan sebuah karya sastra berdasarkan beberapa cara pembacaan.
Pada bagian ini saya membahas kedudukan keduanya dengan mempertimbangkan gejala sosial dan perkembangan teks-teks sastra tersebut. Saya membagi tulisan ini dalam dua bagian. Pertama, saya menyelidiki kemunculan sastra populer dalam khazanah kesusastraan Indonesia dan defenisi-defenisi yang muncul. Kedua, saya memaparkan perkembangan sastra populer saat ini di tengah isu diskriminatif yang melingkarinya.
Masa Kelahiran
Populer atau serius, tidak bisa dilepaskan dari iklim yang membentuk keseriusan dan kepopuleran sebuah karya sastra. Yudiono KS dalam Pengantar Sejarah Sastra Indonesia menggambarkan iklim serius. Katanya, melalui suasana yang dibangun oleh Majalah Horison, Sastra, Pusat Bahasa, Fakultas Sastra dan Dewan Kesenian Jakarta. Mengisyaratkan lingkungan yang “serius” atau resmi untuk berbagai kegiatan sastra yang berkaitan dengan penciptaan (puisi, kritik, prosa dan esai). Demikian juga penelitian dan pengembangan sastra.
Hal tersebut pada akhirnya membentuk stereotipe atas karya sastra Indonesia berdasarkan ruang kelahirannya. Di luar lingkungan-lingkungan itu, karya sastra juga berkembang di wilayah media massa. Koran dan majalah umum yang tidak hanya di kota-kota besar. Misalnya Jakarta, juga telah meluas di kota lain. Malang, Yogyakarta, Medan, Makasar, Semarang, Surabaya dan Padang.
Ranah dan media yang berbeda tersebut melahirkan label yang berbeda pula. Karya sastra yang dibangun dari lingkungan serius disebut sebagai sastra serius. Karya sastra yang beredar di media dan wadah yang menjadi milik masyarakat luas disebut sebagai sastra populer. Sumardjo (1982) menyebutkan, istilah sastra populer sebenarnya lazim digunakan pada tahun 70-an, melalui kesuksesan novel Karmila (Marga T.). Juga Cintaku di Kampus Biru (Ashadi Siregar).
Sastra populer senantiasa disandingkan dengan sastra serius sebagai oposisinya. Penyandingan kedua label ini agaknya tidak sekadar berfungsi menandai media dan ranah, namun lebih jauh, kemungkinan besar bersifat politis.
Dari kondisi yang disebutkan Hilmar Farid dan Razif (2008), pada akhir abad ke-19, industri percetakan mulai bisa diakses oleh kalangan Tionghoa. Mereka menerbitkan beberapa surat kabar dan cerita-cerita silat dalam bentuk novel.
Paparan Jedamski sebagaimana yang dibahas Arief (2014), selain cerita silat, terdapat pula saduran cerita-cerita Barat. Antara lain Robinson Crusoe, The Count of Monte Cristo dan Sherlock Holmes. Menariknya, cerita-cerita Barat ini kerap diadaptasi sedemikian rupa, sehingga memiliki latar cerita di Jawa.
Percetakan dan peredaran bacaan-bacaan tersebut terbatas pada orang-orang partikelir Tionghoa. Orang-orang pribumi baru ikut terjun dalam industri percetakan pada awal abad ke-20 melalui harian Medan Prijaji sebagai pelopor. Kendati demikian, keberadaan bacaan yang diproduksi oleh Tionghoa ternyata dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial.
Sejarah sastra dituliskan Pramoedya Ananta Toer (2006) dan Siregar (1964) pemerintah kolonial Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat pada tahun 1908. Belanda menggunakan bahasa Melayu Riau dengan kampanye besar-besaran. Pendirian Komisi Bacaan Rakyat, bertujuan untuk melindungi rakyat dari bacaan Tionghoa yang dinilai banal. Tidak mendidik dan tidak punya selera seni yang baik.
Tahun 1917 DA Rinkes mengubah nama Komisi Bacaan Rakyat menjadi Balai Poestaka guna menyaingi “batjaan liar”. Istilah ini merujuk pada semua terbitan di luar penerbitan resmi kolonial. Pembentukan Balai Poestaka, sekaligus juga memunculkan kelas dalam sastra.
Pada satu sisi, terdapat “batjaan liar”, sastra kelas rendah. Menggunakan bahasa Melayu Pasar, lingua franca yang hidup sebagai bahasa sehari-hari dalam perdagangan antar pulau di Indonesia. Dikonsumsi pribumi untuk membodohi dirinya sendiri. Di sisi lain, terdapat sastra keluaran Balai Poestaka, sastra serius. Berbahasa Melayu Tinggi dan diperuntukkan bagi pribumi berpendidikan. Kondisi ini sangat jelas menunjukkan bahwa istilah sastra populer (sastra milik masyarakat umum) dan sastra serius sangat politis.
Perkembangan selanjutnya, Arief (2014) menyebutkan, pertengahan tahun 50-an hingga tahun 1965, sastra populer terbagi menjadi dua kategori. Sastra propaganda dan sastra hiburan. Kedua kategori lahir dari asumsi, karya sastra yang ditulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Tanpa metafora dan bunga kata yang menyulitkan pembacaan. Pada tahun 50-an, karya sastra yang muncul adalah cerita-cerita silat, detektif, serial western, dan novel novel saduran. Sastra propanganda yang dimaksud kemudian didominasi oleh sastrawan Lekra dan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN). Ideologi yang mereka usung masing-masing guna mempertahankan kedudukan dalam konfigurasi politik yang sengit. Pada tahun 1990-an dan 2000-an, sastra populer memiliki beberapa label baru. Yaitu chicklit, teenlit, “sastra wangi”, serta sastra pop-islami.
Diskriminasi dan Hegemoni Sapardi Djoko Damono (1979) pernah berpendapat. Pembicaraan tentang sastra puler tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan populer. Menurut Barker (2009) budaya populer adalah budaya yang diproduksi secara komersial. Sebagai makna-makna dan praktik-praktik hasil produksi khalayak populer pada momen konsumsi.
Dari sisi berbeda, Williams (1983) menyatakan empat hal yang dapat kita rujuk pada kata populer tersebut. Pertama, populer dapat merujuk atau memiliki makna : banyak disukai orang. Kedua, populer tersebut dapat merujuk atau memiliki makna: jenis kerjaan rendahan. Ketiga, populer dapat merujuk atau memiliki makna: karya yang dilakukan untuk menyenangkan orang. Keempat, populer dapat merujuk atau memiliki makna: budaya dibuat untuk diri sendiri.
Mengacu pada asumsi ini, dapat disimpulkan. Sastra populer adalah kesusastraan yang berkaitan erat dengan posisinya sebagai komoditi, bersifat komersial dan modern. Kendati demikian, penyandingan budaya populer dengan sastra populer tidak selesai pada pembentukan karakteristik semata. Label populer sendiri telah menjadi perdebatan yang menjurus pada praktik-praktik diskriminasi dan hegemoni.
Pada isu diskriminasi, pernyataan Adorno dan kaum Leavivisme sangat jelas telah menjadi bentuk diskriminasi terhadap kemunculan budaya populer. Pendapat Adorno sebagaimana yang dibahas Barker (2009), budaya populer adalah budaya yang berbasis komoditas. Tidak autentik, bersifat manipulatif dan tak memuaskan. Lebih jauh, Adorno beranggapan, industri budaya yang menghasilkan budaya populer adalah bentuk kebodohan massal.
Hal serupa terjadi pada sastra populer. Stereotipe yang dibangun atas keberadaan sastra populer berkembang dan diamini sebagai sebuah identitas laten. Akibatnya, pada beberapa wilayah, dianggap sebagai wilayah serius seperti perguruan tinggi, keberadaan sastra populer masih dianggap sebelah mata. Tidak sedikit perguruan tinggi yang melarang sastra populer sebagai korpus penelitian. Meski pada kenyataannya di luar batas yang dibangun tersebut, sastra populer telah menjadi bacaan yang berkembang luas di kalangan mahasiswa.
Fenomena seperti ini menurut saya dapat mengindikasikan dua hal. Pertama, perguruan tinggi masih dikuasai oleh kaum konservatif. Mereka menjunjung tinggi sastra serius sebagai satu-satunya karya sastra yang layak dikonsumsi. Konsistensi tersebut agaknya digoyahkan dengan kekuatan isu dan pengaruh beberapa figur sastrawan. Terbukti, untuk jenis chicklit, teenlit sangat dilarang memasuki kawasan kajian ilmiah. “Sastra wangi”, serta sastra pop-islami dibesarkan oleh kritik dan figur sejumlah sastrawan. Sastra ini diizinkan dan diberi ruang oleh perguruan tinggi.
Kedua adalah ideologi cultural studies belum berkembang di perguruan tinggi. Asumsi ini didasari pada dugaan, ideologi yang diusung dalam cultural studies adalah keutamaan menerima segala bentuk. Peneliti yang menganut paham cultural studies tidak melakukan dikotomisasi atas kemunculan fenomena-fenomena kebudayaan.
Terlepas dari fenomena diskriminasi, fakta saat ini harus diakui bersama sebagai sebuah, katakanlah kejayaan sastra populer adalah hegemoni. Berhasil dilakukan karya sastra pop atas pembaca sastra Indonesia. Melalui sejumlah penerbit besar dan penerbit-penerbit indie yang memasarkan novel-novel populer, lambat laun berhasil merebut perhatian pembaca. Sejumlah penerbit besar, terutama gramedia, adalah penguasa pasar.
Karya sastra populer pada umumnya mengangkat tema seputar romantika cinta, petualangan, fantasi, religi, horor. Tema-tema lain yang menarik untuk dinikmati publik. Fenomena kejayaan sastra populer ini tak bisa dipungkiri secara perlahan-lahan telah menghegemoni masyarakat. Mempersempit ruang gerak sastra serius. Daya tarik terhadap kesusastraan menawarkan kemudahan akses dalam memaknai dan menikmati isi. Desain produksi jauh lebih memikat berkali lipat lebih besar daripada deretan karya yang terkesan ‘membungkus diri’ dari masyarakat umum.
Karya sastra populer digandrungi. Karya sastra serius, perlahan-lahan semakin berada di ujung tanduk. Tidak banyak pembaca yang bisa masuk dan menikmati karya sastra serius. Penyebaran karya sastra ini pun tidak seluas karya sastra populer. Dengan sangat jelas dapat dilihat dari antusiasme pembaca. Lahirnya karya sastra (puisi, prosa) yang notabene menggunakan seperangkat gaya bahasa yang ‘tinggi’. Substansi cerita cenderung krusial. Lebih rendah daripada karya sastra yang dikemas lebih modern. Menggunakan bahasa santai sehari-hari serta ide cerita yang familiar dengan masyarakat umum. Alhasil, karya sastra serius tidak mampu bersaing dengan sastra populer hingga pada akhirnya beredar pada kalangan terbatas.
Di luar perdebatan itu, kemunculan sastra populer telah bersumbangsih besar untuk penumbuhan minat baca masyarakat. Melalui bacaan-bacaan yang menarik itu, masyarakat dicekoki selera membaca yang lambat laun tumbuh sebagai sebuah kebiasaan baru dalam budaya populer.
Penulis Mahasiswa Pascasarjana Universitas Padjadjaran