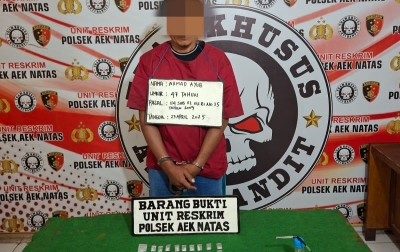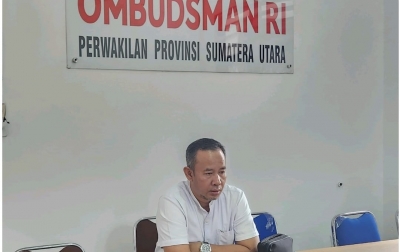Oleh: DR.Ing. Andy Wahab Sitepu.
Penyakit busuk pada tanaman bawang merah, terutama sekali pada daun, umbi dan perakaran, bukanlah masalah baru lagi di dunia pertanian. Salah satu penyebabnya adalah serangan mikroba “pathogen” (jamur/bakteri) yang dapat menggagalkan panen, bahkan mematikan tanaman pada usia muda (mati gadis) dan usia menghasilkan (mati janda). Biasanya setelah terserang parah, barulah muncul gejalanya. Malah tanaman yang terlihat sehat pun bisa mati dalam waktu singkat, karena akarnya telah dirusaki mikroba tersebut. Selain itu konsumsi makanan yang terkontaminasi mikotoxin (racun hasil pembusukan jamur merusak hati/lever).
Hingga kini hanya dilakukan pembasmian mikroba dengan pestisida (fungisida/bakterisida) baik yang kimia sintetik maupun yang hayati (mikroba ”baik”). Karena dianggap cepat dan mudah, manusia lebih memilih kimiawi. Ternyata perlakuan kimiawi habiskan banyak uang dan cemarkan lahan pertanian dengan zat-zat berbahaya serta tanaman pun turut mati. Umumnya penanaman ulang pada tanah yang sama juga mengalami masalah yang sama.
Sadar dari kecewa manusia pun beralih ke sistem hayati. Dari sejumlah mikroba ”baik”, mikroba pengurai lah yang sering digunakan untuk mengatasi mikroba “pathogen”. Untuk melanjutkan hidup dan berkembangbiak mikroba mengkonsumsi bahan organik, padahal makanannya telah terkontaminasi residu dari berbagai bahan aktif pestisida dan bahkan mungkin telah berubah menjadi metabolit yang belum dikenal.
Tingkat bahaya metabolit bisa berkurang dan bisa juga jauh lebih berbahaya daripada residunya. Dalam kondisi terkontaminasi tentu sebagian mikroba “baik” akan terbunuh. Sebagian yang tidak terbunuh tentu terus mengkonsumsi bahan organik tanah terkontaminasi. Sementara sebagian lagi mengkonsumsi bagian tanaman (perakaran, umbi, batang & daun) yang bebas/minim kontaminasi, sehingga tanaman menjadi rusak (penyakit busuk). Setelah beradaptasi hidup dalam lingkungan beresidu/bermetabolit tentu mikroba tersebut akan resisten/kebal terhadap pestisida bersangkutan. Itulah salah satu sebabnya pada lahan pertanian sistem hayati tidak dianjurkan pemakaian pestisida kimia sintetik.
Enzim tidak Membunuh Hama
Sebenarnya bukan mikroba “pathogen" yang langsung merusak tanaman, melainkan zat pembusuk (enzim pengurai) yang dihasilkannya. Baik yang “pathogen” maupun yang “baik”, sama-sama menghasilkan enzim pengurai. Jadi pembasmian mikroba “pathogen” dengan mikroba “baik” belum tentu tepat. Enzim bukan makhluk hidup, melainkan Bio-katalisator (zat kehidupan) yang dihasilkan makhluk hidup. Enzim tidak membunuh hama dan tidak terbunuh pestisida.
Masing-masing enzim memiliki hanya satu fungsi dan tidak bisa digantikan yang lainnya, ibaratnya “Kunci-Gembok”. Prinsip kerjanya terletak pada “gugus aktif” enzimnya. Dengan memblokir “gugus aktif” nya secara selektif, kerja enzim dapat dikendalikan. Sehingga mikroba “pathogen” ini tidak lagi membusukkan tanaman, melainkan akan beralih mengkonsumsi bahan organik lainnya, misalnya sisa-sisa bagian tanaman yang telah mati (yang tidak mengalami pertumbuhan ataupun pergantian sel).
Mekanisme pemblokiran berlangsung, cukup melalui persinggungan selektif antara “gugus aktif” enzim-inhibitor (dihasilkan mikroba “baik”) dengan “gugus aktif” serangkaian enzim-enzim pengurai milik mikroba “pathogen”. Namun sayang sekali enzim-enzim ini sangat peka terhadap reaksi oksidasi. Agar tidak teroksidasi oleh oksigen udara dan untuk mencegah terjadinya saling memblokir, enzim-enzim hasil ekstraksi tersebut dapat dikombinasikan dengan enzim-enzim yang mampu menurunkan kadar oksigen, seperti enzim yang mampu mengadsorpsi nitrogen, karbondioksida maupun uap air. Kombinasi ketiga enzim ini digunakan selain untuk pembentukan “pseudo-urea” dalam tumbuhan sebagai sumber unsur hara C (karbon), H (hidrogen), dan N (nitrogen), juga dapat mengatasi virus (yang butuh oksigen) melalui penurunan kandungan O (oksigen) dalam tumbuhan.
Enzim-enzim tersebut di atas telah dirangkaikan lengkap sebagai multienzim hasil penerapan nanoteknologi dan disajikan dalam bentuk pupuk cair Fitofit. Makanya tanaman yang telah rusak akibat serangan jamur dapat diperbaiki, seperti pertumbuhan dan pergantian sel-sel dapat berlangsung terus setelah applikasi Fitofit tanpa dicampur fungisida dan pupuk.
Tanaman dengan jumlah akar rusak telah melebihi akar sehat akan sulit dipulihkan kembali, namun yang berakar masih sehat lebih banyak daripada yang berakar rusaknya dengan mudah dapat dipulihkan Fitofit. Tahap pemulihan tanaman setelah aplikasi Fitofit dapat diamati seperti dari pengeringan, penutupan luka busukan dan pertumbuhan akar baru pada sekeliling pangkal batang bawah. Setelah perakaran baru tumbuh kokoh pada bekas busukan, tanaman mampu berproduksi kembali bahkan mampu melebihi tanaman yang tidak terserang jamur/bakteri. Jadi pembasmian jamur/bakteri tanpa menangani zat pembusuknya dan memperbaiki kerusakan pada tanaman yang terserang, tanaman tidak dapat melanjutkan kehidupan normal.
Pemberian pupuk dan pestisida baik kimiawi ataupun hayati dianjurkan setelah tanaman mulai pulih. Mulainya pemulihan dipilih sebagai acuan, karena perakaran baru mulai terbentuk. Ini berarti, tanaman mulai sanggup mengkonsumsi unsur hara yang terkandung dalam tanah, untuk bertumbuh menggantikan jaringan tanaman yang telah dirusaki oleh zat pembusuk tadi. Karena tidak terbunuh pestisida dan dapat menyerap nitrogen, karbondioxid dan uap air, Fitofit sering dicampurkan dengan pupuk ataupun pestisida, agar penyerapan pupuk ataupun pestisida lebih optimal.
Pupuk yang diberikan harus berdasarkan perkembangan tanaman. Biasanya applikasi Fitofit segera menimbulkan bunga yang berjumlah melebihi tanaman normal. Artinya, tanah masih mengandung banyak unsur Phosphor (P) yang tidak terserap tanaman, akibat kerusakan perakaran sebelumnya. Selain membantu tumbuhan menyerap karbondioksida dan uap air dari udara untuk kebutuhan proses fotosintesanya, Fitofit juga sangat membantu tumbuhan menyerap sinar Ultra-Violet. ***
Penulis adalah pakar Enzim di bidang Teknologi Katalisator (Nanoteknologi & Reaktor Proses Kimia, Universitas Erlangen Nuernberg, Bayer Jerman.