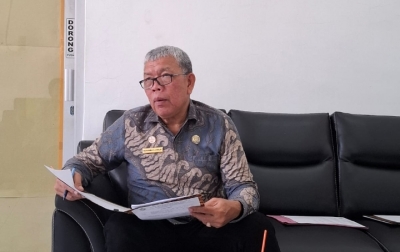Oleh: Prof. Subanindyo Hadiluwih, SH. Ph.D
Ronggeng Deli hasil penelitian di Universiti Malaya, Kuala Lumpur Malaysia, yang dipimpin oleh Dr. Lawrence Ross dan teman-temannya, berhasil membangunkan kembali gaung Ronggeng Deli yang tinggal sayup-sayup sampai.
Sebuah seminar tentang Ronggeng Deli diselenggarakan di USU, dipimpin oleh Prof. Tina Sinar, puteri tokoh budaya Melayu, Tuanku Luckman Sinar Baharsyah II, Sultan Perbaungan. Melibatkan pula beberapa tokoh senior, termasuk ethnomusicolog Rizaldi Siagian. Lulusan San Diego, Amerika Serikat yang pernah kesal karena kenyataan bahwa patung Lili Suhairy, tokoh ‘Pak-Pung’ yang semula tegak di sebuah taman di simpang jalan Palang Merah dan jalan Listrik, kini bak bungkuk berkudis dengan kulit yang mengelupas disana-sini.
Sementara Anjungan Sumatera Utara di Taman Miniatur Indonesia Indah (TMII), berkali-kali menampilkan Ronggeng Deli yang ternyata menarik minat banyak warga masyarakat. Berbondong mereka datang untuk terlibat dan melibatkan diri pada pementasan-pementasan tersebut. Belakangan, gema penampilan ronggeng Deli juga membahana di berbagai lokasi di Medan dan sekitarnya. Berbeda lokasi akan tetapi dengan semangat yang sama, mas Yono USU, Komunitas Jede (Komunitas Jawa Deli) ternyata juga menggugah kembali ‘Kethoprak Dor’.
Meski dengan napas kembang kempis, ternyata kesenian panggung “Jawa’ ini tampil di beberapa lokasi komunitas Jawa. Saya harus menuliskan dalam tanda kutip ‘Jawa’, karena ternyata aneh, mungkin Kethoprak Dor itu sendiri tidak ada di Jawa, meskipun di Medan/Sumatera Utara dibangkitkan oleh komunitas Jawa.
Kerinduan orang Jawa yang bekerja di berbagai perkebunan akan kesenian Jawa pada akhirnya melahirkan institusi budaya berupa ‘Kethoprak Dor’ tersebut. Jurusan Ethnomusikologi Fakultas Sastra USU, kini Fakultas Ilmu Budaya, sempat mengakomodasikan kajian akademis Kethoprak Dor dalam bentuk penampilan dan juga skripsi untuk memperoleh gelar strata S-1. Sementara Dewan Kesenian Medan (Sumatera Utara) pada tahun 80-an juga menyelenggarakan Festival Kethoprak Dor, yang kala itu masih ramai peminatnya.
Utusan dari Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat ikut dalam festival tersebut. Saya pernah memuji mas Alex Sarjowinarko dari Tanah Jawa Simalungun, yang melestarikan, bahkan mengembangkan yang disebutnya sebagai wayang di ‘Tanah mBatak’.
Kegiatannya merupakan ‘budhi-daya’ (budhaya) yang luar biasa. Menyelenggarakan pertunjukan wayang kulit ‘sedalu natas’, bahkan termasuk mendatangkan pesinden Amerika, Megan O.Donnovan yang di Jawa sekalipun masih merupakan pesinden favorit, disamping pesinden dari Jepang, Hiromi Kano.
Kegiatan yang sama juga dilakukan oleh dalang Ki Sunardi Rediguno, setiap ‘selapan’ (35 hari) sekali. Kalau kegiatan sedemikian diselenggarakan oleh Ki Anom Suroto, Ki Manteb Sudarsono dan Ki Entus Susmono, barangkali wajar belaka karena memang disentra-sentra budaya Jawa, akan tetapi diselenggarakan di Tanah Jawa, Simalungun dan di Jalan Bromo, Medan, tentunya unik juga.
Warisan Budaya Kemanusiaan
Ternyata seni dan budhaya yang akhirnya universal ini merupakan kebutuhan humanitas yang memang manusiawi, tanpa mempersoalkan suku, bangsa, bahkan agama sekalipun. Melalui media sosial saya pernah berhubungan dengan seorang teman lama, alm Hardjito, yang sekitar 45 tahun tak berjumpa dan sekarang mengajar kesenian, karawitan di Univesity Wesleyen di Amerika Serikat, yang dinamakannya ‘Kusuma Laras’.
Beberapa nomor tampilan kelompok seninya di Youtube, menampilkan betapa gamelan Jawa ditabuh oleh orang-orang dari berbagai bangsa di seluruh dunia. Tak heran kalau Unesco, badan dunia internasional mempunyai Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan (Unesco List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity). Kontribusi Indonesia dalam daftar tersebut antara lain Wayang (2008), Keris (2008), Batik (2009), Angklung (2010), tari Saman Aceh (2011) dan Noken, Papua (2012).
Kini, Indonesia kembali memasukkan kontribusi seni dan budayanya dalam daftar tersebut. Melalui sidang Unesco yang diselenggarakan pada tanggal 30 November sampai 4 Desember 2015 yang diselenggarakan di Windhock, Unesco sepakat memasukkan tiga genre tari tradisi di Bali yang meliputi sembilan tarian tradisional, yakni Rejang, Sang Hyang Dadari, Baris Upacara. Tiga tari ini merupakan genre tarian sacral. Berikutnya, Topeng Sidhakarya, Sendratari Gambuh dan Sendratari Wayang Wong (Arja).
Ketiganya merupakan genre semisakral. Selanjutnya tari Legong Kraton, Joged Bumbung, dan Barong ‘Kuntisraya’ yang tergolong genre tarian hiburan. Meski dalam pengamatan saya, tari Bumbung adalah tari yang cenderung amat vulgar, bisa ditonton dengan membuka situs Tari Bumbung, namun tentu saja saya cenderung subyektif untuk menilai norma-norma yang berlaku pada tari tersebut, karena penilaiannya berdasar norma budaya yang saya miliki. Bukankah lukisan telanjang yang banyak dilukis oleh pelukis domestik maupun mancanegara di Bali harus dinilai dengan norma obyektif yang berlaku dalam konteks kemanusiaan (humanitas).
Vocal Grup Batak
Dalam Pekan Wayang Nasional yang diselenggarakan oleh Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (Senawangi) yang bekerjasama dengan Perhimpunan Pedalangan Indonesia (Pepadi), saya pernah berkesempatan untuk mengusulkan memperkaya khasanah pewayangan Indonesia dengan memasukkan wayang ‘Batak’, yaitu ‘Tembut-Tembut’ atau ‘Gundala-Gundala’ dari Seberaya, Tanah Karo dan ‘Sigale-gale’ dari Tomok, Tapanuli Utara.
Sebelumnya memang pernah ada wayang Deli Serdang, milik HW Kasno. Tapi wayang itu sebenarnya wayang Jawa belaka. Hanya bentuknya lebih kecil. Sampai sekarang ia menjadi bagian dari pada khasanah pewayangan nasional Indonesia.
Kiranya layak diharapkan bahwa budayawan dan seniman Indonesia mampu mengusulkan kedua bentuk wayang Indonesia itu, ‘Tembut-Tembut’ dan ‘Sigale-gale’, untuk memperoleh pengakuan dari Unesco. Begitu pula sebenarnya bentuk dari pada vocal grup Batak, yang mempunyai ciri amat khas dalam dunia seni suara. Pola ‘chorus’ lagu-lagu Batak sesungguhnya amat spesifik. Lagu-lagu yang punya nada bas, dan tenor bahkan gaya solo song, bahkan memiliki suara ‘palsu’ dengan nada tinggi, terdengar sangat indah.
Ketika Musyawarah Nasional (Munas) Antar Dewan Kesenian se Indonesia, saya dan sekretaris Lazuardi Anwar membawa grup ‘Sipiso’ dari pinggir Danau Toba, suara Batak menguasai panggung. Tiga hari kemudian, ketika suara mengendor, barulah suara ‘Ambon Manise’ dari Maluku, tampil. Seperti halnya genre music khas ‘dangdut’, ‘keroncong’ dan jenis-jenis langgam di berbagai daerah. Selain langgam Jawa, juga ada lagu khas Pasundan, termasuk ‘kliningan’ Sunda.
Kiranya Opera Bangsawan dan Opera Batak perlu pula dipertimbangkan kelanggengan penampilannya. Manakala budayawan kita dan budayawan internasional sudah mulai melirik aneka bentuk genre music dan panggung ini, tentunya layak pula kalau music Melayu (pakpung), Ronggeng Deli atau mungkin juga Kethoprak Dor akan masuk ke kawasan internasional dan merupakan salah satu Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan Unesco. Semoga. ***
Penulis adalah Budayawan dan Guru Besar Filsafat UMSU Medan.