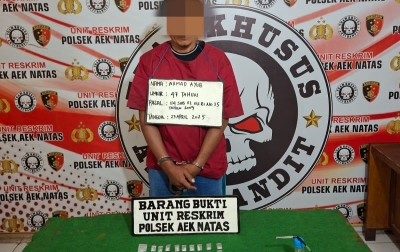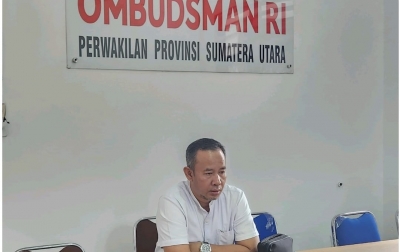Oleh: Armin Rahmansyah Nst, SE, M.Si. Sejak zaman feodal sebenarnya jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia atau ketika para raja dan tuan tanah berkuasa, penarikan upeti (pajak atas rakyat) sudah terjadi. Gambaran peran kaum feodal sudah terlihat pada abad ke-4 Masehi di zaman Raja Purnawarman dari Kerajaan Taruma Negara.
Saat itu raja adalah penguasa tertinggi, tapi mereka mengangkat para bangsawan, dan punggawa sebagai wakil raja. Para wakil raja inilah yang berkewajiban mengumpulkan setoran hasil panen kaum tani untuk keperluan sendiri dan raja. Disamping menyetorkan hasil panen, kaum tani juga wajib bekerja dengan cuma-cuma (rodi, corvee).
Tekanan kepada rakyat yang harus membayar upeti inilah kemudian yang membuat pemberontakan di Kerajaan Mataram ke 1 abad 8 dan 9, pemberontakan Kediri awal abad ke 13 di bawah pimpinan anak petani Ken Arok, pemberontakan terhadap kerajaan Singasari akhir abad ke 13. Lalu pemberontakan dalam kerajaan Majapahit abad ke 14 dan 14 merupakan bentuk pemberontakan kaum tani atas pajak yang dibayarkan.
Kedatangan Portugis 1496 ke Indonesia di bawah pimpinan Vasco da Gama disusul berlabuhnya armada Belanda di bawah kepemimpinan Cornelis Houtman di Banten ternyata malah menimbulkan babak baru tentang penarikan pajak (upeti) atas rakyat.
Inilah era kolonialisme atas Indonesia. Perkumpulan dagang belanda yang diberi nama VOC menancapkan kukunya lebih dalam untuk menarik pajak/upeti atas rakyat. VOC menetapkan sistem pajak tanah yang sangat tinggi dan kewajiban menyerahkan sebagian hasil pertanian dengan harga sangat rendah. Walaupun Belanda telah berkuasa namun mereka tidak menggulingkan kekuasaan feodal, sebaliknya memanfaatkan raja dan kaum bangsawan sebagai perantara mereka dengan rakyat jajahan untuk mengutip pajak dan hasil produksi rakyat tani untuk diserahkan ke penjajah.
Setelah VOC bangkrut dan bubar tahun 1800 kemudian Belanda menjajah secara langsung Indonesia. Singkat cerita mereka memberlakukan culture stelsel (sistem tanam paksa). Penyiksaan atas rakyat dan penarikan upeti/pajak makin menjadi-jadi (Anne Booth & Peter McCawley, 1986).
Sejarah itu hanya sekilas menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya sejak dulu rakyat Indonesia sudah dijadikan obyek pajak (upeti) yang tak pernah habis. Sistem pajak yang diterapkan di zaman Belanda inilah kemudian yang terus menjadi warisan untuk dilanjutkan hingga saat ini.
Sumber Pembiayaan APBN
Dalam porsi APBN pemerintah Indonesia setelah era Orde Baru berakhir, maka sumber pendanaan APBN sudah berpindah dari minyak dan gas ke pajak. Kejayaan Orde Baru sebenarnya ditandai dengan booming minyak. Harga minyak terus naik dan produksi dalam negeri (lifting) pun tinggi.
Sehingga di era Orde Baru, pemerintah tak terlalu fokus mengejar pajak. Akibatnya rasio penerimaan pajak Indonesia memang rendah. Begitu pemerintahan periode Reformasi (zaman Soesilo Bambang Yudhoyono) sadar, bahwa sumber minyak akan habis dan tak sanggup lagi menjadi sumber utama penghasilan, maka pajak pun ditarget tinggi.
Caranya memperluas wajib pajak dan mendorong penerimaan sebanyak-banyaknya dari rakyat. Hingga saat ini seperti yang sedang digalakkan pemerintah dalam Tax Amnesty adalah salah satu upaya memperluas penerimaan pajak.
Tahun lalu saat UU Tax Amnesty mulai digodok sebenarnya sudah memunculkan pro kontra. Pada dasarnya UU Tax Amnesty hadir untuk ‘membujuk’ para pemilik dana di luar negeri memulangkan uangnya ke Indonesia.
Intinya jika pengusaha yang memiliki aset di luar negeri memulangkan dananya dan merepatriasi aset ke dalam negeri akan mendapatkan pengampunan pajak. Besaran pajak yang harus dibayar didiskon hingga 2 persen dari angka normal. Kritikan pun bergulir. Sebab Tax Amnesty ini dianggap mengabaikan asas keadilan penerimaan pajak. Bagaimana mungkin para pengusaha yang menyimpan uang dan asetnya di luar negeri mendapat pengampunan pajak. Sementara masyarakat di dalam negeri selama ini sudah jadi target utama penerimaan pajak terutama kalangan menengah, karyawan, pegawai dan usaha kecil.
Namun bagi pemerintah Tax Amnesty menjadi strategi menghimpun pajak. Coba lihat postur APBN-P 2015 yang menargetkan penerimaan pajak menjadi Rp1.484 triliun yang sebelumnya hanya Rp1.380 triliun. Namun realisasi pajakn Rp1.240,4 triliun, atau 83,3 persen dari target yang ditetapkan. Ada kekurangan (shortfall) Rp160 triliun.
Realisasi Gagal, Target Dinaikkan
Saat itu target sudah tak tercapai. Tapi di APBN 2016 pemerintah malah menaikkan targetnya menjadi Rp1.546 triliun. Melihat potensi yang ada, akhirnya pajak di APBN-P 2016 diturunkan jadi Rp1.355 triliun. Yang terdiri dari target Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp855,8 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 474,23 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp17,7 triliun dan pajak lainnya Rp7,4 triliun.
Melihat komposisi angka dari 2015 ke 2016 terjadi keanehan luar biasa. Sudah jelas 2015 target pajak gagal capai target. Namun di penerimaan 2016, target malah dinaikkan jadi 30 persen.
Wajar kalau kemudian banyak kalangan menilai target penerimaan pajak tidak realistis. Maka untuk mengejar target pajak tinggi itulah sebenarnya Tax Amnesty dikebut. Target penerimaan diproyeksi dari pengampunan pajak mencapai Rp160 triliun hingga Maret 2017.
Gencarnya sosialisasi tentu dengan target paling tidak harus terhimpun Rp1 triliun setiap hari hingga Maret 2017. Data update hingga Jumat (2/9) sore, total uang tebusan sendiri baru mencapai Rp3,95 triliun atau sekitar 2,4 persen dari target Rp165 triliun. Sedang komposisi harta sebanyak Rp187 triliun dengan komposisi hartanya yaitu, deklarasi dalam negeri sebanyak Rp147 triliun (79 persen), deklarasi luar negeri Rp 27,1 triliun (15 persen), dan sayangnya dana repatriasi cuma sebesar Rp11,9 triliun (6 persen).
Padahal pemerintah selama ini menargetkan dapat merepatriasi dana sebanyak Rp1.000 triliun dan yang deklarasi sebanyak Rp4.000 triliun. Artinya apa? Target besar pemerintah untuk merepatriasi aset dan dana di luar negeri itu menjadi diragukan. Atau malah terancam gagal. Lalu muncullah ‘peluru’ baru yang dilontarkan.
Tax Amnesty Ubah Sasaran
Tax Amnesty itu kini bukan hanya ditujukan untuk pemilik dana di luar negeri. Tapi masuk ke kolong masyarakat kelas bawah. Masyarakat dari level bawah sampai ke pengusaha kini gencar diajak sosialisasi Tax Amnesty. Langkah ‘gagap’ pemerintah inilah yang kemudian membuat masyarakat protes sampai muncul gerakan #tolakbayarpajak.
Dengan kondisi keuangan negara yang defisit lebih dari dua persen memang membuat pemerintah berfikir keras mencari sumber dana. Lantas karena Tax Amnesty dari pengusaha di LN terancam gagal, masyarakat awam jadi sasaran.
Coba kita ulang kembali ingatan ketika Indonesia mengalami krisis hebat di 1998. Saat itu pemerintah berwacana mengenakan pajak atas shampoo, sabun mandi, deterjen, sabun cair dan semua perlengkapan rumah tangga. Memang batal dilaksanakan, tapi kondisi itu tidak berbeda jauh dengan situasi saat ini (panik).
Satu hal, rakyat di negara ini memang sudah terbiasa membayar ‘upeti’ ke penguasa sejak zaman feodal. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Hanya saja cara dan etikanya berbeda. Pembayar pajak tentu terkait dengan tingkat kesadaran.
Mirisnya tax ratio (ratio pembayar pajak) di Indonesia yang 13 persen tertinggal dari negara ASEAN. Filipina misalnya memiliki tax ratio 12 persen, Malaysia 12 persen, dan Singapura hingga 22 persen. Indonesia hanya mampu di atas Myanmar yang memiliki tax ratio delapan persen.
Kesadaran dan Keadilan
Jika bicara kesadaran membayar pajak akan banyak hal yang jadi persoalan. Pemerintah bilang karena masyarakat tidak punya kesadaran membayar. Atau karena pertumbuhan ekonomi rendah. Bahkan asumsi ideal pemerintah adalah minimnya kesadaran membayar pajak karena kesalahan masyarakat yang tingkat kesadarannya sangat rendah.
Padahal belum tentu. Sebenarnya keengganan membayar pajak ini hanya pada satu problem utama. Yaitu kepercayaan dan asas keadilan. Pemerintah sebenarnya yang tidak bisa menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dengan membayar pajak akan meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk pembangunan.
Pembayar pajak selalu menginginkan imbal balik atas yang dibayar. Jika seluruh rakyat membayar pajak Rp1.200 triliun kemana uang itu dikeluarkan selain untuk membiayai jalannya pemerintahan. Konteks inilah kemudian yang berkembang sehingga kesadaran masih rendah. Berbeda kalau misalnya setiap tahun pembangunan infrastruktur berkembang pesat atas pembayar pajak dan pemerintah membuat laporan pertanggungjawaban atas pajak yang dibayar.
Memupuk kepercayaan para pembayar pajak memang butuh waktu. Asas transparansi atas penggunaan dana pajak menjadi penting. Bukankah beberapa waktu lalu seorang wajib pajak di Nias bertindak nekat ke petugas pajak yang kemudian jadi korban?
Andai kepercayaan dan manfaat atas pajak yang dibayar dibuat lebih terbuka, tak akan sampai menimbulkan korban seperti itu. Ditambah lagi asas keadilan. Asas keadilan ini maksudnya kesetaraan. Jika semua warga dan profesi wajib membayar pajak tentu berlaku kepada seluruhnya. Bukankah pemilik dana di luar negeri yang sekarang ikut Tax Amnesty berarti selama ini tidak pernah membayar pajak. Sementara mereka tinggal dan berdomisili di Indonesia.
Sehingga pajak yang dikutip selama ini untuk operasional negara berasal dari wajib pajak masyarakat berpenghasilan (karyawan, pegawai, masyarakat biasa, pengusaha kecil, pengusaha menengah dan besar yang peduli dengan negara ini). Sebenarnya tidak adil. Tapi sudahlah. Anggaplah sekarang sudah fair.
Tinggal bagaimana memupuk kepercayaan masyarakat dengan membuktikan janji atas pajak yang dibayar. Pun kalau misalnya Tax Amnesty gagal, bisa saja karena skenario awal sudah salah.
Paling tepat sebenarnya lebih baik pemerintah memperbaiki birokrasi, mempermudah perizinan, membuka pelayanan investasi yang lebih friendly untuk memanggil dana tersebut pulang dalam bentuk investasi. Ketika dana asing itu masuk dalam bentuk investasi di sektor riil dan menghasilkan, baru pajaknya bisa ditagih.
Tapi, sekarang seperti kata Wapres Jusuf Kalla kita semua bertanggungjawab untuk bekerja keras mendanai APBN dari pajak agar negara ini tetap berdaulat di mata rakyat dan dunia internasional. Semoga saja Tax Amnesty dan gencarnya penerimaan pajak tidak berakhir seperti upeti di zaman kerajaan feodal. ***
Penulis adalah pengamat ekonomi