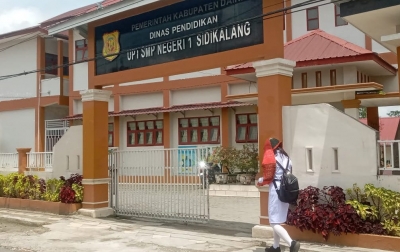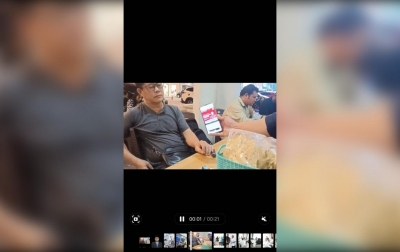Oleh: Amin Multazam Lubis
APA jadinya Kota Medan jika Jacob Nienhuys tak pernah menanam tem-bakau di Tanah Deli? Entahlah, Bisa jadi wilayah Medan sekarang cuma hamparan rawa yang mana jumlah kodok tentu jauh lebih banyak dari pada populasi manusianya. Tak akan muncul sapaan “ketua”, Para Preman Sambu, Baju Monja, atau deretan supir angkot sehebat Lewis Hamilton dari kawasan ini. Tembakau pula yang berkontribusi mendatangkan orang Jawa, China, India (Tamil), dan Batak (Toba, Mandailing) sehingga Kota Medan memiliki beraneka macam etnis yang hidup saling berdampingan. Tanpa tembakau, kuat asumsi saya tetangga anda (warga Medan) barangakali cuma ular sawah, tanpa suku apalagi marga.
Sedikit bercerita, Karl Pelzer, dalam bukunya Toean Keboen Dan Petani secara lebih detail menjelaskan bagaimana kondisi geografis, sosial dan budaya Sumatera Timur. Bahwa wilayah ini awalnya tidak menarik perhatian Pemerintah Kolonial. Kondisi tanahnya yang berawa-rawa dengan jumlah penduduknya sangat jarang menyebabkan investasi di Sumatra Timur menjadi sangat mahal. Selain harus membangun infrastruktur, pengusaha harus mendatangkan pekerja dari tempat lain. Pada tahun 1863, saat Jacob Nienhuys berkunjung ke Sumatra Timur bersama dengan Pangeran Said Abdullah dari Serdang, gagasan untuk membuka perkebunan tembakau akhirnya jadi kenyataan. Percobaan Nienhuys berhasil dengan baik. Ia kemudian mendirikan Deli Maatschppij setelah mendapat konsesi dari Kesultanan Deli. Hasil ini membuat minat orang Eropa membuka perkebunan (onderneming) tembakau merebak. Perkebunan tembakau tumbuh bak kacang goreng dan semua mata mulai tertuju pada Tanah Deli, yang bahkan sempat mendapat julukan sebagai “Dollar Land”
Tembakau Deli memiliki arti begitu besar bagi perkembangan Medan sebagai sebuah Kota sekaligus pusat perdagangan. Lihat bagaimana Logo Universitas Sumatera Utara (USU) dan lambang PSMS Medan berhias tanaman ini. Tembakau Deli adalah marwah, identitas sekaligus kebanggan yang membuat kawasan sepanjang sungai Wampu hingga sungai Ular dikenal sampai mancanegara. Namun sayang, seiring perkembangan zaman Tembakau Deli perlahan terlupakan. Medan tumbuh begitu pesat, begitu sombong meninggalkan Tembakau Deli yang hidup segan mati kasihan.
Ann Laura Stoler dalam bukunya berjudul Kapitalisme Dan Konfrontasi Di Perkebunan Sumatera 1870-1979 mencatat pada tahun 1889 sudah ada 179 kebun tembakau yang tumbuh di Sumatera Timur. Dari ratusan perkebunan itu, Tembakau Deli saat ini hanya ditanam tak lebih dari 3 kebun yang semuanya milik PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II). Penurunan jumlah disebabkan oleh bermacam faktor. Mulai dari kebijakan pembatasan rokok di Eropa, biaya produksi, perawatan tembakau, peralihan jenis tanaman, alih fungsi lahan, hingga konflik dan penyerobotan lahan perkebunan. PTPN II yang tanahnya sebagian besar bekas perkebunan milik kolonial (hasil nasionalisasi) memang menyisakan persoalan. Di Sumatera Utara, mencari pemberitaan soal konflik yang melibatkan PTPN II sama mudahnya dengan mencari penjual lontong dipagi hari. Lantas soal tanaman tembakau? Nyaris tak terdengar. Paling-paling isinya kurang lebih sama dengan tulisan ini, menyoal nasib Tembakau Deli yang diujung tanduk.
Gudang-gudang tua bekas penyimpanan tembakau dengan usia hampir ratusan tahun dibiarkan tak terawat. Para dedemit, kuntilanak dan mahluk halus sejenisnya konon lebih serius mengelola lokasi ini dari pada pemerintah. Buktinya nuansa angker disekitar gudang lebih melekat dari pada cerita nilai sejarah bangunan-bangunan itu. Dalam konteks ini, Saya rasa tidak salah pemerintah membuka diri untuk belajar dari para dedemit agar sukses mengelola tempat-tempat bersejarah.
Tidak diketahui pasti apa penyebab pemerintah Kota Medan, maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kurang serius menjaga kelestarian tembakau sebagai sebuah kebanggan maupun identitas. Mencoba berprasangka baik, saya berasumsi ada dua faktor utama. Pertama, mungkin mereka lebih memilih ngurusin manusia dari pada tanaman. Pemerintah terlalu sibuk mengurusi rakyat. Menghabiskan seluruh waktu dan tenaganya memperbaiki kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia.
Kedua, Pemerintah kami (warga Medan dan Sumatera Utara) adalah tipikal orang yang tidak mau terlalu lama terjebak masa lalu. Ya, bahasa anak gaul zaman sekarang “gampang move on”. Tembakau Deli cuma cerita usang. Contohnya, sekarang Kota Medan lebih identik dengan kota penuh lubang. Lihat saja sebagian besar ruas jalannya rusak parah bak habis dihantam meteor. Maka dari itu, logo dan lambang institusi-institusi diwilayah ini yang berhias daun tembakau (USU dan PSMS misalnya) ada baiknya segera direvisi menjadi Pohon Pisang. Mengapa? Sebab jalan-jalan berlubang itu kerap ditanami pohon pisang oleh penduduk setempat. Apakah satu bentuk kekesalan atau upaya mengganti identitas tembakau, saya juga tidak tau.***
Penulis adalah alumnus Antropologi Fisip USU