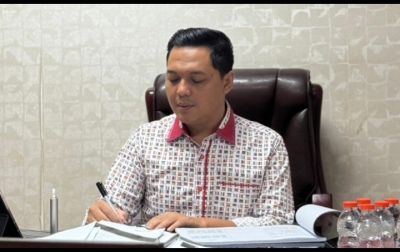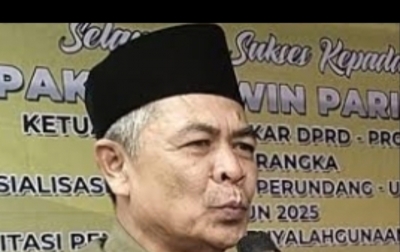Oleh: Abul Muamar.
Di Indonesia, bulan Oktober dikenal sebagai bulan bahasa. Bahasa yang dimaksud tentu saja adalah bahasa persatuan negara kita, bahasa Indonesia. Satu pertanyaan yang langsung melintas di kepala saya adalah, masih pentingkah bahasa persatuan, bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di mana masyarakatnya, semakin hari terasa semakin acuh tak acuh terhadap bahasanya sendiri?
Agar tak gundah sendirian, pertanyaan itu saya ajukan kepada dosen saya, guru besar Filsafat Pancasila Universitas Gadjah Mada, Profesor Armaidy Armawi. Konklusi dari jawaban yang beliau berikan adalah, bahwa bahasa Indonesia itu, bagaimanapun tetap dan akan selalu penting, bahkan sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan upaya dan cita-cita menjaga keutuhan negara ini, baik secara politis maupun secara teritorial.
Sebagai jembatan yang menghubungkan keberagaman, bahasa sejatinya bukan merupakan implikasi dari geopolitik, melainkan lebih berupa buah dari tradisi kultural masyarakat untuk saling memahami dalam perbedaan. Impian itu sudah ada jauh sebelum bahasa Indonesia dikukuhkan melalui deklarasi Soempah Pemoeda pada 28 Oktober 1928. Artinya, sejak zaman dahulu pun, masyarakat kita yang beragam, memiliki keinginan untuk saling mengenal dan berbagi, dan dengan demikian, menyatukan masing-masing kultur bawaan mereka.
Coba bayangkan, di ruang tunggu sebuah bandara misalnya, bagaimanakah kiranya seorang Jawa yang hanya bisa berbahasa Jawa, dapat menyampaikan pesan kepada orang Padang yang hanya bisa dan mengerti berbahasa Padang, untuk menjagai tasnya selagi ia pergi ke toilet sejenak, jika bahasa Indonesia tidak ada? Bahasa isyarat memang ada, tetapi tentunya repot, bukan? Maka dari itu, sepatutnya kita bersyukur, dan berterima kasih kepada para pemuda di bulan Oktober 1928 yang sudah berjasa menahbiskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita.
Sayangnya, dewasa ini kita lupa bersyukur akan nikmat itu. Kita sering lupa bahwa kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang-orang di luar wilayah kita, bahkan di luar pulau kita, karena adanya bahasa persatuan itu. Kita kerap memperlakukan bahasa Indonesia dengan sesuka hati (untuk tidak menyebut semena-mena), dan menganggap seakan itu sudah taken for granted dari sananya, dan karena itu tidak perlu terlalu dijunjung-junjung seperti yang diikrarkan para pemuda waktu itu. Asalkan Anda dan Anda saling mengerti, asal kau dan aku saling mengerti, asalkan kita dan kalian saling mengerti, maka itu sudah cukup. Sedangkan penting tidaknya bahasa Indonesia itu, menjadi hal yang tidak lebih penting dibanding, memeriksa notifikasi dan komentar-komentar di laman media sosial.
Satu kendala besar yang kita hadapi perihal bahasa persatuan ini, sebagaimana juga halnya pada masalah yang menyangkut nasionalitas yang lain, adalah singgungannya dengan ragam lokalitas (kearifan lokal) yang begitu majemuk di negara ini. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan NKRI, masih kerap berbenturan dengan geliat untuk mempertahankan kebudayaan lokal, yang dalam hal ini adalah bahasa daerah. Di Jawa, misalnya, bahkan di lingkungan universitas sekalipun, mayoritas orang-orang masih lebih senang (dan barangkali juga bangga) menggunakan bahasa Jawa dalam pergaulan sehari-hari. Demikian juga kiranya di Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Hal ini sudah berlangsung sejak bahasa Indonesia dicetuskan. Artinya, sampai sekarang pun, kalau kita berani mengakui, kita belum sepenuhnya menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Dalam pada ini, nasionalitas (ataupun nasionalisme) diam-diam berada dalam keadaan vis-a-vis dengan lokalitas.
Tanggalkan Bahasa Daerah di Tempat Umum
Lantas, salahkah keadaan itu? Profesor Armaidy tidak menjawabnya secara gamblang. Namun secara tersirat, beliau menyampaikan bahwa sejak awal negara ini dibangun, termasuk di dalamnya bahasa Indonesia sebagai lingua franca, semestinya segala hal yang berbau lokal, hanya berlaku di dalam lokal itu sendiri saja. Artinya, lokalitas jangan dibawa-bawa “keluar”. Lokalitas hendaknya dilestarikan dalam konteks kelokalannya sendiri. Seorang Batak, misalnya, mestinya hanya berbahasa Batak dengan sesama orang yang mengerti bahasa Batak dalam situasi dan ruang yang privat.
Pandangan ini tentu saja bisa disanggah dengan pernyataan seperti, “nasionalitas negara ini terdiri dari lokalitas-lokalitas yang majemuk; menanggalkan satu lokalitas sama artinya dengan mempreteli keutuhan nasionalitas itu sendiri”. Jika argumentasinya seperti itu, tentu saja bagus dan bisa diterima. Artinya, orang yang menyatakan demikian punya kesadaran penuh terhadap dua hal tersebut. Itu berarti, dia menggunakan bahasa daerahnya di tempat umum bukan karena dia tidak nasionalis, melainkan karena dia sengaja melakukannya dan penuh kesadaran. Paling tidak, ketika ada orang lain duduk di sampingnya yang tidak mengerti bahasa daerah yang dituturkannya, yang barangkali merasa risih, ia bisa cepat-cepat beralih menggunakan bahasa Indonesia.
Selebihnya, adakah alasan lain yang bisa jadi pembenaran untuk menggunakan bahasa daerah di tempat umum? Jika memang ada, pembaca tulisan ini barangkali bisa menyimpannya terlebih dahulu, dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan agar dapat dibaca dan dipahami khalayak banyak—termasuk saya.
Namun saya pribadi, sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Armaidy. Bahwa bagaimanapun, mau tak mau, lokalitas harus tetap berada di bawah nasionalitas. Sekali lagi, itu demi keutuhan negara republik ini, dan demi keberlangsungan hidup bersama dalam keberagaman.
Lawan Invasi Melalui Bahasa
Selesai dengan urusan lokalitas versus nasionalitas tadi, PR kita selanjutnya adalah melawan invasi melalui penjunjungan terhadap bahasa Indonesia. Dalam konteks sosio-linguistik, masuknya bahasa asing dan digunakannya bahasa asing itu dalam sebuah negara sasaran, sebenarnya sudah merupakan bentuk invasi. Apakah kita mau bahasa Indonesia tergantikan oleh bahasa asing, seperti bahasa Inggris atau bahasa Korea, misalnya?
Jika kita memang maunya demikian, tentu perkara ini selesai sampai di sini. Tidak ada lagi masalah yang harus dibicarakan. Akan tetapi, jika yang ada adalah sebaliknya, sudah sepatutnyalah kita sadar akan invasi laten yang dilakukan oleh negara asing melalui bahasa mereka. Ingat, internasionalisasi tidak mesti berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa internasional. Apalagi jika itu ternyata hanya sebuah indoktrinasi yang selama ini kita telan mentah-mentah.
Mungkin kita memang sudah terlanjur basah, apalagi melihat negara-negara lain juga demikian. Tetapi kita belum terlambat. Tidak ada kata terlambat bagi bangsa yang besar seperti bangsa kita. Sebab, bagaimanapun, bangsa yang besar pasti akan membanggakan bahasanya sendiri. Tengoklah bagaimana Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Betapa resistannya mereka terhadap gempuran bahasa Inggris yang dianggap sebagai bahasa internasional. Mayoritas penduduk di negara-negara tersebut bahkan anti (baca: enggan) menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari mereka, sekalipun sekadar mengoplosnya dengan bahasa mereka sendiri, sebagaimana kebiasaan orang-orang kita.
Lalu, bagaimana dengan kita? Kita sudah sama-sama tahu. Yang paling tidak dapat dipungkiri saat ini adalah kebiasaan mencampuraduk bahasa sendiri dengan bahasa asing, dan itu dilakukan dalam percakapan sehari-hari. Kebiasaan ini bahkan telah menyebabkan orang-orang kita lebih akrab dengan kata-kata macam bully, pancake, laundry, dan resign, ketimbang merisak, panekuk, penatu, dan mengundurkan diri.
Sebagai penutup, perlu diketahui, bahwa di luar sana, termasuk Australia dan Tiongkok, orang-orang sedang gencar mempelajari bahasa Indonesia. Untuk apa? Entahlah. Yang pasti kita mesti siap-siap mengantisipasi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. ***
Penulis adalah jurnalis; alumnus Ilmu Komunikasi FISIP USU; mahasiswa pascasarjana Filsafat UGM.