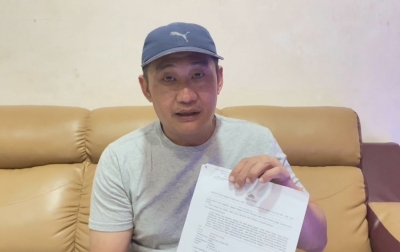Oleh: Arief Sinaga
MINGGU pagi, ayah tengah menikmati kopi sembari membaca koran lokal langganan yang setiap hari diantar pengecer yang tinggal dekat rumah.
Setelah mandi dan berpakaian, Putra menikmati makanan yang disediakan ibu. Nasi goreng dengan telur setengah matang menantangnya. Makanan tuntas, tetapi resah datang karena hari Minggu tanpa kegiatan. Ayah masuk meninggalkan gelas kopinya di luar dan koran yang berserakan di meja kecil.
Putra bergerak ke teras. Koran yang terkulai hendak ia rapikan, sekadar melihat-lihat berita hari ini. Namun, ia malah melihat halaman yang terdapat sebuah cerpen dan resensi dari buku yang tengah popular saat ini. Ia pun membaca cerpen hingga selesai. Cerpen menceritakan tentang seorang anak yang mengejar mimpinya hingga ia mendapatkannya. Dari resensi buku ia mengetahui sinopsis buku tersebut tentang sekelompok anak daerah yang juga hendak meraih mimpi.
“Penulis cerpen yang di koran itu dapat honor,” suara ayah dari belakang. Ternyata ia sedang memperhatikan Putra. “Kalau kau suka baca, seharusnya kau juga bisa menulis.“
Perkataan ayah itu menjadi pembenaran olehnya. Putra memang pendiam sehingga dia hanya mengangguk-angguk setelah ayah bicara. Ayah keluar rumah mengenakan sarung dan peci putih. Ia mungkin pergi ke Pusat Pasar melihat anggotanya yang berjaga di toko kelapa parut miliknya.
Koran masih tetap di genggaman Putra. Tetapi hanya halaman yang berisi cerpen tadi. Lalu ia masuk ke kamar. Adiknya perempuan yang masih SMA kelas satu masih molor di ranjang bawah. Maklum, mereka keluarga sederhana, jadi hanya ada dua kamar di rumah. Adiknya memang lebih sulit tidur kalau malam hari. Walau begitu, Putra sangat menyayanginya.
Hari demi hari ia lewati dan seolah berawal dari cerpen Minggu koran lokal itu ia lantas sering menulis. Di atas buku-buku sekolah yang masih ada sisa kosong atau membeli dobel folio jika ada uang saku yang lebih. Awalnya ia hanya sekadar mencoba namun pujian dari teman-temannya dan guru Bahasa Indonesia membuatnya semakin bergairah untuk menjadi penulis.
* * *
Suatu Kamis, ayah mengajaknya ke sebuah tempat. Ayah mengatakan bahwa ia harus membawa cerpen terbaiknya. Entah tempat seperti apa yang ingin ditunjukkan ayah. Cerpen ia genggam dalam map kuning. Mereka pun berangkat.
Tak sampai duapuluh menit dengan sepeda motor, mereka berhenti di kantor yang tepat di sebelahnya ada sebuah warung kopi. Ayah membawa Putra masuk ke kantor tersebut. Ternyata itu kantor redaksi media lokal walaupun koran lokal yang tak terlalu besar namanya dibandingkan yang lain.
“Mana cerpenmu?”
Putra memberikan map kuningnya. Seperti biasa, ia hanya mengangguk-angguk. Ayah masuk ke dalam dan menyuruhnya menunggu di bangku panjang. Sembari menunggu, ia melihat beberapa mading yang terpajang di dinding ruangan. Kembali ia teringat resensi buku yang ia baca. Di dalam mading ada foto penulis buku yang teranyar saat ini bersama pegawai kantor media ini. Terbayanglah ia pada suatu ketika wajahnya yang ada dalam foto tersebut dan berfoto bersama karyawan media.
“Ayo kita pulang“. Suara ayah membuyarkan lamunannya. Ayah mengembalikan map kuning itu kepadanya. Tiba di rumah, tanpa basa-basi Putra menuju meja makan. Benar saja, nasi dengan sayur daun ubi tumbuk, beserta ikan asin dan sambal belacan menggugah selera. Makanan disantap. Sekilas ia lihat pintu kamarnya terbuka. Adiknya masih saja tidur padahal hari sudah sore menjelang malam.
Dua minggu berselang, hari-hari dijalani Putra seperti biasa. Kegiatan menulis selalu tak pernah tinggal ketika ada waktu selang, meskipun itu hanya sebuah puisi atau pantun. Adiknya lebih memilih teater dibandingkan dunia tulis menulis. Ia juga menyempatkan diri untuk datang melihat adiknya bermain menjadi aktris di pementasan teater kemarin sore.
Cerpennya ternyata belum dimuat. Putra masih bisa tersenyum ketika ia dipanggil untuk menjadi perwakilan sekolah untuk ajang Pekan Seni Pelajar Nasional untuk cabang Seni Sastra. Tiga kategori ia harus ikuti yaitu cerpen, puisi, dan naskah drama. Dengan kepercayaan yang diberikan sekolah, ia pun berusaha semampunya. Namun setelah perlombaan selesai, dan pengumuman dikumandangkan, ternyata tak terdengar dipanggilnya nama Putra Perdana. Sudah pasti rasa kecewa menggerogoti batinnya. Walaupun lelaki rasa kecewa tetaplah mampu mencairkan air matanya.
* * *
“Mas Putra, pukul delapan pagi Anda harus sudah berada di Auditorium Nasional, ya? Seminar akan dilangsungkan pukul sembilan, on time ya, Mas?”
Putra hanya mengangguk seperti biasa mendengar kata dari gadis berpakaian rapi dan anggun saat menemuinya di restoran hotel. Selepas itu ia masuk ke kamar hotel. Istri dan anak-anaknya tengah asyik menonton kartun kucing dan tikus. Begitu mengunci pintu, ia langsung bergabung dengan anak dan istrinya menggendongi si bungsu dan si sulung sekaligus yang umurnya belum sampai sepuluh tahun.
“Sepertinya ayah harus berangkat sekarang, tadi panitia sudah datang mengingatkan harus datang ke sana jam delapan”.
Anak-anak menyalaminya. Ia mencium kening mereka dan istrinya. Putra lalu turun ke basement melalui lift. Di depan pintu lobi hotel, telah menunggu Parjo supir pribadinya yang telah menemaninya lima tahun belakangan.
Sampai di Auditorium, kerumunan orang telah berkumpul memanggil-manggil namanya sembari membawa buku-buku karangannya. Mereka meminta tanda tangannya. Ada pula sebagian yang meminta foto bersama sesaat sebelum ia diamankan oleh panitia untuk segera masuk ke Auditorium.
Dalam seminar itu, Putra mengungkapkan jerih payahnya selama menjadi penulis dan membangun motivasi para peserta seminar agar tak pernah bosan untuk berkarya dalam bentuk apa pun. Ia juga memberi sedikit sinopsis tentang buku terbarunya yang berjudul “Adik Perempuanku Sang Sutradara”. Dalam novelnya itu dinyatakan seorang kakak beradik, yang satu penulis dan satu lagi sutradara. Keduanya adalah satu kesatuan. Lalu berkembang menjadi satu individu. Setelah itu ia mengatakan bahwa novelnya adalah kisah nyata.
Ketika sesi pertanyaan dibuka, seseorang dari sudut paling belakang mengangkat tangan untuk memberikan pertanyaan.
“Selamat pagi menjelang siang, Pak. Saya ingin menanyakan. Biasanya seorang penulis menyimpan tulisan pertamanya yang dimuat di media, akan tetapi setelah saya telusuri tidak ada satu pun tulisan pertama Anda di media. Kalau boleh tahu di mana Anda menyimpannya? Dan kalau boleh tahu apa judulnya? Dan tulisan berjenis apa? Terima kasih.”
Putra termenung. Auditorium hening. Beberapa orang berbisik-bisik. Putra menghela nafas sejenak lalu menggenggam mik di atas mejanya.
“Terima kasih buat pertanyaannya. Saya sangat senang pada seminar kali ini. Pada seminar-seminar sebelumnya tak ada yang pernah menanyakan ini kepada saya. Tulisan pertama saya yang terbit di media adalah cerpen yang terbit di media lokal. Akan tetapi media lokal yang menerbitkan cerpen saya telah berganti menjadi toko roti dan seluruh arsipnya telah hangus terbakar sebelum perusahaan beralih fungsi. Dan di mana cerpennya, pasti akan keluar dan bukan saya tetapi seorang gadis yang menjadi sutradara yang menemukan itu. Judulnya Sekembaliku Dari Langit. Bukan bermaksud membuat teman-teman penasaran, tetapi akan lebih baik gadis sutradara itu yang menemukannya.”
Seorang gadis dari barisan tengah mengangkat tangan. “Di mana gadis itu sekarang?”
“Entahlah”, jawab Putra.
Para hadirin bingung.
“Akan tetapi jika Anda membaca novel saya ini, maka Anda akan mengetahui di mana gadis itu”.
Putra pun bergegas kembali ke hotel untuk istirahat. Ia lihat anaknya si bungsu dan si sulung. Si bungsu yang perempuan jauh lebih mirip ayahnya dibandingkan abangnya. Mereka berbeda tabiat, satu suka baca, satu suka menonton. Putra dan istrinya hanya bisa menikmati kebahagiaan di sela-sela kesibukan mereka.
Setelah dari seminar kemarin, pemberitaan tentang tulisan pertama Putra melesat di seluruh kota. Tak satu pun yang menemukan cerpen itu. Jutaan penggemarnya sangat menantikan cerpen pertama dari penulis besar itu. Tapi, tak satu pun media dan pengamat sastra dapat menemukan cerpen itu. Dan juga tak satu pun orang yang menemukan gadis sutradara yang bakal menemukan cerpen perdana Putra.
* * *
Pagi menyinari rumah mewah. Bungsu sedang duduk di teras yang bernuansa Itali dengan secangkir kopi hitam kesukaannya. Di atas meja dan bangku putih ia duduk sambil menggoyang-goyangkan pena. Wajahnya cantik layaknya gadis kelas atas tetapi pakaiannya tetap urakan.
Ayahnya telah menjadi legenda sastra di negeri ini. Si sulung lebih memilih menjadi pengusaha daripada mengikuti jejak ayahnya. Si bungsu yang tetap menggerusi aliran seni dari ayahnya.
Menjelang siang, dengan mengendarai mobil, bungsu ke rumah neneknya, di sana adalah tempat kelahiran ayahnya yang sekarang telah kosong. Entah mengapa, perasaannya ingin sekali melepas rindu ke rumah neneknya itu. Padahal hampir sepuluh tahun sejak kematian ayahnya ia tak pernah kembali ke sana.
Pagar ia buka, banyak daun kering di pekarangan rumah nenek. Pohon mangga di sebelah kanan rumah masih tegak berdiri. Bungsu masuk melalui pintu depan yang terlihat seperti papan gersang yang dijual para tukang loak. Akan tetapi ketika ia masuk ke dalam rumah, alangkah bersih tanpa debu walau tak lagi ditempati selama sepuluh tahun. Ia melihat-lihat bingkai foto ayah bersama nenek dan kakeknya. Ayahnya adalah anak tunggal.
Rumah ini telah dua kali direnovasi dan diperbesar, sehingga bentuk pada saat Putra kecil tak lagi kelihatan. Bungsu masuk dari kamar-ke kamar. Lalu ia berhenti pada sebuah kamar berukuran mini. Ia pun masuk. Terdapat kasur kecil dan lampu antik, dengan ribuan kertas yang berserakan di sekeliling kamar.
Sebuah kliping koran ia temukan di balik bantal. Ia ambil kliping itu yang tertulis “Sekembaliku Dari Langit” yang ternyata sebuah cerpen yang menceritakan tentang ini dari awal sampai akhir. * Januari 2014