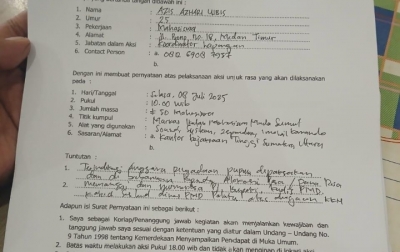Oleh: Hidayat Banjar.
Hingar-bingar jagad politik Indonesia memunculkan tanya tentang makna negarawan. Kompas Sabtu (8 April 2017) memberitakan “Lembaga Negara Minus Negarawan”. Disebutkan, krisis negarawan antara lain terlihat dalam polemik di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Elit di DPD saling memperebutkan kursi pimpinan DPD.
Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, menuturkan lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, DPR dan DPD cenderung mementingkan ego lembaga masing-masing. Padahal, internal lembaga itu juga bermasalah.
“Kondisi ini muncul karena tidak ada lagi kenegarawanan pada pimpinan setiap lembaga. Mereka sibuk dengan nafsu kekuasaan dan kebendaan,” katanya.
Apa jadinya? Sebutan politikus pun dipelesetkan menjadi poli tikus. Poli berarti pelbagai atau banyak seperti dalam poliklinik dan poligami. Jika demikianlah adanya maka politikus bolehlah dihumorkan dengan pengertian pelbagai tikus atau tikus yang pelbagai.
Padahal kata politikus (jamak: politisi) adalah seseorang yang terlibat dalam politik, dan kadang juga termasuk para ahli politik. Politikus juga termasuk figur politik yang ikut serta dalam pemerintahan.
Dari segi maknanya, istilah “politikus” dan “politisi” sebenarnya hampir sama. “Politikus” adalah bentuk tunggal dan “politisi” adalah bentuk jamaknya. Setara dengan beberapa pasang kata lain: “alumnus” (tunggal) dan “alumni” (jamak): “datum” (tunggal) dan “data” (jamak); juga “musikus” (tunggal) dan “musisi” (jamak).
Negarawan
Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan arti ‘negarawan’: ahli dalam kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintahan); pemimpin politik yg secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah negara dengan kebijaksanaan dan kewibawaan: beliau merupakan pahlawan besar dan negarawan agung; ke·ne·ga·ra·wan·an hal yang berhubungan dengan orang-orang yang mengurus suatu negara: sikap negarawan amat diperlukan dalam menghadapi persoalan kemasyarakatan.
Sedangkan politikus/po·li·ti·kus/ n 1. ahli politik; ahli kenegaraan; 2. orang yang berkecimpung dalam bidang politik.
Di Indonesia, makna politik mengarah menjadi sekadar pertandingan, karenanya Kompas menyebut lembaga negara minus negarawan. Kekuasaan telah menjadi sekadar “santapan” yang diperebutkan. Maka, tidak ada yang lebih penting dalam politik selain hanya menjadi pemenangnya. Perpolitikan seperti ini sama sekali bukan pekerjaan yang mulia dan luhur. Politik yang demikian sama sekali jauh dari nilai-nilai spiritual dan hanya menempatkan para pelakunya menjadi political animal (hewan politik).
Bagi hewan politik, tak ada yang lebih penting selain kepentingan. Bagi hewan politik, tidak ada yang namanya ideologi, visi, misi. dan nilai-nilai (vision, mission, value: atau vmv). Kalaupun partai-partai politik mempunyai ideologi dan vmv, jangan terlalu menanggapinya dengan serius. Vmv adalah sekadar alat kelengkapan organisasi.
Jauh beda dengan orang-orang yang memikirkan orang lain, mereka sesungguhnya bukanlah politikus. Mereka adalah negarawan. Thomas Jefferson punya definisi yang sangat baik mengenai politikus dan negarawan ini. Politikus memikirkan pemilihan yang akan datang, sementara negarawan memikirkan generasi yang akan datang.
Seorang negarawan adalah orang yang melakukan hal yang benar bukan sekadar melakukan sesuatu dengan benar. Perhatian seorang negarawan adalah pada arah perjalanan negeri ini. Ia tidak tertarik dengan kepentingan sesaat yang berjangka pendek, tetapi malah akan menjerumuskan bangsa dan negara dalam kesulitan dan keterperosokan di masa depan.
Bukan sebatas politisi
Ya, rakyat mendambakan pemimpin yang negarawan, bukan sebatas politisi. Pemimpin dan kepemimpinannya merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia dan berperan sentral dalam menjalankan roda organisasi.
Dalam falsafah Ki Hajar Dewantara, terdapat Ing Ngarso Sung Tulodho, pemimpin perlu menjadi contoh/teladan yang baik bagi pengikutnya. Orang yang tidak bisa taat pada aturan tidak dapat memimpin. Idiom ini menjadi dasar perlunya orang merasakan menjadi pegawai di level bawah untuk dapat menjadi jenderal besar yang bijaksana.
Saat ini, seseorang gampang untuk menjadi pemimpin, walaupun ditempuh dengan berbagai macam cara, seperti membeli suara/money politic, dan lainnya. Namun belum tentu mereka berhasil di dalam menjalankan kepemimpinannya. Lihat kondisi saat ini, hampir sebagian besar kepala daerah menjadi tersangka atau tersangkut masalah hukum, karena besarnya modal politik untuk mencapai tujuan menjadi seorang pemimpin.
Dewasan ini, menurut Kompas, justru yang muncul adalah kepemimpinan transaksional. Hubungan elit politik dengan konstituen dirusak oleh transaksi material, bukan pertukaran gagasan. Ketegasan menjadi barang mahal karena terlalu banyak pertimbangan dan kalkulasi politik yang dijadikan konsideran (Liddle dkk, 2012). Model kepemimpinan transaksional ini tumbuh subur dalam sistem politik kartel di mana APBN/APBD menjadi ajang bancakan dan lisensi yang diperjualbelikan untuk mengikat loyalitas politik. Kasus dana KTP Elektronik dapat jadi contoh yang paling anyar.
Menurut Liddle, pemimpin transaksional adalah tipe yang paling banyak dijumpai di Indonesia. Sejak Abdurrahman Wahid hingga Soesilo Bambang Yudhoyono (kecuali Habibie), semuanya adalah jenis pemimpin transaksional yang mempertukarkan kekuasaannya dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan diri dan kelompoknya.
Transformatif
Negarawan selalu menerapkan model kepemimpinan transformatif yang punya visi masa depan dan menolak transaksi politik jangka pendek. Pemimpin yang menerapkan model ini akan menularkan efek transformasi pada level individu dan organisasi.
Liddle menjelaskan, tipe transformasional adalah pemimpin yang mampu membentuk ulang situasi politik Indonesia dari satu keadaan kepada keadaan lain. Sementara tipe ”transaksional” adalah model kepemimpinan yang mempergunakan kekuasaannya untuk menukarnya (barter) dengan posisi-posisi yang dapat menguntungkan diri dan kelompoknya.
Tokoh seperti Soekarno, menurut Liddle, adalah jenis pemimpin transformasional yang mengubah Indonesia dari satu fase (penjajahan) kepada fase lain (kemerdekaan). Namun demikian, Liddle membatasi bahwa karakter transformasional Soekarno hanya terjadi sejak awal kemerdekaan hingga tahun 1949. Setelah tahun itu, Soekarno menjadi pemimpin yang tidak lagi punya visi transformatif.
Dalam tingkat tertentu, Soeharto juga merupakan tipe pemimpin transformatif yang berusaha mengubah kondisi Indonesia lewat proyek pembangunan dan modernisasi yang dipimpinnya. Demikian pula Habibie, dengan masa kepemimpinan yang cukup singkat, dia berusaha memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin transformatif. Dengan kekuasaan yang tiba-tiba didapatkannya (setelah mundurnya Soeharto), dia tidak tampak berusaha mempertukarkannya dengan imbalan yang dapat memperpanjang usia kekuasaannya.
Di mata Liddle, Habibie seperti sebuah lilin yang kebijakan-kebijakannya memberikan jalan buat demokrasi dan kebebasan di Indonesia. Ironisnya kebijakan-kebijakan Habibie membakar dirinya. Setelah masa jabatannya selesai, Habibie tidak dipilih lagi, tapi Indonesia menjadi negara yang demokratis. Itulah makna sejati negarawan. ***
Penulis pengamat masalah sosial, budaya dan hukum.