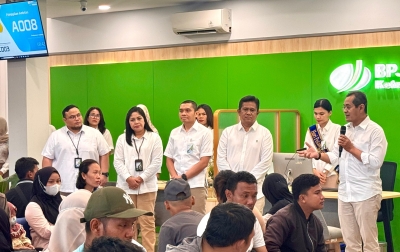Didampingi Perkumpulan Sada Ahmo, sebuah organisasi penguatan perempuan, saat ini ada enam kelompok perempuan yang tengah merevitalisasi tenun ulos pewarna alami agar tak lenyap dari narasi masyarakat Batak.
Di lantai kayu berlapis tikar plastik, di sebuah rumah panggung tradisional Batak yang tanpa penyekat itu, sebanyak 15 orang perempuan larut dalam obrolan hangat. Suasana kadang riuh ketika mereka mengomentari suatu topik.
Begitulah, Selasa (20/6) sore itu, para perempuan di Dusun III, Desa Sidabagas, Kecamatan Simanindo tengah bertutur tentang dunia mereka. Dunia sebagai perempuan penenun ulos. Sebuah profesi yang telah diwarisi secara turun-temurun dari keluarga.
Papan kayu tempat para penenun duduk lesehan, beberapa di antaranya menyisakan celah selebar jari tangan. Bola mata pun menembus ke kolong bawah rumah. Terlihat dua ekor babi berlarian sembari menjerit-jerit meningkahi obrolan para penenun.
"Opung, mamak, dan saya sendiri juga penenun. Rata-rata kami di sini memang jadi penenun warisan. Kalau ada remaja putri dari kampung kami yang tidak keluar Samosir, pasti memilih jadi penenun," ujar Denita Simanihuruk.
Di Kabupaten Samosir memang ada beberapa desa yang dikenal sebagai sentra penghasil tenun ulos. Selain di Desa Sidabagas di Kecamatan Simanindo, juga ada di Desa Parduhul, Hutaraja, Lumban Suhi-suhi dan Siggilombu di Kecamatan Pangururan. Dari desa-desa inilah kebutuhan akan ulos, terutama ulos Batak Karo dipasok.
Unik memang. Penenunnya perempuan Batak Toba, tapi ulos yang dihasilkan umumnya ulos Karo. Menurut Denita Simanihuruk, itu karena dalam identitas berpakaian, orang Karo diakui lebih kental. Entah di pekan, di ladang, terlebih di pesta, orang Karo selalu mengenakan ulos. Sebaliknya orang Batak Toba umumnya mengenakan ulos saat ada pesta dan ulosnya pun sudah tertentu.
"Daya beli orang Karo juga lebih tinggi, " tambahnya.
Menenun memang sudah jadi mata pencaharian utama para ibu rumah tangga di sana. Termasuk sejumlah remaja putri. Tentu saja di samping kegiatan berladang, yang oleh sebagian besar penenun, tetap tak dikesampingkan. Seorang penenun setiap hari menghabiskan 8-10 jam untuk menenun.
“Cuma berladang, tanam bawang hasil nggak tentu, kadang ada musim kemarau. Kalau bertenun sudah pasti penghasilannya,” timpal Romani Simanihuruk. Ia lalu memberi contoh hitung-hitungan sederhana. Untuk menenun kain ulos ukuran 6,5 x 2 meter, dibutuhkan modal kurang lebih Rp 100 ribu. Modal dibelanjakan untuk membeli benang.
Dalam waktu 4 hari, ulos selesai dikerjakan. Tauke pengumpul langsung bisa dihubungi untuk jemput bola. Ulos langsung dibayar kontan. Satu potong ulos dihargai antara Rp 250 ribu - Rp 350 ribu, tergantung jenis benang dan tingkat kesulitan motif ulos.
Ambil contoh harga terendah. Itu berarti penenun meraih keuntungan Rp 150 ribu. Jika keuntungan itu didapat dalam empat hari kerja untuk menyelesaikan selembar ulos, maka rata-rata per hari seorang penenun berpenghasilan Rp 37.500. Walau tak sampai Rp 50 ribu, tapi menurut Romina, penghasilan itu terjamin. Tak seperti kalau mereka berladang bawang yang kadang terkena serangan hama atau gangguan lain, sehingga penghasilan berkurang. Karena itu banyak petani yang juga berprofesi sebagai penenun ulos.
Menurut Denita dan Romina, dalam sebulan rata-rata seorang penenun bisa menghasilkan 8 - 9 potong ulos berukuran 6,5 x 2 meter. Itu artinya per bulan, jika harga ulos rata-rata Rp 250 ribu per potong, seorang penenun bisa berpenghasilan Rp 1, 2 juta sampai Rp 1,3 juta.
Kebutuhan Adat
Ulos memang bukan sembarang kain. Secara harfiah, ulos berarti kain penghangat tubuh atau selimut. Dalam bahasa Batak disebut gobar, yang artinya memberi kehangatan, mengingat orang-orang Batak, awalnya banyak hidup di dataran tinggi yang bersuhu udara dingin.
Sejarah ulos, dituturkan Sarma Erita Sigalingging, staf lapangan Pesada yang mendampingi lima kelompok perempuan penenun di Samosir, erat berhubungan dengan turi-turian tentang seorang anak perempuan dari keluarga marga Silalahi yang dikisahkan berjasa menciptakan ulos.
Dikisahkan, pada zaman dulu keluarga Silalahi memiliki 9 orang anak, satu di antaranya perempuan. Kedelapan anak laki-laki itu tiap hari rajin bekerja di ladang, sementara si anak perempuan malas bekerja. Akibatnya anak perempuan tersebut sering dimarahi ibunya. Karena sering dimarahi, anak perempuan itu suatu hari pergi ke ladang memakan buah jambu biji muda dan padi muda. Selesai makan itu, ia duduk-duduk di atas batu besar sambil berpikir cara menggulung benang dari kapas.
Beberapa hari kemudian, dia mengambil kapas dan menggulungnya menjadi benang. Dalam sehari dia bisa menggulung benang untuk delapan ulos. Tenun ulos yang dibuat itu, pertama kali diberikan kepada kedelapan saudaranya sebagai selimut.
Percaya atau tidak, tapi itulah turi-turian yang sampai kini masih hidup di kalangan masyarakat Batak. Dalam perjalanan waktu, ulos tak lagi sebagai selimut atau alas tidur, namun mengalami pergeseran fungsi. Ulos menjadi multifungsi secara simbolik dalam berbagai aspek kehidupan suku Batak. Ulos tidak dapat dipisahkan lagi dari upacara-upacara adat. Ulos mencerminkan kosmologi orang Batak mulai dari kelahiran, kehidupan, dan kematian.
Ritual pemakaian ulos atau mangulosi menjadi bagian vital dari upacara kelahiran, pernikahan, dan dukacita. Mangulosi bukan sekadar pemberian hadiah ulos, namun merepresentasikan sebuah nilai atau harapan tertentu. Misalnya lambang restu, kasih sayang, harapan, dan doa dari sang pemberi dan hanya bisa dilakukan dengan adat tertentu. Tiap ulos punya makna dan aturan tersendiri.
Misalnya ulos ragihotang, yang memiliki corak rotan diberikan pada saat pernikahan. Ulos ini untuk mengingatkan ikatan pasangan pengantin akan kuat dan kokoh seperti rotan. Ulos bintang maratur diberikan orang tua kepada anak perempuan yang hamil tujuh bulan atau kepada cucu yang baru lahir sebagai parompa (kain gendongan).
Pemberian ulos ini sebagai simbol kepatuhan dan kerukunan dalam ikatan kekeluargaan. Ulos dapat pula diberikan kepada anak yang menempati rumah baru. Intinya, dalam setiap pesta adat, ulos merupakan kebutuhan masyarakat Batak.
Ulos adalah produksi pengetahuan perempuan Batak. Bahkan pada awalnya mulai dari pengetahuan memintal kapas menjadi kain, merancang pola, menentukan warna yang dipilih sampai proses penenunan. Ulos ditenun oleh tangan-tangan terampil perempuan Batak. Pengetahuan dan keterampilan itu diwariskan secara turun-temurun.
Namun keterampilan ini belakangan mulai banyak diambilalih mesin. Saat ulos masih ditenun secara tradisional, penenun juga menggunakan pewarna alami. Namun seiring ditemukannya zat pewarna kimia, dalam sepuluh tahun belakangan, penggunaan pewarna alam makin banyak ditinggalkan.
Penggunaan pewarna kimia umumnya bersifat pragmatis. Tapi yang jelas, mereka abai akan dampak negatif yang dituai perempuan penenun dalam jangka panjang.
Ramah Lingkungan
Menurut Sarma Ernita Sigalingging, penggunaan pewarna kimia punya dampak serius bagi kesehatan penenun, bahkan juga bagi pengguna ulos. Bagi penenun, mereka sudah terdampak bahan kimia mulai saat benang diunggat atau diberus yang sebelumnya sudah dimasukkan ke air kanji atau air nasi supaya benang mengeras. Juga pada tahapan disorha atau benang dirapikan dengan menggunakan mesin gulung. Penenun kembali terdampak saat tahap dihani, (pemilahan sesuai warna). Tahap terakhir adalah saat benang mulai ditenun.
Dalam seluruh tahapan itu, zat-zat kimia yang menempel di benang mudah tergores dan diterbangkan angin serta dihirup hidung. Hal ini bisa memengaruhi kesehatan reproduksi perempuan penenun.
"Sekaligus juga mempercepat proses rabun mata disamping menimbulkan penyakit batuk-batuk. Sedang bagi pengguna ulos, juga bisa membuat kulit gatal-gatal karena ulos berbahan pewarna kimia lebih kasar di kulit tubuh," tambah Desnita Simanihuruk.
Sekalipun sadar penggunaan pewarna kimia berdampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan alam, namun banyak penenun yang tetap menggunakannya. Alasannya beragam, sekalipun muaranya, seperti disebut sebelumnya, pragmatis dan ekonomis.
Misalnya warna yang dihasilkan lebih menyolok, lebih kinclong. Sehingga lebih digemari masyarakat dibanding berpewarna alami yang lebih kalem atau redup. Pengerjaan ulos dengan pewarna kimia juga tak ribet. Penenun tak perlu repot-repot harus meracik zat pewarna. Mereka tinggal membeli benang berwarna yang sudah tersedia di pasaran. Tak hanya itu, harga benang berwarna (kimia) dengan benang putih juga sama.
Alasan itulah yang memengaruhi tingkat antusiasme kebanyakan penenun ulos meninggalkan pewarna alami. Sebenarnya untuk mendapatkan zat pewarna alami, bahannya banyak tersedia di sekitar tempat tinggal penenun. Tak perlu keluar biaya.
Untuk mendapatkan warna biru laut, misalnya, bisa diracik dari daun salaon atau indigo. Untuk hijau daun pisang bisa diracik dari daun mangga atau bangun-bangun. Kemudian ungu diperoleh dari racikan biji sanduduk, kuning dari kunyit, merah pink dari bunga rosela, cokelat kemerahan bisa diperoleh dari kulit manggis dan warna oranye dari bunga kesumba.
Pewarna alami diperoleh dengan cara merebus daun-daun atau biji buah. Setelah jadi zat pewarna lalu dicampur dengan tiga macam larutan (air bening endapan) yaitu fiksasi dengan tawas, fiksasi kapur bangunan (kapur tohor), dan fiksasi besi berkarat (tunjung).
Fiksasi bertujuan untuk mengikat warna pada benang saat dicelup ke zat pewarna. Setelah proses pencelupan, benang kemudian dijemur sampai kering. Proses pengeringan tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Kadang, hal ini butuh waktu 3 - 4 kali penjemuran.
"Butuh waktu lebih lama memang dibanding kalau menggunakan pewarna kimia karena benangnya sudah berwarna sesuai kebutuhan," jelas Sarma Sigalingging, alumni Akademi Sekretaris dan Manajemen Indonesia-Akademi Maritim Belawan (ASMI -AMB) Medan itu.
Selain bahan bakunya mudah diperoleh, sebenarnya proses pembuatannya juga tak butuh biaya besar. Namun semua kelebihan itu tidak membuat semua penenun tertarik meracik dan menggunakan zat pewarna alami.
Dari 200-an penenun yang disurvei pada 2013 oleh Pesada di Pangururan dan Sumanindo, hanya ada 105 penenun yang menggunakan pewarna alami. Dengan catatan mereka juga tetap menenun dengan pewarna kimia.
"Saat ini kami hanya menenun dengan zat pewarna alami jika ada pesanan, ini karena butuh waktu lebih lama untuk menenun, juga pasar yang masih terbatas," ujar Destina Simanihuruk. Untuk membuat ulos ukuran 6,5 x 2 meter dengan pewarna kimia cukup empat hari, sdangkan untuk ulos dengan pewarna alami butuh waktu sampai 10 hari.
Namun begitu, harga kain ulos tenun pewarna alami bisa tiga kali lipat harga ulos dengan pewarna kimia. Ulos ukuran 6,5 x 2 meter bisa dijual seharga Rp 700 rbu - Rp 800 ribu.
Ada beragam motif ulos yang biasa mereka tenun. Setiap motif punya maknanya. Misalnya motif apul-apul (kupu-kupu). Motif ini adalah simbol untuk memperkuat dan menyatukan tali persaudaraan. Ada juga motif seat-seat (bergambar pisau kecil), maknanya memisahkan hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan sehari-hari dalam adat budaya. Ketiga, motif silindung, maknanya melindungi kehidupan manusia dari hal-hal yang kurang baik atau jahat.
Selain motif tradisional tadi, mereka juga melakukan kreasi dan modifikasi sehingga menghasilkan motif seperti hadang-hadang dan sirat penuh.
Ulos tenun dengan pewarna alami memang masih memiliki pangsa pasar terbatas. Menurut Destina Sumanihuruk, baru turis-turis asing yang tertarik dan membeli. Juga beberapa pejabat Samosir. Selain soal harganya lebih mahal, juga soal warna tadi. Pesada juga memanfaatkan jaringan organisasi masyarakat sipil seperti Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) yang bermarkas di Jakarta sebagai tempat konsinyasi, termasuk akses pasar.
"Kita juga bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Samosir yang ada di Parbaba, Kecamatan Pangururan," tambah Sarma Sigalingging. Deskranasda Samosir punya art shop. Di situlah ulos pewarna alami dari anggota kelompok dititipkan. Biasanya satu atau dua bulan baru terjual. Minimnya akses dan daya serap pasar menjadikan kelompok penenun ulos dengan pewarna alami belum berani meninggalkan ulos dengan pewarna kimia secara total.
Berbagai usaha dilakukan Pesada agar revitalisasi tenun ulos berbahan pewarna alam terus berkembang. Salah satunya dengan melakukan diversifikasi produk. Misalnya membuat ulos sebagai handicraft atau oleh-oleh. Seperti selendang (hande-hande) dalam ukuran lebih kecil, juga dalam bentuk baju.
Kepala Divisi Riset dan Pengembangan Kapasitas Pesada, Dina Lumbantobing, menyebut advokasi pentingnya penggunaan bahan alam dalam proses menenun ulos tak hanya karena sifatnya yang ramah lingkungan, tapi juga karena Pesada memandang penting untuk memelihara kelangsungan pengetahuan perempuan Batak tentang tenun ulos yang telah menjadi tradisi dan identitas.
"Pengetahuan lokal dari perempuan Batak ini tak boleh hilang karena berbagai faktor yang ada, kita memperjuangkan keberadaannya agar bisa ditutunkan ke generasi perempuan berikutnya," katanya.