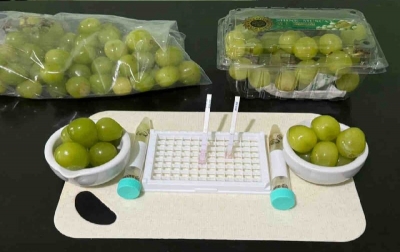Oleh: Meyarni.
Pada 5 Juni masyarakat dari berbagai penjuru dunia merayakan Hari Lingkungan Hidup. Kata yang lebih tepat sebenarnya, merefleksikan sejauh mana setiap manusia menghargai dan mencintai lingkungan sekitarnya. Sayangnya dalam setiap gerakan menjaga dan merawat lingkungan, peran budaya seringkali dilupakan. Seolah-olah persoalan lingkungan hanya milik para pecinta alam dan mereka yang bekerja dalam organisasi-organisasi lingkungan hidup. Budayawan maupun seniman jarang dilibatkan dalam proyek-proyek konservasi itu. Padahal budaya dan lingkungan adalah dua hal yang tidak bisa terpisah. Justru lingkungan itu sendiri seringkali menjadi tema sentral dalam berbagai ekspresi maupun nilai-nilai budaya.
Di dalam kebudayaan itu termuat nilai-nilai ekologis yang kerap diekspresikan lewat berbagai ritus dan medium budaya. Baik di dalam musik, tari maupun sistem adat yang mengatur laku kehidupan masyarakat pemiliknya.
Sebagai contoh budaya masyarakat Batak Toba. Budaya Batak Toba dikenal sangat kental dengan pesan-pesan ekologis. Misalnya, sejak dulu nenek moyang masyarakat Batak Toba sangat memantangkan membuka lahan dengan cara membakar. Membuka lahan bagi masyarakat Batak Toba, harus melalui berbagai ritual tertentu. Itupun mesti memenuhi sejumlah syarat yang sangat ketat.
Pertama sekali, seseorang harus menyampaikan niatnya kepada orang kampung melalui raja kampung di tempat ia tinggal. Jika disetujui barulah niat itu boleh dilanjutkan. Orang Batak tidak boleh sembarang menebang kayu di hutan. Karena mereka yakin, bahwa setiap pohon memiliki kehidupan yang harus dihormati.
Selain itu, mereka juga yakin di setiap pohon ada kehidupan lain yang hidup di sana dan juga harus dihormati. Karena itu, biasanya mereka juga akan bertanya kepada orang pintar untuk menghindari bencana yang tak diinginkan.
Keyakinan itu membuat mereka lebih hati-hati dan selektif dalam memilih pohon yang akan ditebang. Begitu ketatnya. Tidak heran, jika untuk sekedar menebang sebatang pohon saja, orang Batak bisa berlangsung sampai berminggu-minggu lamanya. Beberapa syarat itu, seperti yang penulis kutip dari tulisan budayawan Batak Toba, Monang Naipospos adalah sebagai berikut.
Pertama, pohon yang akan ditebang harus berumur cukup. Kedua, tidak boleh menebang pohon dalam jumlah banyak hanya di satu titik atau areal saja. Ketiga, orang tersebut harus mengganti pohon yang ditebang dengan 3 tanaman baru. Dalam arti, manakala pohon itu ditebang, segera dia harus menanam 3 bibit baru. Istilah ini kita kenal dengan tanam 3 tebang 1. Secara filosofis, 3 bibit pohon ini dimaksud sebagai pengganti. Sekaligus menjadi cadangan untuk anak dan cucunya di masa mendatang.
Selain itu, seseorang tidak boleh menebang pohon yang berada di pinggir kampung. Atau yang termasuk pohon penyanggah air. Karena itu mereka harus masuk ke dalam hutan sampai menemukan areal yang cocok. Hal ini dimaksud agar tidak mengganggu sistem sumber air di kampung tersebut. Tidak heran jika mereka akan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengambil beberapa batang kayu.
Menariknya jika ada salah satu syarat yang dilanggar, orang tersebut tidak hanya akan mendapat sanksi adat maupun sosial. Lebih berat, justru sanksi secara spiritual. Biasanya orang tersebut akan merasa bersalah karena melanggar salah satu syarat. Orang tersebut akan merasa diteror. Batinnya tidak tenang, sekalipun dia sudah kembali dari hutan.
Karenanya biasanya, setiap kali ada hambatan dalam perjalanan selama proses menebang pohon itu, akan dikaitkan dengan roh penghuni hutan atau pohon yang marah. Rasa bersalah ini pun terbukti sangat ampuh.
Biasanya orang tersebut akan menghentikan proses penebangan pohon dan kembali ke kampung. Mereka akan meminta maaf setidaknya kepada tetua kampung dan “orang pintar” yang menjadi “pendamping” mereka. Mereka baru akan kembali melanjutkan pekerjaannya setelah syarat itu dapat dipenuhi.
Biasanya jarang seseorang mendapat kesempatan dua kali. Begitu ketatnya aturan itu, memaksa seseorang harus sungguh-sungguh dan memiliki niat yang kuat dan tulus.
Tidak hanya menebang pohon, demikian juga ketika menangkap ikan di Danau Toba. Para nelayan tidak boleh menggunakan alat yang dapat merusak ekosistem. Seperti menggunakan peledak maupun pukat harimau. Begitu juga dengan jumlah tangkapan haruslah diambil secukupnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ikan yang boleh diambil adalah yang sudah cukup umur serta tidak boleh menangkap ikan yang dalam kondisi pra reproduksi.
Budayawan Tidak Dilibatkan
Demikianlah pantangan dan larangan itu termaktub dalam nilai-nilai budaya yang tidak pernah dituliskan namun harus dipatuhi semua orang. Nilai-nilai budaya itu menjadi pegangan masyarakat sehari-hari sekaligus menjadi alat kontrol bagi mereka. Sayang, nilai-nilai budaya itu perlahan terkikis. Salah satunya karena tidak diajarkan kepada generasi yang lebih muda. Dalam hal itulah, mestinya posisi budayawan menjadi penting dalam setiap pembangunan. Termasuk pembangunan Kawasan Danau Toba yang tengah gencar-gencarnya dilakukkan.
Tidak dilibatkannya budayawan itu secara nyata dapat dilihat dari struktur organisasi Badan Otorita Danau Toba (BODT). Seperti kita tahu, pemerintah telah mengeluarkan perpres tentang Badan Otorita Danau Toba. Peran budayawan nyaris tidak hadir di dalamnya. Khususnya para budayawan lokal yang mendiami Kawasan Danau Toba itu sendiri.
Padahal justru posisi mereka sangat penting. Bagiamanapun mereka paling paham akan pergeseran nilai-nilai budaya yang terjadi di kawasan itu. Lagipula para budayawan merupakan tonggak atas eksistensi budaya itu sendiri.
Para budayawan maupun seniman sekedar diberi panggung. Itu sifatnya sangat terbatas. Mereka sering hanya mendapat peran figuran. Sementara panggung utama biasanya dimiliki oleh seniman-seniman dari Jakarta.
Memang panggung kesenian bukan tuntutan utama sebagaimana yang dimaksud dalam tulisan ini. Lebih dari itu, mestinya budayawan dilibatkan secara struktur organisasi. Mereka harus diberikan posisi yang strategis, sehingga memiliki wewenang dan hak dalam menentukan keputusan. Tidak hanya sekedar memberikan mereka panggung kesenian yang sifatnya seremonial dan seringkali tak berdampak apa-apa.
Terabaikannya para budayawan menurut saya juga tidak lepas dari pergeseran budaya itu sendiri. Orang-orang tidak merasa penting lagi menjaga dan mempertahankan budaya. Seiring dengan kemajuan zaman dan semakin canggihnya teknologi, orang-orang merasa kebudayaan sebagai aturan usang. Tak lagi relevan.
Karenanya pertanyaan mendasar mesti dijawab terlebih dahulu. Apakah kita di zaman global dan modern ini masih memerlukan nilai-nilai budaya yang didasari oleh unsur-unsur spiritual itu? Ataukah memang kita hanya sekedar memerlukan panggung hiburan yang penuh gegap gempita dan riuh tepuk tangan, sebagaimana yang sekarang ini terjadi?