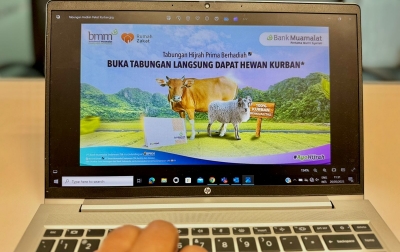Oleh: J Anto.
PADA suatu masa, ribuan manuskrip Batak kuno, baik berbentuk mikrofilm maupun fotokopi dokumen buku, tulisan tangan, menghuni Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak (PDPKB) Universitas HKPB Nommensen, Medan. Inilah lembaga yang digadang-gadang akan memberi karakter pada universitas tersebut lewat tiga matra kegiatan: dokumentasi, penelitian, dan penerbitan. Tapi kini harta karun budaya yang menyimpan sebagian peradaban leluhur masyarakat Batak itu seperti terabaikan.
“Mau menangis saya kalau melihat ruang PDPKB sekarang ini,” ujar Prof Dr Bungaran A Simanjuntak, saat ditemui di rumahnya, di Jalan Seksama, Gang Rela, Medan Amplas, Rabu (10/1) siang.
Ruang yang membuat masgul antopolog dan sosiolog yang produktif menulis buku itu, berukuran kurang lebih 2,5 meter x 5 meter. Kondisinya harus diakui, lebih mirip gudang ketimbang sebuah ruang yang menyandang nama gagah: Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak.
Ruang PDPKB terletak dibawah pojok anak tangga lantai dua atau di depan pintu masuk ruang perpustakaan universitas tersebut. Ruangan itu terlihat sesak memuat lima rak buku, satu buah meja kerja sederhana, dan meja kantor berlaci dengan pesawat televisi yang tak berfungsi.
Buku-buku dan berbagai dokumen seperti kliping koran, skripsi, brosur, majalah, terlihat ditumpuk acak-acakkan. Warnanya sebagian besar sudah menguning tua. Mesin pendingin sebenarnya masih bekerja, tapi hawa dingin yang disemburkan, tak cukup membuat suhu ruangan dingin. Padahal dokumen dengan media kertas, butuh kelembaban tertentu agar tak cepat rusak.
“Makanya saya bantu pakai kipas angin biar buku nggak cepat menguning. Jangan tanya berapa jumlah buku dan dokumen tentang masyarakat Batak di sini, saya tak tahu jumlahnya,” ujar Direktur PDPKB Universitas HKBP Nommensen (UHN), Mangaju Nababan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/1) pagi.
Mengurus sendirian tanpa asisten, juga dukungan finansial, membuat Manguji berkompromi dengan keadaan. Ia memang tampil di berbagai forum, tapi soal biaya, ya cari sendiri. Meski begitu, ia tetap membawa nama lembaga.
Pada masa jayanya, antara 1983 – 1993, PDPKB memiliki ratusan harta karun budaya Batak kuno. Baik dalam bentuk manuskrip aksara batak, latin, maupun aksara kuno. Ada juga Pustaka Laklak dalam bentuk mikrofilm. Manuskrip-manuskrip kuno itu difotolopi dari Universitas Rijks Leiden, Belanda dan Universitas Stuttgart Jerman.
Bungaran Simanjuntak sejak 1977 adalah dosen UHN yang tengah melakukan studi di negeri kincir angin tersebut. Pada 1983 saat PDPKB dibentuk, ia ditunjuk Rektor UHN waktu itu, Prof Dr Amudi Pasaribu sebagai direktur.
Berbagai dokumen tentang masyarakat Batak, atas fasilitas universitas digandakan dan menjadi koleksi PDPKB. Sejumlah peneliti asing yang tengah memelajari masyarakat Batak banyak memanfaatkan dokumentasi PDPKB.
“Apalagi waktu itu kami juga memiliki reader untuk membaca mikrofilm,” ujarnya. Ruang PDPKB cukup representatif. Menempati tiga ruang yang digabung di gedung dosen, ruangan itu full mesin pendingin untuk menjaga kelembaban udara agar dokumentasi tak cepat rusak. Ada tiga staf yang membantu operasional PDPKB.
Sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat Batak sering mampir dan berdiskusi, seperti Koentjaraningrat, TB Simatupang, Bisuk Siahaan, Payaman Simanjuntak, Johan Angler, Uli Kozok, dan Sandra Niessen. PDPKB selain diangankan jadi pusat dokumentasi pustaka Batak terlengkap di Indonesia, juga diangankan sebagai pusat penelitian dan penerbitan buku-buku yang berkaitan dengan masyarakat Batak. Intinya mendokumentasikan semua pengetahuan yang ada mengenai suku Batak.
PDPKB di universitas itu diidealkan mampu menjadi seperti Pusat Javanologi di Yogyakarta. “Para era saya, baru berhasil diterbitkan tiga buku, kalau penelitian sama sekali belum,” tutur Bungaran Simanjuntak.
Tiga buku itu adalah Ruhut Parsaoron di Habatahon (1984), Pemikiran Tentang Batak (1986), dan Patik Dohot Uhum Ni Halak Batak (1987). “Patik Dolok Uhum Ni Halak Batak ditulis Raja Jacob Lumbantobing, 1989 dan diterbitkan American Mission di Singapura,” tutur Direktur PDPKB 1983 – 2000.
Menurut doktor sosiologi UGM yang menulis disertasi Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba itu, buku Patik Dohot Uhum itu semacam kitab Babon yang mengatur berbagai hal dalam relasi kehidupan masyarakat Batak pada masanya.
Patik Dohot Uhum mengatur hukum masyarakat Batak tentang perkawinan, pertanahan, perkongsian, pencurian, pemerintahan, tentang ketuhanan dan persembahan ke dewa, peperangan dan tentang magis. Sedangkan Ruhut Parsaoron mengatur rinci praktik relasi sosial sebagaimana hukum yang terdapat dalam buku Patik Dohot Uhum.
Keberadaan PDPKB menurut Pak Bas, panggilan karib lelaki itu, sangat membantu orang banyak dalam memahami kebudayaan orang Batak. Terutama orang luar yang tengah melakukan studi tentang masyarakat Batak. Dalam istilah Mangaju Nababan, PDPKB berperan membantu orang yang tengah mencari identitas kebatakkan.
Hidup Segan
Sayang, sebagai imbas konflik yang terjadi di jajaran pengurus universitas, membuat PDPKB seperti diurus secara“alang so alang, mate so mate mangolu so mangolu” (hidup segan, mati tak mau). Sejak 2003 saat dipercaya sebagai direktur, Manguji Nababan mengakui lembaganya masih menunggu giliran mendapat kucuran anggaran dari universitas. Beberapa kali kantor PDPKB berpindah-pindah. Akibatnya sejumlah koleksi tercecer, bahkan puluhan rol koleksi mikrofilm yang berisi ribuan potong dokumen visual rusak.
“Beruntung saya berhasil menyelamatkan 6.000 potong yang saya titipkan di PDPKB,” ujar Bungaran Simanjuntak sembari memerlihatkan beberapa rol mikrofilm yang kini disimpan di perpustakaan pribadi, di rumahnya. Saat kuliah di Leiden, ia memang menjadi anggota Pusat Arsip Pemerintah Belanda sehingga gampang mendapat fasilitas mikrofilm tentang berbagai manuskrip kuno masyarakat Batak.
Di PDPKB, menurut Manguji Nababan, saat ini tak lagi menyimpan mikrofilm Batak. Alumni Fakultas Sastra Batak USU Bidang Kajian Bahasa dan Sastra Batak 1996 ini dikenal memiliki keahlian mentransliterasi manuskrip Batak kuno atau Pustaka Laklak.
Pustaka Laklak adalah kitab yang berisi pengetahuan tentang hal-hal magis, nujum, dan obat-obatan yang ditulis tangan di atas kayu haualim, sejenis kayu gaharu ratusan tahun lalu. Pada 2012 penulis buku Torsatorsa Hombung, Turiturian Ni Halak Batak itu, mentransliterasi (menerjemahkan) Pustaha Laklak Simalungun yang telah berusia 200 tahun. Isinya tentang primbon, hari baik, sesajen, syarat berperang, dan mantra-mantra.
Pustaka Laklak hanya salah satu bentuk keberaksaraan masyarakat Batak kuno. Ada juga yang disebut Buluh Suraton, yakni kitab yang ditulis di atas bambu. Isinya menyangkut hari-hari baik dalam kalendar Batak. Hari dalam kalendar Batak berjumlah tigapuluh, demikian juga satu tahun berjumlah 12 bulan.
Diagram pertemuan antara hari dan bulan menghasilkan hari baik yang oleh masyarakat Batak dulu digunakan untul menentukan perkawinan, perjalanan atau menabur benih padi. Media penulisan kitab lain adalah melalui tulang kerbau. Biasanya berisi jimat yang digunakan sebagai gelang tangan atau ikat pinggang.
Manuskrip-manuskrip kuno yang asli saat ini banyak tersimpan di arsip perpustakaan Belanda dan Jerman. Termasuk berbagai dokumen yang disalin dari tradisi lisan setelah kedatangan penjajah Belanda dan misionaris Jerman ke tanah Batak. Masa puncak penulisan aksara Batak ini menurut Manguji terjadi ketika Neubronner van der Tuuk meminta orang-orang Batak di Silindung, tempat ia pernah tinggal, menulis cerita-cerita kuno di kalangan rakyat Batak berupa mitos, legenda, sejarah marga, dan huta (kampung) setempat pada 1850-an.
Lalu pada 1857 saat Van der Tuuk kembali ke Belanda, ia memboyong ratusan pustaha Batak, dan 20 berkas karangan yang masing-masing terdiri dari 300 lembar naskah beraksara Batak. Pustaka itu kini sebagian menjadi koleksi PDPKB.
Mangaju mengaku sudah menerjemahkan 15 Pustaka Laklak. Salah satunya mengisahkan tentang pangulubalang yang dipercaya warga kampung mampu melindungi kampung dari serangan musuh dan menghancurkan musuh, serta menjaga ladang penduduk.
Mangaju juga beberapa kali diminta menyalin Pustaka Lalak, semisal saat Indonesia mengikuti Frankurt Book Fair, 2015. Ia mendapat pesanan dari Perpustakaan Nasional RI. Salinan itu berukuran lebar 12 cm panjang 6,25 meter. Saat ini di Indonesia, sepanjang pengetahuannya ada beberapa orang yang ahli membaca.
“Ciri konsep keberaksaraan masyarakat Batak kuno bukan untuk menarasikan ilmu pengetahuan tapi untuk pengetahuan mistik dan obat-obatan,” katanya. Ada sedikit tentang andung, namun hanya sebagian kecil. Pengetahuan lokal yang mengandung banyak pelajaran moral justru banyak didapati pada sastra lisan Batak seperti turi-turian, mangandung, umpama, umpasa, hutisa dan torkan-torkanan.
Sayangnya sastra lisan telah banyak punah. Dianggap kolot atau sudah tak sesuai zaman. Beberapa usaha untuk melestarikan sastra lisan lewat media tertulis dilakukan sejumlah sastrawan dan penulis, termasuk Bungaran Simanjuntak dan Mangaju Nababan.
Keberadaan PDPKB sebenarnya strategis untuk membangkitkan peran batang yang terendam itu. Karena apa pun, sastra lisan juga bagian dari harta karun budaya orang Batak. Peran PDPKB sebenarnya sangat strategis. Sayang kondisi PDPKB sedang tak menggembirakan.