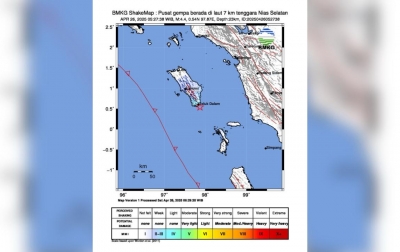Oleh: J Anto
DI Sumatera Utara, Budi P Hutasuhut, pemilik nama pena Budi Hatees, merupakan sastrawan paling ‘galak’ menyerang usaha Denny JA untuk melahirkan, apa yang diistilahkannya sebagai copycat atau para pengekor puisi esai versi Denny JA. Sastrawan dan peneliti Sahata Institute yang kini bermukim di Padangsidimpuan inilah yang pada pekan kedua Januari 2018, memantik perdebatan lewat akun medsosnya.
Berikut wawancara dengan Budi Hatees Senin (22/1) via piranti komunikasi sosial online.
Analisa: Apa alasan Anda menolak puisi esai Denny JA?
Budi: Ada banyak alasan. Pertama, konsep puisi esai itu tak bisa dijelaskan Denny JA karena memang bukan sebuah inovasi dalam ars poetica. Kita mengenal puisi imajis dan puisi liris, bukan hal yang tak bisa diuji secara ilmiah. Puisi esai hanya menggabungkan istilah "esai" dengan "puisi", lalu menyatakan "puisi esai" sebagai genre sastra. Alasan Denny karena puisi esai punya footnote.
Kedua, Denny melakukan penipuan fakta sejarah sastra. Dia membayar orang agar menulis puisi esai, seakan-akan orang itu tertarik menulis puisi esai karena hal itu unggul dibanding genre sastra lain. Semua para penulis itu diakuinya sebagai orang yang akan membuatnya menjadi layak disebut tokoh sastra di negeri ini.
Ketiga, strategi Denny untuk memperkenalkann (meyemarakkan) puisi esai dengan menyusup dan memengaruhi orang-orang (generas muda) berdampak pada perpecahan komunitas-komunitas di daerah. Para sastrawan terbelah menjadi pihak yang mendukung dan menentang. Pesaudaraan sesama sastrawa terbelah.
Keempat, Denny meremehkan karya sastra sebagai keterampilan menulis puisi. Ini yang paling fatal, seakan-akan menulis puisi itu sesuatu yang gampang dan bisa dilakukan orang yang tidak punya basis pengetahuan tentang sastra.
Kelima, khusus di wilayah Sumatra Utara, saya tidak terima karena Denny JA memanfaatkan Balai Bahasa Sumut, melalui oknum di lembaga tersebut. Balai Bahasa Bahasa Sumut soal puisi esai ini tak pernah dianggap masalah. Saya mengkhawatirkan posisi balai bahasa sebagai lembaga yang dimanfaatkan untuk membenarkan puisi esai. Ada lima sastrawan Sumut yang ikut menulis puisi esai. Empat di antaranya dapat kontrak Rp 5 juta dan agennya mendapat lebih Rp 5 juta.
Analisa: Puisi esai versi Denny JA, terlepas dari rekayasa untuk menciptakan epigon-epigonnya, apakah patut diapresiasi? Misalnya dari sisi estetika?
Budi: Sebagai karya esai, ya, boleh. Sama seperti kita membaca esai. Tapi tidak sebagai puisi. Footnote yang diandalkan Denny membuat lebih tepat sebagai esai. Bukan berarti puisi tidak boleh pakai footnote. Boleh, banyak puisi di Indonesia pakai footnote. Ahmad Yulden Erwin banyak memakai footnote dalam puisi-puisinya, terutama untuk menjelaskan tentang aliran aliran dalam dunia seni. Dalam puisi Ahmad Yulden Erwin tentang seni keramik, dia menjelaskan nama sastrawan yang dirujuknya dan proses kreatif mereka.
Analisa:Jadi puisi esai Denny JA yangg ada dalam buku Atas Nama Cinta, lebih tepat disebut esai? Atau esai dalam bentuk seperti puisi? Bukan puisi?
Budi: Bagi saya, ya. Malah mirip reportase jurnalistik. Bandingkanlah dengan buku esai Linda Chirstianty tentang Aceh atau karya jurnalisme sastrawi yang ada di Majalah Pantau dulu.
Analisa: Apakah polemik ini bukan soal positioning saja? Artinya tiap penyair, punya pengikut sendiri? Bukankah yang dilakukan Denny JA, dengan mengupah penyair muda menulis puisi esai versinya seperti pengasuh rubrik budaya meminta seorang penyair menulis puisi dengan tema tertentu dan si penyair mendapat honor?
Budi: Yang kita lakukan sama sekali tidak dihasratkan agar terjadi polemik (dialog). Ini tuntutan. Dalam seni memang ada pioner dan ada copycat (pengekor). Dalam sastra, tidak ada soal itu. Sastra memang seni, tapi bukan seni dalam pemahaman umum sebagai bagian dari ekonomi (entertaint). Sastra soal pendalaman sebuah persoalan, tidak hanya edukasi. Di dalam sastra Indonesia (puisi), kita tak menemukan pengikut.
Semua orang yang berpuisi, selalu menciptakan estetika yang khas dirinya. Persoalannya memang belum menemukan. Denny JA paham soal itu, karena dia memang berteman dengan banyak sastrawan. Selama para penyair tidak menemukan bentuk yang khas dirinya, mereka terus berproses.
Afrizal Malna menemukan khas dirinya meskipun bukan sebuah inovasi artistik kecuali sebagai sebuah strategi teks. Joko Pinurbo juga menemukan khas dirinya. Semua masih dalam lingkup puisi lirik. Puisi kan tidak hanya soal keterampilan berbahasa, tapi soal ilmu pengetahuan, juga soal filsafat. Eksperimen terus menerus dilakukan.
Soal meminta penyair, saya juga lama menjafi redaktur sastra di Lampung Post (grup Media Indonesia). Redaktur meminta penyair menulis untuk tema-tema khusus dan tidak mengintervensi harus menulis berbentuk tertentu seperti puisi esai. Kreativitas tetap pada penyair.
Denny JA berbeda, dia menyuruh karena motif untuk megalomania. Posisi Denny JA dalam sastra kita hanya serta merta, mendadak muncul. Untuk 33 tokoh sastrawan, dia justru mengalahkan Sanusi Pane, Merari Siregar, Bokor Hutasuhut. Memang Denny itu sudah menghasilkan apa? Apa yang dilakukannya lebih dasyat dari yang dilakukan Sanusi Pane atau Merari Siregar atau Bokor Hutasuhut?