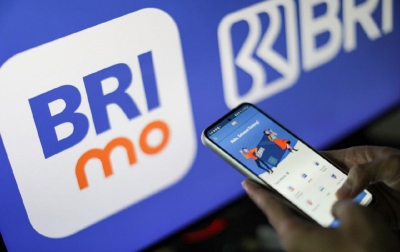Oleh: J Anto
MEREBUT ruang-ruang ekspresi alternatif di luar ruang prosenium, sembari membenahi manajemen organisasi agar profesional, mutlak dibutuhkan para pegiat teater di Sumut. Dalam zaman now, kehadiran teknologi komunikasi massa berbasis internet seperti youtube, tak mungkin juga ditampik.
Puluhan seniman teater Sumut menggelar kemah di halaman Taman Budaya Sumut sejak Jumat hingga Minggu (29-31/12). Sejumlah peralatan dapur mereka boyong dari rumah. Tapi mereka bukan mau demonstrasi. Sebanyak 20 grup teater dari Medan, Binjai, Deli Serdang, Labuhan Batu, dan Tanjung Balai tengah punya gawe besar di penghujung akhir 2017.
Mereka menggelar workshop, diskusi, berpentas dan bermusyawarah. Sejumlah narasumber diundang. Ada sejarawan sekaligus pemerhati sastra Sumut Ichwan Azhari, anggota Teater Koma Ratu Matu Mona, seniman teater generasi 1990-an Darma Lubis, staf ahli Dirjen Kebudayaan Alex Sihar, dan seniman teater Malaysia Ruslan Madun. Mereka bergotong royong menanggung biaya dan hanya mendapat fasilitas ruang pentas TBSU.
“Ini bukan sekadar kerinduan atau acara silaturahmi biasa, tapi bagian dari gerakan untuk mengembalikan teater Medan agar menjadi kiblat bagi teater lain di tanah air,” ujar Ketua Panitia Malam Renungan Teater (MRT) 2017, Agus Susilo usai Diskusi Teater yang digelar Sabtu (30/12) sore.
Niatan mengembalikan Medan sebagai kiblat teater, tentulah bukan keinginan ahistoris. Pada 1970 hingga 1990-an, pertunjukan teater tumbuh subur di Medan. Bahkan menurut Darma Lubis, yang pada 1993 bergabung dengan Teater D'lick pimpinan Yondik Tanto, Medan juga dikenal sebagai lumbung aktor teater.
Lumbung Aktor
T Mulya Lubis di surat kabar Merdeka menyebut, pada 1970 ada dua grup teater di Medan yang cukup terkenal, yakni Actor Studio yang dipimpin Arif Husin Siregar. Lalu sejumlah pemain Actor Studio keluar dan membentuk grup sendiri pada 1963 bernama Teater Nasional (Tena). Dari Tena lahir sederetan legenda teater Sori Siregar, Burhan Pilliang, Djohan A. Nasution, dan lain-lain.
Lalu pada 1980-an, ujar Darma Lubis, lahir Teater Que besutan Porman Wilson Manalu, D’lick pimpinan Yondik Tanto, dan jelang 2000-an muncul Teater Rumah Mata pimpinan Agus Susilo dan Opera Batak pimpinan Thompson HS.
Sementara menurut Mihar Harahap, dunia teater di Sumut juga mengenal Teater Anak Negeri pimpinan Idris Pasaribu, Teater Imago pimpinan D Rifai Harahap, Teater Blok pimpinan Afrion, Teater Merdeka pimpinan YS Rat, Teater Kartupat pimpinan Raswin Hasibuan, Teater Profesi pimpinan As Atmadi, dan Teater Generasi pimpinan Suyadi San.
Budaya melek teater bagi masyarakat Medan dan Sumatera Utara umumnya, menurut sejarawan Ichwan Azhari sudah berumur lebih dari satu abad. Pada saat bersamaan, sejak 1900 -1935 masyarakat di Medan sudah terbiasa menonton pertunjukan teater, baik yang disebut teater tradisional, transisi maupun modern.
“Dari mandu, makjong, opera bangsawan, opera Batak sampai teater modern,” kata Ichwan Azhari. Pada 1935 surat kabar Moetiara edisi 26 Oktober 1935 dan 2 November 1935 menulis, pertunjukan Dardanela (Miss DJA) ke Medan membawa nuansa baru perteateran di Medan. Disebutkan, Dardanela grup yang menjadi cikal bakal teater modern di Medan. Dalam edisi 2 November disebutkan, pertunjukan Dardanela berlangsung selama sepekan dan sukses menggalang penonton yang bahkan banyak tidak kedapatan tiket.
Antusiasme masyarakat menonton teater, menurut Ichwan Azhari, menunjukan tingginya tingkat literasi atau apresiasi masyarakat terhadap seni pertunjukan. Padahal saa itu, jumlah kaum sekolahan atau golongan terdidik, belumlah sebanyak seperti sekarang.
“Ironisnya pertunjukan teater sekatang bertahan hanya 1 malam, paling lama 2 malam dengan jumlah penonton paling banyak mungkin seribu orang, padahal pada 1935, pertunjukan teater bisa bertahan 14 hari dan harga tiket tak ada diskon,” tuturnya. Semua data itu menunjukkan bahwa teater tradisional, transisi dan modern secara bersamaan telah ada di Sumut.
Ichwan mengatakan, pembabakan teater versi Jacob Sumardjo atau Muhammad TWH yang membabakan teater dalam tiga periode, tak berlaku di Medan. Penyebabnya ketiga jenis pertunjukkan itu telah dipertunjukkan pada sebuah fase yang sama.
Ruang Ekspresi
Medan sebagai kiblat teater, termasuk juga sastra, sejak penghujung 2000-an memang tinggal cerita sejarah. Kehidupan teater memang masih berdenyut, tapi menurut Darma Lubis, sudah lemah. Teater masih ada, pertunjukan masih ada. Namun lebih sebagai kegiatan sampingan para pegiat teater. Mereka berkarya bukan memenuhi kebutuhan berkesenian, tapi lebih untuk memenuhi pesanan menyemarakkan sebuah event tertentu, di daerah maupun pada aras nasional.
Penyebab semua kelesuan itu beragam. Selain masalah klasik minimnya dukungan dana, baik dari pemerintah atau swasta, anggota Komite Sinematografi dan Multimedia Dewan Kesenian Medan ini juga menyebut manajemen berteater yang lemah. Banyak grup teater yang tak punya badan hukum dan AD/ART. Akibatnya susah mendapat akses pendanaan dari pihak pemerintah maupun swasta.
“Mereka juga jauh dari akses informasi para pengambil keputusan,” ujar pria yang pada 1999 pernah menyutradari naskah Busung (1999) di Yogyakarta dan lakon Raja Catur (2014) yang dipentaskan di Bali, Yogyakarta, dan Medan itu.
Di luar semua itu, anggota Dewan Pengawas Koalisi Seni Indonesia 2013 itu menyebut, faktor pemahaman tentang ruang ekspresi yang keliru. Sebagian memahami keberadaan panggung sebagai kewajiban negara. Karena itu panggung diartikan sebagai gedung pertunjukkan. Alam pikir seperti itu harus diubah.
Jika panggung adalah tempat berekspresi, maka setiap ruang bisa menjadi panggung. Karena itu panggung bisa di mana saja, tergantung siapa yang akan menonton sebagai kelompok penerima pesan. Bersama Teater Profesi, Darma lubis pernah membuat pentas di Mapple Theatre, sebuah hotel berbintang di Medan dan pertunjukan itu sukses. Kursi penonton penuh terisi sekalipun pertunjukan berlangsung 2 hari.
Panggung juga termasuk ruang maya. Pegiat teater sekarang ini menurutnya tak bisa mengelak dari revolusi teknologi komunikasi massa berbasis internet. Piranti media sosial seperti youtube harus dimanfaatkan sebagai ajang promosi yang murah.
“Seperti pengakuan Rita Ratu Mona, sebagai kurator teater, ia sulit mendapatkan data teater di Sumut yang mau dikurasi. Padahal dia mengandalkan mesin pencari informasi untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan teater,” katanya. Darma Lubis memberi saran agar grup teater menjadikan medsos sebagai media untuk dokumentasi sekaligus publikasi berbagai aktivitas seni teater.
“Lha wong dakwah saja udah di-youtube-kan bisa punya viewer antara 10 ribu hingga jutaan. Bayangkan benefit yang didapat jika sebuah grup teater meng-upload konten secara reguler,” katanya. Tentu saja isi konten yang diunggah harus sesuai dengan kelompok milenial.
Sekalipun tafsor tentang ruang ekspresi harus fleksibel, namun Darma Lubis menyadari infrastruktur teater masih dibutuhkan. Dalam sebuah kota, infrastruktur kesenian adalah cerminan kecerdasan budaya di kota tersebut. Ia setuju bahwa pegiat teater harus berjuang merebut pengadaan infrastruktur tersebut dari negara, apalagi setelah ada Undamg-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaaan.
“Merujuk pada sejarah teater di Eropa misalnya, teater itu dulu tontonan kaum menengah ke atas secara ekonomi dan pendidikan. Hal ini memperlihatkan para pejabat Sumut dan Medan belum berada di bawah posisi kecerdasan budaya yang diharapkan,” ujar Darma Lubis.
Sebenarnya dalam sejarah perkembangan insfrastruktur seni budaya, Kota Medan pernah memiliki infrastruktur seni pertunjukan terbaik di Asia Tenggara di era 1970-an. Itu terbukti dengan dibangun gedung Tapian Daya, akronim dari Taman Impian Kebudayaan Sumatera Utara.
Penggagasnya antara lain Burhan Piliang, Zakaraia M Passe, Rusli A Malem, dan Zaidan BS. Dibangun pada masa Gubenur Marah Halim Harahap dan selesai dibangun pada 1978. Sedari awal Tapian Daya diperuntukkan sebagai pusat kesenian dan panggung teater, auditorium, gedung bioskop, ruang tari, ruang teater, ruang senirupa, studio mini film, wisma seni, dan bangunan perkantoran. Namun sejak ditangani pihak ketiga, infrastruktur itu tidak lagi menjadi pusat kesenian, khususnya seni pertunjukan.
Persoalannya bagaimana mengembalikan hak para seniman teater agar ada lagi infrastruktur kesenian seperti Tapian Daya di Sumut?
Modal sebenarnya sudah ada. Infrastruktur regulasi sudah ada. Para seniman teater juga sudah bermusyawarah. Bahkan sepakat membentuk forum Koordinasi/Komunikasi Teater Sumatra Utara yang bertugas sebagai sentra informasi teater (pertunjukan, diskusi, workshop, laboratorium, literasi) dan pelaksanaan MRT 2018 di Rantauprapat.
Musyawarah seniman juga sudah menunjuk Yan Amarni Lubis sebagai koordinator forum. Jadi mari kita tunggu perjuangan mereka mewujudkan ruang ekspresi untuk mendinamisasi dan mengembalikan marwah perteateran di Medan dan Sumutera Utara.
Puluhan seniman teater Sumut menggelar kemah di halaman Taman Budaya Sumut sejak Jumat hingga Minggu (29-31/12). Sejumlah peralatan dapur mereka boyong dari rumah. Tapi mereka bukan mau demonstrasi. Sebanyak 20 grup teater dari Medan, Binjai, Deli Serdang, Labuhan Batu, dan Tanjung Balai tengah punya gawe besar di penghujung akhir 2017.
Mereka menggelar workshop, diskusi, berpentas dan bermusyawarah. Sejumlah narasumber diundang. Ada sejarawan sekaligus pemerhati sastra Sumut Ichwan Azhari, anggota Teater Koma Ratu Matu Mona, seniman teater generasi 1990-an Darma Lubis, staf ahli Dirjen Kebudayaan Alex Sihar, dan seniman teater Malaysia Ruslan Madun. Mereka bergotong royong menanggung biaya dan hanya mendapat fasilitas ruang pentas TBSU.
“Ini bukan sekadar kerinduan atau acara silaturahmi biasa, tapi bagian dari gerakan untuk mengembalikan teater Medan agar menjadi kiblat bagi teater lain di tanah air,” ujar Ketua Panitia Malam Renungan Teater (MRT) 2017, Agus Susilo usai Diskusi Teater yang digelar Sabtu (30/12) sore.
Niatan mengembalikan Medan sebagai kiblat teater, tentulah bukan keinginan ahistoris. Pada 1970 hingga 1990-an, pertunjukan teater tumbuh subur di Medan. Bahkan menurut Darma Lubis, yang pada 1993 bergabung dengan Teater D'lick pimpinan Yondik Tanto, Medan juga dikenal sebagai lumbung aktor teater.
Lumbung Aktor
T Mulya Lubis di surat kabar Merdeka menyebut, pada 1970 ada dua grup teater di Medan yang cukup terkenal, yakni Actor Studio yang dipimpin Arif Husin Siregar. Lalu sejumlah pemain Actor Studio keluar dan membentuk grup sendiri pada 1963 bernama Teater Nasional (Tena). Dari Tena lahir sederetan legenda teater Sori Siregar, Burhan Pilliang, Djohan A. Nasution, dan lain-lain.
Lalu pada 1980-an, ujar Darma Lubis, lahir Teater Que besutan Porman Wilson Manalu, D’lick pimpinan Yondik Tanto, dan jelang 2000-an muncul Teater Rumah Mata pimpinan Agus Susilo dan Opera Batak pimpinan Thompson HS.
Sementara menurut Mihar Harahap, dunia teater di Sumut juga mengenal Teater Anak Negeri pimpinan Idris Pasaribu, Teater Imago pimpinan D Rifai Harahap, Teater Blok pimpinan Afrion, Teater Merdeka pimpinan YS Rat, Teater Kartupat pimpinan Raswin Hasibuan, Teater Profesi pimpinan As Atmadi, dan Teater Generasi pimpinan Suyadi San.
Budaya melek teater bagi masyarakat Medan dan Sumatera Utara umumnya, menurut sejarawan Ichwan Azhari sudah berumur lebih dari satu abad. Pada saat bersamaan, sejak 1900 -1935 masyarakat di Medan sudah terbiasa menonton pertunjukan teater, baik yang disebut teater tradisional, transisi maupun modern.
“Dari mandu, makjong, opera bangsawan, opera Batak sampai teater modern,” kata Ichwan Azhari. Pada 1935 surat kabar Moetiara edisi 26 Oktober 1935 dan 2 November 1935 menulis, pertunjukan Dardanela (Miss DJA) ke Medan membawa nuansa baru perteateran di Medan. Disebutkan, Dardanela grup yang menjadi cikal bakal teater modern di Medan. Dalam edisi 2 November disebutkan, pertunjukan Dardanela berlangsung selama sepekan dan sukses menggalang penonton yang bahkan banyak tidak kedapatan tiket.
Antusiasme masyarakat menonton teater, menurut Ichwan Azhari, menunjukan tingginya tingkat literasi atau apresiasi masyarakat terhadap seni pertunjukan. Padahal saa itu, jumlah kaum sekolahan atau golongan terdidik, belumlah sebanyak seperti sekarang.
“Ironisnya pertunjukan teater sekatang bertahan hanya 1 malam, paling lama 2 malam dengan jumlah penonton paling banyak mungkin seribu orang, padahal pada 1935, pertunjukan teater bisa bertahan 14 hari dan harga tiket tak ada diskon,” tuturnya. Semua data itu menunjukkan bahwa teater tradisional, transisi dan modern secara bersamaan telah ada di Sumut.
Ichwan mengatakan, pembabakan teater versi Jacob Sumardjo atau Muhammad TWH yang membabakan teater dalam tiga periode, tak berlaku di Medan. Penyebabnya ketiga jenis pertunjukkan itu telah dipertunjukkan pada sebuah fase yang sama.
Ruang Ekspresi
Medan sebagai kiblat teater, termasuk juga sastra, sejak penghujung 2000-an memang tinggal cerita sejarah. Kehidupan teater memang masih berdenyut, tapi menurut Darma Lubis, sudah lemah. Teater masih ada, pertunjukan masih ada. Namun lebih sebagai kegiatan sampingan para pegiat teater. Mereka berkarya bukan memenuhi kebutuhan berkesenian, tapi lebih untuk memenuhi pesanan menyemarakkan sebuah event tertentu, di daerah maupun pada aras nasional.
Penyebab semua kelesuan itu beragam. Selain masalah klasik minimnya dukungan dana, baik dari pemerintah atau swasta, anggota Komite Sinematografi dan Multimedia Dewan Kesenian Medan ini juga menyebut manajemen berteater yang lemah. Banyak grup teater yang tak punya badan hukum dan AD/ART. Akibatnya susah mendapat akses pendanaan dari pihak pemerintah maupun swasta.
“Mereka juga jauh dari akses informasi para pengambil keputusan,” ujar pria yang pada 1999 pernah menyutradari naskah Busung (1999) di Yogyakarta dan lakon Raja Catur (2014) yang dipentaskan di Bali, Yogyakarta, dan Medan itu.
Di luar semua itu, anggota Dewan Pengawas Koalisi Seni Indonesia 2013 itu menyebut, faktor pemahaman tentang ruang ekspresi yang keliru. Sebagian memahami keberadaan panggung sebagai kewajiban negara. Karena itu panggung diartikan sebagai gedung pertunjukkan. Alam pikir seperti itu harus diubah.
Jika panggung adalah tempat berekspresi, maka setiap ruang bisa menjadi panggung. Karena itu panggung bisa di mana saja, tergantung siapa yang akan menonton sebagai kelompok penerima pesan. Bersama Teater Profesi, Darma lubis pernah membuat pentas di Mapple Theatre, sebuah hotel berbintang di Medan dan pertunjukan itu sukses. Kursi penonton penuh terisi sekalipun pertunjukan berlangsung 2 hari.
Panggung juga termasuk ruang maya. Pegiat teater sekarang ini menurutnya tak bisa mengelak dari revolusi teknologi komunikasi massa berbasis internet. Piranti media sosial seperti youtube harus dimanfaatkan sebagai ajang promosi yang murah.
“Seperti pengakuan Rita Ratu Mona, sebagai kurator teater, ia sulit mendapatkan data teater di Sumut yang mau dikurasi. Padahal dia mengandalkan mesin pencari informasi untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan teater,” katanya. Darma Lubis memberi saran agar grup teater menjadikan medsos sebagai media untuk dokumentasi sekaligus publikasi berbagai aktivitas seni teater.
“Lha wong dakwah saja udah di-youtube-kan bisa punya viewer antara 10 ribu hingga jutaan. Bayangkan benefit yang didapat jika sebuah grup teater meng-upload konten secara reguler,” katanya. Tentu saja isi konten yang diunggah harus sesuai dengan kelompok milenial.
Sekalipun tafsor tentang ruang ekspresi harus fleksibel, namun Darma Lubis menyadari infrastruktur teater masih dibutuhkan. Dalam sebuah kota, infrastruktur kesenian adalah cerminan kecerdasan budaya di kota tersebut. Ia setuju bahwa pegiat teater harus berjuang merebut pengadaan infrastruktur tersebut dari negara, apalagi setelah ada Undamg-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaaan.
“Merujuk pada sejarah teater di Eropa misalnya, teater itu dulu tontonan kaum menengah ke atas secara ekonomi dan pendidikan. Hal ini memperlihatkan para pejabat Sumut dan Medan belum berada di bawah posisi kecerdasan budaya yang diharapkan,” ujar Darma Lubis.
Sebenarnya dalam sejarah perkembangan insfrastruktur seni budaya, Kota Medan pernah memiliki infrastruktur seni pertunjukan terbaik di Asia Tenggara di era 1970-an. Itu terbukti dengan dibangun gedung Tapian Daya, akronim dari Taman Impian Kebudayaan Sumatera Utara.
Penggagasnya antara lain Burhan Piliang, Zakaraia M Passe, Rusli A Malem, dan Zaidan BS. Dibangun pada masa Gubenur Marah Halim Harahap dan selesai dibangun pada 1978. Sedari awal Tapian Daya diperuntukkan sebagai pusat kesenian dan panggung teater, auditorium, gedung bioskop, ruang tari, ruang teater, ruang senirupa, studio mini film, wisma seni, dan bangunan perkantoran. Namun sejak ditangani pihak ketiga, infrastruktur itu tidak lagi menjadi pusat kesenian, khususnya seni pertunjukan.
Persoalannya bagaimana mengembalikan hak para seniman teater agar ada lagi infrastruktur kesenian seperti Tapian Daya di Sumut?
Modal sebenarnya sudah ada. Infrastruktur regulasi sudah ada. Para seniman teater juga sudah bermusyawarah. Bahkan sepakat membentuk forum Koordinasi/Komunikasi Teater Sumatra Utara yang bertugas sebagai sentra informasi teater (pertunjukan, diskusi, workshop, laboratorium, literasi) dan pelaksanaan MRT 2018 di Rantauprapat.
Musyawarah seniman juga sudah menunjuk Yan Amarni Lubis sebagai koordinator forum. Jadi mari kita tunggu perjuangan mereka mewujudkan ruang ekspresi untuk mendinamisasi dan mengembalikan marwah perteateran di Medan dan Sumutera Utara.

Salah satu pementasan di luar ruang oleh peserta MRT Sumut 2017

Rita Matumona saat memberi pembekalan dalam workshop MRT Sumut 2017

Para pemateri dalam diskusi MRT Sumut 2017 bersama sejumlah peserta

Agung Suharyanto saat memberi pembakalan olah tubuh dalam workshop MRT Sumut 2017

Sejumlah bilboard pementasan dari grup teater pesertta Malam Renungan Teater Sumut 2017