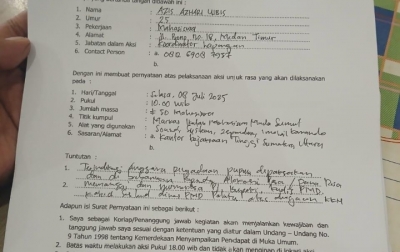Oleh: Fadil Abidin.
Ketika gempa bumi dan tsunami melanda Aceh pada akhir tahun 2004, kita sebagai bangsa bersatu. Bersatu dalam empati, bersatu dalam semangat kerjasama, gotong royong, donasi dan bantuan mengalir dari semua pihak. Tidak ada tudingan bencana itu sebagai azab dari Tuhan. Tidak ada rivalitas politik pasca Pilpres 2004. Tidak ada golongan yang "nyinyir" dan merecoki pemerintah. Tidak ada tudingan macam-macam.
Kini menjelang Pilpres 2019, bencana alam yang berkali-kali terjadi di tahun 2018 ternyata tidak menyatukan kita sebagai bangsa. Hoaks dan penyebaran kebencian justru semakin menjadi-jadi. Saat ini, ketika bencana terjadi maka tudingan bermunculan. Bukannya bersatu dan menunjukkan rasa simpati dan empati.
Hoaks bertebaran memberitakan kabar palsu akan terjadi bencana susulan. Foto-foto korban dengan kondisi mengenaskan tersebar di media sosial. Coba bayangkan seandainya jenazah korban tersebut anak, saudara, orang tua, suami atau istri anda difoto dalam keadaan nyaris tanpa busana tersebar. Bagaimana perasaan anda?
Tudingan yang paling keji adalah ketika bencana itu disebut sebagai azab. Para korban adalah orang-orang yang mendapat azab dari Tuhan akibat perbuatannya. Ada pula yang menyangkut pautkan bencana itu dengan aktivitas politik tertentu. Gempa bumi terjadi karena kepala daerahnya mendukung politisi tertentu. Tsunami terjadi karena si A ditetapkan sebagai tersangka. Bencana alam bukan azab dari Tuhan, apalagi dikaitkan politik. Di mana empati kita?
Agaknya, empati kita saat ini tengah berada di titik nadir. Titik nadir adalah titik paling bawah, titik di mana rasa sebagai "manusia" itu patut dipertanyakan. Manusia adalah kreasi Tuhan yang begitu unik dan spesial. Selain dibekali perangkat otak untuk berfikir, juga dibekali hati yang mempunyai perasaan yang disebut empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Berempati berarti mempunyai empati dan mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain.
Hikmah Bencana
Sebagai bangsa kita harus belajar dari kearifan sejarah masa lalu. Pasa 1 Nopember 1755 terjadi gempa besar di Lisabon, ibukota Portugal. Gempa yang menurut ahli geologi masa kini diperkirakan mempunyai kekuatan 9,0 skala richter menyebabkan tsunami yang dahsyat. Diperkirakan total kematian 60.000 hingga 100.000 orang, yang menyebabkan gempa ini menjadi salah satu gempa paling merusak dalam sejarah.
Gempa tersebut menyulut ketegangan sosial-politik di Portugal bahkan gugatan terhadap dogma yang ada. Gempa terjadi pada pagi hari, ketika itu semua warga Lisabon tengah merayakan Hari Semua Orang Kudus, hari besar umat Katolik.
Setelah gempa tersebut pejungga-filsuf Voltaire menggugat dalam "Poeme sur le desastre de Lisbonne" - Puisi Bencana Lisabon. Ia mengajukan pertanyaan teologis, mengapa gempa terjadi? Voltaire menuding Tuhan sebagai penyebab bencana. Ia mengkritik keyakinan masyarakat bahwa Tuhan itu baik, tapi nyatanya Tuhan juga memberikan bencana.
Sementara Voltaire bergumul dengan pertanyaan mengapa. Perdana Menteri Sebastiao de Mello yang bergelar Marquis de Pombal tidak berminat mempertanyakan penyebab gempa dan dogma-dogma yang ada. Baginya, yang terpenting saat itu adalah bersatu, bangkit, dan bekerja. Dia mengatur pengorganisasian usaha pembangunan dan rehabilitasi. Tim pekerja dan warga biasa dibentuk untuk memindahkan ribuan mayat sebelum penyakit menyebar. Bertentangan dari kebiasaan dan keinginan Gereja agar ribuan mayat itu dikuburkan. Tapi Pombal meminta ribuan mayat tersebut dimasukkan ke dalam tongkang dan ditenggelamkan ke tengah laut agar semuanya berjalan cepat.
Untuk mencegah kekacauan dan penjarahan di kota-kota yang hancur, Pombal mengerahkan tentara dan membuat ratusan tiang gantung. Siapa membuat kerusuhan, penjarahan, atau "nyinyir" terhadap kerajaan akan digantung di tempat umum. Tentara tersebut juga mencegah agar warga yang sehat selamat dari bencana tidak lari atau berpangku tangan. Mereka diharuskan ikut serta dalam kerja rekonstruksi dan pembangunan.
Raja dan Perdana Mentri Pombal meluncurkan usaha pembangunan ulang kota, merekrut arsitek, insinyur dan memerintahkan semua rakyat untuk bekerja keras. Gedung-gedung pemerintah dan pelayanan publik dirancang agar tahan terhadap gempa. Kurang dari setahun, kota bebas dari puing-puing. Ketekunan menjadikan kota menjadi baru dan indah.
Bencana tersebut kemudian dibahas dan diminati oleh para filsuf dan ilmuwan di zaman pencerahan Eropa. Dan pertama kali gempa dipelajari secara ilmiah terhadap dampaknya hingga area yang luas, hal ini membawa kelahiran seismologi modern.
Empati
Lalu apakah kita sudah bersatu untuk bangkit dan membangun kembali? Belum. Justru yang kerap terdengar adalah ocehan para politisi yang berbeda posisi yang kian nyaring di media massa dan media sosial. "Kami akan membantu, jika pemerintah memintanya." Padahal dari dulu kita diajarkan bahwa menolong orang lain yang tertimpa musibah atau bencana, harus segera dilakukan, diminta atau tidak diminta. Bukan kesigapan membantu, malah yang terdengar adalah nyinyiran,"Pemerintah lamban dalam menangani bencana."
Padahal ketika ada satu orang di pihak mereka yang mengaku dianiaya, mereka langsung menelan hoaks tersebut dan dengan sigap melakukan konferensi pers. Ketika kebohongan tersebut terbongkar, mereka dengan sigap pula melakukan konferensi pers ulang untuk "cucitangan". Dan lagi-lagi mengadakan konferensi pers ketika harga dolar naik terhadap rupiah.
Tapi, pernahkah mereka konferensi pers untuk menyatakan belasungkawa dan menyatakan siap sedia membantu para korban bencana? Seolah-olah penanganan bencana alam adalah 100 persen tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab semua warga negara. Empati terhadap para korban bencana dalam sekejap berada di titik nadir bahkan hilang di telan gegap gempita berita hoaks.
Presiden, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua jajarannya tengah bekerja keras untuk segera memulihkan semua yang ada. Pemerintah punya keterbatasan, untuk itu peran serta masyarakat sangat diperlukan. Relawan perlu dikerahkan dan donasi-donasi sosial perlu digalakkan. Pengguna medsos berlakulah arif, jangan malah menyebar hoaks dan membuat tudingan macam-macam seputar bencana. Jokowi bukanlah Pombal yang akan segera menggantung mereka-mereka yang "nyinyir" karena dianggap mengganggu rekonstruksi pasca bencana.
Saat ini ada kebencian yang mendalam yang diidap sebagian masyarakat terhadap pemerintah. Jadi apapun yang dibuat pemerintah akan dibenci habis-habisan tanpa logika dan akal sehat. Ada kalimat sindiran, bahwa maha benar "mereka" dengan segala nyinyirannya. Apapun penjelasan dan fakta yang diberikan, pasti akan dibantah oleh mereka karena kebencian dan kecanduan pada hoaks yang sangat tinggi.
Jika kita tidak bisa membantu dengan sumbangan pikiran, tenaga, dan dana, bantulah dengan doa-doa yang baik. Jika kita tidak bisa berempati apalagi mengulurkan tangan, janganlah juga menambahi penderitaan saudara kita yang sedang terkena bencana dengan mengomentari hal-hal yang sama sekali tidak kita pahami, bonus hoaks pula.
Yang mestinya mudah tersulut emosi adalah mereka. Mereka yang kehilangan keluarga, rumah, harta benda, kelaparan, kehausan, dan tidak tahu harus bagaimana. Bukan hak kita yang hanya bisa menonton dan menyinyiri untuk emosi dan mempolitisasi. Sesungguhnya bencana yang paling mengerikan adalah hilangnya rasa empati dan kemanusiaan dalam diri kita. ***
* Penulis adalah pemerhati masalah sosial-kemasyarakatan.