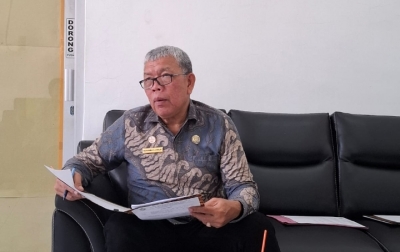Oleh: Roy Martin Simamora.
Thomas Chamorro-Premuzic dalam tulisannya bertajuk “Are millennials as bad as we think?” di surat kabar The Guardian mengatakan generasi milenial adalah kaum yang kompleks. Kaum milenial memiliki sifat paradoksikal dalam karakter mereka-sebuah ketegangan antara kebalikan yang harus didamaikan. Ketegangan ini menghadirkan tantangan, tidak hanya bagi generasi millennial, tetapi juga bagi mereka yang mencoba memahami dan mengelolanya.
Dia membagi beberapa poin yang menggambarkan generasi milenial: pertama, kaum ambisius tapi malas. Menurutnya, kaum muda sangat mudah diberi janji-janji yang tidak realistis. Kaum realistis meskipun mau bertaruh mengorbankan idealismenya. Ketika menamatkan kuliah, mereka diberikan harapan tinggi yang menganggap bahwa pencapaian kesuksesan hanya direalisasikan pada setiap janji-janji itu. Kaum milenial telah berpikir bahwa kesuksesan adalah memiliki kepercayaan diri yang tinggi; bukan disiplin, pengetahuan diri atau kerendahan hati. Ini membuat harapan mereka soal bakat mereka (yang dipersepsikan sendiri) tetap utuh, seolah-olah cepat atau lambat potensi luar biasa mereka akan ditemukan, bahkan jika mereka tidak mencurahkan banyak waktu untuk memanfaatkannya.
Kedua, hyper-connected, tetapi terobsesi pada diri sendiri. Media telah mempercepat waktu interaksi manusia, termasuk interaksi kaum milenial. Misalnya, Facebook. Kaum milenial tidak perlu bersitatap antarsesama teman. Cukup berinteraksi dan berkomunikasi lewat dunia maya. Thomas Chamorro-Premuzic menyebut kaum milenial terhubung secara hiper, tetapi mereka tidak begitu tertarik pada orang lain kecuali sebagai audiens belaka. Seperti slogan YouTube, ambisi utama mereka adalah untuk menyiarkan diri mereka sendiri kepada khalayak publik. Contoh paling nyata: mendokumentasikan keseharian dalam rekam video lalu dibagikan ke Youtube. Saya melihat kaum milenial akan bahagia jika memiliki banyak pengikut. Tergila-gila dengan puja-puji. Bahkan melupakan batas-batas penggunaan teknologi. Mengeksplor diri terlalu jauh. Tidak peduli itu privasi atau tidak. Dia mengatakan fenomena ini adalah revolusi media sosial, tetapi mungkin justru sebaliknya: kekuatan media sosial hanya menyoroti betapa kita telah menjadi sia-sia. Tingkat narsisisme terus meningkat selama beberapa dekade terakhir, membuat generasi millennial lebih terobsesi pada diri sendiri daripada pendahulu mereka.
Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Now Sourcing and Frames Direct, dalam seminggu, milenial membutuhkan waktu sekitar satu jam hanya untuk mendapatkan hasil foto yang paling bagus. Waktu tersebut merupakan waktu yang dibutuhkan saat mulai mengambil foto, sampai melakukan proses editing lewat aplikasi yang diunduh via smartphone. Temuan itu juga melaporkan foto selfie yang beredar di media sosial didominasi oleh milenial dengan 55 persen, diikuti oleh Gen X dengan 24 persen, dan baby boomers sebanyak 9 persen. Penelitian lainnya juga menemukan tingkat narsisme kaum milenial. Sejurus dengan itu, laporan doktor klinik Psikologi dari Case Western Reserve University, Joshua Grubbs menempatkan generasi milenial dengan skor tertinggi terkait narsisme. Mereka mendapat nilai 65,3 dari keseluruhan 100 poin.
Ketiga, nonkonformis (perilaku menyimpang dari norma-norma) tetapi materialistis: faktanya bahwa kaum milenial sangat tertarik pada uang, status dan hal-hal berbau mahal. Namun, obsesi dengan “bling” ini kontras dengan sifat nonkonformis mereka. Memang, kaum milenial lebih individualistis, memberontak dan mandiri daripada generasi masa lalu, kecuali keinginan mereka untuk menyesuaikan diri. Akibatnya, kaum milenial terjebak dalam lingkaran setan: di satu sisi, mereka ingin mengganggu sistem; di sisi lain, mereka lebih takut terhadap penolakan.
Keempat, sulit untuk memotivasi, tetapi lebih mau terlibat: kaum milenial melihat pekerjaan kurang penting bagi kehidupan mereka. Mereka menghargai keseimbangan kehidupan kerja lebih dari generasi yang lain. Ironisnya, ini membuat tuntutan dan standar milenial lebih rendah-ketika Anda melihat pekerjaan sebagai “hanya mencari nafkah”, Anda berharap menemukan makna di area kehidupan lain (misalnya pendidikan, hubungan, atau hobi). Kaum milenial percaya pada kesenangan daripada bekerja. Karenanya, mereka berharap untuk bersenang-senang di tempat kerja.
Jika menganalisa pemikiran Thomas Chamorro-Premuzic di atas menegaskan, kaum milenial telah berevolusi sangat cepat daripada generasi-generasi sebelumnya. Dibandingkan dengan generasi sebelumnya, sikap kaum milenial dalam hal bekerja dan bersenang-senang mungkin membuat mereka lebih rumit untuk dipahami. Hal itu ditandai pula dengan pesatnya teknologi dan informasi di seluruh dunia. Kaum milenial dianggap sebagai kaum yang sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Tetapi, dibalik itu ada beberapa masalah-masalah rumit yang dihinggapi oleh kaum milenial yang tentu saja berkaitan dengan sejauh mana wawasan kebangsaan mereka.
Krisis Wawasan Kebangsaan
Saya punya pengalaman yang unik: saya pernah bertanyapada mahasiswa soal wawasan kebangsaan. Seberapa jauh mereka punya pengetahuan soal wawasan kebangsaan. Beberapa pertanyaan yang saya lontarkan sebetulnya “remeh-temeh” tapi imbasnya lumayan mengecewakan. Pada kesempatan itu, saya bertanya-tanya seputar kapan sebetulnya Indonesia merdeka, siapa pahlawan nasional atau pahlawan revolusi yang mereka kenal, lalu saya kaitankan dengan satu contoh yang paling dekat dengan mereka; berkaitan dengan suku. Siapakah pahlawan dari suku mereka yang ikut memperjuangkan kemerdekaan dan merebut kehormatan bangsa? Lantas, apa jawaban yang saya dapatkan? Sungguh mencegangkan: tak satupun dari mereka yang tahu siapa pahlawan dari suku mereka apalagi pahlawan nasional sampai sekarang ini.
Pengalaman yang lain, pada satu materi kuliah yang membahas identitas nasional, saya bertanya pada mahasiswa: apa itu identitas nasional atau pertanyaan saya ganti agar menjadi lebih mudah dipahami: apa identitasmu sebagai warga negara Indonesia? Meskipun, satu dua orang diantara mereka mampu menjawabnya, tapi tidak cukup memuaskan pikiran saya waktu itu. Ini membuktikan, kaum milenial telah mengalami kemerosotan identitas, krisis kesadaran dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan Indonesia.
Saya pun tepekur seraya menghela nafas: apakah kaum milenial telah memiliki pahlawan baru dalam kehidupan mereka? Faktanya memang begitu. Pencipta, penemu dan raksasa-raksasa teknologi yang hari ini mereka baca, lihat, dan konsumsi setiap hari: Facebook, Youtube, Instagram, Google dan yang lainnya mungkin telah menjadi pahlawan baru dan sesungguhnya bagi mereka. Saban hari, kaum milenial disuguhi dengan akses mudah, cepat, dan praktis dalam menggunakan internet.Mereka menemui segalanya pada kemudahan internet. Bersebab itu, kaum milenial seakan melupakan jati diri, identitasnya sebagai bangsa Indonesia.
Siapa yang gagal dalam hal ini? Ini merupakan kegagalan terbesar keluarga, lembaga pendidikan, guru, dosen dan negara sekalipun dalam melahirkan generasi yang buta dengan sejarahnya sendiri. Peran lembaga pendidikan, pengenalan sejarah, serta wawasan kebangsaan hingga hari ini masih perlu dipertanyakan. Lembaga pendidikan sepertinya belum menghasilkan pribadi yang mengenal sejarah bangsanya sendiri. Peran sekolah dan guru justru gagal dalam pengajaran: tidak melahirkan pelajar yang memiliki jiwa-jiwa nasionalis, patriotis serta tidak memiliki kemauan kuat mempelajari, menyesapkan keluhuran bangsanya dalam dirinya sendiri. Negara justru gagal dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan sebagai landasan utama dalam usaha peletakan prinsip persatuan dan kesatuan.
Elit politik dan penguasa lebih sibuk mengurusi kepentingan politik ketimbang memikirkan nasib bangsa ini ditangan generasi selanjutnya.
Meminjam istilah Anderson (1991) mengatakan wawasan kebangsaan adalah socially and politically constructed. Artinya wawasan kebangsaan merupakan jiwa, cita-cita, atau falsafah hidup yang tidak lahir dengan sendirinya. Ia sesungguhnya merupakan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik. Artinya, wawasan kebangsaan adalah bagian penting dari konstruksi elit politik terhadap bangunan citra (image) bangsa Indonesia. Apa pun perbedaan pandangan, persepsi itu telah membentuk kerangka berpikir masyarakat tentang wawasan kebangsaan, terutama dalam menghadapi pesatnya kemajuan teknologi, informasi dan ilmu pengetahuan.
Lalu, bagaimana dengan wawasan kebangsaan kaum milenial zaman sekarang ini? Apakah mungkin bagi mereka bahwa pemahaman wawasan kebangsaan memang tidak dibutuhkan lagi ditengah cepatnya arus modernisasi, apalagi revolusi industri 4.0 yang sangat massif digaungkan? Saya pikir, wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan di zaman yang serba cepat dan mudah ini. Akan tetapi, tak satupun jejak digital, survey atau laporan, yang menginformasikan seberapa jauh sebenarnya pemahaman kaum milenial tentang wawasan kebangsaan Indonesia. Mestinya dibuat laporan khusus terkait sudah seberapa jauh wawasan kebangsaan kaum milenial zaman sekarang ini. Padahal, wawasan kebangsaan memiliki makna memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa. Menguasai teknologi bukan berarti melupakan pedoman hidup bangsa.
Setidaknya, kaum milenial tidak melupakan jati dirinya sebagai bagian dari Indonesia. Bukankah, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan individu atau golongan?
Bahkan, jelas sekali bahwa nilai-nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental: penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, cinta atas tanah air dan bangsa, demokrasi atau kedaulatan rakyat, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu, masyarakat adil-makmur, dan kesetiakawanan sosial.
Kaum milenial mesti mengamalkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun, kaum milenial disibukkan dengan kerja-kerja teknologis.
Perkembangan teknologi di bidang informasi, telekomunikasi, media elektronik, dan transportasi seharusnya membuat wawasan kebangsaan masyarakat (kaum milenial) semakin luas. Jangan pula ada kasus kaum milenial yang tidak bisa menghafal Pancasila, lupa lirik lagu kebangsaan, tidak tahu identitas dirinya, lupa simbol-simbol negara, dan kasus-kasus lainnya. Jangan ada idiom:“Menghafal Pancasila saja tidak mampu, apalagi upaya menyadarkan diri dengan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.”Ini memang terlihat sepele tapi dampaknya sangat luarbiasa besar. Bagaimana mungkin kaum milenial di masa depan mampu memperkenalkan budaya bangsanya kepada bangsa lain lewat kemajuan teknologi tanpa mengetahui siapa dirinya sendiri?
Pada titik ini, kaum milenial boleh-boleh saja maju dalam hal perkembangan teknologi dan informasi, tetapi mesti diingat, kaum milenial tidak boleh tertinggal dalam hal wawasan kebangsaan. Karena bagaimanapun, wawasan kebangsaan adalah salah satu faktor kunci yang mendorong majunya peradaban sebuah bangsa.***
Penulis adalah Alumnus Hua-Shih College of Education, National Dong Hwa University, Taiwan.