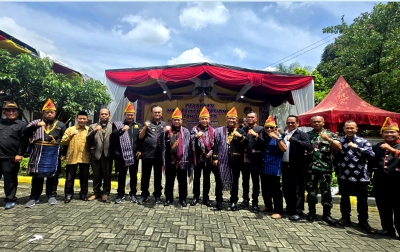Oleh: Bersihar Lubis
SETIAP kali membaca puisi yang ditulis oleh sastrawan legendaris Indonesia, saya selalu bertanya-tanya, “bagaimana mereka merajut kata demi kata yang memukau.” Bukan kata-kata biasa. Bukan pula seperti pidato pejabat, Keppres, juklak, atau opini di koran pagi.
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana
dengan kata yang tak sempat diucapkan
kayu kepada api yang menjadikannya abu
Aduhai, sajak “Hujan Bulan Juni” karya Sapardi Djoko Damono ini telah melukiskan rindu dan cinta yang membatin. Diksi-diksi yang unik. Lirik per lirik sederhana, tapi maknanya menukik.
Atau sajak “Aku” dari Chairil Anwar yang sangat populer. Metafor dari pelopor sastrawan angkatan 45 ini sangat imajinatif “
Aku ini binatang jalang
Dari kumpulannya terbuang
Biar peluru menembus kulitku
Aku tetap meradang menerjang.”
Bebaskan kata
Bagaimana gerangan kata-kata itu lahir ke dunia? Saya pun ingat kredo puisi Sutardji Calzoum Bachri. “Kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian. Dia bukan seperti pipa yang menyalurkan air. Kata adalah pengertian itu sendiri. Dia bebas.”
“Bila kata dibebaskan, kreatifitaspun dimungkinkan. Karena kata-kata bisa menciptakan dirinya sendiri, bermain dengan dirinya sendiri, dan menentukan kemauan dirinya sendiri. Pendadakan yang kreatif bisa timbul, karena kata yang biasanya dianggap berfungsi sebagai penyalur pengertian, tiba-tiba, karena kebebasannya bisa menyungsang terhadap fungsinya. Maka timbullah hal-hal yang tak terduga sebelumnya, yang kreatif.”
Saya kira Tardji ingin mengatakan bahwa puisi bukanlah seperti prosa, atau sebuah opini di surat kabar. Opini yang sarat dengan wacana dan argumentasi.
Ah, sangat berbeda dengan “puisi esai” yang digagas oleh Denny JA – dan kini ramai diperdebatkan — yang sarat dengan penjejalan pengertian bagaikan menulis sebuah features news di suratkabar, dengan kata-kata berhias..
Saya ingat penyair Joko Pinurbo (Jokpin) pernah berpendapat, bahwa banyak puisi bagus yang gagal karena si penyair tergoda untuk berceramah dan menyimpulkan sendiri puisi tersebut di ending-nya.
Padahal, menyimpulkan bacaan adalah otoritas pembaca. “Jangan bernafsu untuk menjadi nabi atau penceramah dalam puisimu. Jangan menceramahi pembaca lewat karya,”kata Jokpin.
Penyair Sapardi Djoko Damono juga punya kiat. Menurut Sapardi, seseorang harus mengosongkan pikiran dari emosi-emosi sebelum menulis puisi. Baik itu perasaan jatuh cinta atau kemarahan.
“Kalau sedang kelepek-kelepek jatuh cinta, kita nulis, yang keluar kata-kata cengeng dan jijikin,” ujarnya, suatu kali. ”Kalau marah nulis sajak, isi setiap kalimat ada tanda seru. Yang baca kan susah kalau semua tanda seru. Kalau marah demo saja, enggak usah berpuisi.” katanya.
Rendra sampai Wing
Tapi, tunggu dulu! Tidak bolehkah pusi berwacana bak esai? Lalu, bagaimana dengan “Puisi Pamflet” Rendra? “Aku tulis pamflet ini// karena pamflet bukan tabu bagi penyair,” cetus Rendra.
Antologi Rendra bertajuk Potret Pembangunan dalam Puisi terbit pada 1993. Kumpulan puisi ini dibuka melalui pernyataan bahwa penyair juga bisa – atau bahkan harus – menulis pamflet, yaitu sebuah selebaran berisi kata-kata atau gambar tertentu yang erat kaitannya dengan aktivitas politik.
Rendra pun turun ke jalanan menyuarakan apa yang selama ini dilupakan pembangunan di negeri ini. Rendra berempati kepada masyarakat marjinal: pada anak-anak putus sekolah, gelandangan, babu dan jongos, orang-orang miskin di jalanan maupun di selokan.
Sebuah sajak Rendra yang paling provokatif adalah “Bersatulah Pelacur-pelacur Kota Jakarta”. Puisi ini ditulisnya di New York. Suatu hari dia membaca berita dari Tanah Air. Dia marah-marah seraya mengumpat: “Ini tai kerbau!” Berita tersebut adalah tentang pengganyangan pelacur-pelacur Jakarta karena dianggap sebagai sumber kebobrokan masyarakat (Kompas, 1969).
Saya kira di sini, puisi esai ala Denny JA bukanlah genre baru dalam satra Indonesia. Lagi pula sudah sejak lama puisi dikenal bercorak ragam. Ada puisi yang terang benderang, gelap, dan remang-remang.
Puisi terang benderang adalah puisi yang rada nir-imajnasi dan mudah dimengerti. Puisi gelap terbangun dari kiasan yang pekat sehingga susah ditafsirkan. Jenis puisi terakhir mengintegrasikan puisi terang benderang dan gelap. Tidak terlalu mudah menafsirkannya, namun tidak terlalu gelap.
Jauh sebelum Denny JA, Wing Kardjo yang pernah tinggal di Perancis dan Jepang, juga beralih dari sajak-sajak individual yang sunyi ke sajak-sajak yang bersifat sosial pada era 1990-an – karena penghayatannya akan perubahan sosial-politik dan ekonomi di Indonesia, seperti pernah diakuinya kepada sastrawaan dan wartawan Soni Farid Maulana di Bandung.
Ada satu sajaknya yang berjudul Ecstasy, penuh dengan bahasa realistis bagaikan sajak pamflet Rendra. Wing tidak lagi berkutat dengan persoalan individual seperti terdapat dalam kumpulan puisinya “Selembar Daun.” “Saya tidak tahu, apakah nilai estetik dalam puisi saya masih ada atau tidak?,”ujar Wing.
Bahwa puisi esai ala Denny JA ditulis panjang dan mempunyai catatan kaki, hanya sekedar menjelaskan peristiwa sejarah dalam puisi. Memang, beda dengan puisi penyair Indonesia juga bercatatan kaki, terutama untuk mejelaskan suatu istilah pada tubuh puisi.
Sastra kontekstual
Syahdan, puisi esai mengeksplor sisi batin individu yang sedang berada dalam sebuah konflik sosial. Puisi esai menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sebab Denny JA berpendapat bahwa puisi yang sukar dipahami adalah sebuah puisi yang kurang baik.
Puisi esai tetap fiksi yang walau melukiskan tokoh real tetapi diperkaya dengan aneka tokoh fiktif dan dramatisasi.
Puisi esai bukan saja hasil ide penulis tetapi isu yang dibangkitkan oleh penulis dari penyelidikan atau kajian atas suatu isu sosial yang menyentuh.
Sastrawan asal Yogyakarta, Saut Situmorang, mengatakan puisi-esai adalah jenis puisi yang bersifat esai.
“Bentuknya, bukan tipografinya kertas! Puisi tapi isinya merupakan esai tentang suatu topik,” kata Saut seperti dikutip dari laman Facebook-nya.
Saut menjelaskan, puisi jenis ini sangat populer dalam kesusastraan Inggris abad 18, terutama seperti yang ditulis oleh sang maestro genre tersebut Alexander Pope. ‘An Essay on Criticism’ adalah puisi panjang Pope yang terkenal itu.
Saya browsing dari berbagai sumber, kegelisahan Denny JA bahwa banyak karya sastra mengesankan jauh dari apreasiasi masyarakat, karena bahasanya dinilai kurang komunikatif, juga bukan tesis baru. Arief Budiman dan Ariel Heriyanto pada 1984 pernah menggagas Sastra Kontekstual.
Kedua akademikus Universitas Kristen Satyawacana Salatiga ini menilai bahwa tradisi “bersastra” dalam sastra Indonesia, yang mereka klaim sebagai tradisi “sastra universal,” merupakan tradisi yang “tidak berakar” dalam realitas kehidupan Indonesia alias “kebarat-baratan.”
Itulah sebabnya menjadi terasing di negerinya sendiri” (lihat buku Perdebatan Sastra Kontekstual, 1985, susunan Ariel Heryanto). Akibatnya, sastra Indonesia tidak akrab dengan publiknya.
“Ibarat pohon, dia tidak bisa tumbuh, karena tidak punya tanah. Dia hanya menggapai-gapai ke atas. Sedangkan akarnya tidak menyentuh tanah.”
Toh, ide sastra kontekstual ini diserang dari berbagai penjuru. Umar Kayam berapi-api mengatakan bahwa sejak dahulu sastra Indonesia sudah kontekstual, karena ia kontekstual dengan kondisi masyarakat. Kayam seolah ingin mengatakan bahwa apa yang dijabarkan oleh Ariel dan Arief tidak mengandung unsur kebaruan.
He-he, toh mucul juga istilah “sastra dangdut” dari penyair Yudhistira Massardi untuk mengacu pada semangat musik dangdut yang dapat berbicara apa saja, dan paling dekat dengan lingkungan serta realitas yang ada di dalamnya.
Tapi saya kira perdebatan demi perdebatan itu tidak sia-sia. Bahkan, mencerahkan. Tak harus ada yang membusung dada, atau merasa dipojokkan. Pada akhirnya zaman kelak akan berbicara. Meskipun penolakan atau penerimaan zaman pun akan selalu menimbulkan perdebatan. ***
Penulis adalah jurnalis berdomisili di Medan