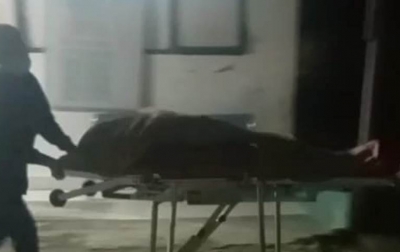HEGEMONI para empu sastra dalam telaah puisi-puisi Chairil Anwar ternyata meringsek juga ke sejumlah penyair Medan. Ambil contoh sajak Aku Chairil Anwar yang kerap dibawakan deklamator dengan nuansa semangat perjuangan, terutama pada larik: biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang, luka dan bisa kubawa berlari, berlari, hingga hilang pedih,danaku tak perduli, aku mau hidup seribu tahun lagi.
Padahal, menurut Damiri Mahmud, sajak Aku itu lahir dari kemelut batin besar yang dialami Chairil. Pergolakan terjadi saat ia harus melawan seorang ayah yang sangat memanjakan hidupnya. Segala yang dipinta diturutinya. Namun saat sang ayah itu menikah lagi, Chairil tidak memihak ayahnya. Chairil memang pernah sebentar tinggal bersama ibu tirinya.
Namun tidak lama ia memutuskan menyusul ke Kramat Sentiong, Jakarta. Ia memilih tinggal bersama ibunya. Ia meninggalkan hidup mewah di Medan bersama ayahnya yang seorang ambtenaar dan memilih hidup sederhana bersama ibunya.
Saat ayahnya datang ke Jakarta dan mengajaknya pulang kembali ke Medan, Chairil menolak. Ia lebih memilih hidup secara bohemian.
“Lalu lahirlah sajak Aku, penuh dengan ungkapan lambang-lambang pemberontakkan walau sebenarnya saat itu Chairil menangis,” ujar Damiri, Selasa (1/5). Jika pengkaji sajak Chairil menafsir pemberontakkan itu adalah melawan kekuasaan fasis Jepang atau Belanda, mungkin karena si pengkaji mengaitkan dengan situasi revolusiner saat sajak itu tercipta. Damiri mengakui, puisi itu multitafsir, ambigu, namun jangan sampai menggelikan, terutama saat sebuah sajak dideklamasikan.
Bukan Sekadar Teks
Menurut Damiri, kerap tafsir yang dilakukan para empu sastra atau sastrawan ternama, termasuk kritikus asing, ditelan bulat seniman lain. Baginya, karya sastra merupakan bagian atau pernyataan jiwa penyairnya. Karena itu menelaah pribadi penyair menjadi penting, termasuk jiwa raganya, kehidupannya, dan tata nilai zaman saat penyair itu mencipta.
Membaca sajak Chairil, tak boleh terpaku pada teks dan alpa mengaitkan konteks diri si penyair maupun tradisi yang memengaruhi gaya hidupnya. Bagi Damiri, kebudayaan Melayu Medan tempat Chairil hidup dan dewasa sangat memengaruhi sikap berkeseniannya. Apalagi, dalam suratnya kepada Jassin, Chairil mengakui sendiri kepenyairannya telah penuh sejak ia berusia 15 tahun. Usia ketika ia masih tumbuh di Medan. ”Seluruh hasrat dan minatku sedari umur 15 tahun tertuju ke titik satu saja, kesenian,” tulis Chairil dalam kartu pos bertanggal 8 Maret 1944 itu. (Tempo, 15 Agustus 2026).
Menurut Damiri, “Karakter Melayu Medan dalam puisi Chairil Anwar itu, 90 persen itu kata-katanya berasal dari bahasa Melayu Medan, sisanya dari Inggris dan Belanda.” Ia mencontohkan penggunaan kata hambus pada larik sajak Perhitungan: Sudah itu berlepasan dengan sedikit heran/ Hambus kau aku tak peduli, ke Bandung, ke Sukabumi….!
Hambus artinya enyah kau. Namun karena banyak pengkaji Chairil tidak faham dengan kosa kata hambus, ada yang mengganti dengan kata hembus. Tentu saja artinya sangat berbeda. Selain itu, ada kata ”menginyam”, ”menjengkau”, ”mereksmi”, ”sintuh”, ”mengelucak”, ”kupak”, ”sekali tetak”, ”bermuka-muka”, ”secepuh”, dan ”remang miang”. ”Chairil secara bersung-sungguh menggoreskan kata, idiom dan simbol yang berasal dari kebudayaan Melayu dalam sebagian besar sajaknya,” ujar Damiri.
Karakter bahasa Melayu Medan adalah karakter pantai yang egaliter, terbuka. Berbeda dengan Amir Hamzah yang bertutur dengan bahasa Melayu agak tinggi. Saat bahasa percakapan ala Melayu Medan yang egaliter, terbuka, cenderung kasar, masuk dalam sajak-sajaknya, banyak sastrawan dan pengkaji Chairil terkaget-kaget.
Maklum, masyarakat sastra sebelumnya terbiasa dengan bahasa dan sastra gaya Pujangga Baru yang santun. Saat Chairil menulis: “Tolol, mampus kau dikoyak-koyak sepi,” banyak yang tak bisa terima.Diksi Chairil dianggap tidak sopan. Chairil bahkan sempat dicap sebagai perusak bahasa.
Goenawan Mohamad bahkan pernah menyebut bahwa Chairil adalah penyair tanpa tradisi. Atau ia adalah seorang penyair yang tradisinya hanyalah kesastraan Chairil Anwar: karena itulah yang diturutinya sebagai puisi sejak pertama kali.
Namun bagi Damiri, Chairil bukanlah si Anak Hilang atau si Malin Kundang. Ia tidak membutakan matanya dan menulikan telinganya terhadap bahasa yang membentuk dan membesarkannya. Bahkan Chairil secara mengejutkan mampu mengangkat, mengetengahkan, memodifikasi, memperbaharui bahasa budayanya itu, Melayu, lebih dari penyair mana pun, sekalipun Amir Hamzah.
Namun ini pula yang kerap diabaikan para empu sastra. Mereka tak mau bertungkus lumus belajar genre bahasa yang lahir dari rahim sebuah budaya yang telah menghidupi sikap kesenimanan seorang Chairil. (J Anto)