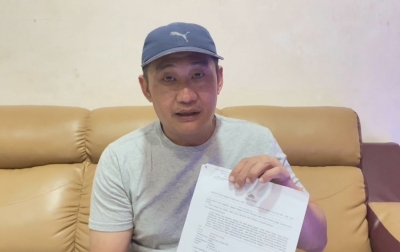Oleh: Marina Novianti
“SIAPA namamu?”
“Kenapa kau tanyakan lagi, Ito?”
“Sebutkanlah. Aku suka mendengarmu menyebutkan namamu. Sebutlah lagi.”
“Boasa? Kenapa kau suka? Kau kan sudah hapal namaku. Dalam tidurmu semalam pun, kau panggil-panggil aku. Padahal aku di sebelahmu.”
“Ah. Sudahlah. Sebutkanlah. Tak pernah cukup bagiku mendengarnya sekali, dua kali, berapa kali pun!”
Bola matamu sarat kegemasan, ketaksabaran, tumpah gelegak cinta. Untukku, semoga hanya untukku! Aku benar-benar rindu mendengarmu bercerita tentang namamu, Pareme. Lekat-lekat kutatap matamu, tak sabar menantikan cericit burung sawah yang melantun dari bibirmu. Di sini, di hutan Sabulan ini.
“Baiklah. Aku Si Boru Pareme. Ompung doliku langit. Ompung boruku mentari. Amangku angin. Inangku bumi. Aku ilalang. Batangku menari bersama angin. Akarku menyusu pada bumi. Kau, Saribu Raja, kau belalang. Melompat-lompat kau kelilingi aku. Kau gerigiti seludangku, hingga meliuk kegelian. Hijaumu, hijauku, bersatu oleh pendar sinar ompung kita.”
Lirihmu bukan hanya membuatku merinding. Seluruh rambutmu turut meliuk, seolah menjelma jadi ilalang, seperti yang kau ceritakan. Pareme, Pareme! Saribu Raja namaku, seribu rasaku untukmu.
Bahkan dengan perutmu yang membuncit oleh kandungan delapan bulan, kecantikanmu semakin perempuan. Kau memancarkan sinar kehidupan dua insan, dagumu tengadah menantang siulan bambu berduri dan kerlip mata binatang buas di sekitar kita.
Sejak kita tumbuh besar bersama, sudah kusadari, kau adalah separuh tondiku. Bukan hanya karena kita silinduat marporhas. Bukan karena aroma keringatmu saat menumbuk beras. Bukan liuk tubuh liatmu manortor dengan iringan gondang. Bukan lengking nyanyian burung sawahmu saat bersembah pada leluhur kita. Bukan!
Dagu keras kepalamu itulah yang selalu membuatku terpesona. Hitam bola matamu yang melebar saat kau menginginkan sesuatu; dan memang, cepat atau lambat, pasti kau dapatkan.
Kau, Pareme, selalu membuatku menoleh dua kali padamu setiap kali hendak membuat keputusan. Bahkan saat aku dan serulingku menaikkan somba-somba untuk Ompung Debata Mula Jadi na Bolon, suara Ompung berbisik di telingaku, ”Mainkan yang bagus! Jangan berhenti bersuling sebelum dagu Pareme ikut terangkat ke langit.”
Ingatkah kau malam saat bapak kita Guru Tatea Bulan marah, karena kau ketahuan bermain-main dengan si Homang?
Dalam gelap, diam-diam kujilati butir air mata yang lolos dari pelupuk mata. Sekeras apapun kupaksa agar tak menangisimu. Saat tubuhmu terlempar ke rumput, rambut panjangmu terurai menutupi dagu kayumu, aku tak tahan lagi. Kubawa serulingku berlari menjauh, ke puncak Pusuk Buhit. Di sana, kutiup segenap amarah menuju bintang-bintang. Dalam klimaks, seruling kulemparkan ke langit, kuhunjamkan pada bulan, sambil berteriak.
”Untuk apa lagi aku berseruling? Siapa yang hendak kumanterai agar mengangkat dagunya padamu, Ompung? Sudah tertunduk dia! Dagu bercahaya itu, kini merapat pada dada berisi luka! Oooi!”
“Ambil serulingmu.” Suara Ompung Mula Jadi na Bolon menggelegar di pendengaranku.
“Ambil serulingmu, jaga baik-baik. Bukan hanya lagu yang terlantun darinya. Nada-nada serulingmu memanggil roh kekuatan dan penghiburan dari langit nomor tujuh. Ibotomu Si Boru Pareme adalah kecintaan semua penghuni langit. Bila dia bergembira, pintu-pintu langit berderak terbuka menumpahkan pasu-pasu bagi tanahmu.”
Pareme, selama ini kau selalu jadi penentu arah langkah, pilihan keputusanku. Malam itu di puncak Pusuk Buhit, aku tersadar: hati dan mata Ompung Mula Jadi na Bolon pun tercondong padamu, Ito!
Ketika Bapak kembali mengamuk, meraung pada langit mengutuki perutmu yang membuncit, mana sanggup hatiku melihatmu hancur? Mana sampai tondiku membiarkanmu menanggung amarah Bapak sendirian?
Waktu Bapak menjambak rambut panjangmu yang kusut masai. Waktu Bapak menampari wajah piasmu yang sembab. Waktu piso gaja dompak Bapak tinggal sejengkal lagi dari perutmu. Apa yang bisa kuperbuat, selain melompat dan melindungimu?
“Unang sai muruk ho, Bapa! Unang tu boru mi. Tu ahu baen, Bapa. Ahu do i. Ahu do i!”
Angin tertegun di langit Sianjur Mula-mula. Ujung piso Bapak membeku tepat di kulit wajahku. Perlahan asin darah dari kulit yang terbelah sayatan piso, mengisi sudut bibir pecahku. Pertanda aku belum mati ditusuk Bapak.
Hal pertama yang kulihat adalah kelam mata Bapak menombak jiwaku dalam-dalam. Suara pertama yang kudengar adalah sedu-sedanmu, Pareme. Hanya suara itu yang terus terngiang di kupingku. Pun saat kita berdua terseok digiring mereka yang diperintah Bapak membinasakan kita, dua pendosa. Ketika mereka akhirnya memilih tidak membunuh kita. Abang dan kakak kandung mereka. Ketika mereka meninggalkan kita setengah telanjang di tengah hutan Sabulan. Dengan membawa ulos kita yang mereka lumuri darah kambing, sensasi pertama yang akhirnya terasa oleh inderaku adalah dingin. Dingin yang menusuk hingga jantung.
Kita dibuang, Pareme. Kau, Boru ni Raja, si Rumondang Bulan, dibuang ke pelosok Sabulan. Kita dibuang, seperti abang tertua kita Si Raja Uti. Abang dibuang karena tubuhnya dianggap cacat di mata halak sahuta kita.
Kita, dibuang karena tondi kita dianggap cacat oleh mereka. Aku tahu, Ito, selama kita masih bersama. Kau dan bayi dalam kandunganmu tak akan pernah bisa hidup tenang. Karena aib yang mereka pasangkan pada kita, akan terus hidup di hati mereka. Selama mereka melihat kedua wajah kita yang serupa; karena kau memang kembaranku, itoku. Apa yang harus kulakukan, untuk menjamin kau dan anakmu, hidup? Apa menurutmu?
Karena ketika Si Raja Uti datang dalam wujud babiat telpang, seketika aku sadar. Kau dan anakmu akan dijaganya. Abang kita tahu caranya melindungimu dari segala makhluk di Sabulan.
Anak kita akan belajar cara bertarung monsak seperti harimau darinya. Aku, hasian? Aku hanya membuat hidupmu terpapar bahaya. Semua yang melihat kita bersama akan teringat amarah Bapak. Bahkan anakmu yang masih dalam kandungan, takkan pernah menganggapku sebagai bapaknya. Karena aku memang bukan.
Dia akan memandangku sebagai laki-laki yang telah menyusahkan hidup kalian berdua. Jadi, Pareme, apa lagi yang bisa kuperbuat, selain meninggalkanmu di tengah Sabulan, dalam penjagaan Babiat Telpang?
Tiga saja permintaanku, Ito. Pertama, namai anakmu Si Raja Lontung. Padanya bermuara angin dari seluruh penjuru, bahkan lebih. Bukan delapan, tapi sembilan. Kedua, simpanlah cincin peninggalan keluarga kita, yang sempat kubawa dari peti penyimpanan bapak kita Guru Tatea Bulan.
Berikan pada Si Lontung saat dia dewasa nanti. Cincin ini akan memberinya petunjuk tentang istrinya. Ketiga, Pareme, kuatlah. Kau perempuan, ibu dari si sia sada ina. Walau cadas jalanmu, walau marsak jiwamu, ketahuilah: ompung kita Mula Jadi na Bolon takkan pernah mengizinkan sembilan marga dilahirkan rahim biasa. Kau perempuan pilihan, Pareme.
Sabulan tak pernah seindah saat kau hidup di dalamnya. Sianjur Mula-mula padam cahayanya sejak jejak kaki rusamu terhapus di sana. Seluruh tano na uli ini, hidup mengada dari tetesan air mata, peluh dan darahmu, kembar dampitku.
Aku, Si Saribu Raja, terlahir pengembara. Aku dan serulingku, punya janji dengan Debata: menceritakan kisah mula-mula pada dunia. Sesekali, saat purnama, pandanglah ke langit utara, sendengkanlah telinga. Di sana akan kau lihat dukaku tergantung. Akan kau dengar alunan andung-andung. Untukmu, hanya untukmu, perempuan berdagu kayu.
MN, Juni 2018
Keterangan:
Ito = panggilan untuk lawan jenis yang sebaya atau bersaudara
Boasa = mengapa
Ompung doli = kakek
Ompung boru = nenek
Amang = bapak
Inang = ibu
Tondi = jiwa
Silinduat marporhas = kembar dengan jenis kelamin berbeda
Manortor = menari
Somba-somba = kidung puji-pujian untuk leluhur
Unang sai muruk ho, Bapak! Unang tu boru mi. Tu ahu baen, Bapak. Ahu do i. Ahu do i! =
Jangan kau marah, Bapak. Jangan marah pada anak perempuanmu. Marahlah padaku, Bapak, Aku yang salah. Aku yang salah!
Piso gaja dompak = senjata khas Batak bergagang bentuk gajah, dianggap sakral dan hanya digunakan mereka yang memiliki kemampuan sakti
Rumondang Bulan = bulan yang bersinar terang
Halak sahuta = sanak saudara sekampung
Babiat telpang = harimau pincang
Monsak = ilmu bertarung khas Batak
Si sia sada ina = Ibu yang satu memperanakkan sembilan orang
Marsak = kesedihan mendalam
Tano na uli = tanah yang indah
Andung-andung = kidung ratapan