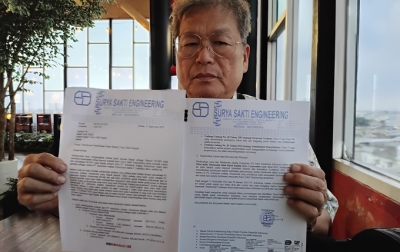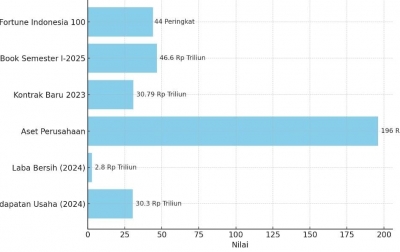Oleh: Nevatuhella.
Sekolah hingga petang merupakan jawaban atas keluhan guru yang menyatakan tidak berhasilnya pendidikan maksimum membentuk karakter siswa yang mumpuni, ternyata lebih banyak berdampak negatif ketimbang positif. Terjadi berbagai anomali. Misal yang sederhana, tapi menyangkut syariah agama. Bukankah di sekolah-sekolah menengah pertama atau atas fasilitas untuk mandi siswa tidak ada. Misalnya seorang siswa yang sudah seharusnya bersih dari haidnya (melaksanakan mandi wajib) pada siang hari, seyogianya sudah bisa melaksanakan salat asar, namun sang siswa tidak mendapat kesempatan ini. Berapa ratus ribu siswa perempuan yang menerima keadaan ini.
Selama ini memang tidak terpikirkan oleh pendidik, guru serta pengambil kebijakan perihal ini. Apalagi yang terjadi di sekolah mayoritas siswa Islam atau sekolah madrasah. Ini anomali, secepatnya harus diatasi. Sekolahlah dengan cara konvensional. Jam setengah dua, sekolah telah bubar, siswa secepatnya sampai di rumah. Bersosialisasi di rumah dan lingkungannya. Karena para pakar pendidikan sudah terlalu banyak mengatakan bahwa pendidikan kita tidak menyentuh realitas. Ini salah satu contohnya.
Anehnya para guru seringkali ikut memperkeruh suasana dengan berapologi bahwa lemahnya moralitas bangsa terjadi akibat kurangnya jam pelajaran yang yang diterima peserta didik. Tidak sedikit dari mereka secara gegabah mengasumsikan bahwa satu-satunya obat mujarab bagi persoalan defisit moralitas adalah dengan cara menambah dosis pelajaran tentang moral kepada peserta didik. Sebuah apologi yang kurang bijak. (Masdar Hilmy, “Pendidikan Berparadigma Induktif”, Kompas (17/12/2018).
Anamoli lainnya, adalah siswa selalu bau keringat alias sudah tak bersih lagi tubuh dan pakaiannya, karena terlalu lama di kelas, pada siang hari pula. Sering di kendaraan umum, siswa yang pulang di jam lima atau setengah enam sore, mereka mengeluarkan bau sangat tak sedap. Bisa dibayangkan mereka sejak jam enam pagi sudah memakai seragamnya sampai jam lima atau jam enam sore. Sudah sedikitnya tiga kali buang air kecil, sebab kalau dalam waktu 10 atau 11 jam orang dewasa atau katakanlah remaja hanya satu kali buang air kecil, adalah hal yang tidak sehat. Sementara kita mengetahui fasilitas air di sekolah-sekolah sangat minum, termasuk juga kebersihannya. Sekali lagi saya sebutkan, maka secepatnya sekolah mengambalikan jam akhir belajar mengajar pada tengah hari. Siswa tak perlu membawa bekal makanan ke sekolah. Selain membebani tas siswa yang sudah berat oleh buku-buku teks yang ampun-ampun tebalnya.
Anomali yang paling parah, apa yang diajarkan kepada anak didik di sekolah tidak menyentuh realitas dimasyarakat. Siswa gemar bercakap-cakap di ruang publik dengan suara keras dan ucapan-ucapan yang menor dan tak menunjukkan kepribadian yang baik sebagai seorang siswa. Selalu mereka menceritakan hal-hal sepele dan cerita-cerita pribadi yang norak dan memuakkan. Pokoknya tata tertib mereka di ruang-ruang publik, bahkan di kendaraan umum sudah tersesat ke jalan yang negatif.
Kalaupun mereka duduk manis di ruang-ruang publik, maka interaksi sosial pada sekitar tidak terjadi. Mereka lebih tertarik melototi ponsel cerdasnya. Kalau menurut rating siswa Indonesia membaca di ponsel, dan apa yang dibacanya adalah pengetahuan, maka betapa sudah pintar-pintar dan cerdasnya siswa kita. Tapi nyatanya melalui ponsel cerdas itu, mereka memilih hal-hal sepele. Berchating ria dengan teman. Membaca kabar mutakhir artis dan lelucon-lelucon yang miris yang mematahkan kesungguhan.
Paradigma Baru
Sistem pendidikan kita memang tak menyentuh relitas. Guru memang mengajarkan pengetahuan yang benar. Misalnya mencuri atau berbohong adalah dilarang oleh agama. Dilarang juga oleh negara, dan diancam hukuman. Tetapi otak kebanyakan siswa tidak seratus persen memegang pengetahuan kognitif ini. Mereka dengan mudah bisa mencuri atau berbohong. Pertama oleh unsur adanya guru atau lingkungan hidup mereka yang suka mencuri dan berbohong. Penguasa mereka lihat mencuri (korupsi), pejabat publik suka berbohong, angka-angka statistik berakrobat. Tak usahlah kita melirik dunia perpolitikan kita yang sudah amat busuk. Guru menyelingkuhkan pengetahuan atau ilmu. Di ujian-ujian nasional anak-anak yang mengikuti ujian diberi jawaban. Bahkan ada siswa yang harus membayar lewat joki dalam ujian masuk perguruan tinggi. Sistem pendidikan kita saat ini benar-benar brengsek.
Kesadaran afektis (teknis) siswa tak bisa terealisasi akibat kendala ini. Mereka telah diselungkupi budaya demikian. Bayangan mereka toh setinggi-tinggi bersekolah, mau bekerja harus menyogok juga. Untuk apa harus capek-capek belajar. Entah wilayah kehidupan mana lagi bisa dijamah oleh kebenaran dan nilai hakiki dari pendidikan kita dan hasilnya.
Ada saya temui seorang siswa pesantren yang tak bisa betah hidup di Jakarta. Di dalam bus, ia melihat perempuan membuka aurat. Makanan pun tidak terjamin kehalalannya, maka ia menarik diri pulang kembali ke wilayah pesantren. Kehidupannya di pesantren dan lingkungan tempat tinggalnya yang bisa merealisasikan pengetahuan kognitifnya. Ia bisa masak sendiri, yang berarti kehalalan mankanannya terjamin. Ia bisa salat di mesjid setiap hari berjamaah, dia bisa membaca buku di kamar dengan santai, sampai ia bisa bersilaturahmi dengan tetangga dan kerabat dekatnya. Ia bisa bertani atau beternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Ini hanya salah satu contoh kecil dalam masyarakat kita. Sebabnya menurut John Dewey dalam bukunya Experience and Education (1938) menyebutkan bahwa inti dari pendidikan adalah mengalami. Maka oleh sebab itu, pengalaman sehari-hari adalah salah satu laboratorium dalam pendidikan. Barangkali guru bisa melakukan berbagai uji nilai kognitif siswa, berurutan dengan nilai afektif. Guru bisa memberikan sejumlah uang pada siswa dengan berbagai alasan. Dari seratus orang siswa berapa orang yang jujur. Berapa orang yang berkilah dengan uang tersebut.
Mengukur parameter keberhasilan pendidikan saat ini dapat dilihat dari kejahatan moral yang kini berkelindan di sekitar kita. Masalah narkoba yang tak tuntas-tuntas belakangan ini. Sesudah tiga presiden berganti. Malah narkoba makin merajalela. Bukan saja mengenai (anak-anak) orang-orang kaya, berjabatan, tetapi merasuk ke kehidupan orang-orang miskin. Produk pendidikan macam apa ini? Lain lagi korupsi yang sudah menggurita. Pendidikan secara revolusioner sudah selayaknya beraksi memangkas ini semua. Apa yang direncanakan dalam pendidikan, baik kurikulum dan aksi lainnya, selalu teramat dangkal saat ini. Berbeda dengan masa-masa jaya belajar berhitung dan aljabar dulu. Siswa dan lulusannya bermental jujur dan mengetahui nilai hitam putih, benar salah menurut ukuran yang benar (agama).
Saat ini revolusi mental harus dilakukan dan digemakan, tidak sekadar sebagai penghias bibir belaka. Nilai-nilai agama ditegakkan. Moral Pancasila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pendidkan berbasis keadilan dan kesenangan. Jangan siswa dibebani dengan sepuluh hingga lima belas mata pelajaran dalam satu semester. Ulang kembali pelajaran eksak yang memberatkan. Penemuan Rektor Universitas Syah Kuala Syamsul Rizal bisa jadi cerminan (“Masa Depan Indonesia 2045”, Kompas, 21/9/2016). Ditemukannya 75 persen siswa lulusan SMA tidak punya kompetensi untuk lulus SD. Ia telah mengetes hitungan pecahan sederhana untuk mereka, hanya 10 dari 40 siswa lulusan yang mampu mengerjakan. Untuk tes mencari akar persamaan kuadarat yang sangat sederhana, yakni persamaan x2-7x+12=0, bahkan hanya 2 siswa yang menjawab dengan benar.
Membanding hal itu, betapa ngawur kita melaksankan ujian nasional setiap tahunnya. Dengan biaya melambung. Soal-soal yang diajukan bahkan sang guru pun tak sanggup mengerjakan dalam waktu yang disediakan. Lapak pembohongan yang memojokkan para guru ke lembah nista. Dominasi pemikiran positivistik, yang melahirkan pola masyarakat yang materialistik dan kapitalistik, inilah paradigma pendidikan selama ini. Kembalilah ke khittah pendidikan yang berhulu pada moral dan berakhir di rasa keadilan. ***
*Penulis adalah esais, pengamat kebijakan publik.