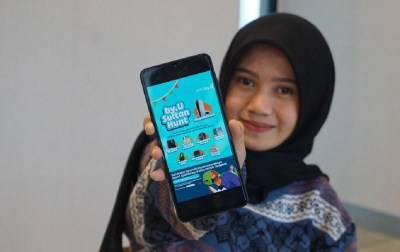Oleh: Januari Sihotang, S.H.,LL.M.
MASA bakti DPR periode 2014-2019 telah berakhir. Berbagai catatan dan kritik perlu dialamatkan atas kinerja mereka. Sebagaimana ketentuan konstitusi, alat ukur kinerja DPR tentu harus sesuai dengan tiga fungsi utama yang mereka lakukan, yakni fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan.
Terkait fungsi legislasi yang sering dianggap sebagai fungsi utama DPR, lembaga terhormat ini ternyata memulai sekaligus mengakhirinya dengan cerita yang kurang mengesankan. Di awal masa kerja mereka, DPR berhasil mengutak-atik UU MD3 hanya demi perebutan kursi pimpinan DPR. Partai pemenang pemilu yang selalu diberikan ‘hadiah’ menempati posisi Ketua DPR, berubah menjadi dipilih melalui suara terbanyak. Akhirnya sangat ironis, PDIP yang memenangi pemilu 2014 justru tidak mendapatkan satu posisi pimpinan pun, baik di DPR maupun MPR. Mudah dibaca, hal tersebut dilatarbelakangi pertarungan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang begitu sengit sebelum dan pasca Pilpres 2014.
Tidak hanya itu, akibat tawar menawar kepentingan yang begitu kental, fungsi legislasi DPR pun baru berjalan normal sekitar 4 (empat) bulan setelah pelantikan. Sederet catatan buruk itupun seakan terus mengiringi perjalanan fungsi legislasi DPR hingga lima tahun selanjutnya. Dari 189 RUU yang tercantum dalam Prolegnas, ternyata hanya 40 UU yang mampu dituntaskan. Bahkan 14 diantaranya adalah UU yang berada di luar Prolegnas.
Ironisnya, kinerja DPR mendadak berubah di akhir periodenya. Bahkan tidak berlebihan jika disebut sebagai anomali.. Beberapa UU yang sangat vital keberadaannya justru dikebut dan tuntas hanya dalam hitungan hari. Sebut saja salah satu contohnya UU KPK. Secara ilmu perundang-undangan, UU ini dianggap bermasalah baik secara formil maupun materil.
Dianggap sebagai upaya melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi, persetujuan RUU KPK mendapat penolakan yang sangat masif dari berbagai elemen masyarakat, baik mahasiswa, akademisi dan civil society pemberantasan korupsi. Mulai dari talkshow di media, opini di surat kabar hingga demonstrasi besar-besaran semakin memperlihatkan betapa sengitnya diskursus yang terjadi. Anehnya, DPR dan Presiden begitu mesra dan dengan suara bulat menyetujui UU KPK tersebut. Perlu diketahui, sepanjang 2019-2024, inilah proses tercepat pembentukan UU yang dilakukan Presiden dan DPR.
Aspirasi Publik
Fakta empiris ini menggelitik logika penulis. Seironis itukah disparitas antara gagasan aspirasi publik dengan implementasi dan rumusan wakil rakyat di parlemen? Bukankah wakil rakyat itu seyogyanya menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya? Apa gunanya masa reses dan dana aspirasi yang begitu banyak digelontorkan jika tidak mampu dirumuskan dalam sebuah UU yang baik? Realitas ini membuktikan, suara-suara rakyat itu seperti mendengung dan terbentur lalu menguap begitu saja di dinding tebing curam.
Melihat komposisi dan latar belakang anggota DPR 2019-2024, maka sepertinya publik tidak perlu berharap terlalu banyak. Tanpa bermaksud berburuk sangka, publik perlu mempersiapkan diri lebih dini menghadapi anomali dan ironisme yang mungkin saja akan dipertontonkan oleh anggota DPR yang baru.
Dana besar untuk penyelenggaraan pemilu seharusnya berbuah manis untuk rakyat. Dinamika perbaikan desain pemilu yang dilakukan terus-menerus tidak ada gunanya jika wakil rakyat yang dihasilkan tidak semakin berkualitas. Hubungan antara rakyat dan wakilnya perlu ditata kembali. Alasannya sederhana, agar wakil rakyat tidak menjadi kacang yang lupa akan kulitnya. Pengawasan publik sangat penting untuk diperkuat dan diinstitusionalisasi.
Dalam teori, pengawasan hanya akan berhasil jika memenuhi dua hal. Pertama, pengawas memiliki bargaining position dalam melakukan pengawasan. Dan kedua, hasil pengawasan tidak menguap begitu saja. Namun, harus didesain adanya tindak lanjut akibat dari pengawasan tersebut. Denga kata lain, perlu adanya sanksi yang diberikan jika yang diawasi tidak berjalan sesuai koridor yang sudah disepakati.
Dalam sistem ketatanegaraan kita, hubungan antara wakil rakyat dan rakyat seolah-olah selesai seiring dengan berakhirnya pemilu. Setelah itu, hubungan dengan konstituen terputus dan akan dijalin kembali menjelang pemilu berikutnya. Wakil rakyat justru menjadi ‘hamba partai politik’ yang mencalonkannya. Praktik demikian menyebabkan wakil rakyat lebih mendengar arahan parpol daripada aspirasi publik. Hal ini bisa terjadi karena parpol memiliki kewenangan penuh atas masa depan si wakil rakyat di parlemen, sedangkan publik hanya mampu berteriak tanpa memiliki daya eksekusi.
Constituent Recall
Jika membaca ketentuan Pasal 22B UUD NRI Tahun 1945, ditegaskan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat dan ketentuannya diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya, ketentuan tersebut diperinci dalam UU MD3 dan UU Parpol, dimana pemberhentian anggota DPR disebut sebagai Penggantian ANtar Waktu (PAW).
PAW hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: meninggal dunia; mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan. Untuk dapat diberhentikan sebagai anggota DPRD terdapat beberapa kriteria yaitu: tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD; dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD; melanggar larangan rangkap jabatan; dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.
Ketentuan tersebut menegaskan betapa kuatnya otoritas parpol terhadap setiap wakil rakyat di parlemen. Di sisi lain, publik seolah tidak memiliki posisi tawar apapun terhadap para wakil yang dipilihnya. Untuk menjamin agar setiap anggota DPR tetap berada di jalur yang sesuai dengan harapan rakyat, maka constituent recall sangat mendesak didesain dalam sistem ketatanegaraan kita. Hal ini tidak terlepas dari logika demokrasi yang sesungguhnya, bahwa setiap anggota DPR adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Dengan demikian, setiap anggota DPR akan menyuarakan aspirasi rakyat dan tidak terbelenggu oleh partai politik.
Constituent recall juga diyakini akan mendorong rakyat lebih aktif mempelajari kebijakan-kebijakan negara. Tingkat akuntabilitas yang tinggi akibat penerapan constituent recall tersebut, kemudian dapat mendorong para wakil rakyat untuk meningkatkan kinerjanya dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya akan diterapkan pada masyarakat. ***
Penulis adalah dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.