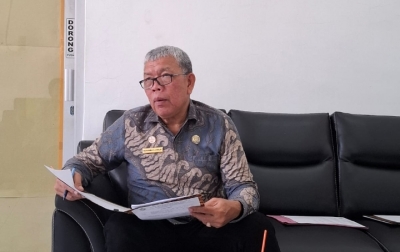Oleh: Alkaushar Lingga
Setiap hari kata radikalisme selalu berkumandang baik di televisi serta media cetak. Sepertinya kata radikalisme ini menjadi populer belakangan ini. Kata radikalisme menjadi buah bibir tatkala sesuatu peristiwa kekerasan terjadi. Ataupun ketika diduga ada sekelompok orang yang paham jihad kata radikalisme pasti turut serta diucapkan. Belakangan Menteri Agama yang masih diragukan kapabilitasnya juga mengucapkan kata radikalisme dalam mengomentari sesuatu hal.
Jikalau dibuat perbandingan dalam kebahasaan radikalisme ini menjadi ‘artis dadakan’ dalam kalimat-kalimat pejabat negara menghiasi wawancara. Kenapa dikatakan kalimat pejabat negara karena para pemangku kebijakan tersebut yang menghadirkan istilah ini dan akhirnya digunakan oleh banyak orang. Istilah ini disebut sebagai artis dadakan karena begitu populer, menjadi sering disebut dan topik pembicaraan hangat. Media pun turut menuliskan kata radikalisme ini di media berita atau mengucapkan di media televisi.
Banyak juga pengamat serta pejabat publik dengan percaya diri membicarakan tentang radikalisme dan membahas seluk beluk radikalisme. Bak pengamat yang selalu ingin tenar di media massa ataupun layar kaca menerangkan bagaimana bahaya radikalisme. Lalu ada juga ikut-ikutan pegiat media sosial ingin terkenal membahas radikalisme ini. Keinginan terkenal dan sikap narsis yang tinggi membuat lupa diri tentang istilah kata yang dibicarakan. Terpenting dia diwawancarai media dan dipuji padahal secara terminologi tidak tahu apa itu radikalisme.
Kata radikalisme ini selalu dikaitkan dengan kejadian atau pelaku terorisme merugikan banyak manusia bahkan manusia yang tidak bersalah. Pemerintah dalam siaran pers selalu menekankan bahwa tindakan teror ialah perilaku radikalisme. Dan siapapun yang terpapar radikalisme harus disadarkan dan kembali kepada Pancasila. Bahkan beberapa institut mengadakan penelitian siapa saja terpapar paham radikalisme termasuk khatib masjid dan ASN. Di era Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu merilis beberapa kampus telah terpapar paham radikalisme.
Pertanyaannya apakah setiap perbuatan teror adalah radikalisme? Apakah tindakan paham anarkistis dapat disematkan kepadanya istilah radikalisme ini? Apalagi setiap tindakan teror selalu dikaitkan dengan agama tertentu, padahal belum tentu benar. Menarik memang bila ada diajukan pertanyaan ini kepada yang menyebut istilah radikalisme di mas media. Mungkin saja seorang menyebut kata radikalisme tidak memahami secara radikal apa makna kata radikalisme yang populer belakangan ini. Kata ini dipakai hanya untuk terkenal agar mudah menyihir para pendengar di tanah air.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2013:1129-1130) menerangkan, radikal ialah berpikir secara mendasar sampai kepada hal yang prinsip, amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan) serta maju dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang meginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis serta sikap ekstrim dalam aliran politik.
Dalam bahasa secara semantik dapat kita maknai apa pengertian radikal pada isi KBBI. Bahwa pengertian radikal ialah cara memahami sesuatu hal dengan penuh prinsip-prinsip, dimaksud secara keras yaitu sacara mendalam atau bekerja keras memahami dan menginginkan perubahan yang baru. Perubahan yang dimaksudkan tentu perubahan yang baik karena berlandaskan pada prinsip-prinsip. Di mana prinsip ini bagian karakter yang positif yang dimiliki manusia dalam kehidupan dan bukan sebaliknya. Bahwa berpikir radikal sama halnya dengan berpikir secara kritis atau mengkritisi sesuatu hal.
Selanjutnya, pengertian radikalisme yang diuraikan dalam KBBI, adalah suatu paham atau perilaku dilakukan dengan prinsip-prinsip pikiran yang mendalam pada lingkup sosial dan politik dan menginginkan pembaharuan atau kemajuan dengan sikap yang tegas bahkan bila perlu kekerasan dalam aliran berpolitik. Keinginan perubahan dalam lingkup sosial dan politik bila perlu sampai melakukan cara kekerasan agar dapat mewujudkannya. Tetapi tidak seutuhnya cara kekerasan itu dilakukan, namun secara drastis artinya secepatnya pembaharuan itu diwujudkan. Jadi, jikalau pembaharuan dilakukan dengan efektif, maka kekerasan itu tidak perlu.
Pengertian yang disebutkan di atas adakah radikalisme diartikan atau dikaitkan dengan lingkup agama? Apakah pengertian radikalisme ada menyebut tindakan teror atau perilaku terosisme? Kata kekerasan memang disebutkan, lalu apakah setiap tindakan kekerasan semuanya disebut radikalisme? Misal ketika mahasiswa demo secara keras menginginkan perubahan, pembaharuan dan kemajuan dalam negara bahkan demonstrasi hingga melakukan kekerasan. Apakah tindakan mahasiswa yang secara keras merusak pagar, gedung, bakar mobil dan bentrok dengan aparat juga disebut radikalisme?
Tampaknya kita harus berpikir secara radikal untuk menjawab pertanyaan di atas. Kalau tidak negara ini akan diurus oleh mereka yang amatiran. Sebab defenisi tentang sesuatu hal saja tidak tepat menggunakan istilah. Hal ini dapat memicu bahaya yang lebih luas dan seluruh rakyat Indonesia dapat terdampak efek negatifnya. Karena salah mengistilahkan sesuatu menjadi komunikasi yang tidak efektif. Sehingga rakyat menjadi kebingungan karena hanya termakan informasi keliru.
Konsep filsafat menyebutkan bahwa untuk memahami sesuatu hal harus bersifat dan berpikir radikal. Dengan mengajukan pertanyaan mendasar apa, mengapa dan bagaimana mengupas sesuatu hal itu dalam mendapatkan informasi hingga ke akar-akarnya. Sampai pada pertanyaan serta jawaban menyimpulkan secara rinci. Contoh, mengapa perlu belajar dan sekolah? Bagaimana jika belajar di rumah saja diajari orang tua? Apakah setiap manusia harus belajar? Mengapa belajar harus diajari oleh guru? Mengapa murid bodoh disalahkan gurunya? Mengapa murid pintar dipuji orang tuanya? Mengapa belajar harus ada kurikulum, RPP, silabus dan buku ajar? Mengapa belajar butuh referensi? Dan banyak pertanyaan kritis lainnya berlandaskan prinsip.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut ialah pikiran secara radikal dalam memahami atau ingin mengetahui sesuatu hal. Jikalau ada yang bertanya seperti di atas lalu dianggap membahayakan keamanan tentu respon tersebut berlebihan sekali. Atau jika ada yang giat belajar dan berlatih secara keras hingga waktu bertahun-tahun disebut perilaku radikalisme tentu semakin keliru. Setiap kekerasan bukan tentu bersifat radikal sebab ada perilaku kejahatan akibat hal sepele dan awalnya bercanda.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres pernah menyampaikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) bahwa hati-hati menggunakan kata radikalisme. Pada pertemuan di New York pada 2018 lalu PBB mengkritik BNPT karena menggunakan istilah radikalisme terhadap kejadian terorisme.
Sebab penafsiran radikalisme ada bersifat positif dan digunakan secara global di dunia. Setelah pertemuan itu kepala BNPT Suhardi Alius meminta maaf dan mengatakan akan ada kehati-hatian dalam menggunakan istilah radikalisme. Berdasarkan pengertian KBBI, konsep filsafat mengenai radikalisme dan kritik PBB penggunaan kata radikalisme bahwa, istilah ini keliru digunakan mengartikan perilaku terorisme. Apalagi mengaitkan radikalisme serta perilaku terorisme terhadap agama tertentu itu salah besar. Karena tidak ada agama yang mengajarkan pemeluknya untuk berperilaku jahat apalagi terorisme. Agama di dunia ini tidak dihadirkan untuk memproduksi teroris. Jadi kesalahan besar bila menghubungkan agama dengan terosirme. Kesalahan itu terjadi akibat tidak berpikir secara radikal dan membuat istilah yang salah.
Belajar dari kesalahan inilah kita sebagai masyarakat terutama pejabat pemerintah perlu belajar bahasa yang baik dan benar. Pemerintah harus melibatkan pakar bahasa dalam memberi istilah terhadap suatu perilaku masyarakat agar jelas defenisinya. Sehingga jelas maksud dan tujuan. Kekeliruan menggunakan istilah radikalisme ini harus segera dihentikan. Jika tidak, kekeliruan penggunaan istilah radikalisme akan menimbulkan gejolak baru yang buruk. Pepatah klasik mengatakan: salah dalam berbahasa, salah memaknai, maka salah yang dilakukan.***
Penulis alumni UMSU, peneliti bahasa dan sastra.