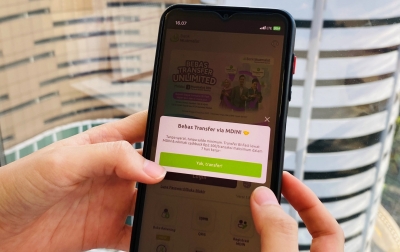Oleh: Januari Sihotang, S.H.,LL.M. Steven Sihombing (21) dan Joni Pernando Silalahi (30) harus meregang nyawa akibat tindakan main hakim sendiri oleh sekelompok massa. Ironisnya, tragedi memilukan ini justru terjadi di kawasan salah satu kampus PTN dan sudah terlebih dahulu ditangani oleh pihak satuan pengamanan (satpam) kampus tersebut.
Dalam penalaran yang wajar, penulis tidak mampu memahami mengapa pihak satpam kampus harus menyerahkan kedua orang tersebut kepada massa. Apakah satpam sudah tidak mampu menangani sendiri permasalahan tersebut?
Bukankah seharusnya kampus sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) jika terjadi dugaan tindak pidana di lingkungan kampus? Penulis meyakini sepenuhnya bahwa SOP keamanan kampus pasti mengedepankan penegakan hukum daripada menyerahkan kepada pengadilan massa.
Berdasarkan video yang viral di media sosial, penulis melihat kedua orang yang diduga mencuri helm tersebut tidak mampu melawan amukan massa yang tak mampu dikendalikan. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan pencurian tersebut, perlu diketahui bahwa tindakan main hakim sendiri bukanlah tindakan tepat dan terpuji dalam menyelesaikan masalah. Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain.
Dalam konteks psikologi kriminal, ada berbagai macam latar belakang mengapa emosi massa begitu liar tidak terkendalikan dalam persitiwa ini. Sangat jamak kita ketahui, bahwa tindakan pencurian begitu sering terjadi di kota Medan, khususnya di kampus dan di wilayah kos-kosan mahasiswa. Orang-orang yang pernah kehilangan sepeda motor atau barang lainnya mungkin saja pernah melapor ke pihak berwajib dan laporan tersebut tidak mendapat tanggapan serius. Akhirnya, ia meluapkan emosinya ketika ada seseorang yang diduga tertangkap tangan melakukan pencurian.
Dengan kata lain, main hakim sendiri terjadi karena masyarakat menganggap hukum tidak berjalan dengan baik sehingga diperlukan alternatif lain untuk menegakkan hukum. Psikologi massa seperti ini menyebabkan tindakan main hakim sendiri semakin sering terjadi di masyarakat.
Padahal, masyarakat seharusnya mengetahui bahwa tindakan main hakim sendiri memiliki akibat hukum yang fatal. Tidak hanya kepada korban amukan massa, tetapi juga kepada pelaku main hakim itu sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus hati-hati melakukan tindakan seperti ini.
Dalam ilmu hukum, tindakan main hakim sendiri sering disebut dengan eigenrichting. Sederhananya dapat diartikan sebagai tindakan melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga berujung kepada kerugian (Sudikno; 2010). Dengan kata lain, main hakim sendiri merupakan upaya menegakkan hukum dengan melawan hukum itu sendiri.
Setidaknya ada 2 (dua) pasal dalam KUHP yang mengatur sanksi bagi para pihak yang melakukan main hakim sendiri. Pasal 170 KUHP misalnya mengatur bahwa “Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
Selanjutnya, tersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh; dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
Hukuman berat kepada pelaku main hakim sendiri semakin ditegaskan dalam Pasal 351 KUHP yang mengatakan bahwa: “(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan; (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun; dan (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
Lalu apakah emosi massa dan ketidakhadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat dijadikan alasan untuk tidak dipidana atas tindakan main hakim sendiri? Hingga saat ini KUHP kita tidak mengatur hal tersebut secara rigid. Lepasnya pertanggungjawaban pidana dalam KUHP hanya karena beberapa hal, misalnya Pasal 44 KUHP yang menentukan sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yakni; (1)Jiwanya cacat dalam tubuhnya.
Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, imbisil, bisu tuli sejak lahir dan lain-lain; (2) Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihinggapi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, hysteria, melankolia, gila dan lain-lain.
Menegakkan Wibawa Hukum
Lalu apa yang harus dilakukan negara agar tindakan main hakim sendiri ini tidak berubah menjadi kebiasaan dalam masyarakat? Dalam beberapa penelitian, ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga penegak hukum merupakan faktor utama terjadinya tindakan main hakim sendiri. Jika diperinci, ketidakpuasan tersebut dapat terjadi karena lamban dan tidak profesionalnya penegak hukum dalam menangani suatu perkara, khususnya perkara pidana. Efek jera yang tidak maksimal terhadap para pelaku tindak pidana juga menyebabkan public distrust terhadap institusi hukum semakin menguat.
Mengutip Lawrence Friedman, hukum akan tegak dan beribawa di mata masyarakat jika ketiga unsur penegakan hukum sama-sama berjalan dengan baik. Substansi hukum (legal substance), aparat penegak hukum (legal structure) dan budaya hukum (legal culture) harus berjalan beriringan. Namun, di atas semua itu, kualitas dan integritas penegak hukum menjadi faktor paling dominan.
Mengutip kata-kata Bernardus Maria Taverne (1874-1944): “Geef me goede rechter, goede rechter commissarisen, goede officieren van justitien, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboeken van strafprocessrecht het geode beruken”. Berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, niscaya aku akan berantas kejahatan meski tanpa undang-undang sekalipun..
Hal ini seiring dengan ungkapan Satjipto Rahardjo (alm), sang begawan hukum progresif Indonesia, bahwa carut-marutnya dunia hukum Indonesia tak lain akibat dari pemahaman hukum yang hanya berkutat pada teks dan peraturan perundang-undangan.
Hukum tidak dibicarakan secara utuh karena dilepaskan dari konteks dan dimensi manusia. Hukum itu bukan sekadar peraturan, tetapi lebih pada perilaku manusia itu sendiri. Apalah artinya peraturan yang bagus dan sempurna jika moral para pelaku dan penegak hukum masih buruk? Oleh karena itu, untuk mengenal betul hukum suatu negara, maka kita harus mengenal kepribadian bangsa itu sendiri. ***
Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan; Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UGM Yogyakarta.