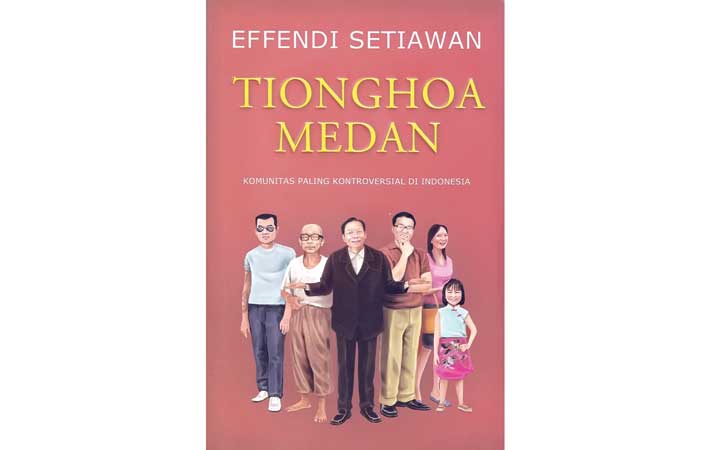
Oleh: Ris Pasha. Kalau kita ke Jakarta, kita akan mudah menemukan mana orang Tionghoa Medan yang biasa dipanggil Cimed. Cimed adalah singkatan China Medan. Walau mereka sudah berganti nama (namanya aneh), namun tetap tidak meninggalkan bahasa Hokkien. Bahasa keseharian di Medan, bahkan di berbagai belahan dunia.
Kenapa kedengaran aneh? Katakan Seseorang bermarga Lim. Dia membuat nama Agus Halim. Bukan Agus Salim. Kurnia Angkasa, jika bermarga Ang. Sunarya Khodiat, jika dia bermarga Kho. Ridwan Tjongarian, kalau dia bermarga Tjong, dan sebagainya. Artinya, mereka tetap menghormati leluhur dengan memakai marga. Sama seperti Batak. Bagi Batak apalah arti sebuah nama, is ok. Jangan coba-coba, apalah arti sebuah marga, bisa marah besar.
Di Prancis, Amerika, Belanda, bahkan di Thailand juga di beberapa kota di Malaysia, orang Tionghoa-nya pandai berbahasa Hokkien. Effendi Setiawan, pernah menjadi wartawan selama 11 tahun di Harian Analisa Medan. Orangnya kecil, namun energik. Kemudian dia beralih menjadi orang yang bergerak di bidang properti. Sampai akhirnya dengan kerja uletnya dia berhasil membangun “kerajaan” bisnisnya, baik properti maupun bisnis lainnya.
Buku berjudul; Tionghoa Medan, Komunitas Paling Kontroversial di Indonesia, diterbitkan PT Buku Pintar Indonesia, Jakarta, 2018. Memiliki dua Nomor ISBN, 233 halaman. Buku ini terdiri dari XVIII bab.
Masalah sebutan Tionghoa atau China, dibahas dengan manis pada halaman 33 sampai 37. Memang kaum tua, tak suka disebut China, karena dinasti Qin yang membuat mereka terusir dari daratan Tiongkok. Mereka pun sampai ke Sumatera Utara secara berangsur. Diaspora terjadi bertahap, dimulai dari kuli di perkebunan.
Lantas kenapa ada Cimed? Sebenarnya yang memberikan sebutan itu adalah orang-orang China (Tionghoa) yang ada di Pulau Jawa, khususnya Jakarta. Selain rasa salut atas kegigihan orang-orang yang mereka sebut Cimed, mereka juga iri bahkan takut. Apa yang ditakutkan? Tentu saja ungkapan negatif. Ungkapan negatif itu, tidak segan-segan dituliskan oleh Effendi Setiawan.
Hal menarik lainnya, menurut saya dalam buku ini, kata China dan Huan Na. Apa yang ditulis menurut saya adalah sangat benar. Kalau ada yang tak mau disebut China, kenapa justru menyebut orang lain Huan Na? Sebenarnya kata Huan Na itu bukan pribumi. Kata Huan Na itu adalah primitif.
Lantas kata Huan Na harus diganti dengan sebutan In Ni Lang. In Ni adalah Indonesia dan Lang adalah orang. In Ni Lang adalah orang Indonesia. Manis bukan? Jika jalan damai ini bisa secepatnya dijalani, maka dua perasaan etnis akan menyatu. Satu menyebut rekannya Tionghoa dan temannya menyebut yang lain In Ni Lang. Sebenarnya apa susahnya?
Hal lain yang menurut penulis cukup berani dituliskan Effendi Setiawan, soal gaji. Jika di perusahaan orang Tionghoa, gaji orang Tionghoa pasti lebih besar dari kaum In Ni Lang. Bahkan berkali lipat. Alasannya karena orang Tionghoa, biaya hidupnya lebih besar.
Dalam Novel Acek Botak, hal ini juga menjadi perbincangan para tokoh dalam novel tersebut. Padahal pada zaman penjajahan Belanda bahkan masa orde lama, tidak ada pemerasan seperti zaman orde baru. Gaji orang Tionghoa tetap lebih besar. Walau posisi pekerjaannya sama. Bahkan selalu terjadi, pekerjaan dan jabatan orang pribumi lebih tinggi/besar, namun gajinya lebih rendah dari hanya seorang kerani biasa.
Efendi Setiawan, ternyata sangat jeli melihat fenomena ini. Sayangnya Effendi Setiawan tidak menuliskan, bagiamana terhadap orang pribumi selalu terjadi pembunuhan karakter.
Banyak hal menarik dalam buku ini. Seperti orang Tionghoa di Siantar. Ada tiga daerah yang memiliki logat (intonasi kata) seperti orang Siantar. Mereka berasal dari satu daerah di daratan Tiongkok, hingga logat Mandarinnya tidak terlepas dari logat daerahnya. Seperti Kuala Simpang, Siantar dan Mataram di NTB. Logat mereka mirip sekali.
Kesenjangan Sosial
Effendi Setiawan mengatakan, dalam bukunya ini kesenjangan sosial adalah pemicu utama tidak kompaknya Huanna dengan In Ni Lang. Orang Huanna tinggal di rumah eksklusif. Orang In Ni Lang tinggal rumah sederhana. Makan enak di restoran dan In Ni Lang masih banting tulang demi sesuap nasi.
Karena itu Effendi Setiawan selalu berkata pada rekan-rekannya, jangan berlaku diskriminatif. Kesenjangan sosial, melahirkan kecemburuan sosial. Terkadang kesenjangan sosial melahirkan kebencian tak beralasan.
Pendidikan juga mengalami kesenjangan. Pendidikan anak-anak Tionghoa dari luar negeri dan kembali langsung mempraktikkan ilmunya. Remaja di luar Tionghoa masih ramai-ramai merokok di mal. Bahkan ikutan menyaksikan balap liar. Membuang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat.
Sedang anak orang Tionghoa dalam kurun waktu 20 tahun lagi akan menjadi kekuatan dahsyat dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Perlu dipertanyakan, adalah transfer ilmu dari mereka kepada rekannya yang non-Tionghoa? Hal yang tak mungkin. Sebaliknya mereka berupaya keras mendapatkan ilmu apa saja dari rekannya yang non-Tionghoa.
Satu hal lagi yang mungkin dilupakan Effendi Setiawan dalam bukunya ini. Soal rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Begitu tidak pentingnya bagi mereka untuk tidak memelajari sejarah Bangsa Indoneisa. Tidak penting menyanyikan lagu-lagu nasional mulai dari Bagimu Negeri, Satu Nusa Satu Bangsa, Maju Tak Gentar, dan sebagainya, sebagai awal pendidikan rasa nasionalisme. Bahkan banyak di antara mereka, mulai dari SMP sampai mahasiswa tidak perlu meghafal urutan Pancasila.
Diskriminasi karena orang Tionghoa tidak mendapat kesempatan menjadi TNI, Polri, dan PNS. Perlu dipertanyakan, adakah yang mau menjadi TNI, Polri, dan PNS, kalau sejak kecil mereka ditanamkan menjadi pengusaha/pedagang? Rasanya tidak. Sebab mereka tahu, gaji TNI, Polri, dan PNS sangat kecil. Selain itu, adakah kaum Tionghoa terutama yang masih muda perduli pada seni dan budaya tradisi kaum Ini Ni Lang?
Kalau Tionghoa di Tapanuli, mereka begitu membaur dan tidak ada masalah. Mereka mendapat anugerah marga dan diperoleh dengan upacara adat. Ikut dalam pesta-pesta adat dan memakai bahasa daerah. Di Tarutung, Balige, Porsea, Siborong-borong, Dairi, dan Sibolga. Bagaimana dengan daerah Lain? Hal ini mungkin juga kelupaan Effendi Setiawan menuliskannya dalam bukunya ini.
Ini juga terlihat jelas dari 50 orang Tionghoa yang sukses dalam gambaran Effendi setiawan di bukunya ini. Ke-50 tokoh itu semuanya adalah pengusaha sukses dan hanya ada beberapa orang sebagai politisi. Ini pertanda, kalau belum terlihat orang Tionghoa Medan yang sukses sebagai seniman dan budayawan yang menggeluti budaya tradisi di Sumut.
Dari beberapa banyak pendapat dalam buku ini, semuanya bagus. Hanya ada satu pendapat yang penulis sangat setuju. Pendapat Rajamin Sirait. Katanya orang Tionghoa Medan, tidak terbuka karena enggan dan merasa tidak aman. Rasa tidak aman itu, membuat rumah orang Tionghoa dipagari terali besi yang tinggi. Akibatnya terkesan eksklusif, enggan bergaul dan menarik diri dari lingkungan.
Seharusnya ini tidak terjadi. Jika terjadi kedekatan dengan lingkungan, maka lingkungan juga akan mengamankan saudaranya. Pada 1998, kata Rajamin Siratit, banyaknya orang Tionghoa eksodus ke luar negeri, karean merasa tidak aman. Perasaan tidak aman ini menurutnya karena tidak adanya keterbukaan. Dengan eksodusnya ke luar negeri, membuat orang bertanya-tanya, di mana rasa nasionalisme itu?
Buku ini, menurut penulis, sebuah trobosan baru dari kaum Huanna terhadap kondisi objektif yang ada. Effendi Setiawan menurut penulis cukup berani menuliskannya sebagai kririk otokritik terhadap kaumnya. Penulis justru mengatakan, wajib dibaca oleh siapa saja. Apakah oleh kaum Huanna atau kaum Ni In Lang. Selamat membaca.









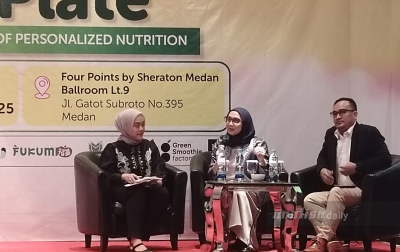
![Hati-hati! Pendaftaran CPNS 2025 di Kementerian Imigrasi [Hoaks]](https://analisadaily.com/imagesfile/202510/__20251018-164427_hatihati-pendaftaran-cpns-2025-di-kementerian-imigrasi-hoaks.jpeg)













