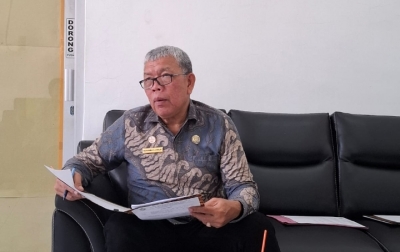Oleh: J Anto
DERITA kuli kontrak di Perkebunan Tanah Deli telah menginspirasi lahirnya novel Koeli, Berpacu Nasib di Kebun Karet karya MH Szekely - Lulofs, Living in Deli karya W.W. Wertheim dan Berjuta-juta dari Deli, Satoe Hikajat Koeli Contarct karya Emil W Aulia. Tapi kisah kuli kontrak Jawa di Suriname belum banyak dilirik novelis kita.
“Setelah lelah seharian bekerja, aku pergi dengan Mei menonton tonil di bioskop Thalia milik pemerintah di Julianastraat. Walau namanya bioskop, tak pernah di sini diputar film hidup. Bioskop Thalia disewakan untuk pementasan tonil atau penyelenggaraan rapat umum perusahaan. Kali ini, Group Tonil Kau Cung Lie yang datang dari Betawi menggelar pertunjukan. Ceritanya tentang agresi yang dilakukan pasukan Jepang terhadap Tiongkok.
Pada garis depan digambarkan para prajurit Tiongkok berjuang habis-habisan. Jika diperlukan siap untuk mengorbankan nyawa. Lakon di atas pentas sangat hidup. Mei Ching sampai menitikkan air mata karena terharu.”
Nukilan di atas bagian dari naskah Permulaan Musim yang Baru di Suriname. Sebuah naskah novel bergenre sejarah. Penulisnya, Koko Hendri Lubis. Lebih dikenal kolektor sekaligus peneliti buku-buku tua yang telah menulis sejumlah buku. Di antaranya Komik Medan, Sejarah Perkembangan Cerita Bergambar di Medan (2015), Biografi Taguan Hardjo: Langsung dari Dalam Hati (2016), dan Roman Medan, Sebuah Kota Membangun Harapan (2018).
Sebuah penerbit di Jawa, dalam waktu dekat, segera meluncurkan novel tersebut: menjawab kerinduan para keturunan kuli, baik yang telah mukim kembali di Indonesia, atau yang tinggal di Belanda. Sebagai kolektor, peneliti dan penulis, Koko sadar bahwa berbagai dokumen lawas, sering diabaikan banyak pihak. Dianggap sekadar masa lalu yang tak punya signifikansi dengan masa kini.
Itu yang mendorongnya menulis di sejumlah media massa. Entah artikel atau berupa buku. Tujuannya mendudukkan karya-karya lawas agar dipahami lebih kritis oleh masyarakat.
Komik dan roman Medan adalah contohnya. Karya komik Medan, seperti juga komik di kota lain, keberadaanya sering dipandang karya seni kelas dua. Komik dianggap bacaan hiburan murahan. Tak berkelas, juga tak mendidik. Orang tua kerap melarang anak mereka membaca komik. Bacaan bergambar itu dipandang sumber perusak moral anak, sarat cerita mistik, horor, dan cacat moral lain. Setali tiga uang, hal itu juga dialami roman Medan.
Namun lewat riset mendalam terhadap komik dan roman Medan, Koko membuat kesimpulan mengejutkan. Ternyata kedua bentuk industri kreatif itu adalah harta kebudayaan orang Medan yang luar biasa. Jika sastrawan, akademisi atau sejarawan emoh mengkaji lebih mendalam, entah karena stigma atau dianggap produk budaya populer, kitsch, rahasia kecerdasan suatu masyarakat yang tergambar dalam karya kreatif itu tak tergali.
Komik-komik karya Taguan Hardjo dan Zam Nuldyn, menurutnya memiliki nilai edukasi bagi pembaca. Cerita Zam Nuldyn selain memiliki kualitas gambar di atas rata-rata komikus sesaman, juga memiliki khasanah sastra yang kuat. Karya-karya komikus Medan memerlihatkan bahwa hasil goresan kuas mereka sejajar dengan produk literasi lain seperti novel, film atau karya seni lain. Selain itu, cergam-cergam Medan juga menawarkan genre yang beragam, mulai cerita pewayangan, komedi, superhero, legenda lama, perjuangan kemerdekaan, juga kisah cinta.
Sementara berapa roman Medan yang dikaji, ternyata memuat pesan-pesan antikolonialisme dari si pengarang. Sudah tentu, karya sastra seperti ini tak sesuai kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Lewat sastra resmi Balai Pustaka, aspek perjuangan yang ‘direstui’ adalah perjuangan melawan nilai-nilai adat yang dianggap kolot, tidak sesuai nilai-nilai modern yang dipromosikan lewat politik etis.
Bagi Koko, periode 1930-1965 di Medan adalah sebuah milestone munculnya industri kreatif penerbitan. Pelakunya berbeda. Namun keberadaan mereka dulu sudah bisa membuktikan bahwa seniman Medan telah dikenal luas dan mendunia.
Sudut Pandang
Penelitian tentang komik dan Roman Medan itu sendiri telah dibukukan. Namun kali ini, saat meneliti sejarah kuli kontrak Jawa yang dipekerjakan di sejumlah perkebunan teh, kopi, di Suriname, koloni Belanda, Koko tak memerankan diri sebagai penulis dan penafsir sejarah. Ia juga tak hendak menulis buku sejarah. Ia memanfaatkan data-data penelitiannya justru untuk menulis sebuah novel. Kenapa novel?
“Saya sudah tanya ke beberapa penulis novel senior di Indonesia. Belum ada novel tentang kuli kontrak Jawa di Suriname yang ditulis penulis Indonesia,” ujar Koko Hendri Lubis saat dijumpai di kantornya, Yayasan Badan Warisan Soematera (YBWS), Kompleks Perumahan Menteng Indah yang didampingi Wakil Sekreataris YBWS, M Syukri Nasution, yang juga peneliti, Senin (11/3).
Di YBWS berhimpun sejumlah peneliti, penulis dan penyuka sejarah yang berjuang menyelamatkan buku-buku dan dokumen tua. Mereka berburu ke berbagai tempat, mengoleksi dan berusaha merekonstruksi berdasarkan dokumen yang ada.
Menurut Syukri, saat ini mereka telah rampung merekonstruksi sejarah Lapangan Merdeka yang sejak zaman Walikota Abdillah berubah nama dan fungsi sehingga jadi Merdeka Walk. “Tahun 1900-an, namanya Esplanade.” Jika tak ada aral, April ini buku tentang sejarah Lapangan Merdeka terbit.
Naskah novel Permulaan Musim yang Baru di Suriname itu sendiri ditulis Koko selama 1,5 tahun. Tokoh utama novel itu adalah Supriono (orang Jawa) dan Mei Ching (gadis Tionghoa-Suriname). Ada kisah kawin campur, pergolakan politik para kuli Jawa menuntut persamaan hak, repratiasi para kuli ke Indonesia sampai debat arah kiblat masjid.
Di Suriname, kehidupan para kuli kontrak Jawa, juga Hindustan mengalami diskriminasi. Secara hukum kedudukan mereka tak setara dengan orang Eropa atau peranakan Eropa hasil perkawinan dengan orang Maron dan China. Hukum perkawinan misalnya tak ada. Stigma bahwa orang Jawa pemalas, bodoh, berkembang kuat di kalangan pengusaha dan pekerja kerah putih sehingga menimbulkan diskriminasi pengupahan.
“Terus terang inspirasi untuk novel saya bersumber dari hasil wawancara lisan yang saya lakukan saat di Amsterdam,” kata Koko. Mereka yang diwawancara merupakan generasi kedua para kuli kontrak. Rata-rata sudah tak bisa berbahasa Indonesia, tapi mahir berbahasa Belanda.
Sejak tahun 2000 mereka menetap di Rotterdhan dan Denhaag. Jumlahnya ada 30-an orang, namun hanya 5 orang yang diwawancarai mendalam, saat Koko terpilih sebagai peserta program Residensi Penulisan Kemendikbud 2017.
Namun penulis kelahiran 1977 ini juga menggunakan puluhan buku tentang sejarah kuli kontrak, sebagian besar dalam bahasa Belanda. Termasuk buku biografi Salikin M Hardjo yang ditulis Klaas Breunissen, Ik heb Suriname altijd liefgehad: Het leven van de Javaan Salikin Hardjo. Salikin Hardjo adalah ayah dari Taguan Hardjo, komikus terkenal Medan. Buku itu diterbitkan KITLV Uitgeverij 2001. Sayang sampai saat ini belum ada penerbit yang tertarik untuk menerbitkan dalam edisi bahasa Indonesia.
Menurut Klaas Breunissen, Solikin Hardjo tak lain adalah Bok Sark, seorang penulis yang mengungkap kasus-kasus kekerasan yang dialami para kuli kontrak Jawa di perkebunan-perkebunan Suriname. Bok Sark menulis di surat kabar De Banier van Waarheid en Recht atau Panji Kebenaran dan Keadilan, antara 1932-1935.
Salikin Hardjo alias Bok sark menulis 11 tulisan berbentuk surat esai dengan kepala surat Brieven uit Commewijne (surat-surat dari Commewijne). Berkat kritik-kritik Bok Sark itu, pemerintah Belanda di Suriname memperbaiki kondisi kerja para kuli kontrak asal Jawa.
Untuk menyusun novelnya, Koko juga meneliti komik perbudakan yang dibuat komikus Perancis, termasuk mengoleksi sejumlah piringan hitam untuk mengetahui lagu-lagu yang berkembang saat era kuli kontrak di Suriname.
Menurut Koko, pengiriman kuli kontrak asal Jawa dimulai 1890. Kisah mereka mirip para kuli yang dikirim ke perkebunan di Tanah Deli. Mereka berharap bisa memperbaiki nasib di tanah orang. Suriname metupakan koloni Belanda. Pulau ini terletak di Benua Amerika, dekat Brasil. Pemerintah Belanda membuka perkebunanan tebu, kopi, karet, dan tambang bauksit.
Untuk kepentingan tersebut, Belanda mendatangkan para kuli Afrika (orang Creol), orang Tionghoa asal Macao, dan orang Hindustan asal India. Orang-orang Creole tidak tahan bekerja sebagai budak, banyak melarikan diri ke dalam hutan. Kelompok ini menamakan diri sebagai “suku” Marron, suku asli Suriname.
Menurut Koko, besaran upah yang dijanjikan diterima para kuli di Suriname lebih besar dibanding upah di tempat lain pada masanya. “Untuk kuli pria 80 sen per hari dan perempuan 60 sen, di Hindia Belanda masih 3,5 sen.” Namun kenyataannya upah itu fluktuatif. Ancaman bagi kuli yang melanggar kontrak (5 tahun), bukan main-main: dihukum mati. Itu sebabnya kuli kontrak di sana jarang melakukan perlawanan seperti di Deli.
Koko berkesimpulan, ordonansi kuli di Suriname belajar dari penerapan ordonansi kuli di Deli. Ia lalu menyebut Gubernur Rudgers, yang pernah ditempatkan di Medan 1916-1923. Rudgers lalu ditarik sebagai Gubernur Suriname.
Pada perkembangannya, berbagai perbaikan peraturan telah ikut memperbaiki kesejahteraan para kuli Jawa. Pada 1946 saat berkembang isu Belanda akan melepaskan negara-negara koloninya. Termasuk Suriname, lalu muncul gerakan repratiasi, atau mulih nJowo.
Salikin Hardjo menjadi pelopor gerakan ini. Bersama keluarganya, termasuk Taguan Hardjo, mereka pulang ke Indonesia pada 1954. Namun oleh pemerintah mereka ditempatkan ke Tongar, Kabupaten Pasaman, dengan alasan penduduk Jawa sudah padat.
Mengutip Sarmoedji, seorang repratrian yang ikut rombongan, di Desa Tongar mereka ditampung dan tinggal dirumah berbentuk los panjang, terbuat dari bedeng anyaman bambu dan disekat menjadi ruangan-ruangan kecil ukuran 3 X 3 meter. Kondisi wilayah Tongar waktu itu berupa hutan lebat. Sekolah belum ada, pasar untuk menunjang kebutuhan pokok sehari-hari hanya ada di kota kecil, Simpang Empat, sekitar 5 km dari Tongar.
Alat transportasi umum tidak ada, jalan kaki adalah moda yang membawa mobilitas mereka. Situasi malam hari dilukiskan cukup mengerikan. Binatang buas seperti harimau, kadang masih berkeliaran. Setiap saat terdengar suara nyaring siamang, memecah kesunyian baik siang maupun malam. Babi hutan (celeng) sering mengganggu tanaman yang ada. Beruntung ada aliran listrik dari diesel yang dibawa dari Suriname.
Semua itu membuat repatrian sedih dan ingat Suriname. Akibatnya beberapa orang yang memiliki ketrampilan tertentu mulai meninggalkan Tongar. Tak terkecuali Taguan Hardjo yang akhirnya dikenal sebagai komikus sukses di Medan. Bagi mereka yang memilih bertahan, seperti Salikin M Hardjo yang wafat pada 1993, Tongar adalah medan juang kedua yang harus ditaklukkan. Ini tentu bukan sebuah cerita fiksi.
Foto-foto: Analisa/istimewa